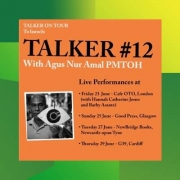Abraham dan Arjuna
Oleh Tony Doludea
Tanggal 9 Oktober 2004, kantor resmi Presiden Perancis Jacques Chirac mengumumkan kematian Jacques Derrida pada usianya yang ke 74. Pada tanggal 8 Oktober 2004 malam, Derrida meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Paris, setelah tahun sebelumnya didiagnosa menderita kanker pankreas. Bukunya yang berjudul The Gift of Death (donner la mort), yang diterbitkan tahun 1995, menjadi semakin menarik setelah kepergiannya itu. Perhatian utama Derrida dalam bukunya ini adalah makna moral dan tanggung jawab etis dalam agama dan filsafat Barat. Buku ini merupakan lanjutan penggalian atas pertanyaan yang diperkenalkannya dalam bukunya sebelumnya Given Time (1992), tentang kemungkinan atau ketidakmungkinan mengenai persembahan atau pemberian secara ekonomis dan antropologis sebagai hakikat pemberian atau persembahan. Dan Apporias (1993), yang mempertanyakan, menggali dan menganalisa tentang kemungkinan kematian. Kematian merupakan jalan akhir, jalan buntu dan batas dari kebenaran. Mungkinkan seseorang melampaui batas kebenaran itu? Apa yang dimaksud sebagai akhir dan batas? Apa yang dimaksdukan sebagai melampaui di sini?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut berusaha dijawab oleh Derrida. Dalam The Gift of Death, Derrida sampai pada gagasan tentang tanggung jawab dan persembahan maut atau pengurbanan diri sebagai pemberian yang tertinggi. Persembahan maut atau pengurbanan diri di sini berarti bahwa seseorang memberikan hidupnya, mati demi orang lain. Derrida mempertanyakan batasan rasional dan tanggung jawab di mana seseorang sampai pada memberikan hidupnya atau menerima kematian untuk sesamanya, apakah melalui pengurbanan, pembunuhan, hukuman mati atau bunuh diri.
Buku ini diawali dengan sebuah diskusi mengenai karya Jan Patocka (1907-1977) Heretical Essays on The Philosophy of History (1975). Patocka adalah seorang filsuf fenomenologi Czech yang paling berpengaruh di Eropa Tengah, ia adalah salah seorang murid terakhir Edmund Husserl (1859-1938) dan Martin Heidegger (1889-1976). Derrida mengembangkan gagasan Patocka berkenaan dengan yang kudus (the sacred) dan tanggung jawab melalui perbandingan dengan pandangan Heidegger, Emmanule Levinas (1906-1995) dan Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855). Terlebih dari semuanya itu, Derrida sangat terpengaruh oleh akhir hidup Patocka yang tragis tersebut.
Pada usianya yang ke-69, Patocka bersama dengan teman-temannya, Vaclav Havel dan Jiri Hajek ditahan karena berhasil mendeklarasikan Charta 77. Charta 77 adalah sebuah seruan terhadap pemerintah Komunis Czechoslovakia untuk mengakui Hak Asasi sebagaimana yang dideklarasikan di Helsinki. Setelah 11 hari diinterogasi oleh polisi, Patocka yang selama ini dikenal sebagai intelektual yang tidak pernah terlibat dalam tindakan pelanggran politik, meninggal karena pendarahan otak. Derrida memandang kematian Patocka sebagai sebuah persembahan maut dan sebuah kematian bagi orang lain. Derrida memiliki kesamaan keprihatinan yang jelas dengan Kierkagaard, karena Derrida membaca dengan teliti karya Kierkegaard, Fear and Trembling (1843). Derrida membandingkan dan memperjelas gagasannya tentang tanggung jawab dengan pandangan Kierkegaard itu, kemudian memperluas dan memperdalam pikirannya tentang persembahan dan pengurbanan. Bagi Derrida, hal yang paling mungkin dari persembahan, khususnya pengurbanan hidup seseorang untuk orang lain, sebagai pengurbanan tertinggi, dipertanyakan.
Dalam Fear and Trembling, Kierkegaard ingin menyertai Abraham dalam perjalannanya bersama Ishak mendaki gunung seperti yang diperintahkan Allah, agar ia dapat bersama-sama Abraham pada saat-saat penuh kesusahan. Kierkegaard ingin bersama-sama dengan Abraham pada waktu ia melangkahkan kakinya ke tanah Moria nun jauh di sana. Ia ingin hadir ketika Abraham menyuruh pelayan-pelayannya menunggu keledai-keledai yang mereka bawa dan hanya dengan Ishak ia mendaki gunung itu. Hati Abraham tidak dipenuhi pintalan fantasi-fantasi. Hatinya penuh dengan ketakutan. Ia bukan seorang pemikir. Ia tidak merasa perlu untuk secara mendalam memikirkan iman. Tetapi menurut Kierkegaard Abraham menghadapi nasib yang sangat diinginkan orang. Nasib seperti itu pasti sangat membahagiakan, sekalipun tidak seorangpun yang mengetahui hal itu.
Kitab Kejadian 22 mengkisahkan: “Lalu Allah mencobai Abraham dan berkata: ‘Ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi itu, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu.’”
Hari masih pagi benar, bagunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu, dan memanggil dua orang pelayannya beserta Ishak, anaknya itu. Lalu bersama-sama, mereka meninggalkan rumah dan menempuh jalan menuju ke lembah. Sarah berdiri di depan jendela dan mengikuti mereka dengan pandangannya, sampai mereka tidak kelihatan di telan lembah.
Tiga hari lamanya mereka berjalan, tanpa mengatakan sesuatu. Pada hari keempat Abraham belum juga mengatakan sesuatu. Waktu ia melayangkan pandanganya, kelihatan olehnya gunung Moria dari jauh. Ia meninggalkan para pelayannya itu dan sambil menggenggam tangan Ishak mereka berjalan menuju gunung itu.
Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sementara mereka berjalan, Abraham berkata dalam hatinya: “Aku tidak mau lebih lama lagi merahasiakan maksud perjalanan ini kepada Ishak.” Ia berhenti berjalan, lalu menumpangkan tangannya atas Ishak yang sudah bertelut dan memberkatinya. Ishak menundukkan kepalanya untuk menerima berkat bapaknya. Dengan perasaan terharu Abraham melihat anaknya, pandangannya penuh dengan kasih dan suaranya dengan nasihat.
Tapi Ishak tidak mengerti kata-katanya. Pikirannya tidak mampu menembus masuk ke dalam dunia-pikiran bapaknya, Abraham. Ia memeluk kaki Abraham, mengeluh dan memohon pengertian untuk hidupnya yang masih muda. Ia berkata-kata tentang apa yang ia harapkan dalam hidupnya. Ia mengingatkan Abraham pada kegembiraan yang mereka alami bersama di rumah mereka, dan pada kesepian dan kesedihan, kalau ia tidak ada lagi.
Abraham membangunkan anaknya yang sedang berlutut, lalu sambil menggenggam tangannya, mereka melanjutkan perjalanan. Kata-kata Abraham penuh dengan penghiburan dan nasihat. Tetapi Ishak tidak memahaminya. Abraham mendaki gunung Moria dan Ishak tidak dapat memahaminya.
Abraham memalingkan wajahnya sebentar dari Ishak. Ketika Ishak kembali melihat muka bapaknya, muka itu sama sekali telah berubah; pandangannya liar, wajahnya sangat menakutkan! Lalu Abraham mengulurkan tanganya, memegang dada Ishak dan melemparkannya ke tanah serta berkata: “Hai anak yang bodoh, apakah engkau mengira, bahwa aku ini bapakmu? Aku adalah penyembah berhala. Apakah engkau menyangka, bahwa persembahanmu sebagai kurban adalah perintah Allah? Tidak, persembahanmu ini adalah kemauanku sendiri.”
Maka gemetarlah Ishak dan dalam ketakutannya ia berteriak: “Ya Allah di dalam surga, kasihanilah aku! Allah Abraham, kasihanilah aku! Kalau di dunia ini aku tidak memiliki bapak lagi. Engkaulah bapakku.”
Diam-diam Abraham berdoa: “Tuhan di dalam surga, aku mengucapkan syukur kepada-Mu. Lebih baik kalau ia percaya bahwa aku adalah mahluk yang bukan manusia dari pada kalau ia kehilangan percayanya kepada-Mu.
Pagi-pagi sekali Abraham telah bangun. Ia memeluk Sarah, pengantin perempuan pada hari tuanya dan Sarah mencium Ishak yang oleh kelahirannya, ia tidak dipermalukan lagi. Ishak adalah kebanggaan dan harapannya di masa depan.
Tanpa berkata-kata, Abraham dan Ishak menempuh jalan yang menanjak. Pandangan Abraham tertuju ke jalan yang mereka tempuh. Baru pada hari yang ke empat ia mengangkat kepalanya dan jauh di sana ia melihat gunung Moria. Tetapi sekali lagi pandangannya ia arahkan ke bumi. Tanpa berkata-kata, ia menyusun kayu-kayu api, dan tanpa berkata-kata ia mengikat Ishak, lalu mengambil pisau. Tetapi tiba-tiba ia melihat domba, yang dikirimkan Allah kepadanya. Lalu Abraham mempersembahkan domba itu. Dan kemudian mereka kembali ke rumah mereka.
Sejak waktu itu Abraham adalah seorang tua. Ia tidak dapat lupa, bahwa hal yang berat ini dituntut Allah dari dirinya.
Sementara itu Ishak makin bertambah besar dan sehat. Tapi mata Abraham mulai kabur: kebahagiaan, kegembiraan, telah hilang dari hidupnya.
Pagi-pagi sekali Abraham telah bangun. Ia mencium Sarah ibu yang muda, dan Sarah mencium Ishak, yang merupakan kebanggaan dan kegembiraan hidupnya.
Sesudah itu mereka berangkat, sedang Abraham memikirkan sesuatu. Yang ia pikirkan itu ialah Hagar dan anaknya, yang ia usir ke padang gurun. Ia mendaki gunung Moria dengan pisau di tangannya.
Pada suatu sore yang sunyi Abraham sendiri, pergi ke gunung Moria. Di situ ia melemparkan diri ke bumi dan memohon ampun kepada Allah. Ia telah bermaksud untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai kurban bakaran. Dengan jalan itu ia melupakan kewajibannya sebagai Bapak.
Beberapa kali Abraham mengadakan perjalanan ini, tetapi ia tidak memperoleh ketenangan. Mengapa perbuatannya itu, yaitu mau mempersembahkan kepada Allah apa yang ia paling cintai itu adalah dosa. Apakah Abraham tidak sering berpikir untuk mempersembahkan dirinya untuk Ishak? Dan kalau hal itu benar-benar adalah dosa, karena ia sebagai bapak tidak cukup mencintai Ishak, bagaimanakah dosa ini dapat diampuni? Apa yang lebih buruk, yakni tidak memenuhi apa yang Allah minta atau bersalah terhadap darah dan dagingnya sendiri?
Hari masih pagi. Dalam rumah Abraham segala sesuatu telah siap untuk perjalanan mereka. Ia berpisah dengan Sarah. Dan Eliezer, pelayannya yang setia, mengantarnya ke luar. Abraham dan Ishak berjalan dalam suasana damai, sampai mereka tiba di gunung Moria. Di situ Abraham dengan tenang mempersiapkan segala sesuatu untuk kurban, yang mau dipersembahkan. Tetapi waktu ia membalikkan badannya untuk mengambil pisau, Ishak melihat bahwa tangan kirinya ragu-ragu bergerak. Ia melihat bahwa seluruh tubuh bapaknya gemetar. Sungguhpun demikian Abraham menarik pisau itu ke arahnya.
Lalu mereka kembali ke rumah. Sarah datang berlari-lari menemui mereka. Sejak waktu itu Ishak tidak dapat percaya lagi. Tidak pernah Abraham dan dia berbicara tentang yang ia lihat. Abraham tidak menyangka bahwa ia tahu tentang kebingungannya.
Atas jalan ini dan atas banyak jalan lain lagi, Kierkegaard berpikir. Setiap kali ia tiba di rumah dari suatu perjalanan ke gunung Moria, ia merebahkan dirinya karena letih, meliputi tangannya dan berkata: “Tidak ada seorangpun yang sama seperti Abraham. Siapakah yang mampu mengerti hal ini?”
Dalam karyanya Fear and Trembeling orang membaca bahwa Kierkegaard telah memutuskan pertunangannya dengan Regina Olsen karena Allah, karena jalannya dipenuhi suatu tugas yang tidak dapat dipahami orang, kecuali orang yang hidup kemudian dan yang mengenal sejarah. Di situ orang mendapatkan kesan bahwa Kierkegaard menganggap dirinya sebagai “hewan kurban” dan dengan itu ia, katanya, memenuhi tugasnya tanpa suatu prospek atau harapan akan kebahagiaan duniawi. Sekarang ia merasa berbahagia bukan saja karena pemutusan pertunangannya itu sesuai dengan kehendak Allah, tetapi juga karena ia telah memiliki suatu ide, yang untuknya ia mau hidup dan mau mati, suatu tujuan yang ia tetapkan bagi dirinya sendiri.
Derrida memusatkan perhatiannya pada keputusan Abraham untuk menghadapi ujian itu sendirian saja, tidak mendiskusikannya dengan orang yang akan mencoba mengendalikannya dengan mengajukan perintah etis, yang apabila ditaati, akan membuatnya tidak taat kepada Allah. Abraham sedikit melipur lara dengan suatu etika “tanggungjawab kepada orang lain”; setiap orang lain adalah sesama manusia, Sehingga pertanyaannya adalah bukan apakah memberi atau tidak, tetapi kepada siapa seseorang akan memberi.
Tujuan Derrida adalah membangun prioritas pengurbanan diri sebagai dasar atas pemberian individualistik yang radikal, bukannya pada dasar utilitarian. Hal ini yang membuat pengurbanan diri tidak hanya menjadi prioritas terkait dengan tanggapan individual kepada mysterium tremendum, tetapi juga sekarang sebagai tanggung jawab kepada kehidupan orang lain. Derrida menunjukkan bahwa sebagaimana tanggung jawab dan pengurbanan memiliki dasar pada mysterium tremendum, keduanya itu juga pada dasarnya melampaui etika dan moral tradisional. Tanggung jawab seperti demikian itu menyebabkan seseorang gemetar, yang di dalamnya tercakup masa depan yang tak dapat diperhitungkan sebelumnya, yang berarti bahwa dia harus kehilangan seseorang di sana.
Allah adalah the Wholly Other (yang tak terperikan, tan kena kinaya ngapa), Dia yang menuntut ketaatan absolut yang mensyaratkan Abraham untuk melampaui, bahkan melanggar pemahamannya tentang moral dan etika. Pikiran Allah tetap tak terpahami, di mana Abraham juga menemukan tindakannya itu tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Tanggung jawab absolut sekarang tampak malahan sebagai tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Tindakan moral menjadi penghambat, bahkan menjadi godaan yang bertentangan dengan tugas Abraham itu.
Derrida menekankan ketakterpecahkannya dan kontradiksi paradoksal antara tanggung jawab moral yang umum dan tanggung jawab absolut itu. Tanggung jawab absolut melampaui tanggung jawab umum dan olehnya pasti tak terpahami, tak terpikirkan. Ini juga berarti bahwa tanggung jawab absolut itu menggangkat seseorang naik mengatasi yang universal dengan memperlihatkan bahwa pengurbanan diri seseorang atas tugas absolut itu adalah sesungguhnya panggilan tertinggi baginya.
Di sini Derrida melihat sebuah pembenaran bagi dekonstruksi etika. Karena atas nama tugas absolut, seseorang harus melanggar tuntutan moral. Sementara pada saat yang sama, tugas itu merupakan bagian dan dipahami sebagai tugas moral. Dalam kontradiksi dan paradoks tersebut, seseorang sungguh-sungguh menganggap tanggung jawab absolut itu sebagai tindakan miliknya. Derrida memandang tindakan Abraham itu sebagai tanggapannya kepada mysterium, yaitu Allah sebagai the Wholly Other.
Tanggung jawab kepada sesama manusia inilah yang menggerakkan seseorang masuk ke dalam resiko pengurbanan diri absolut. Derrida tahu hal ini berarti bahwa konsep tanggung jawab, keputusan dan tugas secara apriori merupakan sebuah hukuman paradoks, skandal dan kebuntuan (aporia). Pardoks, skandal dan aporia di dalam dirinya sendiri tidak lain adalah pengurbanan diri, penyataan (wahyu) pemikiran konseptual dalam keterbatasannya, atas kematiannya dan kefanaannya.
Melalui Kierkegaard Derrida mampu membangun sebuah diskusi mengenai persembahan maut secara dekonstruktif. Hubungan Abraham dengan Allah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk tanggapannya kepada setiap orang lain, sebagaimana setiap orang lain, secara khusus hubungan seseorang dengan sesamanya, atau orang yang dikasihinya. Hal itu merupakan suatu yang tak terpahami, sebagai sebuah rahasia dan bersifat transenden sama seperti YHWH.
Setiap orang lain harus diperlakukan sebagai the Wholly Other, sebagaimana masing-masing mereka juga menuntut tanggung jawab absolut itu. Hal inilah yang membedakan antara tugas umum dan tugas absolut yang tak terpahami tersebut. Semua tugas sekarang menjadi absolut dan secara absolut melekat pada tugas seseorang dan tak terelakkan, yang menuntut pengurbanan diri seseorang demi tugas absolut kepada orang lain. Dan ini dilakukannya tanpa ada tujuan untuk membenarkan pilihannya. Dia memilih dan mengambil keputusan. Dia memilih untuk memilih yang satu ini dan menolak yang lainnya. Berpihak kepada seseorang dan melawan yang lainnya. Menurut Derrida tanggung jawab umum dan absolut harus bertentangan satu dengan yang lainnya.
Pilihan seseorang pada kenyataannya ditentukan atau dibatasi oleh kesepakatan umum, yaitu seperangkat perilaku yang disepakati bersama oleh masyarakat. Hal seperti inilah yang membuat Abraham menjadi takut dan gentar ketika dihadapkan dengan sebuah tugas tertinggi yang melampaui moralitas konvensional. Menurut penilaian Derrida, kesepakatan umum dan tanggung jawab absolut harus berdiri pada posisi saling bertentangan. Kesepakatan umum dikritik karena masyarakat sendiri tidak dapat menghindari untuk memilih berpihak kepada seseorang dan mengabaikan yang lain, untuk bersekutu dengan yang satu dan berperang dengan yang lainnya. Masyarakat tidak dapat menilai keputusannya dan pembenaran selalu diberikan atas pilihan yang diambilnya itu. Apabila anak domba jantan itu tidak muncul di belakang Abraham, maka ia dapat saja membunuh Ishak, suatu tindak yang oleh masyarakat akan dianggap tak masuk akal dan dikutuk.
Dengan itu, Derrida ingin menunjukkan bahwa sikap hidup masyarakat saat ini, yang secara mendasar terletak pada struktur hukum pasar di mana masyarakat ini telah terlembagakan dan dikendalikan. Masyarakat membunuh dengan membiarkan 10 juta anak-anak mati karena kelaparan dan penyakit. Tanpa kesadaran moral dan pengadilan hukum untuk menghakimi suatu pengurbanan seperti itu. Orang lain dikurbankan demi menghindarkan seseorang mengurbankan dirinya. Derrida menegaskan bahwa kebenaran yang ia temukan tertanam dalam cerita Abraham merupakan sebuah alternatif dari bentuk masyarakat pasar ekonomis seperti ini.
Pada saat Abraham memegang dan takluk pada tugas absolut yang paradoksal itu, yang malampaui dan melanggar tugas umum, Allah mengembalikan Ishak anaknya dan hal ini sebenarnya menyatakan bahwa paradoks tersebut pada dasarnya merupakan sebuah bentuk ganjaran ekonomis. Kemudian Derrida merujuk Injil Matius 6: 4,6,18 sebagai kunci untuk mengungkap makna konsep ekonomi semacam itu dalam janji, bahwa Allah yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan mengganjar seseorang.
Setelah melukiskan kontradiksi antara ganjaran spiritual dan tak terlihat dengan yang bersifat duniawi seperti itu, Derrida kembali memperhatikan arti “melihat dengan sembunyi”. Derrida memahami hal ini sebagai “jernihnya terang ilahi yang menembus segala sesuatu dalam kerahasiaan yang tersembunyi.” Namun Derrida menolak bahwa ayat-ayat Alkitab itu harus dipahami sebagai dalil tardisional Judeo-Kristenitas tentang Allah. Sebaliknya Derrida mengusulkan sebuah pemahaman tentang Allah sebagai “nama kemungkinan yang dipegang secara tersembunyi, yang nampak dari dalam tetapi tidak nampak dari luar.”
Derrida melanjutkan bahwa sekali kesadaran semacam ini ada di dalam diri seseorang dan orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi seseorang yang ada di dalamnya, yang lebih akrab melihat rahasia itu secara tersembunyi, yaitu Allah. Maka ia adalah dirinya yang absolut. Allah di dalam dia, dia dapat saja menyebut dirinya Allah. Di sini Derrida mengganti pemahaman tradisional tentang Allah dengan keberadaan personal yang disebut incorporeal radically individualistic. Di mana terjadi perubahan, perjuampaan transendensi misterius sebagai perjumpaan yang mengerikan menjadi perjumpaan rahasia, yang tak terpahami, dengan yang tak terlihat (gaib) dalam dirinya sendiri.
Gagasan Derrida seperti itu dapat ditemukan juga dalam cerita Bhagavad Gita. Di mana orang dapat menyaksikan kegentaran Arjuna dalam mengahadapi sudara-saudaranya sendiri di medan perang Kurukshetra. Bhagavad Gita Bab I: 24-47 menceritakan bahwa setelah mendengar keinginan Arjuna Krishna menarik keretanya ke garis depan dan mengambil posisi, persis di tengah kedua pasukan. Setelah berhadapan dengan Bhisma, Drona, dan lain-lainnya yang berpihak pada Kurawa, Krishan bersabda: “Lihatlah, Arjuna, lihatlah para pasukan Kurawa”. Dan Arjuna pun melihat bahwa di antara pasukan Kurawa, begitu banyak wajah yang ia kenal baik, di antara mereka ada para paman, sepupunya, sahabatnya, juga mereka yang umurnya jauh lebih tua dan selama ini ia hormati.
Melihat itu, Arjuna merasa kasihan. Melihat mereka, Arjuna merasa begitu lemah, bibirnya gemetaran. Kulitnya seolah-olah terbakar, senjata pun tidak dapat dipegang dengan baik, pikirannya kacau. Arjuna tidak dapat berdiri tegak lagi dan mendapatkan firasat-firasat buruk. Arjuna tidak melihat kebaikan, apabila dia harus membunuh para anggota keluarga besarnya sendiri. Arjuna jadi tidak menginginkan harta benda, kekayaan dan kedudukan lagi. Baginya tidak gunanya lagi segala kenikmatan duniawi ini. Baginya Kurawalah yang harus menikmati kerajaan ini bersama-sama mereka. Namun sekarang dia harus melawan mereka. Mereka ini masih punya hubungan keluarga dengannya. Daripada membunuh mereka, Arjuna rela dibunuh oleh mereka. Arjuna tidak dapat membunuh mereka demi kekuasaan, kerajaan. Kenikmatan apa yang akan dia peroleh dari pembunuhan massal ini? Arjuna justru merasa berdosa. Arjuna tidak seharusnya membunuh mereka. Apakah dia bahagia setelah membunuh mereka?
Kurawa memang serakah, pikiran mereka sudah kacau dan oleh karenanya mereka siap bertempur dengan Pandawa. Namun Pandawa masih dapat berpikir secara jernih. Kenapa mereka harus terlibat dalam perang semacam ini? Perang antar keluarga ini akan menghancurkan dinasti mereka. Mereka tidak dapat mempertahankan kebudayaan serta tradisinya dan dalam keadaan seperti itu, para wanita yang manjadi tulang punggung keluarga akan mengalami kemerosotan moral. Hidup di dunia ini dalam keadaan yang demikian kacaunya, persis sama seperti hidup di neraka. Sayang, Pandawa yang seharusnya sadar dan menghindari perang, justru sekarang terlibat dalam perang. Apabila putra Destarata ingin membunuh Pandawa, silakan. Arjuna akan menghadapi tanpa senjata. Demikian, setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, Arjuna melepaskan senjatanya dan duduk di bagian belakang keretanya.
Namun Krishna tahu persis bahwa air mata Arjuna tidak disebabkan oleh kasih, tapi rasa kasihan. Melihat Arjuna terbawa oleh rasa kasihan dan air mata membasahi pipinya, Sri Krishna bersabda demikian, “Arjuna, apa yang terjadi padamu? Dari mana datangnya kelemahan yang memalukan ini? Dari mana datangnya sifat yang tidak mulia ini? Jangan menyerah pada kelemahan dirimu.” Maka bangkitlah Arjuna, “kelemahan ini tidak pantas bagimu.” Arjuna menjawab, ”Tetapi Krishna, bagaimana kau dapat melawan Bhisma dan Drona, yang justru harus kuhormati? Lebih baik aku hidup sebagai seorang pengemis, daripada mendapatkan kekuasaan dengan cara membunuh mereka. Segala kenikmatan akan tercemar oleh darah mereka. Mereka yang menang, ataupun kita yang menang, mereka adalah keluarga kita; apa arti kemenangan yang kita peroleh setelah membunuh mereka. Aku merasa begitu lemah, pikiranku pun kacau. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan… “
Krishna berkata, “Jangan lupa pula kewajibanmu sebagai seorang Satria. Jangan gentar bertempurlah demi menegakkan Kebenaran. Betapa bahagianya para Satria yang mendapatkan kesempatan untuk bertempur demi menegakkan Kebajikan dan Kebenaran… Dengan menganggap sama suka dan duka, keberhasilan dan kehilangan, kemenangan dan kekalahan, bertempurlah! Demikian kau akan bebas dari dosa… Berkaryalah tanpa keterikatan, wahai Arjuna. Jangan terpengaruh oleh kegagalan maupun keberhasilan. Itulah Pencerahan… Ia yang pikirannya tak tergoyahkan dalam keadaan duka, ia yang tidak mengejar suka, ia yang bebas dari rasa takut dan amarah ialah manusia yang Cerah… Inilah Kesadaran yang Tertinggi, wahai Arjuna. Setelah mencapai kesadaran ini, seseorang tidak akan bingung lagi. Apabila saat kematian pun tiba, seseorang yang berada dalam kesadaran semacam ini akan menyatu dengan Sumbernya.”
Ada satu yang perlu dikuak di sini, seperti yang telah dilakukan oleh Alain Badiou (1937) dalam Ethics of Truth-nya itu, yaitu kesetiaan (fidelity). Ethics of Truth dirancang untuk mengelola ketajaman rasa (tidak merancukan antara yang benar dengan yang jahat), keberanian, keteguhan hati dan ketabahan (tidak menghianati kebenaran), juga bersikap tidak ekstrem dan menolak gagasan kebenaran total dan substansial.
Ethics of Truth terjadi dalam tiga tahap: Iman, Kasih dan Pengharapan. Iman merupakan sebutan bagi subjek yang mendeklarasikan keyakinannya akibat perjumpaannya dengan truth-event. Kasih adalah sebutan bagi subjek yang dengan militan memperjuangkan keyakinannya tadi sebagai kebenaran universal dalam rangka emansipasi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa iman itu diwujudnyatakan dalam kasih. Pengharapan adalah sebutan bagi subjek dalam mengantisipasi Yang Benar dalam keteguhan, meskipun saat ini pada kenyataannya Yang Benar itu hanya terealisasi dalam ketidaksempurnaan. Pengharapan merupakan suatu kekuatan yang memampukan subjek mengantisipasi Yang Benar meskipun terjadi kegagalan. Ketiga hal tersebut merupakan aspek fidelity subjek. Ethics of Truth merupakan suatu proses terus-menerus yang secara konsisten setia dan mempertaruhkan diri seseorang dalam mengejar apa yang tidak dapat dia pahami. Dalam kalimat singkat Ethics of Truth dapat diungkapkan sebagai: “Keep going!”
Truth, event, situation, dan subjek merupakan aspek-aspek dari satu proses penegasan, yaitu terwujudnya kebenaran melalui subjek yang dengan tabah dan ulet mempertahankan fidelity sebagai akibat perjumpaannya dengan event pada situation tertentu meskipun ia (event) bukanlah ia (event) yang sesungguhnya itu. Zizek menyebut hal itu that’s not it. Rahasia yang sangat tersembunyi, yang hanya dapat dilihat oleh Allah dari tempat rahasia yang tersembunyi.
Kita dapat berbagi bersama Abraham dan Arjuna tentang hal yang tidak dapat dibagi ini. Tentang sebuah rahasia yang tak dapat dibagi. Rahasia yang tak terpahami oleh seorangpun juga, baik oleh Abraham sendiri, oleh Arjuna, apalagi oleh orang yang lain. Berbagi rahasia ini tidak berarti orang kemudian dapat memahami dan menggungkapkan rahasia tersebut. Ini adalah berbagi hal yang tak terpahami. Apalah sebuah rahasia, yang merupakan rahasia tentang suatu hal, yang tidak ada. Dan berbagi tentang hal yang tidak memberikan apapun juga. Untuk itu Arjuna adalah seorang Satria dan Abraman adalah bapak orang beriman.
————————–
Kepustakaan
Abineno, J.L. Ch. Soren Kierkegaard: Filsuf, Religius dan Teolog. BPK Gunung
Mulia, Jakarta, 1994.
Badiou, Alain. Ethics: An Essay on the Understanding of Evil. Verso, New
York, 2001.
Derrida, Jacques. The Gift of Death. University of Chicago Press, Chicago &
London, 1995.
Kierkegaard, Søren. Fear and Trembling. Cambridge University Press,
Cambridge, 2006.
Pendit, Nyoman S. Bhagavadgita. Gramedia, Jakarta 2002.
Zizek, Slavoj. The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology.
Verso, London and New York, 1999.
*Penulis adalah peneliti di Abdurrachman Wahid Center UI