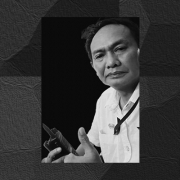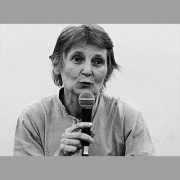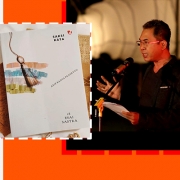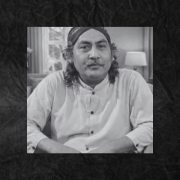Gayo adalah Budaya Kopi
Oleh: Pietra Widiadi & Dewi Arum Nawang Wungu*
Belum tahu tahun berapa pastinya, tetapi Pemerintah Hindia Belanda mulai menggalakkan kopi di Dataran Tinggi Gayo PD tahun 1908. Kopi-kopi Gayo di bawa dari Jawa, salah satunya dari Malang. Mungkin seperti di Lampung yang di awali dari orang-orang dari Blau, Ngajum, Malang.
Dari beberapa diskusi tentang Kopi di Sumatra, bahwa dibawa dari Jawa Timur, salah satunya dari Blawan/“Blauan/Blauw” di Dataran Tinggi Ijen atau di Malang. Selain kopi, pada tahun-tahun sampai dengan tahun 1942, Hindia Belanda mengirim tenaga kerja kontrak ke Sumatra, salah besarnya ke Gayo.
Beberapa lokasi yg disebut dg Blau, itu merupakan salah satu estate utama (bersama Jampit, Pancoer, Kayumas) yang sudah aktif sejak akhir abad ke-19 dan dikenal sebagai sentra arabika jadi secara logis tempat seperti inilah yang kerap menjadi sumber bibit ketika pemerintah memperluas areal ke luar Jawa. Namun, dokumen yang menyebut “bibit dari Blawan/Malang dikirim ke Gayo” secara eksplisit belum temukan dalam.
Di Gayo, lokasi awal tanam dan pembibitan di Gayo yang sering disebut antara lain Paya Tumpi (Kebayakan), namun lagi-lagi sumbernya tak menuliskan asal kebun bibit di Jawa. Kemungkinan besar benih arabika awal Gayo berasal dari Jawa (karena pada masa itu pusat arabika pemerintah memang di Jawa dan ekspansi biasanya bertumpu pada stok bibit dari estate-estate pemerintah/partikelir di Jawa).
Yang terdokumentasi jelas bahwa pada tahun dan konteks introduksi (±1908), lokasi awal tanam/pembibitan di Gayo, yang disertai arus tenaga kerja/keahlian dari Jawa.
Jadi jelas bahwa Arabika diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda ke Gayo sekitar tahun 1908. Kemungkinan besar menggunakan sumber bibit dari sentra arabika di Jawa (mis. Ijen/Blawan), meski rujukan yang secara eksplisit menyebut asal kebun bibit belum ditemukan, dan diperoleh dari cerita beberapa orang Jago (Jawa Gayo) tentang keberadaan mereka.
Imajinasi membangun Gayo menjadi pusat kopi, mungkin sudah dikembangkan oleh Pemerintah pada waktu itu. Meski bentuknya mungkin belum terbayangkan. Bangunan rumah-rumah para mandor yg dibuat dr kayu, masih berdiri kokoh dengan menyisakan kelam perjalanan kopi, pada awal-awal tahun 1960an. Kopi hanya sebagai komoditi sampingan yang tak penting sepertinya.
Saat ini bisa dibilang 3 kabupaten di Dataran Tinggi Gayo penuh dengan Kopi. Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Bisa dibilang 70-80% adalah kopi. Kehidupan sehari-hari seperti digendong oleh kopi. Anak-anak main di kebun kopi, sambil bantu mamak memetik buah merah kopi.
Kopi adalah bagian penghidupan yg tak terpisahkan dari kehidupan yang berkembang. Anak-anak sekolah ke Jawa dengan bekal kopi, seperti Lae Manulang yang membuka kafe Horas di poros kota Takengon. Anaknya menuju Malang, mengambil jurusan Tata Boga dengan harapan kembali ke Gayo tidak hanya menyuguhkan plain kopi pada pelanggan.
Atau seperti bang Gembel Seladang yang anaknya sedang mengarungi pengetahuan di Bogor, sepeti berkarung-karung kopi dibawa untuk menggali kemampuan. 80an mobil kopi di Takengon yang dikelola oleh para muda, adalah harapan-harapan masa depan hidup bergelimang kopi. Atau seperti Bu Sutirah, warga Jagungjagad mengandalkan kopinya untuk kesembuhan sang kakak yang lagi tergolek lemas di ICCU RSUD Datu Beru.
Kopi adalah penghidupan lestari
Siapa bilang pemerintah Hindia-Belanda, meninggalkan kesedihan dan kesengsaraan. Mereka meninggalkan masa depan menuju tahun emas pada 2050, seperti yg didengungkan oleh Pemerintah sekarang. Membangun negeri tidak hanya dislogankan sebagai cita-cita, tapi harus menjadi kenyataan. Mimpin 100 tahun lalu baru bisa terealisasi setelah hasil dari dasar menjadi budaya masyarakat.
Penghidupan lestari adalah dasar kuat menggantang budaya anak negeri. Kopi di Gayo masih kokoh berdiri meski sudah mulai ada ancaman yang datang seperti cabe dan tanaman buah. Pilihan-pilihan pada kopi masih utama. Tanaman tumpang sari adalah bagian yang menjadi siasat untuk menambang penghasilan.
Ateng Super, atau Aceh Tengah Super atau janda atau TimTim pilihan-pilihan bibit kopi yang masih berkibar. Arabika yang utama dan juga Robusta yang berikutnya. Menyusul di ekor ada liberika yang mulai dikenalkan. Dari berbagai jenis kopi ini, bekembabgkan Takengon, kita pinggir Danau laut tawar berada.
Kehidupan kota meski hidup sampai pk. 20.00 malam dan dingin mulai menerpa yang diiringi sanger (susu kopi) panas dan sekedar pisang goreng membuat kota masih berkelip-kelip sampai tengah malam. Meski pertokoan yang berkembang mirip pasar bazar di Turki atau kawasan timur Tengah lain, belum tertata. Tapi modal untuk menjadi kota yang nyaman.
Takengon meski hanya seputaran “4 kali lapangan bola” patut bermimpi seperti awal kopi hadir. Warung-warung makan khas Aceh, Gayo dan Padang berjajar. Kafe kopi yang berserak di setiap sudut jalan, mobil kopi yang mangkal di sekitar Masjid Agung Rumah Takengon. Pangannan gorengan seperti pisang, ubi, tempe dan tahu mudah kali ditemukan.
Dari gambaran ini, kapasitas alam di dataran Tinggi menopang kehidupan masyarakat. Tantangan terbesar adalah deforestasi dan alih fungsi lahan Karena godaan fluktuasi harga. Berkat kopi dan tanaman pelindung, air yang mengalir ke danau tak berhenti. Harga barang kebutuhan sehari-hari, sama seperti di Jawa. Pendidikan mudah ditemui, ada sekitar 5 Perguruan Tinggiz dan salah satunya IAIN Gajah Putih.
Tiga hal penting bahwa modal penghidupan nampak berkembang. Infrasturktur dan pendanaan seperti bukan hal yg dikuwatirkan. Meski pasokan BBM nampak sedikit jadi kendala, antrian konsumen BBM selalu mengular. Tak ada Pertamax tidak penting, asal pertalite masih tersedia. Infrastruktur ini, bisa menopang Takengon lebih berkembang dengan syarat ada rekayasa yg dikembangkan. Kota tidak dibiarkan bertumbuh sendiri tanpa batasan tanpa pagar.
Persoalan rejayasa sosial, pemerintah sekarang nampaknya jauh tertinggal dari ide dan impian pemerintah Hindia-Belanda. Jalan kita tanpa pedetrian, gang-gang, lorong-lorong jalan yg tak bertanda serta tak disertai drainase, saluran pembuang. Bisa dicemaskan kalau hujan besar, genangan akan terjadi di mana-mana, meski akhirnya tumpah ke danau.
Dalam analisa penghidupan lestari (sustainable livelihood analysis), apa yang ada di Aceh Tengah, Gayo Lues dan Bener Meriah sudah lebih dari cukup, terutama Takengon yang bisa menjadi pusat. Takengon bisa bermimpi jadi Vitznau yang terletak di Danau Lucerne dan berada di kaki Pegunungan Rigi, di Swiss. Kota bersih, udara dingin dan kehidupan yang tidak hingar-bingar, tapi bergairah.
Tidak perlu Mall atau gedung besar yang megah seperti Plaza di Jakarta atau kota pinggiran Seperti Malang. Tapi cukup toko-toko kebutuhan sehari-hari di downtown yang berjajar rapi dan sampah tidak berserakan. Cukup toko-toko kecil, kafe-kafe kecil seperti di Amsterdam. Warung makan yang berhiaskan motif lokal. Sekali lagi penataan kota, transportasi kota, keamanan pejalan kaki dan saluran pembuangan air yang tidak mencemari danau dan pasar tradisional yang indah.
Modal manusia, masyarakat adalah tumpuan, pengetahuan turun-temurun tentang menanam dan memelihara kopi diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Modal sosial, mereka hidup dalam bentuk gotong royong, berbagi tenaga dan alat dalam masa panen. Dan tidak bisa ditinggalkan, modal alam, masyarakat menjaga dengan menanam pohon pelindung seperti lamtoro air tinggalan belanda, durian dan alpukat sebagai pembatas lahan antar tetangga di tepi kebun, agar tanah tidak longsor.
Perempuan Gayo
Dataran tinggi Gayo, Takengon, kopi tumbuh sebagai nadi ekonomi dan kebanggaan kolektif. Namun di balik barisan tegakan hijau itu, ada sosok-sosok perempuan yang memikul sebagian besar beban kerja, dari awal musim tanam hingga panen. Mereka menyemai biji, menyiangi gulma, memangkas dahan, memetik buah merah satu per satu, menjemur, hingga menyeleksi biji yang layak jual. Hampir semua tahap yang menuntut ketelatenan dan ketepatan rasa dilakukan oleh tangan perempuan.
Meski begitu, posisi mereka dalam sistem produksi kopi masih tersembunyi di balik nama-nama laki-laki yang tercatat sebagai kepala keluarga dan pemilik lahan. Dalam struktur administrasi pertanian, perempuan kerap disebut “membantu,” padahal kontribusinya bersifat penuh dan berkesinambungan. Ketika harga kopi turun atau cuaca ekstrem mengancam panen, perempuan jugalah yang mencari jalan keluar, menjual hasil kebun sampingan, mengolah kopi sangrai, atau menambah pendapatan lewat usaha kecil di sekitar rumah.
Dari sudut pandang gender dan keterbukaan sosial, terdapat ketimpangan. Ini menunjukkan bahwa kerja perempuan belum diakui secara formal, meski menjadi fondasi penghidupan rumah tangga. Akses terhadap pelatihan, modal, dan bantuan teknis masih lebih banyak dinikmati laki-laki, sementara beban ganda, yakni produksi dan reproduksi yang terus menempel pada perempuan. Namun, di tengah keterbatasan itu, muncul ruang-ruang baru yang dibangun oleh inisiatif mereka sendiri dalam kelompok dampingan, koperasi kecil, dan jaringan informal yang memperkuat solidaritas antarpetani perempuan.
Dari sinilah muncul bentuk inklusi sosial yang tumbuh dari bawah yakni dari refleksi ketidakpastian hidup di tanah yang rapuh oleh cuaca dan harga pasar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan penghidupan di Takengon tidak cukup diukur dari produktivitas lahan, tetapi juga dari pengakuan terhadap aktor yang merawatnya.
Program bantuan bibit dan pelindung kopi di banyak desa seperti Cemparam Jaya di Mesidah kerap gagal berkelanjutan karena tidak menyentuh ranah sosial, dalam hal ini siapa yang benar-benar merawat tanaman setelah bibit ditanam? Dalam banyak kasus, jawabannya adalah perempuan, mereka yang paling dekat dengan tanah, tetapi paling jauh dari pengambilan keputusan.
Bagi perempuan Gayo, menanam kopi bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan memperpanjang nafas kehidupan. Mereka menyebut tanah sebagai inong, ibu yang memberi makan dan tempat berpijak. Dalam pandangan ini, keberlanjutan berarti keseimbangan antara menjaga bumi, menghidupi keluarga, dan mempertahankan martabat kerja. Jika arah pembangunan ingin benar-benar berkelanjutan, maka suara perempuan di tanah kopi harus ditempatkan bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pusat dari strategi penghidupan itu sendiri.
Kopi adalah budaya
Ngopi di Takengon banyak jenisnya, yang happening adalah sanger, susu kopi Takengon. Sanger expresso, atau sanger coffee katanya. Banyak ide, banyak inovasi tawaran menum kopi. Coldbrew yg keren, yang diolah dari King Gayo. Saat Ateng Super, Ateng Janda dan Tim-tim jadi bahan baku, dan sajian begitu beragam.
Natural, semi natural, wash atau bahkan fermentasi adalah proses mengolah kopi, dari biji kopi yang disebut dengan cherry, atau glondongan di Takengon, menjadi berasan atau green bean menjadi specialty. Petani tetap saja bertani, prosesor jadilah rekan yang transparan dengan petani dan pemilik kafe penghidang kopi yang membanggakan. Kealihan menyajikan dari para barista muda, adalah keistimewaan yg hakiki.
Anak-anak muda bangga menjadi penyeduh kopi, menjadi merasa dihargai dengan kemampuan menyajikan kopi sebagai minuman yang memikat. Satu hal lagi yang penting, hospitality yang tidak dibuat-buat, senyuman penanda keramahan. Ini lah budaya negeri, sekali lagi bukan soal prestige pasaran yang elitis tetapi sikap menjaga kemampuan dan ketrampilan olah kopi yang tidak tersaingi.
Ini bekal 20 tahun yang akan datang dalam pasar karbon yang sedang berkambang. Menjaga kopi adalah menjaga kehidupan, itu yang disebut berbudaya. Bukan terian suara nyanyian, atau lengkingan orang sedang menari. Tetapi dentingan gelas saat kopi diolah atau wadah kertas menghindari kerusakan. Plastik masih berserakan, ini budaya lain yang merusak.
Penghidupan sudah berjalan, kelestarian tetap menjadi tanda tanya. Penghidupan sehari-hari adalah budaya yang berkembang. Ngopi ke warung kopi atau ke Kafe adalah bagian dari kehidupan sehari-harim itulah budaya Takengon dan warga masyarakat di Perbukitan Lauser dataran tinggi Gayo. Budaya tradisional masih perlu dipelihara, dan tidak perlu dibuat-buat. Keramahan, senyuman bapak-ibu-kakak dan penolong jangan jadi hilang.
*Pietra Widiadi, petani kopi di Desa Sumbersuko, Wagir Malang; sosiolog praktisi;Dewi Arum Nawang Wungu, fasilitator dan founder Kelas Betumbuh Malang.