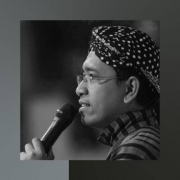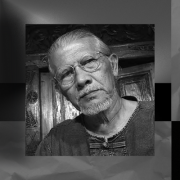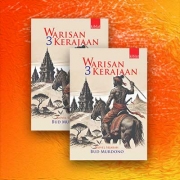Politik Pangan, Tubuh yang Sakit, dan Seni sebagai Kritik
Oleh Purnawan Andra*
Tragedi keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyentak kesadaran publik. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan yang digadang-gadang sebagai penopang kehidupan justru menelan korban? Pangan, yang mestinya menyehatkan, justru berubah menjadi racun yang melumpuhkan tubuh rakyat.
Tapi persoalan ini tidak bisa hanya dibaca dengan kacamata teknokratis seperti soal distribusi, pengawasan mutu, atau kegagalan manajemen. Di titik inilah seni memberi tawaran cara pandang lain: bahwa tubuh manusia yang sakit bukan sekadar statistik, melainkan arsip penderitaan, dan penderitaan itu bisa disuarakan kembali sebagai gerakan moral sekaligus sosial.
Michel Foucault dalam Dicipline and Punish (diterjemahkan menjadi Disiplin dan Hukum: Lahirnya Penjara, 1997) pernah mengingatkan bahwa tubuh adalah locus utama dari politik kekuasaan. Dalam tragedi MBG, tubuh yang keracunan memperlihatkan bagaimana kebijakan publik merasuk dalam daging dan darah rakyat. Janji “bergizi” yang ditelan berubah jadi kenyataan “beracun”.
Arsip Tubuh
Tubuh yang sakit, tubuh yang lemas, bahkan tubuh yang kehilangan nyawa, menjadi bukti telanjang bahwa negara gagal menjaga hidup warganya. Di sini, seni bisa mengambil alih peran dengan menghadirkan tubuh bukan sekadar sebagai objek penderitaan, melainkan subjek perlawanan.
Tari, misalnya, dapat menjelma sebagai “arsip tubuh” yang menggugat. Semisal sebuah pertunjukan yang dimulai dengan gerak bertenaga, penuh vitalitas, lalu pelan-pelan berubah menjadi tubuh yang roboh, gemetar, terkulai.
Kontras ini menghadirkan refleksi tajam tentang ironi MBG: antara imajinasi gizi yang menyehatkan dan realitas pangan yang meracuni. Koreografi demikian bukan hanya estetika, tetapi kritik sosial yang menohok. Itu hanya salah satu contoh sederhana belaka.
Karena filsuf Prancis Jacques Rancière dalam The Politics of Aesthetics (2004) menulis tentang distribution of the sensible, tentang bagaimana seni mendistribusikan apa yang dapat dirasakan dan dipikirkan dalam ruang publik. Dalam kasus MBG, pemerintah bisa saja menyajikan data angka korban yang sistematis, laporan teknis yang normatif, atau bahasa birokratis yang mensterilkan tragedi. Namun seni, melalui pertunjukan, mural, musik, atau teater, membuka distribusi rasa yang berbeda, yang bisa membuat penderitaan menjadi dekat, empati menjadi nyata, dan suara publik menemukan resonansinya.
Seni tidak berhenti pada ruang pementasan. Ia bisa menjelma menjadi koreografi sosial, sebuah gerakan bersama yang melibatkan publik luas. Aksi flash mob dengan piring kosong, mural di dinding kota bergambar meja makan yang terbalik, atau konser amal yang mengangkat kisah korban MBG, adalah contoh bagaimana seni menyeberang dari estetika menuju etika. Para ibu di Yogyakarta melakukannya di Bundaran UGM dengan panci-panci pada 26 September 2025 dan rantang-rantang (3 September 2025).
Seperti yang dikatakan dramaturg Brasil Augusto Boal lewat Theatre of the Oppressed (diterjemahkan menjadi Teater Kaum Tertindas, 1999), seni bisa menjadi latihan kebebasan di mana publik tidak lagi sekadar penonton, tetapi ikut bermain dalam drama sosial yang mereka alami.
Kekuatan seni terletak pada kemampuannya menghidupkan kembali apa yang sering dibekukan oleh politik. Tragedi MBG mungkin akan cepat dilupakan dalam pusaran isu lain jika hanya ditangani melalui angka statistik. Tetapi seni mampu menjaganya tetap terpatri di ruang kesadaran.
Musik yang lahir dari jeritan orang tua korban, atau puisi yang dibacakan di depan kantor pemerintahan, bisa lebih mengguncang kesadaran kolektif daripada seribu tabel dan lembar laporan. Dengan kata lain, seni melampaui fungsi informatif menuju fungsi afektif: ia menyalakan emosi yang mendorong aksi.
Imajinasii Alternatif
Namun seni tidak hanya berperan reaktif, merespons krisis setelah terjadi. Ia juga bisa menawarkan imajinasi alternatif. Pertunjukan teater komunitas, misalnya, bisa memvisualkan dapur rakyat yang dikelola warga sendiri, menghadirkan gagasan bahwa kedaulatan pangan tidak boleh semata diserahkan kepada birokrasi atau logika proyek politik. Di sinilah seni menautkan kritik dengan harapan, menggugat kegagalan sekaligus mengimajinasikan cara lain.
Ekonom dan filsuf India Amartya Sen dalam Development as Freedom (diterjemahkan menajdi Pembangunan dan Kebebasan, 2001) menekankan bahwa pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan pelebaran kebebasan substantif, termasuk hak untuk hidup sehat dan makan layak.
Tragedi MBG menunjukkan betapa jauh kita dari cita-cita itu. Seni, dengan logika reflektifnya, dapat membantu mengartikulasikan “hak makan” sebagai bagian dari martabat manusia, bukan sekadar proyek politik musiman. Dengan begitu, seni menegaskan kembali bahwa pangan bukan hanya soal kalori, tetapi soal keadilan.
Gerakan seni yang konsisten bisa bertransformasi menjadi gerakan sosial. Ingat bagaimana teater rakyat, lagu-lagu protes, atau mural jalanan pernah menjadi bagian dari gelombang reformasi? Begitu pula dalam kasus MBG, seni bisa menjadi bahasa moral publik untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan reformasi kebijakan pangan. Seni dalam hal ini tidak menggantikan peran hukum atau politik, tetapi menjadi katalis—penggugah kesadaran kolektif yang mendorong perubahan struktural.
Contoh konkret sudah kita lihat dalam sejarah seni Indonesia. Teater Koma kerap mengangkat persoalan sosial-politik lewat alegori, dan pesannya sampai ke publik luas. Begitu juga puisi-puisi Wiji Thukul yang sederhana tapi menghantam, membuat orang-orang biasa merasa suaranya sah untuk melawan. Dalam konteks MBG, praktik serupa bisa dilakukan dengan seniman mengolah tragedi menjadi ekspresi, warga ikut serta, dan lahirlah sebuah koreografi sosial yang menolak bungkam.
Lebih jauh lagi, seni memberi kemungkinan membaca tubuh bukan hanya sebagai penderita, tapi juga sebagai pengetahuan. Filsuf Amerika Richard Shusterman dengan gagasan somaesthetics (dalam Body Consciousness, 2008) menekankan pentingnya tubuh sebagai sumber refleksi filosofis.
Dalam tragedi MBG, tubuh-tubuh keracunan justru menjadi pengingat bahwa kesehatan tidak bisa direduksi menjadi jargon politik. Tubuh mengajarkan kebenaran yang sering diabaikan birokrasi: bahwa makan bukan hanya soal kenyang, tetapi soal hidup yang layak.
Akhirnya, seni mengajarkan bahwa tragedi MBG bukan hanya soal kegagalan teknis, tetapi kegagalan imajinasi: imajinasi negara tentang bagaimana rakyat seharusnya diberi makan. Negara mungkin membayangkan rakyat sebagai angka penerima manfaat, bukan tubuh hidup yang memerlukan perawatan penuh tanggung jawab. Seni, justru, menawarkan imajinasi yang lebih manusiawi: rakyat sebagai tubuh yang berhak sehat, sebagai jiwa yang berhak bermartabat.
Maka, seni dapat menjadi semacam meja makan alternatif: meja tempat rakyat tidak disuguhi sajian tak sehat, tetapi mencecap rasa kesadaran, empati, dan solidaritas. Dari meja makan seni inilah bisa lahir sebuah koreografi sosial baru—gerakan moral yang menuntut kebijakan pangan lebih adil, transparan, dan benar-benar bergizi. Dan mungkin, hanya lewat seni, tragedi MBG bisa dirasakan kembali bukan sekadar sebagai berita, melainkan sebagai luka yang harus dijahit bersama.
—-
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, penerima fellowship Governance & Management of Culture di Daegu Catholic University Korea Selatan.