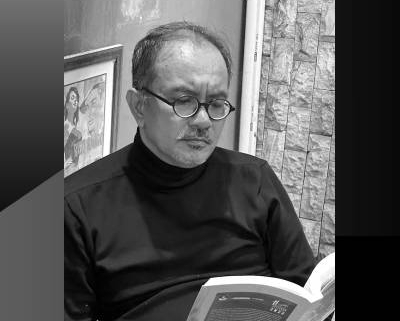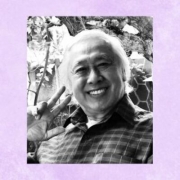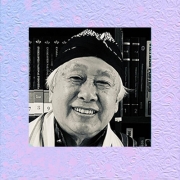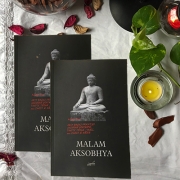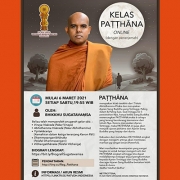“Berdamai dengan Diri Sendiri”: Terapi Jiwa Racikan Ki Ageng Suryomentaram
Oleh Tony Doludea*
Kudiarmaji adalah anak ke 55 dari 79 putra-putri Sultan Hamengku Buwono VII (1839–1921), yang berkuasa antara 1877-1921. Kudiarmaji lahir pada 20 Mei 1892 dan diberi gelar Bendoro Raden Mas (BRM). Masa muda Kudiarmaji dihabiskan di Keraton. Pada usia 18 tahun, BRM Kudiarmaji diangkat menjadi pangeran dan diberi gelar Bendoro Pangeran Haryo (BPH) Suryomentaram.
Kudiarmaji mendapat pendidikan yang baik dari pemerintah Belanda dan merupakan generasi pertama yang mengenyam pendidikan modern. Pendidikan yang bagus itu membuatnya mencintai ilmu pengetahuan. Ia belajar bahasa Belanda, Inggris dan Arab, yang kemudian membantunya mendalami ilmu pengetahuan umum, agama-agama dan Teosofi.
Ki Ageng Suryomentaram membaca buku Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer dan Jiddu Krishnamurti. Ia rajin shalat, mengaji, juga mempelajari agama Kristen.
Seusai lulus dari pendidikan dasar, karena kepiwaiannya, Kudiarmaji diijinkan mengikuti ujian masuk pegawai sipil junior (Klein Ambtenaar) dan menjadi tenaga administratitf di Residen Yogyakarta. Ia bekerja di posisi itu selama 2 tahun.
Keadaan keraton Yogyakarta di masa muda Suryomentaram itu berada pada puncak kemakmuran. Pada masa itu dibangun 17 pabrik gula dan jalur rel kereta api. Sultan diperkirakan menerima sekitar F 200.000 (Florin) dari setiap pabrik itu. Sehingga ia sangat kaya dan mendapat julukan Sultan Sugih.
Namun dalam keadaan seperti itu, setiap hari Suryomentaram muda justru merasa hanya bertemu dengan yang disembah, diminta, diperintah dan dimarahi. Ia tidak puas karena merasa belum pernah bertemu orang, “seprana seprene aku durung ketemu wong”, yang dapat membuatnya merasa sebagai manusia lumrah.
Suryomentaram merasa menjadi orang-orangan, manusia palsu, yang disamarkan oleh pakaian sutera dan perhiasan yang dikenakannya. Itu membuatnya seolah berbeda dengan orang lain. Ia merasa ada sesuatu yang kurang. Ia sudah bosan dan muak dengan kepalsuan karena slamuran (penyamaran) kehidupan di kraton.
Suryomentaram masygul, kecewa dan mengalami kecemasan mendasar (fundamental anxiety). Ia menyaksikan bahwa orang hidup itu rupanya hanya mencari semat, drajat dan kramat. Semat adalah uang, harta, kekayaan dan lainnya. Drajat adalah kehormatan, status sosial, pujian dan lain sebagainya. Kramat adalah kekuasaan dan pengaruh kepada orang lain.
Setiap orang ingin meraih ketiganya. Orang akan merasa bahagia apabila memiliki harta kekayaan, kedudukan yang tinggi dan kekuasaan serta pengaruh yang besar. Banyak orang mengartikan kebahagiaan itu adalah memiliki ketiga hal tersebut, namun apabila tidak memiliki atau ketiga hal tersebut hilang, maka ia merasa tidak bahagia, sedih.
Kegelisahannya terkait dengan kebahagiaan itu diperkuat ketika pada suatu hari Suryomentaram terkesima saat melihat para petani yang sedang bekerja di sawah. Baginya jenis pekerjaan mbungkak-mbungkuk tandur itu menyebabkan petani sakit punggung, petani mengalami penderitaan yang berat. Sementara orang-orang di Keraton yang sering ditemuinya itu malah menikmati kehidupan mewah tanpa perlu bersusah payah mendapatkannya.
Perenungan dan perjalanan menggali makna kehidupan itu semakin membuat Suryomentaram tidak puas dengan kemewahan dan belenggu aturan kerajaan. Ia mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pangeran. Namun permintaannya tersebut ditolak oleh Sultan Hamengku Buwono VII. Ia juga pernah minta persetujuan untuk dibaptis menjadi Kristen, lalu minta untuk diijinkan naik haji ke Mekkah, namun hal itupun juga ditolak oleh ayahnya.
Penderitaan batinnya makin memuncak ketika kakeknya, Patih Danurejo VI, yaitu Pangeran Cakraningrat meninggal dunia setelah diberhentikan dari jabatan Patih. Ibunya, Bendoro Raden Ayu (BRA) Retnomandoyo, putri Pangeran Cakraningrat itu dicerai oleh Sultan dan diserahkan kepadanya. Kemudian istrinya juga meninggal saat putranya baru berusia 40 hari.
Karena sudah tidak tahan lagi, diam-diam Suryomentaram meninggalkan kraton dan pergi ke Cilacap menjadi pedagang kain batik dan setagen. Ia mengganti namanya menjadi Notodongso.
Kemudian Sultan memerintahkan R.L. Mangkudigdoyo dan Bupati Cilacap, KRT Wiryodirjo untuk mencari Pangeran Suryomentaram dan membawanya kembali ke Yogyakarta. Akhirnya Suryomentaram ditemukan di Kroya sedang memborong pekerjaan menggali sumur.
Setelah kembali ke Yogyakarta, kehidupan kraton tetap mengecewakan batinnya. Suryomentaram sadar bahwa yang menyebabkan rasa kecewa dan tidak puas itu selain kedudukan sebagai pangeran, juga termasuk harta benda. Oleh karena itu ia melelang seluruh isi rumah.
Mobil dan kudanya dijual dan hasilnya diberikan kepada sopir dan perawat kudanya, pakaian-pakaian yang ada dibagi-bagikan kepada para pembantunya. Ternyata inipun tidak menghapus keresahannya.
Ia juga melakukan tirakat dan pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Namun hal inipun juga tidak menghilangkan keresahan dalam dirinya. Demikian juga ia melakukan ibadah agama dan belajar ilmu-ilmu agama, tetap saja tidak memuaskan dirinya.
Setelah Sri Sultan Hamengku Buwono VII mangkat pada 1921 dan kakak kandungnya yakni Raden Mas Sujadi diangkat sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Suryomentaram memohon lagi untuk mengundurkan diri dan berhenti sebagai pangeran, permohonannya itu dikabulkan.
Suryomentaram lalu tinggal di Desa Bringin, Salatiga dan hidup sebagai petani. Ia kemudian dikenal sebagai Ki Gede Suryomentaram atau Ki Gede Bringin. Pada 1925, setelah menduda lebih kurang 10 tahun, Suryomentaram menikah lagi. Kehidupannya yang baru ini menjadikannya lebih bebas menggali dan mencari jawaban atas keresahannya tersebut.
********
Pada suatu malam di 1927, Ki Ageng Suryomentaram membangunkan isterinya, Nyi Ageng Suryomentaram, yang sedang lelap tidur dan berkata, “Bu, aku sudah menemukan yang kucari selama ini. Aku tidak bisa mati! Ternyata yang merasa belum pernah bertemu orang, yang merasa kecewa dan tidak puas selama ini, adalah orang juga, wujudnya adalah si Suryomentaram. Diperintah kecewa, dimarahi kecewa, disembah kecewa, dimintai berkah kecewa, dianggap dukun kecewa, dianggap sakit ingatan kecewa, jadi pangeran kecewa, menjadi pedagang kecewa, menjadi petani kecewa, itulah orang yang namanya Suryomentaram, tukang kecewa, tukang tidak puas, tukang tidak kerasan, tukang bingung. Sekarang sudah ketahuan. Aku sudah dapat dan selalu bertemu orang, namanya adalah si Suryomentaram, lalu mau apa lagi? Sekarang tinggal diawasi dan dijajagi.”
Setelah dirasa menemukan jawaban atas pengertian tentang manusia, Ki Ageng semakin gencar memperdalam kebatinannya tersebut. Setelah kurang lebih 40 tahun menyelidiki alam kejiwaan dengan menggunakan hidupnya sebagai laboratorium dan dirinya sebagai kelinci percobaan. Pada suatu hari ketika sedang mengadakan ceramah di desa Sajen, Salatiga, ia jatuh sakit dan dibawa pulang ke Yogya untuk dirawat di rumah sakit.
Sewaktu di rumah sakit itu, Ki Ageng masih sempat menemukan “puncak belajar kawruh jiwa, yaitu mengetahui gagasannya sendiri”. Aku Tukang Nyawang (ATN), Aku saksi atau Aku pengamat.
Sakit Ki Ageng semakin parah, namun ia tidak memperlihatkan rasa takut mati sedikitpun. Walaupun sedang terlentang athang-athang, sedang dalam proses mretheli, tetapi Ki Ageng menyatakan, “saiki, neng kene, mretheli kaya ngene, aku gelem.” Ia telah berdamai dengan dirinya, dengan tangan terbuka ia mau menerima saat ini, di sini, keadaanya seperti ini.
Pada 18 Maret 1962, hari Minggu Pon, jam 16.45 Ki Ageng Suryomentaram wafat, dirumahnya di Jl. Rotowijayan No. 24 Yogyakarta. Ia dimakamkan di makam keluarga di desa Kanggotan, Pleret, Bantul, Yogyakarta.
Temuan terakhir Ki Ageng tersebut, yaitu “Aku Tukang Nyawang” (ATN). Aku sebagai pengamat itu merupakan puncak belajar kawruh jiwa, dengan cara menyadari pikiran (mind) sendiri. Kawruh jiwa adalah upaya untuk ngudari reribet, mengurai masalah yang rumit.
Aku adalah saksi (ATN) ini terkait dengan “Aku Kramadangsa” (AK). Kramadangsa adalah ego, yaitu kristalisasi pikiran (mind). Kramadangsa merupakan kepribadian seorang manusia, yaitu identitas, ego, subjektivitas dan sifat khas masing-masing orang.
Secara umum kramadangsa berusaha untuk meraih tiga keinginannya (karep), yaitu semat (harta), drajat (kehormatan) dan kramat (kekuasaan). Kramadangsa itu bersifat sewenang-wenang, suka menumpuk kesenangan diri sendiri dan mengabaikan bahkan menghalangi kesenangan orang lain. Karena wataknya inilah, maka muncul reribet, masalah, yaitu terjebak pada penderitaan dan kerusakan jiwa.
Penderitaan dan kerusakan jiwa terjadi karena ia terjerumus pada jurang meri dan pambegan. Meri adalah perasaan lebih rendah dari orang lain dan orang lain lebih beruntung dari dirinya, yang menciptakan iri hati. Pambegan adalah merasa lebih tinggi dari orang lain. Orang menjadi sombong dan angkuh, memandang orang lain lebih rendah dari dirinya.
Kramadangsa penuh dengan kegelisahan. Gelisah karena egonya selalu menuntut untuk menginginkan ini dan itu. Gelisan karena khawatir keinginannya itu tidak tercapai. Gelisah karena merasa dirinya menjadi orang yang paling tidak beruntung di dunia ini.
Kramadangsa terbentuk saat manusia berusia dua atau tiga tahun, masa di mana anak mulai mengenali, mengingat benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang terekam oleh indranya, lalu menanggapi peristiwa-peristiwa itu dengan perasaan senang dan sedih.
Menurut Ki Ageng, manusia harus mawas diri, supaya karep itu tidak memimpin dirinya. Jika orang dapat mengatur karep, maka ia akan berbahagia (bungah) dalam hidup. Ini disebut nyawang karep, mengawasi keinginannya sendiri. Mawas diri adalah dengan cara nyawang karep.
Mawas diri adalah pengawikan pribadi (pengetahuan diri sendiri), yaitu kemampuan seseorang untuk memahami keinginan sendiri dan mampu melihat gerak-gerik rasa. Diri sendiri yang mampu merasakan apa saja, memikirkan apa saja dan menginginkan apa saja.
Semakin jelas orang memahami dan memenuhi keingingannya itu, maka semakin besar peluangnya untuk bahagia. Seperti seorang nahkoda dan karep adalah kapalnya, yang sedang berlayar menuju bungah (kebahagiaan).
Kebahagiaan itu datang silih berganti bersama dengan penderitaan. Maka tidak ada satu objek pun yang layak yang dicari dan diperjuangkan mati-matian atau juga ditolak mati-matian.
Karena saat semat, derajat dan kramat seseorang bertambah, maka bungah menjadi mulur (mengembang). Sebaliknya apabila ketiganya berkurang maka bungah menjadi mungkret (menyusut). Maka orang harus nyawang karep, mengawasi keinginannya itu.
Mengawasi keinginan berarti memahami lebih dalam apakah yang ia miliki sudah cukup membuatnya bahagia. Jangan sampai ia terlena oleh karep, sehingga ia tidak mengenal kebahagiaan sejati. Karena pada dasarnya, sebanyak apapun semat, derajat dan kramat yang dimiliki seseorang, manusia cenderung tidak pernah puas olehnya.
Menurut Ki Ageng, orang yang weruh (tahu) karep (keinginan), yaitu weruh jika karep bungah, maka ia senang. Weruh jika karep susah, maka ia tetap senang dan tidak susah. Mengerti dan memahami jika karep itu tidak dapat diubah, maka ia lalu memisahkan diri dari karep.
Melalui mawas diri orang dapat menjadikan ketiga jenis karep itu dapat memotivasinya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Melalui memahami diri sendiri orang juga akan lebih mudah memahami orang lain dan tidak akan merasa diri paling benar.
********
Mawas diri (nyawang karep) adalah merenung untuk menemukan kelebihan dan kekurangannya, memperbaiki kekurangan dan mengubur keinginan-keinginan yang membawanya kepada kesedihan, kekhawatiran, penyesalan, iri, sombong dan malu.
Si pengawas ini mengawasi keinginannya sendiri yang sebentar mulur, sebentar mungkret, sebentar mulur, sebentar mungkret dengan rasa sebentar senang, sebentar susah, sebentar senang, sebentar susah.
“Aku kuwi tukang nyawang karep”. Mawas diri merupakan usaha menjernihkan pikiran dan penghayatan perasaan seseorang, untuk mengerti tanpa memberi penilaian terhadap hal-hal yang diamati dalam perenungannya itu.
Aku adalah seorang pengawas yang mengawasi tanpa perasaan suka maupun benci, tanpa menyalahkan maupun berharap. Aku tidak mengatur, tidak memaksa, tidak mencintai dan tidak mengarahkan karep. Maka orang akan sadar, “Aku mengawasi keinginan, aku senang, aku bahagia.” Ia kemudian sadar bahwa “Itu bukanlah aku.”
Melalui mengenali “Aku yang mengamati” itu, orang menyadari bahwa diri manusia sejatinya itu bukanlah “Aku kramadangsa“. Tetapi “saksi” bagi rasa-rasa yang sedang dialami. Semakin orang terlatih menyadari hakikat kramadangsa, maka potensi kesadarannya untuk menjangkau dimensi Menungso Tanpo Tenger, manusia tanpa ciri, tanpa sifat, tanpa identitas dan tanpa predikasi itu semakin besar.
Secara sistematis proses nyawang karep itu dapat dijelaskan dalam 9 langkah berikut:
1. Mengerti bahwa segala hal yang ada di muka bumi ini tidak ada suatupun yang pantas dikejar atau dihindari mati-matian. Sebab apa yang dikejar mati-matian tidak akan membuatnya bahagia sepenuhnya, melainkan hanya mendapatkan kesenangan sesaat. Sebaliknya, apa yang ia hindari mati-matian, tidak akan membuatnya sengsara selamanya, melainkan hanya susah sementara.
2. Mengerti bahwa manusia adalah karep, hasrat, kehendak, dorongan dan harapan, yang dicari dan dihindari mati-matian. Manusia mengira jika keinginannya tercapai dan harapannya terwujud, maka ia akan merasa senang selamanya. Sebaliknya jika keinginan tidak terwujud maka ia akan tenggelam dalam petaka kehidupan selamanya. Perasaan seperti itu akan selalu mengiringi kehidupan manusia.
3. Mengerti bahwa bungah dan susah adalah rasa hidup. Bungah adalah senang, gembira, lega, marem dan sifat-sifat ceria lainnya. Sedangkan susah adalah prihatin, gela, kecewa, marah, malu dan sifat-sifat terpuruk lainnya. Hidup manusia akan selalu diiringi rasa bungah-susah yang akan selalu mulur-mungkret sampai akhir hayatnya.
4. Mengerti jalan kerja keinginan (karep) manusia. Keinginan orang hidup adalah mencari semat, drajat dan kramat. Semat adalah kekayaan, uang dan harta. Drajat adalah kedudukan dan status sosial. Kramat adalah kekuasaan dan pengaruh.
5. Mengerti karep adalah sumber hidup manusia yang paling mendasar, sifatnya mulur-mungkret, yang melahirkan rasa bungah-susah. Semua manusia merasakan hal tersebut, semuanya sama. Orang kaya dan orang miskin, raja dan buruh, pengusaha restoran dan tukang gorengan sama-sama mempunyai rasa bungah-susah dalam hidupnya.
6. Jika orang sudah mengerti bahwa rasa hidup manusia adalah sama, yaitu kadang bungah kadang susah, maka manusia akan merdeka dari rasa meri dan pambegan. Meri adalah adalah perasaan iri. Sedangkan pambegan adalah perasaan sombong. Meri dan pambegan ini yang menyebabkan rasa beda (membeda-bedakan). Karena dua hal itu, orang akan salah mengerti hal-hal dan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Karena pemahaman yang salah dan ruwet tersebut orang dapat bertindak tanpa nalar, yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Sebaliknya jika mengerti bahwa sifat rasa hidup manusia adalah sama, ia akan selamat dari rasa meri dan pambegan, yang akan membuat hidupnya menjadi tentram. Tentram dan damai, tidak terombang-ambing oleh keinginannya sendiri.
7. Jika orang sudah mengerti bahwa sifat karep itu langgeng, maka ia bisa keluar dari jurang getun dan sumelang. Getun adalah perasaan susah terhadap hal yang sudah terjadi. Sumelang adalah perasaan khawatir atas apa yang akan terjadi, yaitu rasa takut. Getun-sumelang ini menyebabkan manusia kemrungsung (gegabah) dan semplah (putus asa), yang menyebabkan ia bertindak tanpa nalar.
8. Jika orang sudah mengerti bahwa karep itu langgeng dan sifat karep adalah bungah-susah, maka dalam hidupnya tidak akan ada hal yang perlu ditakuti lagi. Susah tidak dapat dihindari, namun tidak akan ada satu kesusahan pun yang tidak bisa dilewati. Sebaliknya, bungah adalah hal yang paling dicari dan dikejar manusia, namun tidak akan ada satu kebahagian pun yang akan dijalani tanpa rasa susah.
9. Jika orang sudah mengerti langkah-langkah tersebut, maka ia akan menjadi pengawas karep, sehingga ia dapat mengendalikan karep. Jika karep sedang menuntut untuk dipenuhi, maka sang pengawas karep akan berdialog, bahwa apa yang diinginkannya itu belum tentu terwujud. Jadi tidak perlu khawatir atau pun menyesal, walau bagaimana pun dirinya akan tetap dan selalu susah dan senang. Hidup akan terus berjalan tanpa harus ada yang ditakuti dan dikhawatirkan.
Jika sembilan langkah itu sudah dijalani dengan baik, maka orang akan merdeka dari dirinya sendiri, dari egonya yang selalu menuntut untuk hidup nyaman dengan patokan semat, drajat dan kramat, tanpa memberi ruang yang layak untuk kehidupan yang sebenarnya.
Manusia yang sudah dapat mengendalikan dan berdialog dengan dirinya sendiri adalah manusia yang sudah dapat melahirkan aku sejati. Aku yang damai dengan kehidupan apapun, aku yang tentram dengan berbagai kondisi kehidupan. Ki Ageng menyebutnya sebagai Menungso Tanpo Tenger (manusia tanpa ciri).
Menungso tanpo tenger adalah puncak fase kehidupan manusia, di mana ia sudah mampu membebaskan dirinya dari gejolak ego yang selalu menuntut untuk diperhatikan secara lebih.
Manusia tanpa ciri adalah orang merdeka yang tidak diikat oleh ego (kramadangsa), predikat dan identitas apa pun yang melekat pada dirinya, termasuk kehendak untuk dikuasai maupun menguasai.
Melalui nyawang karep atau pengawikan pribadi (pemahaman tentang diri), orang akan lebih mudah mempraktikkan strategi mulur-mungkret (mengembang-mengempis) untuk menentukan waktu yang tepat menuruti karep yang mulur dan karep yang mungkret.
Membatasi kebutuhan hidup agar tidak berlebihan merupakan usaha untuk tidak terjebak pada dorongan yang sekadar memuaskan keinginan pribadi. Kebutuhan berbeda dengan keinginan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang mendasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan tidak mutlak dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia.
Bila hal ini sudah dimengerti, orang akan keluar dari penderitaan neraka iri-sombong dan sesal-khawatir, yang menyebabkan prihatin, celaka. Maka ia masuk dalam surga tenteram dan tabah yang membuat orang bersuka-cita dan bahagia.
Jika kebahagiaan saat sudah didapatkan, maka tidak ada keinginan lagi. Jadi bahagia itu adalah: “Sekarang di sini, begini, aku mau.” Demikian rasa aku itu bahagia dan abadi. Karena itu, di mana saja, kapan saja, bagaimana saja, orang itu berbahagia.
Kebahagiaan sejati adalah hidup biasa-biasa saja, sewajarnya. Hidup sewajarnya itu tidak kekurangan, tidak juga berlebihan. Hidup sewajarnya itu adalah memenuhi keinginannya terkait dengan semat, drajat dan kramat itu secara: 1. Sakepena’e (senyamannya), 2. Sabutuhe (sekadar memenuhi kebutuhan), 3. Saperlune (sesuai keperluan), 4. Sacukupe (secukupnya), 5. Samestine (semestinya) dan 6. Sa’benere (sebenarnya).
Sabutuhe, saperlune dan sacukupe artinya membatasi kebutuhan hidupnya tidak sampai berlebihan. Sakepenake yaitu tidak memaksakan diri (ngoyo, ngongso). Sabenere dan samestine artinya dilakukan menurut jalan lurus, benar, adil dan susila.
Tidak mencari dan mengejar semat, drajat dan kramat mati-matian, juga tidak menolaknya mati-matian. Dengan demikian orang akan hidup tenang, tentram dan damai.
Jika seseorang sudah mampu menerima segala hal, segala peristiwa dan kejadian secara ikhlas, menyadari bahwa bungah-susah itu bersifat mulur-mungkret. Maka ia akan sentosa dan dipenuhi oleh ucapan syukur.
—-
Kepustakaan
Adimassana, J. B. Ki Ageng Suryomentaram tentang Citra Manusia. Kanisius, Yogyakarta, 1986.
Afthonul, Afif (ed.). Matahari Dari Mataram. Menyelami Spiritualitas Jawa Rasional Ki Ageng Suryomentaram. Kepik, Depok, 2012.
Fikriono, Muhaji. Puncak Makrifat Jawa: Pengembaraan Batin Ki Ageng Suryomentaram. Noura Books, Jakarta, 2012.
Fikriono, Muhaji. Kawruh Jiwa. Warisan Spiritual Ki Ageng Suryomentaram. Javanica, Tangerang Selatan, 2018.
Sarwiyono, Ratih. Ki Ageng Suryomentaram. Sang Plato dari Jawa. Cemerlang Publishing, Yogyakarta, 2007.
Suryomentaram, Ki Ageng. Ajaran-ajaran Ki Ageng Suryomentaram Jilid 1. Inti Idayu Press, Jakarta, 1985.
Suryomentaram, Ki Ageng. Ajaran-ajaran Ki Ageng Suryomentaram Jilid 2. Inti Idayu Press, Jakarta, 1985.
Suryomentaram, Ki Ageng. Ajaran-Ajaran Ki Ageng Suryomentaram Jilid 3. Inti Idayu Press, Jakarta, 1986.
Teddy Rusdy, Sri. Epistemologi Ki Ageng Suryomentaram. Yayasan Kertagama, Jakarta, 2014.
Wintala Achmad, Sri. Ilmu Bahagia Ki Ageng Suryomentaram.Araska, Yogyakarta, 2020.
—–
*Toni Doludea, Peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indo.