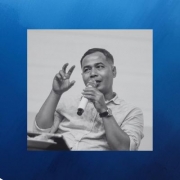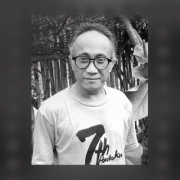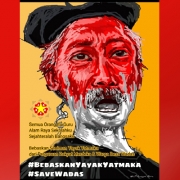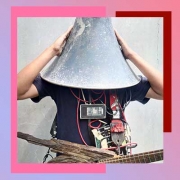Rumah Makna
Oleh Prof. Dr. Mudji Sutrisno SJ*
I.
Kebudayaan, ketika dibaca oleh manusia atau kita sebagai pelaku pemberi makna (baca: the signifying actor), ‘harus’ disadari melalui 4 tahap membacanya agar paham artinya.
Tahap pertama, kita baca dari sumber dan oasenya. Tahap ini mengajak mata baca kita dengan kesadaran dari bahasa logis ke tulis serta semiotis (tanda). Tahap pertama ini kebudayaan diungkap dalam kamus yang menuliskannya dan mewacanakan realitas dunia dimana manusia hidup dan merajutnya. (Mudji Sutrisno SJ., ‘Membaca Rupa Wajah Kebudayaan’, Kanisius 2014, hal 10 dan seterusnya). Untuk memahami bahasa kebudayaan disini, orang harus masuk dari dalam dan hidup di dalamnya termasuk mengenali makna dan simbol-simbolnya agar bisa membaca hati kebudayaan dalam tahap bahasa ini. Inilah rumah makna dalam bahasa kamus, simbol-simbol dan tanda-tanda makna yang kita kenal sebagai semiotika.
Yang kedua, kebudayaan oleh masyarakat pendukungnya ditradisikan melalui peribahasa, pepatah, pantun, gurindam. Maka membacanya pada tahap ini adalah menangkap makna dan memahaminya dalam tradisi dongeng kebijaksanaan hidup yang dibahasakan dalam mitos, ritual, upacara-upacara tahap-tahap penting kehidupan (rites of life passages), ingatan kolektif dalam saga kisah-kisah pelajaran kehidupan. Ia termuat pula dalam adat kebiasaan dan bahasa tanda serta salam uluk sambut penghormatan. Tahap baca ini membutuhkan pemahaman dan pengenalan yang tidak hanya rasional tetapi intuitif untuk masuk memahami episitemnya (local knowledge) alias rumah maknanya.
Ketika kebudayaan mulai dilembagakan karena manusia adalah makhluk yang berbudi, yang membuat sistem sebagai penataan apa yang diolahnya (baca: sistem adalah a rational ordering of something) maka pengertian struktur menjadi tempat ‘makna’ sistemik kebudayaan. Artinya, kebudayaan tahap ini dibaca sebagai pemantapan makna-nya dalam sistem kemasyarakatan yang memuat (memaktub) pengaturan hidup bersama agar rukun dan saling menghormati, tolong menolong untuk terus melangsungkan kehidupan. Disini makna mempunyai ‘rumah’ berjenjang bertahap-tahapan dari sesuatu yang organik menjadi sesuatu yang organisasi. Inilah langkah ketiga dalam membaca kebudayaan dalam rumah maknanya.
Yang keempat, tahapan yang menarikan kebudayaan dalam seni tari, menyanyikan kehidupan dalam musik. Lihatlah gerak-gerak daya hidup ditarikan dalam rancak dengan gendang. Lihatlah hembus angin, air mengalir ditarikan dalam irama gerak tubuh yang bersyukur, yang memuji deras hujan sebagai berkah dari langit ke bumi. Namun amati pula gelegar gendang, teriak lengking yang kagum sekaligus gentar karena merasakan berkah subur tanah vulkanik Nusantara, namun sekaligus harus menghormati letusan gelegar magmanya! Kebudayaan ditahapan ini harus dibacakan pula dalam torehan di gua-gua rumah alami ditembok-temboknya yang maknanya terus menerus harus dibaca lagi dan lagi untuk menemukan makna peristiwa syukurkah? Atau kisah perburuan dan pergulatan demi kelangsungan hidup?
Ketika aksara dicipta dan terus menerus secara kreatif menjadi tulisan, dan tulisan menjadi tulisan sastrawi, kita disadarkan ada perjalanan dari menaruh kisah tuturan dalam kelisanan menuju pengisahan dalam tulisan. Lalu dirumuskanlah kisah ‘pahlawan’ dan cita-cita hidup baik, selaras alam bumi dan selaras langit dalam etos laku sujud ke ‘langit’ sekaligus laku hidup selaras semesta bumi bersama penghuni-penghuninya. Disini, bacaan kebudayaan membutuhkan proses membangun rumah makna dengan batu penjuru nilai (baca: sebagai yang berharga dan bermakna dalam hidup ini). Pembacaan butuh mata baca intuisi religius etis terhadap tingkah laku harmonis kosmis (dalam semesta) dan tindakan-tindakan yang dipilih untuk dihayati oleh komunitas. Dibutuhkan pula pemahaman estetis religius dalam proses membaca dengan intuisi keindahan dan yang suci dari kehidupan.
Yang terakhir, kita membaca kebudayaan sebagai acuan cita-cita dan oase dari sapa yang dipandang berharga. Kebudayaan pada tahap ini mesti dibaca dari norma, aturan tingkah laku, pantangan, pemali serta tabu yang mengatur hubungan bersama anggota-anggota komunitas namun juga ritual kelahiran, kematangan, perkawinan dan kematian. Dari semesta makna yang berumah di alam semesta, menuju semesta ‘gua’, semesta bumi. Dalam bumi yang bertanah sekaligus dirajut direkatkan dan dihubungkan oleh semesta air maka makna hidup sekaligus berumah di semesta air dan semesta bumi. Sebuah kepulauan Nusantara semayam makna kepulauan dimana bentang samudra air menaruh pulau-pulau di keluasan rahim samudra.
II.
Mengenali kebudayaan dalam semesta makna ya rumah maknanya untuk proses sejarah dari Nusantara menjadi Indonesia akan menggugatkan pertanyaan kritis kita penghuni dengan: mengapa bacaan kita kacau baca atau salah baca apalagi buta baca?
Pertama, proses membaca adalah proses kerja kesadaran untuk mau membaca makna dalam ‘rumah’nya atau semestanya. Ketika dari pendidikan kita tidak diakrabkan dan tidak diajari serta dilatih untuk mencintai semesta air dan rumah makna bumi yang bergunung-gunung, sawah serta vulkanik, maka kita tenggelam saat di laut. Kita memaki-maki letusan gunung-gunung berapi, padahal merekalah pemberi kesuburan tanah Nusantara hingga pada jamannya sumber beras dan sumber rempah-rempah. Ketika edukasi yang semestinya kultural mengajak kita menghayati modernitas rasional dengan cerdas untuk tidak merebut hati dan merampas intuisi pemuliaan hidup karena terus menerus sepihak diisi rasionalitas instrumental (budi yang memperalat dan memperlakukan segala sebagai alat dan melulu sarana). Padahal intuisi pencapaian makna merayakan, memuliakan semesta laut dan rumah bumi sudah kita ketahui tersimpan dalam harta pusaka ditahapan-tahapan 1-5 kebudayaan. Namun mereka merana menjadi artefak, menjadi relief batu mati yang menanti lebih banyak lagi guru-guru kehidupan untuk menghidupkan makna-makna prasasti, candi-candi melalui pengembangan arkeologi, antropologis, paleontologi, kepurbakalaan yang kini berhadap-hadapan dengan teknologisasi, ekonomisasi, positifisasi serta materialisasi ilmu-ilmu modern.
Kedua, membaca proses berumahnya makna dalam kebudayaan membutuhkan kebangkitan kita dari lupa sejarah dan tidur sejarah. Sejarahlah yang mendidik kesadaran kita sebagai pelaku pemberi makna hidup dalam prosesnya dari Nusantara klasik di tiap kearifan-kearifan lokal sejarah-sejarah bhineka Nusantara lalu jaman pra-Indonesia dilanjutkan dengan Indonesia yang ika. Disini rumusan rumah makna dengan bahasa undang-undang adalah puncak-puncak kebudayaan daerah yang membuat rumah Indonesia. Segeralah disadarkan bahwa tiap sejarah ‘kecil’ adalah pencipta dan perawat-perawat yang sah untuk life wisdom sukunya, identitas-identitasnya pra-Indonesia. Sehingga, tiap sumbangan tersuci, terbaik dan terindah serta terbenar dari cerlang budaya hidup lokal merupakan perekat dan perajut keIndonesiaan dari bhineka ke ika saat syukur atas proklamasi merdekanya RI disadari karena rahmat berkah Tuhan Yang Maha Esa.
III.
Lupa sejarah atau mininya ingatan sejarah akan membuat kita susah bersyukur dan terus mudah berkelahi saling mengalahkan dan menyalahkan akibat dan hasil idap ‘penyakit’ virus pecah belah kolonialisme yang membuat mentalitas bangsa pasca kolonial ini susah menghargai dan menghormati sesama anak negeri kalau mereka memberi arti dan makna yang mensejahterakan bagi sesama. Kita orang-orang bermental pasca kolonial selalu berperilaku ‘mengecilkan’ sesama dan membesarkan diri sendiri lalu bermimpi jago kandang seperti pepatah moyang berbilang katak dalam tempurung dan bagi cebol merindukan bulan.
Lupa sejarah inilah menjadi salah satu ‘pingsan kita’ sehingga harus bangun menyadari bahwa Nusantara sudah secara kebudayaan itu estetis religius manakala memproklamasikan kemerdekaan RI. Estetis, karena kita dalam bawah sadar dan sadarnya selalu berusaha menghayati hidup dalam gendang tari, rancak derap langkah, dan nyanyi hati. Religius, dalam arti Proklamasi merdekanya RI didasarkan atas syukur terhadap bekerjanya rahmat dan berkat Tuhan. Lihatlah itu di mukadimah Undang-undang Dasar, bacalah maknanya di pernyataan kemerdekaan bangsa Nusantara yang majemuk menjadi Indonesia yang bersatu , berdaulat dan berkeadaban.
—–
*Guru Besar STF Driyarkara, Dosen Pasca Sarjana UI, Budayawan.