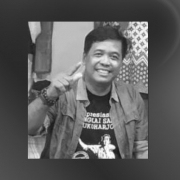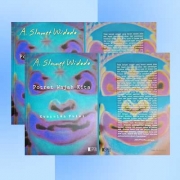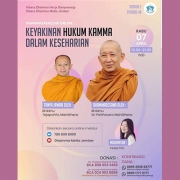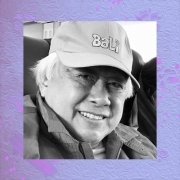Bendera Bajak Laut dan Tafsir Ulang Nasionalisme Kita
Oleh Purnawan Andra*
Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena visual muncul di sejumlah ruang publik dan media sosial. Bendera bajak laut dari serial One Piece, lengkap dengan lambang tengkorak dan tulang bersilang, berkibar menggantikan bendera Merah Putih. Hal ini tentu saja menimbulkan reaksi pro-kontra, tidak hanya di ruang maya, tapi juga menimbulkan respon aparat keamanan negara di lapangan.
Dalam suasana yang semestinya didominasi nuansa patriotik dan simbol-simbol kenegaraan, kehadiran panji fiksi ini menjadi penanda penting. Ia tidak hanya mencerminkan kegandrungan budaya populer, tetapi juga membuka ruang bagi pembacaan simbolik yang lebih dalam tentang bagaimana generasi muda memaknai nasionalisme hari ini.
Konstruksi Simbol
Secara historis dan antropologis, bendera Merah Putih telah menjadi penanda penting dalam konstruksi identitas bangsa Indonesia. Ia bukan hanya lambang konstitusional, tetapi juga mengandung lapisan-lapisan makna yang berasal dari praktik budaya lokal.
Dalam banyak kebudayaan Nusantara, merah dan putih muncul sebagai warna sakral dalam ritus kesuburan, makanan dalam ritus komunal seperti jenang abang-putih, serta dalam ikonografi kesenian seperti topeng Panji dan Klana. Dua warna ini mencerminkan paradoks dan harmoni: antara bumi dan langit, darah dan susu, kehidupan dan kematian.
Namun sebagaimana ditegaskan Victor Turner dalam kajian simbolik ritual, simbol hanya efektif sejauh ia dapat menjaga relevansinya dalam kehidupan sosial yang terus berubah. Ketika simbol tidak lagi merefleksikan pengalaman kolektif, ia akan kehilangan daya transformasinya. Hal ini tampaknya terjadi pada Merah Putih hari ini. Bukan karena simbolnya melemah, tetapi karena artikulasi nilai yang melekat padanya tidak terdistribusi secara adil dan nyata dalam keseharian warganya.
Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari One Piece dapat dibaca sebagai bentuk counter-symbolic expression. Dalam perspektif cultural studies, khususnya melalui kerangka pemikiran Stuart Hall, simbol tidak bersifat tetap, melainkan terbuka untuk negosiasi, pergeseran, bahkan resistensi. Apa yang dilakukan sebagian anak muda bukanlah bentuk anarki simbolik, melainkan reading against the grain terhadap narasi dominan nasionalisme yang dianggap kehilangan vitalitasnya.
Simbol bajak laut dalam One Piece tidak bisa dipahami sebatas visualisasi tengkorak. Dalam narasi serial tersebut, bajak laut Luffy dan krunya digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang melawan sistem hegemonik dunia seperti pemerintahan korup, hierarki sosial yang tidak adil, dan monopoli kekuasaan oleh segelintir elite. Simbol tengkorak, dalam hal ini, justru menjadi emblem perlawanan terhadap tatanan represif. Ia merangkum nilai kebebasan, kesetaraan, solidaritas, dan keberanian untuk menyimpang demi kebenaran.
Ketika simbol negara tidak lagi mampu menampung aspirasi akan nilai-nilai itu, maka simbol alternatif pun hadir, bukan untuk menggantikan, tetapi untuk mengingatkan. Michel de Certeau dalam The Practice of Everyday Life (1984) menunjukkan bahwa masyarakat kerap menciptakan “taktik” simbolik untuk mengintervensi narasi dominan. Pengibaran panji bajak laut dalam konteks HUT RI dapat dimaknai sebagai taktik diskursif generasi baru untuk menyampaikan kegelisahan yang tak tertampung dalam saluran formal.
Delegitimasi Nasionalisme
Nasionalisme, dalam pandangan Benedict Anderson, dibayangkan sebagai komunitas politis yang bersifat imajiner, di mana ia hidup sejauh warganya percaya dan menghayati keberadaannya. Dalam kerangka ini, nasionalisme tidak bisa hanya dilestarikan melalui seremoni dan regulasi simbolik. Ia perlu dikokohkan melalui penghayatan yang terus-menerus atas nilai-nilai yang mendasarinya yaitu keadilan, kebenaran, kesetaraan, dan solidaritas.
Ketika nilai-nilai tersebut tak terwujud dalam kebijakan publik, ketika hukum dimanipulasi, representasi politik disumbat, dan ketimpangan sosial-ekonomi memburuk, maka nasionalisme akan mengalami delegitimasi dari dalam. Generasi muda yang lahir dalam era digital, dengan literasi global dan sensibilitas kritis, tidak bisa lagi diyakinkan dengan narasi normatif semata. Mereka menuntut koherensi antara simbol dan realitas.
Oleh karenanya, pengibaran bendera bajak laut dalam konteks ini bukanlah penolakan terhadap Merah Putih, tetapi sebuah gestur semiotik untuk menanyakan di manakah letak keberanian dan kesucian yang diwakili warna-warna itu dalam praktik kenegaraan hari ini?
Dengannya, kita bisa membaca bahwa simbol bajak laut bukanlah simbol nihilistik. Ia justru mengusung cita-cita alternatif. Di dalam dunia fiksi One Piece, bajak laut tidak identik dengan kriminalitas, melainkan dengan mereka yang menolak tunduk pada sistem korup demi mencari makna sejati hidup. Jika generasi muda kita lebih merasa terwakili oleh panji fiksi ini, barangkali bukan karena mereka kehilangan nasionalisme, melainkan karena mereka merasa nasionalisme yang ada tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang mereka yakini.
Dengan demikian, kita seharusnya tidak tergesa memaknai fenomena ini sebagai ancaman. Sebaliknya, ia bisa menjadi refleksi penting tentang bagaimana membangun kembali kepercayaan simbolik dan afektif terhadap institusi kebangsaan. Bendera negara tidak akan digantikan oleh panji bajak laut, selama bendera itu benar-benar menjadi cermin dari nilai yang diperjuangkan.
Delapan puluh tahun setelah proklamasi, Indonesia perlu mengevaluasi bagaimana simbol-simbol kenegaraan hidup di tengah rakyatnya. Simbol bukan sekadar peraturan atau atribut seremonial, tetapi konstruksi sosial yang menuntut kejujuran kolektif. Bila Merah Putih hendak terus dikibarkan dengan kebanggaan, maka negara harus memastikan bahwa ia benar-benar menjadi perwujudan dari keberanian melawan ketidakadilan dan kesucian dalam niat membangun kehidupan bersama.
Kita harus memastikan agar bendera di ruang-ruang kerja tidak lagi justru menjadi saksi bagi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar bendera di perbatasan tak menjadi saksi terjadinya pengerukan atau eksploitasi SDA bangsa kita demi kepentingan segelintir orang/kelompok. Agar bendera yang terjahit dalam seragam tak menjadi saksi penindasan dan penjajahan sesama anak bangsa. Agar bendera di ruang-ruang kelas tak jadi saksi meredupnya kebanggaan sebagai orang Indonesia. Agar bendera di mana pun berada tetap jadi saksi tegaknya hakikat kebangsaan yang sesungguhnya (Firman Noor, 2021).
Tugas kita bukan mengecam simbol alternatif, melainkan merevitalisasi makna simbol nasional kita. Agar Merah Putih kembali hidup—bukan karena diwajibkan, tetapi karena dipercaya.
—-
*Purnawan Andra, alumnus Governance & Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan.