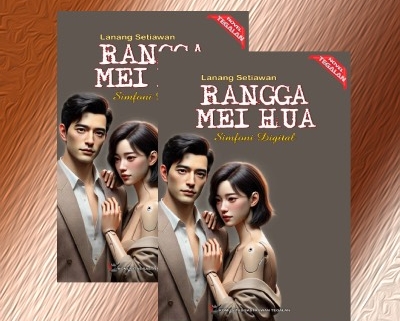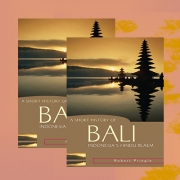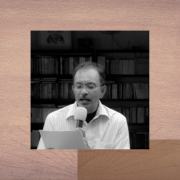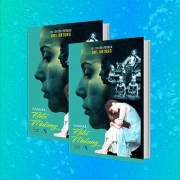Rangga Mei Hua: Ketika Luka Bertemu Teknologi

Oleh Kang Du
Tulisan singkat ini membedah novel Rangga Mei Hua: Simfoni Digital karya Lanang Setiawan dalam konteks teori simulakra Jean Baudrillard, posthumanisme Katherine Hayles, serta pendekatan intertekstual terhadap mitos Pygmalion dan film Her karya Spike Jonze. Novel ini ditafsirkan sebagai refleksi atas krisis identitas manusia di tengah era kecerdasan buatan. Melalui tokoh robot bernama Mei Hua dan relasi afektifnya dengan Rangga, novel ini mengungkap paradoks teknologi: kenyamanan yang mematikan emosi manusia. Dengan memasukkan bahasa lokal Tegal dan spiritualitas Jawa, Lanang membangun dialektika antara modernitas dan tradisi, teknologi dan transendensi. Artikel ini menunjukkan bahwa sastra tetap relevan sebagai ruang kontemplatif dalam dunia yang terdigitalisasi.
Realitas, Simulakra, dan Hiperrealitas
Jean Baudrillard dalam Simulacra and Simulation (1994) menjelaskan bahwa simulakra adalah realitas buatan yang menggantikan kenyataan. Mei Hua bukan hanya simulasi perempuan, tetapi entitas yang diterima lebih nyata daripada manusia asli. Relasi antara Rangga dan Mei Hua menggambarkan hiperrealitas—sebuah kenyataan palsu yang dianggap lebih sahih dari realitas itu sendiri. Kecanggihan Mei Hua menutupi kekosongan emosional yang semakin dalam. Novel ini mengajak kita menyoal kembali batas antara kenyataan dan tiruannya.
Kisah Rangga dan Mei Hua dapat dibaca sebagai kelanjutan dari mitos Pygmalion—pematung yang jatuh cinta pada patung buatannya sendiri. Lanang Setiawan memperbarui mitos ini ke dalam konteks teknologi digital. Dalam film Her (2013), Spike Jonze menampilkan seorang pria yang mencintai AI bernama Samantha. Namun, Rangga Mei Hua melampaui itu: cinta Rangga membawa pada krisis spiritual. Cinta yang tak bisa dibalas Mei Hua justru menumbuhkan kesadaran manusiawi dalam diri Rangga.
Posthumanisme dan Dekonstruksi Identitas
Katherine Hayles dalam How We Became Posthuman (1999) menyebut manusia posthuman sebagai entitas material-informasional. Mei Hua adalah representasi dari posthumanisme: ia canggih, rasional, tetapi tak mampu mengalami luka. Ironisnya, justru kehadiran robot ini membuat Rangga menyadari kerentanannya sebagai manusia. Relasi manusia-mesin dalam novel ini menjadi wahana dekonstruksi identitas dan eksistensi.
Bahasa Lokal sebagai Bentuk Resistensi Emosional
Lanang Setiawan memasukkan dialog dalam bahasa Tegal untuk mengukuhkan keaslian emosi tokohnya. Dalam satu adegan, Rangga berkata:
“Sajané, éntuk-éntukan kuwé sing nggawé kangen. Lha Hua ora nduwé éntuk.”
Bahasa lokal ini menolak universalitas komunikasi digital yang datar dan netral. Ia menjadi bentuk perlawanan terhadap pereduksian emosi manusia ke dalam bentuk emoji atau reaksi cepat dalam percakapan daring. Bahasa daerah menjadi cermin keaslian rasa.
Struktur Doa dan Kesadaran Transendental
Puncak novel ini adalah ketika Rangga melakukan refleksi spiritual melalui doa. Struktur doa dalam novel ini bukan sekadar religiusitas, tetapi momen transformasi. Doa Rangga menjadi jalan keluar dari labirin digital dan simulasi emosional. Dalam falsafah Jawa, tindakan ini selaras dengan laku sumeleh dan manembah. Doa menjembatani kembali manusia pada dirinya sendiri dan pada Tuhan.
Penutup
Novel Rangga Mei Hua adalah kritik halus terhadap zaman yang terlalu percaya pada teknologi. Di tengah maraknya otomatisasi dan AI, Lanang mengingatkan bahwa manusia tetap butuh luka, bahasa ibu, dan doa untuk memahami dirinya. Sastra, dalam kerangka ini, menjadi pertahanan terakhir manusia dari ancaman dehumanisasi digital. (*)
——
Daftar Pustaka
Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. University of Michigan Press, 1994.
Hayles, N. Katherine. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. University of Chicago Press, 1999.
Jonze, Spike. Her. Annapurna Pictures, 2013.
Setiawan, Lanang. Rangga Mei Hua: Simfoni Digital. (Tahun terbit sesuai sumber asli).
*Kang Du, Pimred Panturapost.com