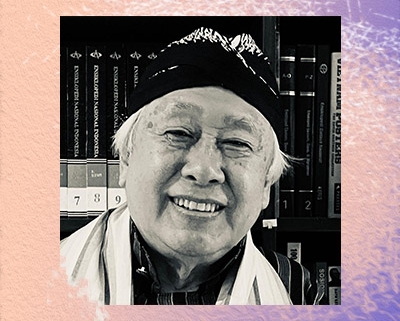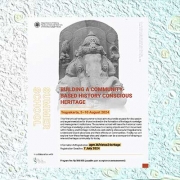Keringat Pinggir Laut
Oleh Agus Dermawan T.*
Para porter berebut memanjat tali tambat kapal penumpang, berayun-ayun di atas laut untuk menawarkan jasa angkat barang. Remaja penyelam duit beratraksi demi makan sehari-hari. Begitu susahnya pekerjaan. Begitu beratnya kehidupan.
————
PADA medio Maret 2025, pada minggu-minggu bulan puasa, di media sosial beredar video mengenai para porter (penjual jasa kuli angkat barang) di pelabuhan. Dalam fragmen satu menit sembilan detik itu terkisah belasan pemuda berlari-lari menuju hawser atau tali tambat KM Lambelu yang baru sandar di dermaga Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Di sejumlah bentangan tali tambat mereka berebut memanjat sambil bergantung-gantung seperti monyet. Satu pekerjaan yang sangat riskan, lantaran resiko tercebur ke laut jelas ada di hadapan.
Pemandangan itu disampaikan youtuber dengan penuh empati. Youtuber pun menulis teks untuk video yang dibuatnya. “Beginilah nasib rakyat kecil. Mereka hidup di negeri bernama Indonesia. Yang dalam pidato para pejabat digembar-gemborkan sebagai negeri yang kekayaannya melimpah ruah.” Di ujung video youtuber dengan nada murung mendoakan para porter itu: “Sehat selalu ayah dan pejuang keluarga.”


Para porter berebut menaiki tali tambat kapal atau hawser, agar bisa lebih dahulu mendatangi penumpang yang mau memakai jasanya. (Sumber: Youtube)
Konten video yang seru, atraktif dan sekaligus miris tersebut saya konfirmasi ke seorang kerabat yang lama tinggal di Makassar. Ia membenarkan. “Memang begitulah keadaannya setiap kali ada kapal penumpang bersandar. Mereka berebut untuk jadi lebih dulu sebisa-bisanya. Karena kenyataannya, banyak dari yang memanjat-manjat dan merayapi tali itu tidak mendapat order dari penumpang. Sehingga, kasian, upaya awal mereka sia-sia. Padahal sudah begitu mati-matian.”
Dari kejadian itu lalu terjelaskan, bahwa pihak pengelola kapal ternyata tidak memperbolehkan para porter itu menyongsong penumpang yang siap menuruni boat ladder. Atau tangga kapal – tangga akomodasi – yang merupakan akses resmi penumpang untuk turun (dan naik) kapal. Buntunya akses resmi itu menyebabkan para porter berjuang lewat jalan ilegal, memanjat hawser.
Situasi ini berbeda dengan porter di kereta api, terutama di Jawa. Dengan seragam yang bernomor mereka bisa tenang keluar-masuk kereta untuk menjual jasanya. Dan dengan tarif yang berstandar mereka terjamin penghasilannya. Itu sebabnya ketika kereta siap berangkat pergi, para porter berjajar di tepian rel dengan telapak tangan ditaruh di dada. Mengucapkan terimakasih kepada para penumpang yang sudah menggunakan jasanya.

Kapal penumpang KM Lambelu sedang menurunkan penumpang dari tangga akomodasi, yang sulit diakses para porter. (Sumber: Republika)

Porter kereta api sedang nyaman bekerja, lengkap dengan seragam. (Sumber: Agus Dermawan T.)
Kisah empat dekade silam
Apa yang terjadi di Pelabuhan Makassar mengingatkan saya dengan apa yang terlihat pada 42 tahun silam, di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kejadian itu saya rekam dalam tulisan yang dimuat harian Kompas halaman satu, edisi Kamis, 26 Mei 1983, dalam judul Syamsul dan Kawan-kawan: Tampang Generasi Penyelam Duit. Tulisan itu demikian.
Syamsul, berusia 16 tahun, berbadan kurus namun tegap sehat-walafiat. Kulitnya coklat. Parasnya khas bumiputera Jawa pinggiran pulau. Rona wajahnya polos. Ekspresinya nampak datar dan kering, kurang memperlihatkan luapan gairah. Tetapi walau tertatap garing, dirinya selalu basah. Paling sedikit, delapan jam dalam sehari ia basah.
Maklum Syamsul adalah penyelam duit. Sebutan yang aneh kedengarannya. Tapi tepat, karena memang itulah yang selalu dilakukannya dengan sengit, sejak beberapa jam setelah matahari terbit.
Di Selat Bali pemuda remaja ini tiap hari bercokol. Tepatnya di kapal ferry yang menyeberangkan pelancong dari dermaga Ketapang (Pelabuhan Banyuwangi) menuju Gilimanuk (Pelabuhan Bali). Setiap hari ia bergelantung di sisi kapal yang sedang berlabuh.
Syamsul tidak sendirian di sana. Ia ditemani oleh sekitar 10 anak lain yang lebih muda usianya. Keberadaannya menciptakan pemandangan yang unik. Saksikanlah ketika lengan-lengan mereka mengait railing pagar dek lantai tiga kapal, dengan tubuh yang dimiringkan ke arah kedalaman air. Seperti burung kokokan yang siap terbang menukik untuk mencokok ikan! Simak ketika mereka duduk di pagar ferry, sehingga tampak bagai jajaran burung gereja yang tepekur tenang di kawat listrik di panas terik.
Sebentar-sebentar Syamsul dan beberapa rekannya menengok ke bawah, ke lantai dua kendaraan laut itu. Sudah banyak penumpangkah? Jika belum, mereka menunggu.

Syamsul sedang bertengger di dek lantai tiga kapal, di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. (Sumber: Agus Dermawan T.)
Ketika saatnya sudah sampai, atau ferry telah sarat dengan penumpang, mereka pun beraksi. Syamsul dan para rekannya beruntun menceburkan diri ke laut yang kedalamannya sekitar 15 meter. Seperti dikomando mereka lalu berkerumun di sehampar permukaan sambil ramai-ramai menengadahkan wajahnya ke arah ratusan penumpang. Sehingga dari atas ferry kepala-kepala kecil mereka seperti butiran cendol yang mengapung. Pada momentum itu Syamsul dan kawan-kawannya segera berteriak-teriak, mengais untung.
“Om! Tante! Om! Lempar uang Om! Lempar uang Tante!!”
Teriakan-teriakan lantang yang berbaur dengan suara mesin kapal itu mendapat sambutan. Seperti sudah biasa, beberapa penumpang pun mengeluarkan uang logam 50 atau 100 rupiah. Uang itu lalu dilempar jauh ke tengah laut. Uang logam nyemplung menembus air, hilang dari pandangan. Begitu juga para lelaki berusia antara 12 sampai 16 tahun itu. Mereka segera menyelam dan raib dari penglihatan. Tapi tak lama kemudian kepala-kepala mereka nongol ke permukaan. Setelah kembali membentuk formasi, wajah mereka serentak menengadah ke atas. Dan lihatlah. Di antara banyak kepala itu, ada seorang yang mengangkat tangannya, meringiskan mulutnya, sengaja untuk memperlihatkan giginya. Gigi remaja itu tampak menggigit sekeping uang logam. Berarti, dialah yang berhasil menangkap uang koin yang tadi dilemparkan.
Atraksi tentu belum selesai. Sejenak setelah itu Syamsul dan rekan-rekannya berteriak lagi. “Ayo Om! Ayo Tante. Lempar! Jauh! Jauh!” Koin dilempar, berkilau menembus biru laut. Para remaja itu menyuruk kembali ke dalam air dengan kesigapannya yang profesional. Begitu seterusnya. Dengan cebar-cebur itulah Syamsul dan segenap rekannya menyambung hidupnya yang banal.
Apakah sampeyan berbasah-basah begini setiap hari? Saya bertanya kepada Syamsul.
“Ambi nyilep peces, isun biso oleh madyang,” katanya. Artinya, “Dengan menyelam duit, saya bisa makan”. Ia menjawab seolah mewakili rekan-rekan sepeceburan.
Untuk makan sehari-hari
Tak jelas sejak kapan tradisi melempar koin dan profesi menyelam uang ini muncul di selat itu. Tapi Syamsul sendiri mengaku telah lima tahun melakukan pekerjaan tersebut. Syamsul, anak Dusun Gladak, pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar sampai kelas V. Tapi kemudian putus sekolah karena kesulitan biaya. Ayahnya yang tukang batu merasa berat untuk membelikan ilmu baginya. Dan Syamsul pun dibawa ke pelabuhan tempat ayahnya bekerja sebagai kuli angkut barang. Sang ayah tak pernah mengajarkan kepada Syamsul untuk jadi penyelam duit. Tapi juga tak pernah melarang ketika Syamsul setiap hari cebar-cebur di laut, dan pulang membawa uang.
Memburu uang di dasar lautan bagi Syamsul sudah jadi mata pencarian. Sehari ia berhasil memperoleh uang receh sekitar 25 keping. Bila semua dihitung sebagai pecahan 50 dan 100, berarti di atas 1.500 rupiah berhasil ia kantongi. Syamsul bekerja sejak kapal ketiga berangkat dari Pelabuhan Ketapang, yakni sekitar pukul delapan pagi. Dan ketika matahari menjelang tenggelam, ia pun pulang. Sejumlah opelet langganan yang selalu memberi gratisan setia mengantar, ulang alik Dusun Gladak – Pelabuhan Ketapang, yang berjarak 18 kilometer.
Untuk apa penghasilan yang lumayan itu?
“Gawe njajan. Dinggo emak olah-olah neng pawon. Kanggo apak kadung perlau,” ujarnya terbata-bata. Untuk jajan. Buat ibu masak di dapur. Untuk ayah kalau perlu.
Syamsul bukannya bekerja tanpa perangkat. Setiap kali praktik ia selalu mengantongi kacamata. Kerangka kacamata itu terbuat dari kayu. Di tengahnya terlekat kaca plastik yang tahan air.
“Dengan kacamata ini saya bisa melihat uang sampai ke dasar samudera.” Ia bertutur bahwa sebagian besar rekannya tidak punya.
Kacamata itu dibeli dengan keringatnya sendiri. Seribu rupiah harganya. Satu kacamata bisa ia pakai dalam waktu cukup lama. Dengan perangkat itu pekerjaannya diperlancar. Kesehatan matanya terlindungi. Namun yang terpenting, bagi remaja seperti Syamsul dan rekan-rekannya, dengan kacamata itu keaksiannya sebagai penyelam duit semakin dipandang orang. Bukankah ketika di permukaan air dengan kacamata menempel di kepala, mereka tampak seperti anggota pasukan katak jalesveva? Ihwal Kopaska itu (Komando Pasukan Katak – satuan elit TNI Angkatan Laut) ia ketahui lewat gambar kalender yang ada di pelabuhan. Dengan kacamata itu Syamsul bangga jadi tontonan para penumpang kapal. Setiap hari, sepanjang minggu, di seluruh bulan, mengisi senggang penumpang sebelum kapal berjalan nyusur lautan.
Syamsul dan segenap generasi penyelam duit ini mengenal benar medannya. Karena itu ia tahu benar risikonya. Bahaya kram kaki atau benturan yang menyebabkan cidera di dalam air bukannya tak mungkin terjadi. Namun sakunya menuntut hal yang lebih penting. Apalagi seperti Syamsul yang sudah berusia 16 tahun. Itu berarti, setahun lagi ia harus pensiun. Sebab menurut “rencana undang-undang” yang buru-buru disepakati, pekerjaan ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang berusia maksimal 17 tahun. Memang, di atas usia itu tidak lucu apabila masih cebar-cebur di laut merebut uang koin.

Para penyelam duit (lembaran) sedang beraksi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. (Sumber: Antara)
Syamsul dan kawan-kawannya telah mencipta bidang pekerjaan sendiri. Dengan itu mereka bisa jajan-jajan dan bahkan makan siang dan malam. Sementara itu mereka tidak pernah tahu bahwa pemerintah dan Menteri Tenaga Kerja Sudomo berkali-kali menyelenggarakan “bursa tenaga kerja”, yang lebih terlihat sebagai sekadar upaya, citra dan gaya. Bahkan Syamsul & Rekan juga tidak mengenal siapa itu Sudomo sang laksamana! ***
Catatan :
- Sejak dimuat di koran Kompas, nama Samsyul populer. Itu sebabnya ketika setahun lebih kemudian, 1985, ia meninggal karena terbentur badan kapal, koran Surabaya Post memberitakan.
- Pada tahun 2025, sejumlah sahabat yang naik ferry Ketapang – Gilimanuk – Merak – Teluk Bayur – Tanjung Perak, masih menyaksikan atraksi penyelam duit itu. Pelakunya – yang usianya meningkat jadi maksimal 20 tahun – tentu generasi keempat setelah Syamsul.
- Karena uang logam sudah jarang, maka gulungan uang kertas yang dilemparkan. Sehingga atraksinya lebih ringan, karena uang kertas jatuhnya mengambang. Uang kertas basah yang didapat itu lalu dijemur sampai kering. Persis seperti situasi ekonomi wong cilik pelabuhan di Negeri Bahari ini, yang selalu garing.
—-
*Agus Dermawan T. Pengamat kebudayaan, pengintip situasi sosial. Penerima Anugerah “Adikara Cipta Budaya” dari Sri Sultan Hamengku Buwono X.