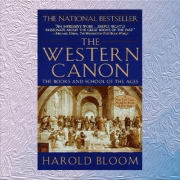Dindon W.S: Teater Selalu Memberi Kesaksian Pada Zaman Sulit Apapun
Salah satu yang jarang diteliti secara mendalam oleh para pengamat teater Indonesia – adalah sesungguhnya banyak teater kontemporer Indonesia muncul dari komunitas-komunitas kampung. Gelegak estetika teater dan nalar kritis teater bermula dari energi komunalisme kampung sering luput dari analisa sosiologi teater kita.
Di Yogya, misalnya – kita mengenal Kampung Dipowinatan. Pada tahun 70-an dari kampung ini lahir teaterawan-teaterawan kuat seperti Joko Kamto, Novi Budianto, Jemek Supardi dengan lain-lain. Mereka bergabung dengan eks-eks Bengkel Teater seperti Fajar Suharno, Gajah Abiyoso, Tertib suratmo melahirkan Teater Dinasti. Dalam teater Dinasti juga bergabung penyair Emha Ainun Nadjib – dan penulis naskah , Simon hate yang saat itu menempuh studi di Fakultas Filsafat UGM.
Bersama Emha Ainun Nadjib – para seniman kampung Dipowinatan bereksprimen menciptakan musikalisasi puisi-gamelan. Teater Dinasti – pada zamannya melahirkan naskah-naskah kritis terhadap rezim Orde Baru, seperti Dinasti Mataram, Geger Wong Ngoyak Macan, Patung kekasih, Sepatu Nomer Satu, Sosok Diam di Kandang Bobrok, Keajaiban Lik Par, Calon Drs Mul, Mas Dukun. Keberadaan Teater Dinasti menginspirasi lahirnya teater-teater kritis di Yogya setelah itu – misalnya Teater Gandrik.
Di Jakarta – dari Gang Kober Kampung Melayu, Jakarta Timur –suatu wilayah yang tak jauh dari kuburan umum juga lahir dari tangan Dindon W.S sebuah teater yang fenomenal. Yaitu: Teater Kubur. Teater ini awalnya beranggotakan “berandal-berandal” kampung setempat. Ditambah sanak saudara, tetangga-tetangga kampung Dindon sendiri. Teater yang awalnya pentas dalam even-even Agustusan – dan disokong oleh RT/RW ini akhirnya masuk Taman Ismail Marzuki – mengikuti dan merajai festival.
Berkat kerja kerasnya yang luar biasa, Dindon mampu membawa Teater Kubur menjadi sebuah kelompok teater garda terdepan. Teater Kubur – di masa-masa akhir Orde Baru menyajikan sebuah bentuk teater yang lain daripada lain – yang oleh pengamat disebut bertumpu pada physical theater. Antara lain: Sirkus Anjing, Tombol 13, Sandiwara Dol. Trilogi ini pada dasarnya adalah refleksi kritis terhadap kekuasaan Orde Baru. Tapi dikemukakan secara berbeda. Adalah menarik menggali pemikiran Dindon, bagaimana secara estetis dia sampai ke karya-karya ini. Sebab sebelumya yang sering disajikan Teater Kubur adalah naskah-naskah masterpiece Arifin C Noer – bukan sebuah physical theater. Dindon W.S sebelumnya dianggap sutradara yang paling berhasil menerjemahkan pikiran Arifin C Noer. Tiga kali beturut-turut Teater Kubur memenangkan Festival Teater Jakarta dengan membawakan naskah Arifin.
Untuk itu lah Seno Joko Suyono dan Edy Susanto dalam wawancara ini berusaha menggali pemikiran-pemikiran Dindon. Bagaimana awalnya ia dari menjelajahi naskah-naskah Arifin kemudian bisa sampai menemukan bahasa teater sendiri. Wawancara juga menggali –bagaimana pandangan Dindon tentang lab teater atau latihan-latihan teater yang ideal. Bagaimana dia menggembleng anak-anak kampung – masuk dalam latihan-latihan berjangka panjang sampai setahun-dua tahun –secara mengalir. Wawancara juga mengorek pengalaman penting Dindon tinggal bersama dua komunitas tradisi di India Selatan yang sangat berbeda, yaitu komunitas tari Yakhsagana Kendra dan komunitas Bhootha Kola . Sebuah pengalaman yang membuat Dindon mampu merefleksikan akar-akar pengalaman estetisnya di masa kecil bersinggungan dengan kesenian tradisi – termasuk keseniah Bodeh yang magis dan berbasis sihir.
Berikut perbincangan—Seno Joko Suyono dan Edy Susanto dengan Dindon. Perbincangan diawali dengan membicarakan pandangan Dindon mengenai bagaimana kondisi teater di saat pandemi ini .
Pandemi sudah lebih dari satu setengah tahun. Selama pandemi ini bagaimana Anda melihat kehidupan dunia teater? Bisakah survive? Bagaimana teater mensiasati era pandemi?
Begini. Teater itu selalu memberi kesaksian pada zaman apapun. Walaupun kita dibatasi oleh situasi sulit, yang ditunggu dari teater adalah kejujurannya. Teater harus menjadi bagian dari sebuah kesaksian. Di Indonesia saya kira teater tak akan mati di era pandemi ini. Bahkan saya lihat makin muncul geliat menumbuhkan cara-cara alternatif dalam berteater. Ada kalangan teater yang meyakini pandemi ini mampu melahirkan generasi “teaterawan digital” yang juga penuh ide-ide alternatif. Mau tak mau kita harus mengakrabkan diri dalam dunia digital, dengan segala kemungkinan-kemungkinannya.
Ada yang berpendapat, dunia panggung telah selesai. Anda setuju?
Itu pendapat yang menarik walaupun saya tidak setuju. Panggung tidak akan selesai sampai kapanpun menurut saya. Tapi memang dunia teater digital membuat dimensi teater menjadi lebih luas. Ada katarsis juga di sini. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dalam sebuah ruang teater biasa – pertemuan langsung antara penonton dengan pelakunya membuat sebuah peristiwa terjadi. Suatu “upacara”. Dalam konteks digital – “upacara”nya mungkin dalam bentuk berbeda. Banyak teman-teman teater yang kini sudah bisa merasakan kenikmatan menonton teater digital. Itu menarik bagi saya.
Selama pandemi ini, apa saja yang Anda kerjakan bersama Teater Kubur?
Pandemi adalah realitas yang harus kita hadapi. Saya harus bisa hidup dalam habitat situasi sosial dan politik yang terjadi. Tidak ada istilah, pandemi lalu membuat kami Teater Kubur berhenti latihan. Kami terus latihan. Kami kan punya kultur tradisi latihan yang terus-menerus. Dalam latihan-latihan itu kita menumpahkan apa yang kita serap dari realitas. Seni atau teater bahan bakunya adalah sebuah realitas. Dan di situasi seperti ini bahan bakunya banyak. Mulai kepanikan-kepanikan masyarakat dan sebagainya. Nah Desember lalu saya mementaskan karya baru Operasi Bocor.
Anda pentaskan di mana?
Saya pentaskan di rumah sendiri. Di loteng rumah saya ada tempat pertunjukan kecil. Saya pentaskan dengan penonton terbatas. Penontonnya tidak lebih dari 40 orang. Operasi Bocor bertema situasi sosial politik pandemi. Saya pentaskan Desember lalu, namun latihannya sudah lumayan lama. Membuat bentuk pementasanya bagi saya nggak begitu sulit dan tidak butuh waktu lama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memasuki situasi secara intens terus kita geluti. Kemudian di dalam latihan itu kita libatkan situasi-situasi itu menjadi karya. Meng- conditioning meng-kontemplasikan itu saya kira yang lama. Jadi dalam situasi pandemi ini tidak ada halangan untuk berkarya, tinggal bagaimana menyiasatinya, harus pintar-pintar. Harus terukur supaya tidak merugikan orang.
Anda dalam karya baru ini katanya melibatkan Yuyun (Yuniati Arfah) yang kita tahu penari dan juga vokalis Discuss grup musik rock progresif. Tidak biasanya Teater Kubur menampilkan “aktor” tamu seperti ini …
Sebetulnya beberapa tahun yang lalu saya pernah kerjasama dengan Yuyun. Saat itu kita pentas di Graha Bakti Budaya TIM khusus memperingati hari ulang tahun Jakarta. Saya tahu vokal Yuyun sangat bagus. Ekspresinya juga bagus. Saya ajak dia untuk pentas Siti Ratu Asia – semacam drama musikal. Dia menjadi pemeran utama. Dia menjadi Siti Ratu Asia. Siti Ratu Asia itu personifikasi dari Jakarta….

Foto pementasan “Operasi Bocor” Teater Kubur, 2020 (Sumber foto: Arsip Facebook Yuniati Arfah)
Kemudian Anda ajak Yuyun dalam proses Teater Kubur?
Ya. Dan ternyata Yuyun bisa langsung cair sebagai keluarga Teater Kubur. Sangat susah apabila seorang aktor latihan dengan Teater Kubur tetapi jiwanya tidak menyatu. Teapi Yuyun ternyata mudah sekali menyatu – tune in dengan kami….
Tadi Anda mengatakan bahwa Teater Indonesia itu seharusnya bisa bertolak dan bertahan dari kesulitan-kesulitan apapun. Tidak hanya dalam pandemi. Anda sendiri saat zaman Orde Baru mendirikan Teater Kubur penuh dihadapkan kesulitan-kesulitan dan tantangan. Anda saat itu tetap bertahan. Dan tetap eksis sampai kini. Kalau boleh bisakah – dengan latar belakang kesulitan-kesulitan era pandemi seperti sekarang ini – Anda merestropeksi – menceritakan ke kami awal-awal kemunculan Teater Kubur?
Ya betul. Seperti Anda katakan- sesungguhnya awal Teater Kubur berdiri pun, kita sudah disodori oleh tantangan yang luar biasa. Saya tinggal di kampung – dekat kawasan kuburan di bilangan Jakarta Timur. Banyak persoalan luar biasa dalam kehidupan kampung. Saat itu setiap saya keluar rumah selalu ada saja orang mabuk di jalanan. Mengganja. Apa saja. Saat itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang di jalan-jalan, kita minum sedikit sudah ada polisi datang. Dulu, bahkan anggota ABRI pun, bisa sama-sama mabuk kalau di jalanan.
Ha ha ha. Narkoba dimana-mana…?
Ya betul. Awal tahun ‘70-an, awal ‘80-an begitu. Banyak banget yang “bermain” dengan narkoba. Gila. Rata-rata kalau besar sedikit, di kampung saya – saya lihat remaja sudah mengenal apa itu yang namanya narkoba dan segala macam. Saya sendiri nyaris kalau nggak sadar diri juga bisa masuk ikut ke dunia ini. Nah, di sanalah, saya diteror oleh sebuah kenyataan. Kenapa kampung saya bisa terjadi seperti itu ? Saya lama merenung apa yang bisa saya perbuat untuk ini. Saya akhirnya berkesimpulan: situasi demikian karena di kampung saya tidak ada kegiatan kesenian. Saya melihat remaja-remaja yang narkoba itu sesungguhnya memiliki potensi kesenian. Saya melihati mentalitas mereka itu cenderung orang yang merdeka bebas. Mereka begadang dari malam sampai pagi. Nah menurut saya itu ada potensi kesenian dalam diri mereka. Itu keliaran potensi. Tapi sayang mereka nggak tahu potensinya itu harus dibawa kemana.
Lalu apa yang Anda kerjakan saat itu?
Saat itu saya berusaha manfaatkan momen-momen peristiwa tahunan yang telah ada di kampung. Di kampung kan dari dulu ada yang namanya: Festival Tujuh Belas Agustus. Saat 17 an selalu ada panggung – yang diisi pertunjukan ala kadarnya, cuma tari-tarian apa gitu. Nah momen panggung Tujuh belasan itu – saya ambil sebagai sebuah jalan untuk mencari perubahan. Saat itu saya ajak tetangga-tetangga di sekitar rumah saya, saudara-saudara saya, orang-orang di sekitar kampung – saya ajak merespon tujuh belasan. Ternyata mereka senang sekali. Saya ajak mereka membikin panggung sendiri. Ngangkut-ngangkut sendiri. Tidak ada dana. Tidak ada sponsor. Jadi apa saja yang kita punya – kita buat sebagai materi panggung: balok-balok, drum-drum…
Anda membuat apa saat itu?
Nah, saat itu saya melatih tetangga-tetangga saya, saudara-saudara saya, remaja-remaja kampung untuk latihan improvisasi teater. Latihan model teater rakyat. Bukan teater dengan konsep modern. Saya terus menerus mengajak mereka latihan melakukan improvisasi-improvisasi. Latihannya itu di tempat terbuka – di dekat kuburan. Nah saat latihan itu ternyata banyak warga yang menonton. Mereka tertawa-tertawa. Senang menyaksikan latihan. Warga terhibur. Jadi latihan improvisasi saja sudah begitu ditonton banyak orang. Dan itu membuat bangga mereka.
Setelah itu Anda pentaskan hasil latihan-latihan itu? Judulnya apa?
Ya. Saya pentaskan. Judulnya: Sandiwara dalam Sandiwara. Biasanya di panggung 17 an itu kan yang ditampilkan ya seputar tari-tarian atau tema perjuangan. Itu melulu. Dan rata-rata tidak menarik. Tidak komunikatif. Asal asalan. Nah, saya ingin di panggung 17 an itu bisa diisi pertunjukan yang bagus seperti pertunjukan-pertunjukan teater di TIM (Taman Ismail Marzuki) . Lalu saya bikin pementasan yang standarnya seperti pentas di TIM. Jadi pertunjukan yang betul-betul serius. Meskipun temanya komedi. Dan saat Sandiwara dalam Sandiwara dipanggungkan – banyak yang surprise dan suka.
Itu pertunjukan sebelum Anda membentuk Teater Kubur ya?
Ya. Sebelum Teater Kubur.
Itu cikal bakal Teater Kubur….
Waktu itu kami latihan-latihan saja. Tidak ada pretensi untuk bikin Teater Kubur. Di kampung sendiri, responnya bagus. Orang-orang tua pada kaget. Mereka kaget melihat anak-anak muda yang biasanya mabuk, yang biasanya mengganggu orang, yang biasanya tukang bikin ribut tiba-tiba kok bisa menghibur masyarakat. Teman-teman yang ikutan main di Sandiwara dalam Sandiwara kemudian juga tiba-tiba merasa eksis, merasa mendapat pengakuan di masyarakat. Dari situ kemudian mereka tanpa sadar, tiba-tiba berubah seperti menjadi tokoh di kampung. Ternyata keterlibatan mereka di teater mampu mengangkat nama baik mereka. Nah, saya terus memanfaatkan hari-hari besar untuk pementasan di kampung. Selain 17 Agustus, lalu ada hari Ulang Tahun Jakarta. Kita latihan terus, improvisasi terus untuk pementasan menyambut momen Ulang Tahun Jakarta. Mereka tak bisa lagi meninggalkan latihan. Kita bikin panggung sendiri, di depan kelurahan, di depan kuburan. Masyarakat akhirnya menjadi tahu kita punya kelompok teater. Dan lama-lama mereka – yang tadinya mabuk-mabukan menjadi menjadi tokoh-tokoh, menjadi artis kecil di lingkungan…
Ha ha artis kecil di kampung ya…
Ya. Nah, setelah itu saya sering ngajak mereka nonton ke TIM. Saya ajak mereka menonton Festival Teater Jakarta berkali-kali. Selama dua tahun itu mereka terus menerus saya ajak menonton teater di TIM.
Waktu itu Anda tergabung di teater lain nggak?
Waktu itu saya anggota Teater SAE.
Saat itu apakah teman-teman Teater SAE tahu kegiatan Anda berteater di kampung?
Tidak tahu. Orang-orang Teater SAE tidak tahu bahwa saya mengayomi anak-anak kampung. Saya akhirnya juga keluar dari Teater SAE, karena saya lebih concern dengan kegiatan saya, dengan masyarakat di sekitar rumah. Saat itu Boedi S Otong (sutradara Teater SAE) tidak percaya saya bisa membuat teater di kampung….
Anda dengan Teater SAE ikut pertunjukan apa aja….
Polisi (karya Slawomir Mrozek), Umang-Umang (karya Arifin C Noer), Machbeth, Konstruksi Keterasingan, Androcles dan Singa (karya George Bernard Shaw), Ekstase Kematian Orang-Orang, banyak sekali.

Foto salah satu pementasan Teater SAE. (Sumber foto: http://encyclopedia.jakarta-tourism.go.id)
Berapa tahun Anda di Teater SAE?
Hampir 7 tahun. Tapi pada ujung saya harus keluar, meninggalkan Teater SAE karena ada ideologi yang tidak cocok buat saya. Ya saya harus lebih concern..mengikuti apa yang saya mau.
Jadi karena Anda mulai membina teater di kampung, mungkin itu alasan yang paling kuat untuk keluar dari Teater SAE…
Ya memang betul…Saya harus pindah. Saya harus lebih banyak terjun berteater dengan masyarakat kampung.
Waktu itu tekad Anda sudah bulat ?
Ya. Itu nggak bisa ditawar walaupun katakanlah saat itu ada orang yang mau mengasih saya rumah untuk mencegah saya berteater di kampung Kober saya tetap tak mau. Itu ujian yang mengasyikkan buat saya saat itu – bertahan dengan keputusan saya.
Tradisi estetis apa yang Anda warisi dari Teater SAE waktu itu. Anda kan tujuh tahun di Teater SAE. Terlibat banyak pementasan. Sudah .senior di Teater SAE….
Teater SAE dikenal mengeksplor tubuh. Tapi boleh ditanya siapa sih yang awalnya mempresentasikan tubuh di latihan-latihan Teater SAE. Jadi sebelum Boedi S Otong melakukan latihan-latihan tubuh, saya sudah mengeksplorasi tubuh saya di Bulungan. Suatu kali saat saya latihan, Boedi S Otong datang melihat. Dia merespon latihan saya..terus..terus…katanya. Latihan saya itu menjadi inspirasi buat dia. Saya memang lebih merasuk ketubuhan di Teater SAE. Saat saya melakukan latihan-latihan tubuh di Teater SAE beberapa anggota Teater SAE agak keberatan. Tapi saya dipercaya Boedi S Otong melatih tubuh mereka. Mereka inginnya ya Teater SAE seperti kelompok teater lain..teriak-teriak. Apalagi kalau nggak ada Boedi S Otong, tambah lebih nggak kuat mereka. Jadi saya selalu datang jam tiga sore, sebelum Boedi S Otong atau anggota Teater SAE lain datang saya sudah mengeksplor diri saya.
Itu latihan-latihan Teater SAE di mana, di Bulungan?
Di Bulungan. Jadi saya memang sudah mengeksplor tubuh semenjak awal. Namun saat saya mulai bikin grup di rumah dengan anak-anak kampung, latihan-latihannya tidak saya awali dengan eksplorasi tubuh, tapi lebih kepada latihan-latihan teater rakyat: kekuatan improvisasi.
Tahun berapa Teater Kubur berdiri?
Tahun 1983 . Selama setahun kemudian kami menyiapkan diri untuk mengikuti festival.
Festival Teater Jakarta di TIM?
Ya. Saya sebetulnya tak setuju ikut festival. Kenapa? Karena menurut sayaujung-ujung festival sering anti klimaks. Saya sesungguhnya tidak mengajak mereka ikut festival, tapi karena seringnya mereka saya bawa nonton ke TIM, mereka yang justru ingin sekali terlibat festival. Mereka – setelah saya ajak nonton berbagai pertunjukan di Festival Teater Jakarta – mengatakan: kalau main seperti ini – kita juga bisa dong.
Anda bilang apa ke anak-anak Teater Kubur saat itu?
Saya bilang, kita memang harus pentas tetapi nggak mesti ikut festival. Saya berat rasanya kalau tujuannya berteater hanya festival. Saya nggak mau. Akhirnya kita voting. Saya kalah, kalah suara (tertawa kecil), karena cuma satu yang mendukung saya untuk tidak ikut festival, selebihnya 20 orang anggota Teater Kubur di awal itu lebih setuju harus ikut festival. “Salahnya kamu ngajak-ngajak kami nonton teater di TIM. Ayo kita buktikan…kita bisa main di TIM, kita nggak kalah,” mereka bilang begitu.
Terus bagaimana?
Akhirnya saya kasih syarat yang paling berat apabila mereka memang betul mau ikut festival. Saya tanya ke mereka: ”Kalian mau menang atau mau kalah. Nah, kalau mau menang, maka syaratnya berat sekali,” kata saya. “Apa syaratnya?” tanya mereka. Saya jawab: ”Latihan tiap hari selama setahun-dua tahun, tiap hari, tanpa libur. ”Saya kira mereka pasti mundur mendengar syarat itu, karena biasanya kita latihan seminggu tiga kali. Eh ternyata mereka mau.
Waktu itu naskah apa yang Anda angkat?
Naskah Arifin C Noer AA II UU. Naskah Arifin ini sesungguhnya untuk televisi, drama televisi tetapi saya adaptasi jadi struktur panggung. Sebelumnya tidak pernah ada AA II UU dibikin untuk panggung. Jadi saya ubah strukturnya menjadi naskah untuk dipentaskan di panggung. Alasan mengapa saya memilih naskah tersebut karena saya melihat potensi para aktor saya belum sampai jauh. Harus naskah yang ringan-ringan. Situasi yang ada di naskah Arifin itu cocok. Tipikal orang-orangnya ada di sekitar saya. Kebetulan mereka sudah terampil improvisasi. Begitu sudah terampil improvisasi, kita latih mereka, nggak sulit. Nah saya selama dua tahun bergulat dengan itu. Selama dua tahun menyiapkan diri untuk ikut festival itu – berdirilah yang namanya Teater Kubur.
Anggota awal Teater Kubur kalau boleh sebut, namanya siapa saja itu.
Ada Siti Anisa, ada Mbak Sri, masih banyak lagi. Saya terus mempertinggi kualitas mereka. Rentang waktu workshop saya bikin lebih panjang, karena saya lihat kekurangan mereka masih banyak. Saya butuh waktu banyak melatih mereka. Mereka harus bermain yang bagus. Pada awalnya mereka saya ajari teknik akting realisme. Mereka saya kenalin dengan metode Stanislavski segala macem. Mereka butuh waktu lama. Itu kira-kira setahun. Dan ternyata militansi mereka untuk latihan luar biasa. Sampai orang-orang kampung dari mulai Pak RT semua membantu kami untuk persiapan ikut festival….
Wah gila ya…
Ya, Orang sekampung semua ikut partisipasi. Mereka membantu membikin set, membikin properti. Warga kampung bangga. Semua terlibat ada RT, RW dan sebagainya…
Akhirnya saat ikut festival hasilnya bagaimana?
Menang. Ketika menang, kita akhirnya diarak-arak di kampung. Warga kampung bangga sekali…
Tahun berikutnya ikut lagi festival?
Ya. Tahun berikutnya, saya bawain naskah Arifin: Kucak-Kacik. Agak naik sedikit tingkat kesulitannya.
Kucak- Kacik susah. Susah itu….
Iya susah… Cuma menurut saya saat itu secara kualitas aktor-aktor Teater Kubur sudah bisa memainkan….Saya sendiri saat itu sudah lama mempelajari naskah-naskah Arifin. Sudah lumayan khatam. Kapai-Kapai, Umang-Umang semua sudah ada di kepala saya. Saya bisa menakar – naskah Arifin mana yang bisa dibawain oleh anak-anak Teater Kubur. Akhirnya saat bawa Kucak-Kacik pada festival, kami menang lagi…

“Kucak-Kacik” karya Arifin C Noer yang dipentaskan oleh Teater Kubur, 1987. (Sumber foto: seputarteater.wordpress.com)
Menang lagi ya?
Ya, menang lagi. Tatkala Danarto (almarhum) saat itu meresensi pentas kami di Kompas dia sampai menulis (tertawa kecil): Dindon bawa penonton sekampung…..(Dalam resensinya di Kompas tahun 1987 berjudul: Teater Kubur Mementaskan Kucak Kacik, Menuju Teater Tanpa Penonton, Danarto amat memuji Teater Kubur. Dia menulis begini:Yang hebat dari grup ini adalah kemampuannya memboyong penonton “sekelurahan”, mengingat banyaknya sampai gedung arena penuh. Para penonton itu berfungsi sekaligus sebagai supporter, sekaligus sebagai pemain. Alasan pertama karena festival itu dilombakan dan alasan kedua, karena konsep “teater tanpa penonton” dicoba dikembangkan. Di akhir tulisannya Danarto mengatakan: Teater Kubur jangan sampai mengubur grup senior. Awas!– red)
Tahun ketiga festival lalu memainkan apa?
Tahun ketiga kami akhirnya memainkan Kapai-Kapai. Kapai-Kapai sangat surealis dan tingkat kesulitannya tinggi. Tapi secara teknik, saya melihat para pemain sudah matang untuk membawakan Kapai-Kapai. Dan kami menang lagi – di tahun ketiga …Tapi sebelum mementaskan Kapai-Kapai di TIM, kami mementaskan naskah Danarto: Rintrik di Bulungan…
Rintrik itu dari cerpen Danarto…
Ya. Rintrik saya pentaskan dalam bentuk teater. Waktu itu ada Festival Teater Lima Kota di Bulungan. Yang ikut Teater Dinasti Yogya, Bengkel Muda Surabaya –semua senior-senior. Yang paling muda adalah Teater Kubur Jakarta. Saya pentaskan Rintrik saat itu. Banyak yang menonton. Nah ternyata surprise. Begitu pementasan selesai mereka kaget, karena aktor-aktor saya yang main masih anak-anak SMA, remaja semua. Orang nggak habis pikir, kok bisa gitu. Sedangkan Rintrik kan naskah dewasa. Saat di panggung penonton banyak yang tidak tahu kalau para pemain saya anak SMA. Saya kan tahu bagaimana tekniknya menghadirkan. Secara pengalaman, aktor-aktor saya mungkin belum berpengalaman. Tapi begitu main – dasyat. Penonton langsung percaya. Saya waktu itu menampilkan pola-pola pemanggungan yang tidak lazim…

Alm. Danarto (Sumber foto: Tempo.co)
Bagaimana pemanggungannya?
Pemanggungannya saya buat semua menonton melingkar. Di tengah dikasih cahaya. Nah Rintrik ada di tengah. Center. Lalu saya bikin semua peran ada lima. Pemuda lima, Bapak lima, anak lima, semuanya lima. Jadi pendekatan panggung saya sebetulnya lebih kepada teater rakyat. Teater rakyat dengan nyanyian-nyanyian.
Bagaimana reaksi penonton?
Banyak yang suka. Waktu itu Rendra menonton, Emha Ainun Najib, Teguh Karya juga menonton. Lalu banyak tokoh-tokoh lain. Widji Tukul itu bahkan saking senengnya ingin memeluk saya, ngasih saya bunga. Pak Teguh Karya sampai kaget-kaget. Dia komentar ke saya: ”Kamu ternyata kenal betul, hal-hal yang sifatnya tradisi….”
Anda memang banyak menyelami kesenian tradisi?
Ya, dari kecil, sebelum berteater – saya sudah mengenal tradisi. Saya kenyang menonton pertunjukan tradisi. Di Jakarta saja, setiap Sabtu Minggu, waktu saya hanya untuk menonton Wayang Orang Bharata, menonton Miss Tjitjih, menonton di RRI kalau ada pementasan Wayang Golek – begitu selama masa kecil. Umur sepuluh tahun itu saya kursus tari. Jadi Gatot Kaca, gara-gara saya sering nonton Wayang Orang Bharata. Bapak saya itu penggembira kesenian. Kalau liburan Bapak saya sering mengajak saya menonton Topeng Banjet Karawang di kampung Bapak saya. Wah luar biasa itu….
Kelebihannya Topeng Banjet Karawang itu apa?
Topeng Banjet itu ada cerita. Dia bukan menari solois, tapi ada ceritanya. Diawali dengan menari topeng terus penari itu yang menjadi tokoh utamanya. Dalam pertunjukan Topeng Banjet itu ada komedi, ada nyanyi-nyanyi, segala macem..menghibur itu. Nah itu, tontonan awal saya di masa kecil. Sampai sekarang pertunjukan Teater Banjet tersebut terngiang-ngiang dalam diri saya. Sebab setiap liburan, saat Kerawang lagi panen, pasti Topeng Banjet main – dan saya diajak bapak saya menonton. Saya ingat nama primadona topeng Banjet Kerawang adalah Ijem.

Seni Topeng Banjet, Kerawang. (Sumber foto: merahputih.com)
Kampung Bapak Anda itu Karawang?
Bukan. Bapak saya asal Sumedang. Topeng Banjet waktu itu selalu keliling – dari Karawang ke seluruh Bogor, Cianjur sampai desa Sundulan Sumedang yang sekarang sudah hilang menjadi Waduk Jati Gede. Kebetulan setiap liburan itu pasti Topeng Banjet main di kampung Bapakku. Nah aku senang sekali. Banyak cerita soal menonton Topeng Banjet ini. Waktu itu kan nontonnya harus beli karcis, tapi kita nggak punya duit untuk beli tiket. Saat itu saya masih kecil banget di bawah 10 tahun. Saya nggak punya duit. Tapi waktu itu saya melihat bentuk karcisnya kok sangat gampang sekali membikinnya. Cuma kertas ditulis Rp 30 tidak ada stempelnya. Kok gampang banget. Lalu aku waktu itu mengajak teman-teman kecil di sana untuk membikin tiket sendiri. Eh ternyata bisa masuk hahaha.
Hahaha..Oke kembali ke pementasan Rintrik di Bulungan tadi. Setelah mementaskan Rintrik, baru Anda kemudian mempersiapkan pementasan Kapai-Kapai di TIM?
Ya betul…
Kapai-Kapai kan naskah berat dari Arifin. Tokoh Emak dalam Kapai-Kapai itu sesungguhnya hanya ada dalam benak Abu, tokoh utama. Ia tidak ada secara riil. Banyak adegan-adegan dalam Kapai-Kapai sesungguhnya adalah adegan-adegan yang hanya ada dalam benak Abu. Naskah ini penuh lapisan-lapisan antara yang terlihat dan yang ada dalam ilusi. Kalau sebuah kelompok teater tidak mampu memaknai itu ya pentasnya pasti gagallah. Bagaimana Anda dengan teman-teman kampung akhirnya bisa menghasilkan pementasan Kapai-Kapai yang bagus. Yang dianggap banyak orang merupakan salah satu ‘referensi’ bagi teater manapun untuk memainkan Kapai- Kapai…
Sebetulnya Kapai-Kapai sudah ada sejak lama dalam kepala saya. Saya bisa mengukur, apakah aktor-aktor saya sudah bisa memainkannya apa belum. Saya memberikan latihan-latihan intens – latihan teknik, latihan-latihan lainnya sehari hari, salah satu sasarannya adalah agar mereka mampu memainkan Kapai-Kapai. Jadi nggak mungkin saya bikin pementasan pertama langsung saya beri Kapai-Kapai. Saya harus latih lama dulu kemampuan teknik mereka….
Butuh latihan beberapa tahun akhirnya baru Anda merasa yakin, anak-anak Kampung yang bergabung dalam Teater Kubur mampu memainkan Kapai-Kapai?
Baru setelah lima tahun. Setelah lima tahun saya baru merasa anak-anak bisa mementaskan Kapai-Kapai. Setelah lima tahun baru bisa mereka memahami bagaimana karakter bawah sadar tokoh utama Kapai-Kapai: Abu dan mementaskan hal-hal bawah sadar itu. Target ideal pementasan Kapai-Kapai saya itu sudah ada di kepala saya. Untuk meraih target ideal itu sumber daya manusianya harus dikuatkan. Jadi saya tidak memaksakan segera pentas. Saya baru berani mementaskan Kapai-Kapai setelah sumber daya manusianya sesuai dengan target ideal. Jadi saya ukur betul aktor-aktor saya. Latihan-latihan harus sudah tuntas untuk mencapai itu, supaya paling tidak pementasan bisa dinikmati. Memainkan Kapai-Kapai jadi harus melewati fase-fasenya dulu, pelan-pelan baru mereka bisa memasuki alam Kapai-Kapai.
Bisakah memberi contoh bagian paling sulit dari Kapai-Kapai ?
Bagian saat Abu dan Iyem – istrinya mau membunuh anaknya sendiri. Itu momen sangat dramatik. Luar biasa dramatik. Tidak gampang menampilkan adegan itu di panggung. Dan saya melihat banyak kelompok teater yang mementaskan Kapai-Kapai gagal saat adegan itu….

Arifin C. Noor. (Sumber foto: http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id)
Kenapa gagal?
Bayangkan, Abu dan Iyem membunuh anaknya tapi dengan rasa cinta. Itu kan pengalaman batin yang dasyat. Nah banyak sutradara atau aktor teater yang gagal menafsirkan itu. Mereka mengerti – namun tidak bisa menghidupkan adegan tersebut di panggung. Walaupun dimainkan, tapi suasananya, nggak muncul. Situasi psikologisnya tak hidup. Sebab ini situasi meta – yang susah sekali ditampilkan. Sampai-sampai saya lihat banyak pementasan Kapai-Kapai yang membuang adegan itu. Malah ada sutradara yang menganggap adegan itu kurang menarik. Justru menurut saya tantangannya di situ. Sebagai sutradara kita diuji betul sampai sejauh mana kepekaannya.
Lalu bagaimana Anda melatih aktor-aktor Anda untuk paham soal itu?
Nggak gampang..nggak gampang..harus ekstra sabar, harus ada analogi cara melatihnya. Saya harus memiliki teknik untuk menstimulasi agar mereka bisa sampai ke sana. Biar bisa lahir emosi itu dalam diri mereka sendiri. Saya menemukan cara bagaimana mereka bisa mengeksplor dimensi itu. Tapi saya harus sabar. Jangan buru-buru menghukum aktor gitu. Nggak gampang itu…
Apakah Anda merasa dekat dengan naskah-naskah Arifin? Artinya naskah-naskah itu sesungguhnya bisa Anda saksikan percikan-percikannya di kehidupan sosial Anda?
Ya. Saya merasa dekat dengan naskah-naskah Arifin. Seperti ada kesamaan gitu. Mas Arifin itu masa kecilnya dekat dengan kesenian rakyat – teater rakyat. Jadi unsur menghiburnya kuat gitu. Tapi menghibur dalam tanda kutip. Mas Arifin membangun sebuah peristiwa-peristiwa puitik dalam naskah-naskahnya – namun peristiwa puitik itu tidak membuat orang menjadi ‘jauh’, tapi membuat orang bisa masuk, orang bisa tertawa, orang bisa menangis. Naskah-naskah Arifin menurut saya tidak berjarak dengan masyarakat.
Kuat secara sosial juga ya naskah Arifin?
Ya. Saya makanya heran ada sutradara saat memainkan naskah Arifin, kemudian memotong-motong naskahnya. Membuang adegan yang dianggap susah. Wah begitu dipotong, rangkaian kekritisan dan kepuitikan naskah Arifin menurut saya hilang. Improvisasinya hilang. Kedalaman dramanya itu bisa hilang. Apalagi diubah dialognya…
Fatal ya menurut Anda itu….
Ya. Naskah Arifin itu luar biasa. Kita tidak perlu melucu, Arifin sudah meramu kelucuan itu di dalam teksnya. Kedalaman puisi dan guyonan itu diramu betul menjadi sebuah ‘hiburan’ dalam tanda kutip. Hiburan dengan ‘H’ besar: menghibur batin. Arifin pernah bilang kalau karyanya dipentaskan- penonton tidak tertawa berarti pementasan itu gagal. Saya sendiri merasa terwakili dengan naskah-naskah Arifin. Terwakili sebagai rakyat jelata.
Kalau Anda membandingkan naskah Arifin dengan naskah-naskah Rendra bagaimana?
Beda ya. Kalau Rendra kan sangat ketat sekali dengan bahasa. Rendra mengekspresikan teater dengan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa yang baik penting buat Rendra. Tapi kalau Arifin nggak harus baku begitu – dia bilang “ Kalau kamu orang Sunda ya pakailah bahasa kamu.” Makanya naskah Arifin itu sangat unik. Naskahnya bisa mewakili sifat masyarakat marginal atau masyarakat bawah. Naskah Arifin bagi saya tidak perlu diadaptasi lagi. Naskah itu sudah jadi. Ada sutradara yang mengadaptasi naskah Arifin malah jadi ‘kering’. Ada yang mengubah-ubah naskah itu malah jadi ‘kering.’
Anda belajar sendiri…menafsirkan sendiri naskah Kapai-Kapai?
Ya. Saya bener-bener semua sendirian. Saya keasyikan dengan naskah-naskah Arifin. Dalam Kapai-Kapai misalnya ada tokoh kakek yang membawa cermin. Menurut saya itu harus dipahami sebagai metafor. Kakek membawa cermin merupakan metafor seseorang nabi atau guru membawa ajaran-ajaran atau dakwah-dakwah. Tapi terkadang banyak sutradara yang gagap dalam memahami metafora-metafora dalam Kapai-Kapai. Sehingga kebanyakan menafsirkan cermin – ya naïf. Cermin ya cermin….
Jadi bukan cermin fisik ya menurut Anda?
Ya. Arifin kan ngomong bahwa ada Nabi yang membawa ajaran kitab. Sebetulnya itu yang dimaksud dengan cermin. Bukan naïf cermin, ya cermin kaca sungguhan. Itu metafor. Tapi orang sering tidak bisa membaca metafor. Makanya dulu dalam pementasan saya, cermin itu saya ganti dengan daun.
Daun?
Ya. Saya ganti dengan daun, karena daun (lontar) dalam sejarah itu sering digunakan untuk menulis teks-teks suci. Jadi naskah-naskah Arifin – tidak verbal. Arifin nggak semurah itu. Kewajiban kita untuk menafsir wajib melacak sendiri…Saya lihat juga sering orang menafsirkan naskah Arifin dengan logika yang aneh-aneh gitu…Wah tidak ada yang aneh-aneh..
Banyak sutradara juga gagal – dalam menafsirkan tokoh Emak. Tokoh Emak betul-betul seperti seorang tokoh riil – padahal tokoh Emak hanya ada dalam kepalanya si Abu.
Ya betul. Tokoh Emak itu hanya ada dalam benak Abu. Tapi kemudian sering divisualkan menjadi orang yang di luar Abu. Itu kan salah. Naskah Arifin sangat dalam. Kalau aktornya kurang kuat atau sutradaranya lemah pasti akan kedodoran – tidak bisa menggiring ke situasi psikologis yang pas. Aktor dan sutradaranya harus peka. Harus mampu menangkap substansi naskahnya. Saya itu sampai sekarang masih hafal dialog-dialog dalam Kapai-Kapai….
Omong-omong Arifin sendiri nonton pertunjukan Kapai-Kapai Anda?
Nggak nonton dia. Dia nontonnya saat saya mementaskan Kucak-Kacik .
Apa komentar Arifin saat itu?
Saat diwawancarai wartawan, dia bilang pementasan saya lebih bagus dari saat dia sendiri memanggungkan Kucak-Kacik haha.
Saat Anda mementaskan Kapai-Kapai, Arifin ada di mana?
Waktu itu katanya lagi pergi. Jajang C Noer yang menonton.
Apa komentar Jajang?
Jajang berkomentar selama dia menonton Kapai-Kapai pertunjukan Teater Kubur yang dianggap paling pas.
Jadi Arifin ini sangat berpengaruh sekali ya dalam diri Anda?
Begini. Orang yang pertama kali menandai saya mempunyai bakat besar sebagai sutradara sebetulnya jujur ya Arifin C Noer itu. Saya sebelum tak tahu sama sekali bahwa saya punya bakat menjadi sutradara. Saya kaget saat mas Arifin mengatakan begitu. Awalnya adalah saya mengikuti workshop teater yang diselenggarakan Teater Kecil – teaternya Mas Arifin. Teater Kecil itu memiliki lab – namanya Lab Teater Kecil. Yang ikut workshop-mulai dari anak-anak Teater Kecil sampai Teater SAE. Nah saat saya ikut workshop – nomor-nomor pertunjukan yang saya bikin selalu dianggap Arifin bagus. Arifin bilang kepada saya bahwa saya memiliki bakat menjadi sutradara. Kaget saya. Soalnya setiap kali membikin pertunjukan di Tujuh Belasan di kampung, saya nggak pernah bilang sebagai sutradara – karena malu. Akhirnya saya merenung . Saya baru yakin bahwa di sinilah hidup saya. Karena selama ini saya bertanya-tanya siapa saya. Tapi begitu Arifin C Noer mengatakan bahwa saya bakat menjadi sutradara – saya semakin yakin , semakin serius…
Teater Kubur kemudian dikenal menemukan bahasa estetika teater sendiri. Dengan menciptakan pertunjukan-pertunjukan seperti Sirkus Anjing yang lebih banyak mengekplor physical theater, berbeda sama sekali dengan pertunjukan-pertunjukan sebelumnya. Bagaimana Anda bisa mengarah ke sana? Padahal Teater Kubur saat itu – sudah dianggap mapan dengan berturut-turut memenangkan festival dengan memainkan naskah-naskah Arifin C Noer?
Begini, saat itu saya sudah banyak belajar dengan Teguh Karya, Putu Wijaya, Rendra dan lain-lain. Semua memiliki kekuatan masing-masing. Saya belajar akting realisme dari Teguh Karya. Saya , pernah menjadi aktornya Teguh. Saya belajar surealisme kepada Arifin C Noer, pernah jadi aktornya juga. Terus Bengkel Teater. Walaupun saya bukan aktornya Bengkel, tapi saya akrab betul sama Rendra, karena sering ngobrol dari sampai pagi sampai malam. Terus juga dengan Boedi S Otong, Teater SAE. Saya belajar dari Putu Wijaya kreativitasnya yang tidak pernah menyerah. Juga dari Riantiarno. Petualangan teater mereka semua luar biasa. Kemudian timbul pertanyaan dalam diri saya sendiri – lalu di mana posisi saya. Semua sudah memiliki kapling estetikanya masing-masing. Lalu dimana saya? Posisi saya dimana? Saya bertanya: kalau saya mapan dengan pola yang sudah ada di festival, apalah artinya saya? Saya akhirnya sampai pada keyakinan bahwa saya harus menjelajahi kemungkinan-kemungkinan lain, sesuatu yang tak terduga di dalam teater. Nah itu asyiknya teater itu. Teater selalu membuka kemungkinan-kemungkinan penjelajahan bentuk baru …
Itu pertanyaan-pertanyaan dalam diri Anda paska festival?
Ya..paska festival
Lalu apa yang Anda perbuat?
Saya dengan Teater Kubur paska menang-menang di festival lalu mengeksplor diri selama dua tahun . Jadi kita bertanya pada diri sendiri apakah kita masih akan seperti penampilan di festival selamanya ? Kita lalu komitmen tidak berhenti pada kemenangan festival tapi mencari kemungkinan-kemungkinan lain. Kita sepakat komit, kita tidak berpikir untuk pentas. Tapi selama setahun dua tahun latihan terus, eksplorasi terus sampai kita punya cara-cara tertentu. Murni lab, selama dua tahun. Bener-bener hanya latihan. Dari situlah muncul Sirkus Anjing. Yang pentasnya menggunakan tong-tong.

Foto karya Sirkus Anjing. (Sumber foto: dokumentasi pribadi)
Pentas pertama Sirkus Anjing di mana?
Pentas pertama di Bengkel Teater Rendra Cipayung. Saat menonton Sirkus Anjing Rendra kagum. Ya tahu sendiri kalau Rendra kagum semuanya lalu kagum. Rendra membandingkan karya saya dengan karya-karya teaterawan yang pernah jadi muridnya, termasuk Arifin, Putu Wijaya, segala macam. Menurutnya pentas saya nggak kalah dengan mereka. Saya merasa Rendra terlampau memuji habis-habisan saya. Saya bilang kepada Rendra, bahwa dia sebetulnya menaruh ‘bom’ di kepala saya….

W.S Rendra (Sumber foto: kepogaul.com)
Apa yang dilihat Rendra dalam pementasan Sirkus Anjing?
Rendra mampu membaca idiom-idiom yang ada dalam pertunjukan saya. Dia membaca tong sampai celana jeans yang kita pakai. Semua ditafsirkan. Dia bilang ini pementasan yang sangat global. Sangat universal.
Sirkus Anjing saat itu benar-benar mengeksplor tong ya?
Ya. Tong menjadi aktor tersendiri. Tong tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk buang sampah, tapi dia kita mainkan sebagai radio – aktor masuk di dalamnya dan kemudian menceracau di dalamnya. Tong juga bisa menjadi roda menggelinding. Dalam pertunjukan saya itu tong-tong menjadi sebuah sistem yang membelenggu orang.

Foto pentas karya Sirkus Anjing di Teater Populer. (Sumber foto: Dokumentasi pribadi)
Bagaimana awalnya Anda memiliki inspirasi memain-mainkan tong?
Begini. Kami tidak mencari-cari awalnya. Pada karya-karya lain kami juga tidak mencari-cari. Ide tong itu muncul dengan sendirinya – secara intuitif. Kalau kita mampet selalu akan muncul kecerdasan intuitif. Saya selalu mencoba memberi prioritas pada kecerdasan intuisi kita yang mengalir dalam proses. Jadi dalam proses bekerja saya, sebetulnya tidak ada pretensi untuk membuat seperti apa. Biarkan Tuhan saja yang ngasih tahu nanti. Jadi awalnya saya tidak tahu betul mau bikin apa itu. Kita hanya mengondisikan diri dengan latihan-latihan terus…
Nah lalu munculnya intuisi menggunakan tong saat latihan tersebut awalnya bagaimana…
Begini. Dalam latihan-latihan, selalu kami mengawali dengan kegiatan sapu-menyapu. Jadi semua aktor-aktor saya itu kira-kira jam 3 sore atau 4 sore sudah mulai menyapu-nyapu. Di mana-mana disapu. Sampah dimasukkan tong sampah. Demikian selama bertahun-tahun begitu. Jadi kami itu boleh dikatakan tiap hari selalu berhubungan dengan tong. Lama-lama tong seperti dirinya sendiri yang harus dijelajahi. Akhirnya ya tiba-tiba setelah bertahun-tahun muncul intuisi untuk bermain-main dengan tong. Aktor-aktor saya memasukkan badannya ke dalam tong sampai lentur betul, sampai akrab betul. Bahkan aktor-aktor saya bisa jungkir balik di dalam tong itu. Nah, akhirnya itu menjadi inspirasi buat saya, bahwa melalui tong kita bisa membicarakan sebuah energi global, membicarakan sebuah sistem.. Itulah awal Sirkus Anjing.
Kemudian setelah Sikus Anjing, Anda mementaskan Tombol 13 dan kemudian Sandiwara Dol yang penuh dengan selang infus. Betul?
Ya..ya…. Semua itu trilogi Orde Baru. Sirkus Anjing – Tombol 13 – Sandiwara Dol. Saat mementaskan Tombol 13 di Teater Arena TIM, bangku-bangkunya saya cor dengan besi-besi. Nah zaman kekuasaan Orde Baru yang represif itu saya ingin membangun kesadaran kritis. Pada Sandiwara Dol sebetulnya saya meramalkan kejatuhan Soeharto. Soeharto bakal ambruk…
Itu ramalan tentang Soeharto?
Dalam Sandiwara Dol saya meramalkan kekuasaan itu pasti hancur. Namun dari Sirkus Anjing sesungguhnya teks-teksnya sudah mengarah ke situ. Misalnya: ”Kering kerontang kumbang-kumbang tak bergoyang..kumbang-kumbang hilang melayang, ke liang-liang, lubang-lubang.Bang-bang, bang, bang, berkubang-kubang bang, berkubang-kubang bang, bangkuku bang, bangkuku bang, bangku bangkrut bang, bangkuku bang, bangkuku bangsat bang.” Sejak tahun 90 an awal saya sebetulnya sudah melihat kekuasaan Soeharto bakal bangkrut. Jadi dalam pementasan trilogi itu saya betul-betul banyak bermain metafora. Sebab kalau kita menyebut rezim secara verbal kita bisa ditangkap. Intel setiap hari ada di tempat latihan saya. Saya bisa ditangkap. Maka saya bungkus pementasan saya dengan metafor. Mereka nggak ngerti kan. Kalau saya mainin secara verbal, saya sudah ketangkap.
Dalam resensinya di Majalah Tempo atas pentas Tombol 13, Nirwan Dewanto terpukau dengan kebisingan pentas Anda yang menurutnya membuat perih. Besi-besi dipukul-pukul. Besi-besi itu membuat suasana menekan. Masuk dalam ruangan Teater Arena sedari awal penonton sudah tertekan. Besi-besi yang Anda pukul dengan para pemain itu menjadikan pertunjukan penuh dengan aura kesakitan…
Ya, karena memang Tombol 13 merupakan refleksi dari ketertekanan kita. Bayangkan dari tahun ’80 sampai’90, kita sebagai seniman hanya gelisah karena mahasiswa-mahasiswa itu nggak berani bergerak. Jadi saat itu saya main ke kampus-kampus. ITB, UI, semua kampus-kampus besar. Tujuannya sehabis pentas, kita diskusi. Jadi kita ngomong tentang situasi Indonesia. Kita membakar-bakar mahasiswa. Nggak penting lagi saya pentas terus dan kumpul-kumpul di TIM, karena nggak efektif. Jadi target saya saat itu – bukan TIM lagi, tapi bagaimana mengeluarkan daya kritis mahasiswa-mahasiswa di kampus untuk menjadi tindakan.
Pada zaman itu – di TIM, padahal teater yang sudah menjadi senior – akan mendapat subsidi pementasan kan?
Ya. Tapi target saya itu setelah Teater Kubur dinobatkan sebagai teater senior di TIM bukan untuk subsidi itu. Saya nggak suka, saya tolak subsidi itu. Saat mentas di ITB saya harus jualan kopi. Saya juga jualan kopi kalau ada pentas-pentas wayang. Jadi tujuan saya bukan cari duit saat itu. Nggak penting lagi itu duit. Nggak penting itu proposal.
Waktu main di ITB itu bagaimana reaksi mahasiswa?
Di ITB pas kami main ada demo. Kebetulan dalam Sirkus Anjing itu, ada tokoh yang masuk di masyarakat, dialog langsung, seperti orang gila. Nah aktor saya kemudian masuk di tengah demo. Saat itu baru mulai panas-panasnya. Demo-demo masih di dalam kampus – bukan keluar. Ketika saya main di kampus, mereka akhirnya saya ajak berdiskusi kenapa ada sistem yang membelenggu mereka…..
Selain ITB, Anda pentas di kampus mana lagi?
UI. UNJ. UNAS.
Tahun 1998 menjelang Soeharto runtuh, apa yang Anda mainkan?
Sandiwara Dol. Saya sudah sudah memprediksi itu.. Saat main di Banyuwangi – setelah pentas dari Bali dan Lombok, saya tiba-tiba memasukkan ke dalam pementasan sosok semacam ninja. Nah ternyata- Banyuwangi kemudian anehnya ada kasus ninja- santet itu. Jadi kekuatan intuisi saya kira lebih sekedar nalar. Latihan-latihan panjang itu kadang-kadang bisa mengalami kedasyatan daya intuisi. Saya kan saat memasukkan sosok seperti ninja itu tidak berpikir nanti akan begini. Tapi ternyata apa yang saya bikin terjadi. Nah…
Nah setelah pasca 1998 ada pergeseran situasi politik Indonesia. Anda membikin apa?
Ya saat era Megawati kita masuk dalam era transisi. Saya menampilkan karya: Jas dalam Toilet di Surabaya. Saat itu saya mengkritisi euforia demokrasi. Nilai-nilai feodalisme segala macam masih terus melekat, nggak hilang. Situasinya nggak berubah. Waktu itu saya merasa demokrasi ya kelihatan, tapi belum melebar. Saat periode SBY saya mencipta karya berjudul: On/Off. Tentang demokrasi yang On/Off. On/Off saya pentaskan di Salihara, Jepang dan India.
Tadi Anda sempat menyebut India. Nah, ada fase dalam kehidupan Anda yang banyak orang tidak tahu, yaitu Anda pernah residen – tinggal bersama sebuah komunitas kesenian tradisi di India bukan? Bisakah Anda ceritakan soal ini? Apakah pengalaman tinggal di India ini mempengaruhi Anda? Sebab banyak yang belum tahu…

Foto pementasan karya On/Off Instalasi Macet, Teater kubur (1). (Sumber foto: Majalah.Tempo.co)
Seperti yang saya ceritakan tadi sebetulnya sejak kecil saya kagum dengan cerita wayang. Saat latihan tari di umur 10 tahun obsesi saya menjadi Gatotkaca. Tapi saat diajak ke tempat kursus tari oleh bapak saya semua yang ikut kursus ternyata perempuan semua.. Jadi kemudiam saya latihan menari Srimpi. Suatu hari karena bapak, ibu saya sakit, paman saya mengantarkan saya ke tempat kursus tari naik sepeda. Begitu saya naik sepeda, jatuh karena ngantuk, tangan saya patah. Saya terus diledek sama saudara saya. Kata saudara saya:” Gatotkaca, kok tangannya patah.” Akhirnya frustasi saya. Frustasi karena saya tidak bisa menjadi Gatotkaca. Suatu saat saya sekolah SD, saya makan kacang. Bungkus kacang itu ternyata kertas komik yang menceritakan Mahabharata. Akhirnya saya cari komik wayang itu di penyewaan buku komik. Dari komik itulah akhirnya saya mengenal Mahabharata. Saya selalu berharap saya bisa ke India untuk melacak akar-akar tradisi Mahabrata. Akhirnya Tuhan kasih jalan, saya bisa ke India..
Anda di India tinggal bersama komunitas masyarakat kesenian apa? Di mana lokasinya?
Saya tinggal bersama komunitas seni tari tradisi Yakhsagana Kendra dan komunitas Bhootha Kola (Buta kala -red) di kota Udupi, Karnataka India Selatan. Itu dua mazhab yang sangat berbeda. Yang satu Wisnu. Yang satu Syiwa.
Bisa ceritakan bagaimana pengalaman Anda tinggal bersama kelompok Yakhsagana Kendra…
Saya masuk ke sana, saya ikut berlatih. Mereka sangat luar biasa. Mereka berlatih setiap hari dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Itu tradisi mereka. Saya belum pernah lihat orang latihan segila itu. Saya bisa menari. Saya ikut latihan tari mereka. Saya juga ikut keliling pentas-pentas. Bagi mereka latihan dan pentas seperti ibadah ritual, kayak pesantren. Jadi mereka kayak hidup di pesantren.

Yakhsagana di Udupi. (Sumber:Wikipedia.org)
Terus tarian-tarian apa yang Anda pelajari saat tinggal di komunitas Yakhsagana Kendra?
Saya belajar tarian Kresna. (tertawa kecil).
Anda belajar berbulan-bulan?
Selama berbulan-bulan kami latihan. Betul-betul saya melihat ada kekuatan pengabdian kesenian untuk jalan ibadah. Di sana saya belajar tari, musik, nyanyi dan sebagainya. Saya pelajari semua. Saya ikut menyanyi. Kuncinya adalah bagaimana kita beradaptasi dengan mereka. Sebetulnya kultur India tidak begitu beda dengan kita. Mereka tidak materialistik. Mau berapa lama tinggal di situ nggak ada unsur perhitungan materi. Dan yang membuat saya luar biasa ya pengabdian itu. Seni tidak hanya sebatas materi tapi ada pengabdian, seni adalah ibadah. Seni adalah sebuah panggilan yang memang harus dijalankan.
Mainnya di mana?
Setiap minggu kita main di kuil-kuil. Udupi itu daerah dengan 1000 kuil. Setiap hari saya mendengar suara mantra-mantra dan burung Gagak….
Anda kan orang Muslim. Bagaimana tanggapan mereka saat Anda ikut dalam tarian sakral di kuil kuil…
Orang-orang Yakhsagana Kendra tak masalah. Malah kan kurang lebih seratus meter dari lokasi komunitas Yakhsagana Kendra ada masjid. Begitu adzan saya selalu segera shalat di masjid itu. Oleh orang-orang muslim di masjid saya malah ditanya kenapa saya belajar di Yakhsagana Kendra, kan itu tempat orang Hindu. Hahaha lucu banget,
Nah kalau ke Bhootha Kola bagaimana?
Komunitas Bhoota Kola itu berbeda sekali dengan Yakhsagana. Orang-orang kelompok Yakhsagana Kendra sendiri takut, datang ke Bhoota Kola. Saat saya sudah mengunjungi komunitas Bhoota Kola , saya ditanya orang-orang Yakshagana mengapa saya datang ke situ. Kan menyeramkan. Komunitas Bhoota Kola adalah komunitas ilmu sihir kata mereka. Nah saya sendiri tak ada perasaan takut. Saya mencari di mana letak komunitas Bhoota Kola. Dari kota Udupi , komunitas Bhoota Kola lokasinya sekitar 10 kilo meter. Letaknya di sebuah hutan yang sepi.
Wah, Anda mencari lokasi Bhoota Kola di hutan itu, sendiri atau diantar orang?
Saya mencari sendiri. Saya nanya-nanya. Jarak dari Udupi ke tempat Bhoota Kola itu seperti saya katakana tadi lumayan jauh. Akhirnya, dari bertanya-tanya saya sampai masuk ke sebuah hutan. Dari pinggir jalan – hutan itu sejauh dua kiloan. Orang yang saya tanya di pinggir jalan juga memperingatkan saya agar hati-hati kalau ke situ. Saya berjalan menembus hutan – akhirnya menjelang siang hari – aneh memang saya bisa ketemu rumah pemuka Bhoota Kola. Wajahnya memang menyeramkan. Rambutnya panjang sekali dan kelihatannya jarang mandi. Dia orang paling ditakuti dan disegani di kawasan itu. Begitu dia keluar rumah, dia akan bergerak terus menerus selama 24 jam. Orang-orang akan menyembah-nyembah.

Foto Bhoota Kola. (Sumber: Bhoota Kola – Fiery Folk Art Form of Konkan Culture. https://caleidoscope.in/art-culture/bhoota-kola. Foto: Sanpaiya)
Sampai di sana lalu apa yang terjadi?
Saya dilarang merokok. Karena di situ area kuil Syiwa. Saya kemudian menerangkan maksud kedatangan saya. Saya mau belajar. Dia menjawab bahwa ritualnya tidak bisa dipelajari. Dia lalu bertanya kepada saya: “Agamamu apa? “ Saya jawab Islam. Langsung dia bilang: “Nggak boleh belajar di sini.”
Terus bagaimana?
Saya akhirnya cari akal. Dia susah berbahasa Inggris. Akhirnya saya menjelaskan maksud saya kepada anaknya. Bahwa tujuan saya, hanya untuk mencoba belajar tentang budaya. Saya bilang, saya merasa ada tali kesamaan antara Indonesia dan India. Banyak tradisi Indonesia berasal dari India. Saya cerita dari kecil saya sudah belajar tarian Mahabrata. Karena saya merasa di India ini, sumbernya, saya harus ke sini.. Setelah diskusi alot di antara mereka sendiri saya baru dibolehin. Tapi sebelum mereka memperbolehkan saya, mereka melakukan meditasi-ritual dulu ke Bhoota Kola, apakah Bhoota mengijinkan. Lalu mereka sembahyang di kuil Syiwa yang berada di sebelah rumah pemuka. Saya bilang Bhoota Kola pasti ngijinin, sebab kedatangan saya kan baik-baik. Saya bercanda gitu. Eh mereka marah. “Hati-hati kamu, kamu bisa mati di jalanan,” mereka bilang ke saya. Saya langsung bilang:” Maaf, maaf.”
Lalu?
Setelah meditasi, pemuka Bhoota Kola terus diam. Dan kemudian berkata saya diperbolehkan belajar di situ. Tapi syaratnya saya tidak boleh menginap di situ. Waduh. Susah apabila saya tidak boleh menginap, karena kan tempat tinggal saya jauh. Saya bilang saya akan membayar berapa saja asal bisa menginap di situ. Tapi pemuka Bhoota Kola itu tetap tegas menyatakan bahwa saya setelah latihan selesai harus pulang. Dia bilang itu bukan kemauan dia tapi kemauan Bhoota Kola. Saya harus pulang- tidak bisa tinggal di kuil karena saya bukan orang Hindu.
Latihannya seperti apa?
Latihannya tidak ada pakem, teknik tari atau aturan. Latihannya adalah seperti mengkondisikan orang untuk trance. Musik tidak boleh sembarangan dibunyikan. Bila tidak harinya, musik dilarang. Saya ingat saat itu – mereka menggunakan terompet, dasyat bunyinya: ..huuunngggg,pang, pang, pang… saya langsung bergerak di bawah sadar. Saya seperti mengalami katarsis. Pemuka Bhoota Kola itu dipercaya titisan dewa. Jadi momen-momen tertentu akan ada roh dewa yang menitis ke dia. Dan kalau sudah menitis dia akan menari 24 jam, bergerak, 24 jam. Masyarakat akan menyembah-nyembah dia untuk tolak bala. Nah, saya bilang ke dia – saya ingin bisa trance begitu.

Foto pemain Bhoota Kola. (Sumber: https://caleidoscope.in/art-culture/bhoota-kola. Foto: PMK)
Saat Anda bilang bahwa ingin trance, bagaimana reaksi mereka?
Buat mereka itu aneh. Saya bilang saya ingin mengerti bagaimana cara atau teknik menconditioning diri, agar bisa trance. Saya hanya ingin tahu saja. Bagi mereka, saya aneh, karena saya kan Muslim.
Berapa lama Anda belajar trance di Bhoota Kola itu?
Berminggu minggu. Hampir sebulan. Saya belajar soal kondisi untuk trance.
Terus pulangnya Anda bagaimana setiap hari?
Ya tiap sore – saat mau maghrib saya harus pulang. Saya harus pulang melewatin hutan lagi. Hutan itu kalau malam sangat sepi dan gelap. Saya sampai harus menyalakan korek api – agar bisa tahu jalan. Bisa keluar dari hutan sampai jalanan itu rasanya luar biasa…
Wah tiap malam lewat hutan, sangat berbahaya sekali.
Ya, saya harus 2 kilo atau mungkin lebih – 4 kilo menembus hutan untuk bisa sampai ke jalan besar. Sampai jalan besar – saya masih harus menunggu angkutan umum. Bila malam sudah sangat jarang sekali angkutan umum. Saya harus menunggu lama sekali. Nah hampir sebulan saya terus begitu. Orang-orang di Yakhsagana Kendra sampai mempertanyakan saya, sebab bagi mereka – Bhoota Kola ibarat ilmu hitam, ritual-ritual ilmu sihir.
Kenapa Anda begitu antusias ingin belajar trance?
Jujur. Sejak kecil saya akrab dengan dunia kesenian trance. Paman saya di Jati Gede dekat Karawang punya grup kesenian Bodeh. Ini kesenian mistik. Sebelum pentas iringan musiknya itu berjam-jam. Kemudian saat pentas para pemain berteriak seperti orang kesurupan. Para pemain bisa menjelma, kerasukan apa saja…
Di mana sekarang kesenian Bodeh itu.
Kesenian itu sudah tinggal nama. Hilang. Kesenian Bodeh ini penuh atraksi mistik. Para pemainnya itu nggak tahu akan memerankan apa, bisa jadi binatang atau apa. Paman saya itu shaman nya – dukunnya. “Cuk cuk’ dia merapal mantra “Jadi..jadi.” Lalu pemainnya bisa menirukan –menjadi sesuatu –binatang misalnya. Penonton sampai takut lari-lari, karena merasa para pemain menjelma menjadi harimau. Sampai kini saya masih shock mengingat bagaimana ada seorang pemain menjelma menjadi monyet dan meneror, mengejar-ngejar penonton…
Itu kesenian akarnya Islam atau apa- karena kan ada rebananya…
Iya campuran..sebetulnya antara Islam dan tradisi. Ini kan tradisi mistik orang kampung. Ini kesenian bernuansa sihir. Pada tingkat yang ekstrem pertunjukan Bodeh ada atraksi potong manusia. Orang dipotong lehernya. Lalu terus ditutupin kain putih. Menjelang pertunjukan selesai, kain putih itu dibuka leher orang yang dipenggal sudah menyatu. Dan yang mati dan terpenggal lehernya ternyata adalah seekor kambing. Nah di India pertunjukan dengan atraksi sihir demikian banyak. Saya melihat ada pertunjukan yang juga pemainnya berperangai seperti macan. Nah saya nggak kaget ketika di India saya menyaksikan seperti itu karena paman saya sendiri juga begitu.
Anda berulang kali ke India. Setelah residen di India, beberapa tahun kemudian –Anda juga membawa On/Off ke India. Itu di kota mana?
Di kota kecil Bareilly Saya menghadiri Festival Bareilly yang ke 11. Bareilly itu sebelah utara New Delhi. Dari New Delhi naik kendaraan kira-kira satu hari baru sampai ke sana. Bareilly itu daerah dingin dekat Kashmir. Daerah itu kelihatannya agak terkucil. Di situ banyak populasi Muslim. Daerah itu minim fasilitas.

Foto pementasan karya On/Off Instalasi Macet, Teater kubur (2). (Sumber foto: Majalah.Tempo.co)
Tahun berapa itu di sana dipentaskan?
Tahun 2016. Meski kota kecil –tak banyak fasilitas = mereka punya nyali bikin festival. Infrastrukturnya, gedung-gedungnya sesungguhnya tak pantas untuk tempat pertunjukan. Tapi yang salut mereka percaya diri mengundang teater-teater dari luar negeri. Walaupun kelihatannya kurang di-support oleh pemerintah luar biasa spirit orang-orangnya. Mereka punya idealisme. Festival teater itu menjadi milik kota. Kelompok-kelompok teater yang datang diarak keliling kota. Dasyat.
Apa reaksi mereka menyaksikan pentas On/OFF?
Pentas On/Off yang menggunakan bambu-bambu mengagetkan mereka. Sutradara-sutradara teater di sana menghampiri saya dan bilang: “Kamu memberikan inspirasi banyak buat kami.” Para pemain saya melingkar dengan bambu-bambu. Dan kemudian banyak peristiwa terjadi keluar masuk lingkaran. Mereka bilang, saya memberi inspirasi dari hal sederhana bisa menjadi sesuatu. Bagi mereka pertunjukan saya merupakan hal baru.
Sampai sekarang masih ada ya festival itu?
Masih ada. Setiap tahun mereka adakan festival. Mereka meminta saya agar setiap tahun bisa datang. Tapi nggak gampang untuk ke sana. Menuju ke sana mobil harus menempuh jalanan tinggi yang berkabut tebal. Mendekati Kashmir kabut seolah membuat jalanan gelap. Memang sangat berbeda pentas di festival teater seperti Bareilly. Apalagi dibandingkan dengan festival yang mapan. Tapi kalau ingin merasakan suatu festival yang lain – ya datanglah ke Bareilly.
Itu berbeda sekali dengan Festival Teater di Jepang ya, saat Anda mementas On/Off di gedung teater Setagaya..
Ya beda sekali. Kalau di Jepang semua kan sudah beres. Semua well organized. Ongkos, honor, akomodasi, transportasi segala macem nggak ada persoalan. Kalau di India memang masih punya persoalan. Soal infrastruktur, duit membayar orang. Betapapun demikian saya cukup senang di Bareilly karena kebanggaan mereka muncul. Sampai sekarang mereka masih terima kasih kepada saya, karena saya mau datang ke sana.
Di Jepang itu pentas berapa kali ?
Dua kali. Setelah pementasan On/Off saya ke Jepang lagi memberi workshop teater selama 2 minggu.
Pengalaman estetik Anda begitu kaya, dari teater di kampung, Teater Kubur menjadi sebuah teater kontemporer Indonesia yang unik. Bersama Teater Kubur Anda pernah pentas di India dan Jepang. Anda juga memiliki pengalaman pribadi hidup bersama komunitas tari tradisi di India. Daya tahan Anda untuk menghidupi teater terasa kuat. Berdasar hal itu apa yang Anda harapkan dilakukan teater Indonesia di era pandem ini?
Saya mengharapkan, di era pandemi ini – teater Indonesia bisa memberi kesaksian. Dengan begitu teater tidak akan mati, tidak akan stagnan. Harapan saya semoga daya kritis orang-orang teater dalam situasi apapun harus tetap menyala. Kalau teater hanya dianggap sebagai mata pencaharian – maka dalam situasi sulit begini, orang teater akan mengeluh terus dan teater akan mati. Tapi kalau ada daya kritis – justru semua ada hikmahnya. Hikmah yang luar biasa. Kita punya cara-cara baru, untuk mendekati segala persoalan. Saya kira pada saat pandemi inilah orang teater diuji. Ia tidak boleh panik. Pandemi ini tantangan. Situasi sosial berubah. Orang teater tidak boleh kehabisan akal. Pandemi justru bisa menjadi sumber kreativitas sebetulnya.
————–