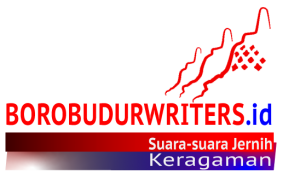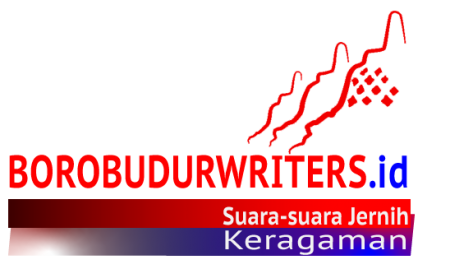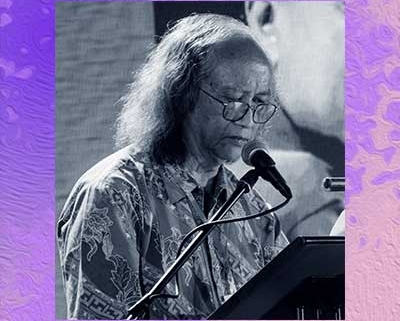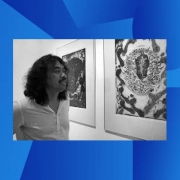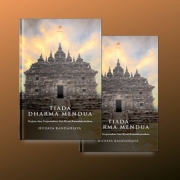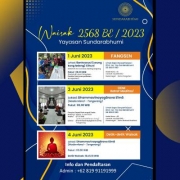Krisis Humanisme?
Driyarkara Dalam Homo Homini Socius
Oleh Mudji Sutrisno SJ.*
I. Siapa Driyarkara?
Nicolaus Driyarkara S.J. dilahirkan pada tanggal 13 Juni 1913 di Kedunggubah, Purworejo. Tahun 1952, ia mendapat gelar Doktor di bidang Filsafat di Universitas Gregoriana dengan disertasi mengenai Nicolas Malebrance.
Tahun 1941-1942, ia sudah mengajar sebagai dosen di Girisonta. Lalu 1943-1946, menjadi pengajar filsafat di Seminari Tinggi Yogyakarta. Tahun 1952-1958 setelah Ph.D.,
N. Driyarkara menjadi dosen filsafat di Yogya. 1960-1967 Gurubesar Luar Biasa di Fak. Psikologi, Universitas Indonesia; Universitas Hasanudin, Ujung Pandang (Makasar) 1961-1967; dosen tamu di Univ. St. Louis, Amerika Serikat 1963-1964. Inilah jejak-jejak tahun Driyarkara sebagai guru pendidik filsafat.
Namun Driyarkara bukan hanya guru filsafat, ia mencoba menghayati filsafat di dunia politik. 1962-1967, ia menjadi anggota MPRS, dan menjadi anggota DPA 1965-1967. Inilah jejaknya diketerlibatan politik di samping pemikir.
Jejak sebagai pemikir, dibukukan dari siaran-siaran radio R.R.I. renung filsafatnya dalam buku “Pertjikan Filsafat” (P.T. Pembangunan, Jakarta, 1962). Lalu Kumpulan kuliah-kuliahnya disatukan dalam “Filsafat Manusia”, Kanisius, Yogyakarta 1969 Cet. I, 1975 Cet. II. “Driyarkara tentang pendidikan; Driyarkara tentang Manusia, Driyarkara tentang Negara dan Bangsa”, Yayasan Kanisius, Yogyakarta 1980.
Pada tanggal 11 Februari 1967, Driyarkara meninggal dunia setelah sakit dan kini ia beristirahat di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah.
Bulan Februari menjadi bulan menentukan dan menyentuh tidak hanya karena Driyarkara di bulan itu dipanggil Tuhan setelah menapakkan jejak-jejaknya sebagai pemikir, guru dan pendidik tetapi terlebih karena tanggal 2 Februari 1969 (tepat 2 tahun setelah RIP Driyarkara), di sebuah ruang tamu di Susteran Theresia JI. H. Agus Salim, Jakarta, jejak perintisan Sekolah Tinggi Filsafat dengan nama Driyarkara dibidani lahirnya tanpa sang bidan itu sendiri.
Jejak pembidanan sebuah sekolah filsafat seorang Driyarkara bisa dirunut Bersama rekan-rekan almarhum yaitu Prof. Dr. Fuad Hassan; Prof. Dr. Slamet Iman Santosa yang mendambakan didirikannya sebuah institut filsafat di Indonesia yang terbuka untuk umum, berdiri sendiri dan merupakan pusat yang mampu menarik dosen untuk lebih memantapkan usaha pengembangan filsafat di Jakarta. Inilah dies natalis pertama S.T.F. (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara di tahun 1969.
Lima puluh enam tahun sudah usia S.T.F. Driyarkara kini dengan gedung di Cempaka Putih Indah Jakarta Pusat, dan sudah 46 tahun menyelenggarakan pendidikan limu Filsafat untuk jenjang Strata-1 sebagai jejak-jejak perujudan cita-cita Driyarkara untuk menjawab harapan masyarakat akademik yang haus bingkai-bingkai teoretik logis rasional mendasar buat membedah simpang-siur dan riuh-rendah wacana ilmu dan problem kemasyarakatan.
Sejak 1996, dimulailah jejak langkah Driyarkara berikut yang mau mengisi tenaga ahli filsafat dengan kompetensi kualitatif dengan mendirikan Program Pasca Sarjana dalam bentuk Program Magister Ilmu Filsafat.
Dalam meniti jejak-jejak sosok Driyarkara yang digedungkan dan diwujudi program pendidikan filsafat dalam dies natalis. Inilah renung relevansi pikiran pokok Driyarkara untuk bangsa ini harus menjadi spirit perayaannya agar tidak jadi ritualisme dan upacara belaka.
Jejak besar pertama pikiran Driyarkara adalah posisi manusia dengan eksistensinya sebagai pusat. Dalam Filsafat Manusia-nya, “manusia adalah siapa yang ber-apa dan apa yang bersiapa”. Kesiapaannya diuraikan Driyarkara dalam kata-kata: manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri dalam dunianya. Manusia adalah subyek atau persona yang sadar. Dinamika persona, adalah, rentetan tenunan subyek sadar diri dan subyek yang berbuat dan ber-apa untuk menampilkan siapanya di dunia ini. Dalam proses mendunia inilah, sebagai persona, manusia dunia dalam kebudayaan. Salah satu hasil kebudayaan adalah struktur bernegara dan model kenegaraan. Di sinilah manusia menata, memanusiawikan sistem penggunaan kekuasaan untuk hidup bersama dalam sebuah negara.
Hidup bersama oleh Driyarkara disoroti sebagai sosialitas yaitu eksistensi manusia dalam hidup bersama orang lain dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Tesis (pendapat) pokok Driyarkara di sini benar dahsyat yaitu: manusia adalah kawan bagi sesamanya. Manusia adalah rekan atau teman bagi sesamanya di dunia sosialitas ini (homo homini socius). Pikiran homo homini socius ini ditaruh untuk mengkritisi, mengkoreksi dan memperbaiki sosialitas preman; sosialitas yang saling mengerkah, memangsa dan saling membenci dalam homo homini lupus (sesama adalah serigala bagi manusia).
Dalam tesis ini sosialitas sebagai rekan dirumus kultural, artinya bersama-sama selalu mencipta tata hidup bersama yang makin sejahtera dalam sistem sosial, politik di satu pihak. Di lain pihak, memperlakukan sesama sebagai rekan (dalam keanekaragaman etnik, bakat, beda-beda watak dan agama), adalah sekaligus saling menghantarkan menuju pusat kebahagiaan hidup manusia di sini dan nanti yaitu Tuhan Sang Pencipta. Di sini nuansa religius sosialitas diletakkan.
Dengan tesis ini Driyarkara sekaligus meng-counter (melawan) tesis Thomas Hobbes peletak sistem negara yang harus represip, otoriter karena yang diatur adalah para serigala dengan kekuasaan mutlak Leviathan.
Karena itu pula tata bernegara bagi Driyarkara adalah bagian dari tata kultural atau istilah kunci khas Driyarkara adalah proses kebudayaan, di mana manusia sebagai kawan dari muda harus dididik untuk mampu “mengartikan dunianya secara bebas dan kreatif”. Proses kebudayaan untuk merajut sosialitas antar rekan agar bisa hidup bersama dalam ika dan kebhinekaan (khusus di Indonesia Driyarkara menunjuk bingkai sosialitas Pancasila), diwanti-wanti (diingat-sadarkan selalu) olehnya agar tidak menjadi proses “KEBUAYAAN” (Kumpulan Karangan alm. Prof. N. Driyarkara SJ., yang pernah dimuat di BASIS, tempat, penerbit, tahun tidak disebut, hal. 239-262).
Artinya, saling mengerkah dan memperlakukan sesama sebagai buaya. Konsekuensinya, Driyarkara lalu menulis bagaimana proses pembudayaan itu sebagai berikut: “sebagai kesimpulan, “… dapatlah kita katakan bahwa kekuasaan negara itu ditjiptakan manusia dalam pembudayaannya dan untuk pembudayaannya, agar supaya ia sampai ke eksistensi yang autentik, artinya sampai ke kemerdekaan yang selalu bergerak untuk memasuki SEIN atau ADA itu. Kebudayaan yang tulen harus bebas; tidak boleh dirintangi oleh kekuasaan manapun juga. Bagi kita ada norma yang menentukan ketulenan dari kebudayaan yaitu: sesuai atau tidak sesuainya dengan Pantjasila” (Basis, 20(1970-1971), 256).
Jadi relevansi pertama jejak pokok pikiran Driyarkara di sini adalah tafsiran kebudayaan (kultural) proses bernegara kita dan bersesama antar warga sebangsa sebagai socius (=kawan). Ketika menjelang Pemilu 2024 hiruk-pikuk tafsiran dan nilai kebersamaan kita terlalu jangka pendek politis yaitu kursi jabatan dan kekuasaan, maka Driyarkara memberi tafsir kultural proses bernegara jauh ke depan dengan ukuran nilai religiositas, sosialitas adil, beradab dari sila-sila Pantjasila.
Ketika orang mengacu pada kebendaan materialisme dan untung rugi ekonomisasi, Driyarkara memberi kulturalisasi sebagai tafsiran keindonesiaan. Jejak agung yang kedua dari Driyarkara ada pada pikiran dan refleksi filsafatnya mengenai permainan dan homoludens: manusia yang senang bermain-main tetapi lupa bahwa permainan itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan hidup bahagia bersama sesama dan dalam Tuhan.
Driyarkara memaparkan itu dalam judul “Permainan sebagai aktivisasi dinamika” yakni untuk menuju pembebasan manusia (Filsafat Manusia, hal. 79-86, terutama pedoman penutup pada hal. 83-84). Begini bunyinya: “Bermainlah dalam permainan tetapi janganlah main-main! Mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh. Kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya, sehingga
permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Mainlah dengan eros, tetapi janganlah mau dipermainkan eros. Mainlah dengan agon tetapi jangan mau dipermainkan agon. Barang siapa mempermainkan permainan, akan menjadi permainan-permainan. Bermainlah untuk bahagia tetapi janganlah mempermainkan bahagia” (Driyarkara, idem, ibid. di atas).
II. Driyarkara dan Homo Homini Socius
Ketika seorang Driyarkara menuliskan pikiran homo homini socius, artinya, manusia adalah sahabat bagi manusia lain untuk secara wacana maupun bahasa tulisan melawan keadaan hidup saling makan memakannya antar manusia dalam homo homini lupus (artinya, manusia merupakan serigala bagi sesamanya), di situ terpadatkan cita-cita kemanusiaan sebuah hidup bersama.
Tetapi pada saat yang sama terbahasakan pula cermin renung realitas hidup bersama yang saling mencakar, menjegal, tega mengerkah bahkan membunuh seperti serigala pada hal di tiap pandangan religi ia itu suci, fitri, gambar agung dan citra ayu Allah itu sendiri alias seharusnya (digarisbawahi) semestinya saling bersaudara sebagai cita-cita. Namun mengapa jauh asap dari panggangnya?
Ungkapan pikiran yang menaruh posisi manusia sebagai bernilai karena punya dasar teks suci religi atau ia berharkat karena memiliki kemerdekaan kehendak dan budi jernih berdasar akar moral kemakhlukannya, keduanya, hanya sebagian contoh humanisme yang mau sebagai isme (baca: arus pikiran) memperjuangkan harga kemanusiaan orang karena ia itu manusia. Harga atau berharganya orang karena ia itu manusia disumberkan dari akal budinya yang merdeka; kemerdekaan kehendaknya; sumber teks suci dari religi-religi berkitab tetapi pula kearifan-kearifan hidup lisan yang diturun-temurunkan dalam tradisi lisan yang intinya mau mengajari dan menyadarkan; penghargaan pada manusia.
Pikiran yang menjunjung kemanusiaan dalam humanisme mengalami ujian tajam dan krisisnya saat memutlakkan kebenaran harga dan nilai manusia melulu pada akal budinya (rasionalitas); kebebasan kehendaknya (libertas) dan keindividuan kemandiriannya atau otonominya saat dihadapkan pada kenyataan dua perang dunia I dan II; dikoyak-koyaknya manusia sebagai korban-korban kekerasan apalagi teganya atas nama ideologi, religi dan keyakinan meletakkan sesamanya berkeping-keping dalam bom kekerasan atau bom teror serta bom bunuh diri atas nama sebuah perjuangan.
Krisis humanisme mempunyai 3 lapis sejarahnya yaitu pertama, ketika akal budi dan kehendak bebas otonomi subjektivitas manusia ternyata sebagai agency atau pelaku diremukkan oleh konstruksi politik kekuasaan yang tak bisa dijawab oleh akal budi rasional itu sendiri manakala dengan rasionalitas bom-bom dirancang akal budi secara dingin dan tega untuk membunuh sesamanya. Di sini krisis epistemologis menjadi lapis pertama.
Lapis kedua, humanisme rasionalis liberalis tak bisa menjawab krisis-krisis perusakan tata kosmos oleh olah pikiran dan kemauan bebas manusia yang dengan kelihaian rasionalisasi visi dan sentralisasi serta manipulasi modal kapital dengan kemauan sadar mau menguasai sendiri maupun kelompoknya sumber-sumber alam hingga dampak- dampak ekologis dan perusakan ruang tinggal manusia terancam pada buminya sendiri tempatnya bereksistensi. Inilah lapis krisis keberadaan (ontologis) karena mengguncang alasan dasar mendiami dan hidup di bumi ini (raison d’être).
Lapis ketiga berada pada konstruksi simbolik aksara atau bahasa di mana komunikasi antar manusia yang dahulu digemborkan oleh humanisme rasionalis bersumber pada proses bahasa sebagai ekspresi benar, tulus, jujur, baik komunikasi antar manusia kini ditentukan maknanya, arti kebenarannya dan isinya oleh mereka yang mempunyai kuasa membuat, menafsir dan mengkomunikasikan bahasa dalam monopoli tafsiran serta mereka yang dengan kapital menguasai pusat-pusat pendidikan berkomunikasi untuk kepentingan penguasaan dan bukan untuk nilai pencerahan peradaban manusia. Lapis ketiga inilah lapis teks, tafsiran kontekstual. Di sini Krisis menjadi parah karena tak terjadi komunikasi setara dalam memaknai hidup bersama.
Konsekuensinya, secara logis, pertanyaan kritis dan tajam yang langsung muncul adalah sudah matikah humanisme?
Menjawab pertanyaan kritis ini, bila tafsiran humanisme dibingkai asumsi (pengandaian) adanya subjek manusia d