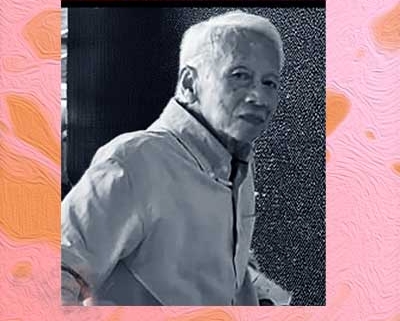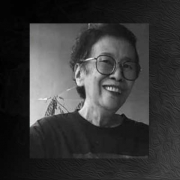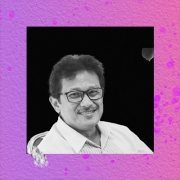Mengapa Teater Koma Belum Titik
Oleh Bambang Bujono*
Sebuah catatan dari menonton pementasan Teater Koma Mencari Semar, naskah dan sutradara Rangga Riantiarno, di Ciputra Theatre, Jakarta, 13-17 Agustus 2025.
Teater Koma belum titik. Grup yang didirikan pada 1977, ketika penggagas Taman Ismail Marzuki habis masa jabatannya sebagai Gubernur Jakarta, seolah hendak membuktikan bahwa tanpa seorang “maecenas” sekaliber Bang Ali, Teater Koma bisa produktif dan bermutu.
Dan itu benar. Produktif, tak bisa disangkal. Bermutu, kenyataan mengatakan tidak ada seniman atau sebuah grup teater yang karya dan produksinya selalu mendapat pujian para kritikus. Kalau ada yang mengernyitkan dahi untuk Teater Koma, silakan mengingat, meriset setidaknya dua pementasannya yang mendapat apresiasi para pengamat teater: Bom Waktu (1982), dan Opera Ular Putih (1994) –- untuk menyebutkan yang saya ingat saja. Yang pertama, seingat saya, adalah naskah yang padat dengan dialog yang bernas, jauh dari jargon kosong, dan kocak menghibur. Yang kedua, apa mau dikatakan bila pementasan lebih dari empat jam ini serasa hanya sejam? Panggung yang memikat dan kisah yang disajikan para pemain beserta musik, tata pentas dan lain-lain membuat kita menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Teater Koma belum titik, dibandingkan dengan grup-grup yang besar di tahun-tahun Dewan Kesenian Jakarta dan TIM-nya mencapai kreativitas yang membuat para seniman belum merasa seniman bila belum berkiprah di TIM. Bengkel Teater Rendra, Teater Populer, Teater Kecil, Teater Alam –untuk menyebutkan yang paling dikenal—yang tak lagi ada denyutnya.
Mengamati dari “jauh”, saya menduga yang tak lagi berdenyut itu merupakan grup yang hadir dan populer berkat peran seorang tokoh –mungkin ia pendiri, pemain atau sutradara atau ketiga-tiganya. Maka ketika sang aktor absen untuk seterusnya, dan tanpa penerus yang kira-kira sebanding, grup akan kehilangan penonton.
Kita ingat postulat klasik: tanpa penonton tidak ada teater. Bahkan istilah “teater tanpa penonton” pun bukannya tidak ada penonton sama sekali, melainkan karena penonton menjadi bagian dari pertunjukan. Dan penonton datang ke pertunjukan karena ada yang mau ditonton, dan “ada yang mau ditonton” kurang lebih merupakan juga upaya dari orang-orang yang tak muncul selama pertunjukan berlangsung –lazimnya, mereka hanya tampil di akhir pertunjukan.
Saya melihat, grup teater memang bukan hanya pemain dan naskah, dan sutradara, dan segala yang terkait dengan yang tampak di panggung atau arena. Yang tak tampak di panggung atau arena pun juga orang-orang yang menjadikan pementasan berlangsung sukses. Singkat kata, “ada yang mau ditonton” tidak terbentuk hanya oleh mereka yang tampil di pertunjukan. Mungkin hal mereka yang tidak tampil di pertunjukan dan kinerjanya tak disadari benar oleh (yang bakal menjadi) penonton. Padahal, minat penonton sebenarnya juga dibangun oleh orang-orang yang tak tampak di pertunjukan. Alhasil sebuah grup teater yang berusia panjang adalah sebuah segitiga yang dibentuk oleh mereka yang tampak di pertunjukan, dan mereka yang tak tampak, ditambah sisi ketiga adalah penonton. Segitiga ini tidak hanya terlihat di saat pertunjukan, juga sebelum pertunjukan. Sebuah grup bisa berpotensi menyuguhkan pertunjukan yang apresiatif bila ketiga sisi segi tiga itu rutin “beraktivitas” –dalam makna yang luas– bukan hanya kala mau pementasan. Segitiga akan eksis sepanjang waktu bila ketiga sisinya saling terhubung.
Koma adalah segitiga itu. Ketiga sisi saling berhubungan, saling mendukung, saling membentuk. Teater koma bukan hanya Riantiarno (mendiang), Ratna, Sari Madjid, Salim Bungsu, dan lain-lain. Ada juga penata panggung, kostum, rias, lampu dan sebagainya. Dan, penonton yang selalu disapa, dengan newsletter dan lain-lain cara.
Maka, herankah kita bahwa Mencari Semar adalah produksi ke-230-sekian dalam kurun hampir setengah abad? Sebuah pementasan dengan napas mutakhir, dengan teknologi multimedia yang menghadirkan dunia “angkasa luar” dengan kehidupan di planet lain, mungkin? Inilah berkat segitiga yang terpelihara apa pun yang terjadi.
Bila toh kita melihat, misalnya bahwa dialog di panggung tidak serasi dengan dunia “angkasa luar” itu, kita bisa berharap pada pementasan selanjutnya keserasian itu bakal terwujud. Bila misalnya dialog-dialog kurang membuat kita menunggu apa yang akan terjadi berikutnya –seperti misalnya pada Opera Ular Putih 30 tahun lalu—namun dialog-dialog itu rasanya masih nyambung membangun cerita.
Saya rasa, soal dialog adalah soal naskah. Ada satu hal yang tersimpan dalam ingatan saya, sebanyak pementasan Teater Koma yang saya tonton, pementasan dengan naskah terjemahan atau adaptasi hampir selalu melegakan; artinya, bagus. Maka Bom Waktu, naskah asli karangan Riantiarno adalah sebuah perkecualian yang mesti dicatat.
Teater Koma memang belum titik. Segitiga itu masih kukuh, masih terpelihara. Melihat Merncari Semar dengan multimedianya, segitiga ini saya rasa bisa menjadi sebuah teater urban yang bisa manggung rutin dan menghibur para urbanis dan generasi Z dan selanjutnya. Dengan perbandingan agak “dipaksakan”, dulu, tahun 1950-an, adalah dua segitiga pertunjukan yang kukuh. Grup Wayang Orang Sriwedari di Solo dan Wayang Orang Ngesti Pandawa di Semarang. Pada zamannya, dua teater ini adalah teater kota idaman seluruh warga. Pementasan selalu diminati penonton dan menjadi pembicaraan sehari-hari. Ya, ceritanya, pemainnya, dekornya dan banyak lagi. Satu hari dari lima hari pertunjukan Mencari Semar, konon di antara penton adalah beberapa anggota Wayang Orang Sriwedari. Mereka mau belajar, mengapa Teater Koma belum titik.
***
*Bambang Bujono. Penulis Peristiwa Kesenian.