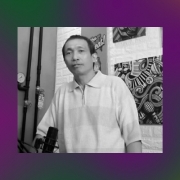Membaca Kebisingan di Forum Bukan Musik Biasa #98
Oleh Wahyu Thoyyib Pambayun
Menuju usianya yang hampir mencapai 17 tahun, Forum Bukan Musik Biasa (BMB) yang digagas oleh Wayan Sadra telah menjelma menjadi wadah yang konstruktif, di mana para komponis musik dapat mengadu ide, gagasan, dan eksperimen inovatif mereka. Forum musik dan dialog dwibulanan yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) Surakarta ini telah menampilkan puluhan komponis dan kelompok musik dengan latar belakang yang beragam.
Karya-karya yang ditampilkan di BMB tidak sekedar untuk dinikmati semata, melainkan juga diposisikan untuk dipahami dan dimengerti secara mendalam. Pendekatan khusus dalam mengapresiasi musik di forum ini tercermin dari kesediaan untuk terbuka terhadap ragam jenis musik, sudut pandang, dan gagasan. Sikap terbuka ini juga menjadi modal utama bagi para penampil dalam menerima tanggapan dan kritik, yang pada akhirnya memacu mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas karyanya.
Pada Forum BMB edisi ke-98 yang diselenggarakan pada 25 Maret 2024, menghadirkan 3 penampil, yaitu Srangan Fajar dari Surakarta, Rezja Dwi HVFT dari Purwokerto dan Seakar dari Pacitan. Ketiganya menggunakan bunyi-bunyi bising sebagai medium ekspresinya.
Mengandalkan Kebetulan
“Apa yang akan terjadi dalam satu detik kemudian, satu menit kemudian, sepuluh menit kemudian, dan seterusnya adalah sesuatu yg tidak pasti dan penuh dengan kemungkinan”
Inilah kutipan pendek dari teks pengantar “What If?” karya dari Srangan Fajar. Ia menawarkan konsep improvisasi bebas dan mencoba bermain-main dengan kemungkinan-kemungkinan. Sebagai sebuah konsep, “musik kebetulan” atau “chance music” yang ditawarkan oleh Fajar tidak baru. Konsep “musik kebetulan” dapat ditelusuri kembali ke abad 20, terutama melalui kontribusi dari para komponis eksperimental seperti John Cage, Iannis Xenakis, dan Karlheinz Stockhausen. Pada awalnya, “chance music” muncul sebagai bagian dari gerakan eksperimental yang bertujuan untuk membebaskan musik dari struktur dan aturan yang baku di zaman itu.

Penampilan Srangan Fajar (Sumber; Dok @syakhirul5 BMB #98)
Betapa bahagianya melakukan sesuatu tanpa melakukan kesalahan. Barangkali itulah yang hendak disampaikan oleh Fajar. Ia menjelma menjadi anak-anak yang asyik sendiri dengan mainannya, memutar knob, bermain volume, meniup peluit “prat-prit-prat-prit”. Bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak prima, tinggi rendah campur bawur, pengaturan keras-lirih nampak kurang cermat, mendhem bak dalam gua. Pada suatu titik, anak itu mulai jenuh, bingung dan barangkali kehabisan akal, kemudian ia berteriak keras, memukul-mukul mainnannya, melempar dan membanting alat-alat yang ada di depannya. Ya, fajar benar-benar menghancurkan alat-alat yang ia gunakan. Dengan menghancurkan “instrumen” penghasil noisenya, Fajar seolah menghilangkan relasi “kasih sayang” antara pemusik dan alat musiknya. Lagi-lagi, atraksi menghancurkan alat musik juga bukan sesuatu yang baru. Musisi seperti Jimi Hendrix, Paul Stanley dan Kurt Cobain, menggunakan atraksi menghancurkan gitar dalam aksi panggungnya. Semoga si “what if” ini tak abai pada peristiwa di masa lalu.

Aksi Panggung Srangan Fajar (Sumber; Dok @syakhirul5 BMB #98)
Seolah tak puas sampai di situ, fajar masih melanjutkan bermain-main dengan alat yang tersisa, bunyi yang dihasilkan dan pengolahannya tak jauh beda dengan sebelumnya. Bunyi terus mengalun tak terkendali, mungkin itulah yang ia anggap ketidakpastian. ia nampak mulai gelisah dan bingung mencari cara bagaimana mengakhiri pertunjukan. Akhirnya ia melambaikan tangan, memberi tanda kepada operator sound untuk segera mengecilkan volume speaker. Dan pertunjukan pun akhirnya bisa selesai. Itulah kebetulan, tapi kebetulan yang tidak diharapkan. Apa yang hendak disampaikan oleh Fajar melalui aksi panggungnya itu? Dari 1001 kemungkinan yang ada, mengapa ia memilih menghancurkan perangkat yang ia gunakan? Bagaimana jika aksi panggung itu hanya gimmick belaka? Dalam sesi diskusi, Fajar nampak gagap dan belum mampu memberikan sudut pandang, gagasan dan alasan-alasan yang gamblang atas apa yang ia perbuat di panggung. Fajar bingung, penonton juga bingung. Ia masih muda, pengalaman kelak akan mendewasakannya, bahwa modal nekat saja ternyata belum cukup.
Presisi
Berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Srangan Fajar, penampil kedua yaitu Rezja Dwi HVFT menampillkan karya yang matang. Ia terlihat sangat menguasai alat-alatnya, sehingga bunyi yang dihasilkan tampil dengan terperinci. Seperti seorang gitaris yang butuh latihan panjang, seorang praktisi noise juga memerlukan waktu intensif untuk menguasai alatnya. Rezja mampu mengontrol efek pedalnya dengan presisi, sehingga bunyi yang dihasilkan sesuai dengan sistem tata suara yang ada, tanpa ada peak atau volume yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah mempertimbangkan dengan matang ruang presentasinya dan berupaya agar tidak merusak sistem tata suara yang telah disediakan.

Penampilan Rezja HVFT (Sumber; Dok @syakhirul5 BMB #98)
Kelihaian dalam mengatur dinamika patut diapresiasi, dimana ia mencoba mengelola dualitas secara cermat, bunyi yang keras-lirih, pekat-cerah, berat-ringan, kanan-kiri di organisir sehingga pilah penataan ruang bunyinya. Ia mampu membuat dua dunia yang berbeda berjalan beriringan. Bunyi lembut dengan frekuensi rendah dibiarkan terus menyala sepanjang karya. Sedangkan bunyi kasar nan pekat muncul secara patah-patah mengitarinya. Tiba-tiba muncul ritme yang tegas kemudian memuncak lalu tiba-tiba berhenti, hening sejenak. Ia memberikan kesempatan kepada audiens untuk menghela nafas dan menikmati keheningan. Justru di momen jeda hening sekian detik itu, terasa kenikmatan, ngrasakke kuping’e bolong, ketenangan pasca mendengarkan yang riuh. Karya Rezja melemparkan imaginasi pada pengalaman menyaksikan film Zone of Interest karya Jonathan Glazer. Film ini memenangkan Academy Awards ke-96 untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik. Film ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Komandan Kamp Konsentrasi Auschwitz yang membangun rumah mewah di samping kamp konsentrasi. Ia menjalani hidup bahagia bersama istri dan anaknya di rumah mewah itu. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di kamp konsentrasi. Di tengah gemuruh jeritan dan tembakan dari kamp konsentrasi Auschwitz yang menghantui sekitarnya, keluarga Komandan Kamp Konsentrasi, yang menikmati kehidupan bahagia di rumah mewah mereka, tampaknya hidup dalam realitas yang terpisah. Rumah mereka adalah sebuah oasis dari kengerian yang terjadi di sebelahnya, sebuah tempat di mana bayangan pembantaian dan penderitaan tampaknya tidak dapat merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, keluarga itu abai terhadap genosida yang terjadi di sekitarnya. Kenyataan bahwa keluarga dalam film tersebut tampak abai terhadap genosida yang terjadi di sekitarnya, mencerminkan juga bagaimana kita, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali bisa “membuang” realitas yang tidak nyaman atau tragis di sekitar kita, Film ini mampu mengetuk nurani, sebagaimana rekayasa dualitas yang ditawarkan oleh Rezja melalui karya noisenya.
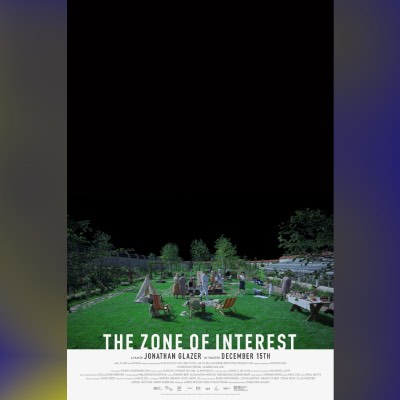
Official Poster Zone Of Interest (Sumber; a24.com)
Kolase
Spirit kolaborasi berusaha disampaikan oleh Seakar dengan menampilkan karya berjudul “Hiruk Pikuk”. Seakar berkolaborasi dengan pemusik tradisi, penari dan pelukis. Pada bagian awal karya, garapan musiknya masih mendasarkan pada kesesuaian “harmoni” tonal diatonis dan pelog jawa, vokal uran-uran jawa belaras pelog diiringi bunyi drone tipis memberikan kesan ngawang-awang mengambang dan mengakasa. Pada bagian selanjutnya, Seakar mencoba memasukkan instrumen tradisi seperti suling dan terompet pencak sunda dalam bangunan komposisi bunyi elektronik. Sayang hasilnya tidak padu.

Penampilan Seakar (Sumber; Dok @syakhirul5 BMB #98)
Instrumen tradisi masih diposisikan sebagai pelengkap. Bunyi instrumen tradisi yang lirih tak mampu berbuat banyak berhadapan dengan bunyi hasil olahan elektronik yang keras. Penggabungan instrumen belum dikerjakan dengan maksimal. Seakar juga mencoba menampilkan idiom semacam shalawatan dalam karyanya. Barangkali Ia mencoba menyesuaikan penampilannya dengan bulan Ramadhan. Pengolahan atribut agama dalam karya memang penuh resiko. Penetrasi vokal bergaya timur tengah masih terasa sebagai tempelan. Pun juga penampilan penari dan pelukis yang seakan numpang lewat dan belum menjadi satu kesatuan pertunjukan yang utuh. Namun, ketidakutuhan dan ketidakpaduan antar berbagai unsur itu, justru berhasil mencitrakan “hiruk pikuk” sesuai dengan judul karyanya. Semoga itu memang dilakukan dengan penuh kesadaran dan dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran yang fundamental.

Pelukis dalam karya Hiruk Pikuk (Sumber; Dok @syakhirul5 BMB #98)

Penari dalam karya Hiruk Pikuk (Sumber; Dok @syakhirul5 BMB #98)
Forum BMB telah berhasil menjadi ruang presentasi karya yang dinamis. Perayaan Forum BMB ke-100 akan diselenggarakan pada bulan Juli 2024, momen yang tepat untuk melakukan sesuatu yang besar. Semoga ada wacana baru yang dihembuskan. Panjang umur musik seni. Panjang umur kebebasan berekspresi.
*Komponis dan Pengajar di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta