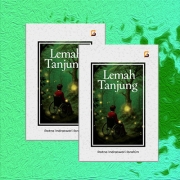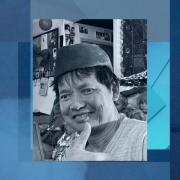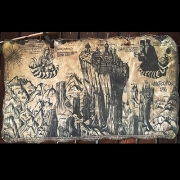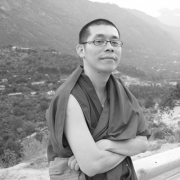Jazz yang Disembah: Festival, Pasar, dan Ingatan Kolektif yang Tergerus Zaman
Oleh Mukhlis Anton Nugroho*
Saya tidak pernah menyangka bahwa perbincangan soal jazz—genre yang biasanya hidup dalam lorong sunyi ruang jam session dan percakapan musikal para musisi jazz di panggung yang mungkin jauh dari gemerlap—akan menyentuh lapisan emosi publik seperti yang terjadi belakangan ini. Dalam waktu singkat, kata “jazz” mendadak keluar dari klub dan ruang dengar, menyeberang ke laman media sosial, headline berita, hingga kolom komentar netizen mulai dari yang halus hingga brutal. Semua bermula dari satu kalimat sederhana yang diunggah oleh Indra Lesmana: “Tanpa jazz, festival jazz kehilangan jiwanya.”
Pernyataan itu bukan sekadar gugatan tentang susunan panggung atau daftar penampil dalam festival berlabel jazz. Ia memantik kembali pertanyaan lama yang sering tak kita selesaikan: untuk siapa musik diciptakan? Untuk siapa festival digelar? Apakah musik ada demi dirinya sendiri, atau demi tiket, grafik penonton, dan warna-warni lampu sorot? Apakah festival jazz masih tentang jazz, atau telah menjadi nama tanpa isi, sebuah etiket pasar?
Dikotomi klasik antara “seni untuk seni” dan “seni untuk komersial”—atau dalam kasus ini, musik untuk musik dan musik untuk industri—tiba-tiba terasa sangat dekat, bahkan menyesakkan. Di satu sisi, kita mendambakan musik yang bebas, liar, dan jujur, yang tak tunduk pada algoritma atau hitungan sponsor. Tapi di sisi lain, kita hidup dalam dunia di mana panggung butuh dana, artis butuh promosi, dan festival perlu eksistensi sosial agar bisa berlangsung. Polemik Prambanan Jazz mengandung lebih dari sekadar keluhan teknis. Ia adalah gejala dari ketegangan zaman, antara romantisme bunyi dan realisme ekonomi. Antara suara minoritas musisi jazz yang merasa terpinggirkan, dengan semangat kurator yang ingin menciptakan ruang yang inklusif dan cair.
Sri Hanuraga, seorang pianis dan pemikir muda jazz Indonesia, menulis bahwa jazz sejatinya bukan genre, melainkan organ eksosomatis—ekstensi budaya dari tubuh komunitas Afrika-Amerika yang tertindas. Jazz bukan semata teknik improvisasi atau progresi akor yang kompleks, melainkan cara bertahan hidup, cara memberi suara bagi yang dibungkam. Dalam logika ini, mengusung nama “jazz” tanpa ruhnya adalah penghapusan ingatan—sebuah bentuk kekerasan estetika yang senyap. Namun kurator festival, Anas Alimi, tak kalah tulus dalam visinya. Ia menyatakan bahwa Prambanan Jazz bukan ingin menjadi panggung yang steril dan eksklusif. Ia ingin menjadi ruang, tempat “Miles Davis tak keberatan duduk di bangku penonton ketika Nasida Ria membawakan lagu perdamaian dalam balutan non jazz.” Ia tidak ingin menyembah jazz, tapi menghidupinya. Jazz bukan museum, katanya, melainkan napas.
Di titik inilah persoalan menjadi kompleks sekaligus penting untuk direnungkan. Apakah keterbukaan genre justru menghapus makna? Apakah inklusivitas harus dibayar dengan penghilangan sejarah? Dan bisakah ruang komersial merawat estetika yang lahir dari luka? tulisan ini mencoba menelusuri pertanyaan-pertanyaan tersebut namun bukan untuk menjawab secara mutlak, melainkan untuk merayakan ketegangan antara idealisme dan realitas, antara bunyi yang murni dan ruang yang berisik.
Jazz sebagai Ruang Sejarah dan Perlawanan
Jazz tidak lahir dari studio rekaman atau panggung yang penuh gemerlap. Ia lahir dari lorong-lorong penderitaan dan kebudayaan yang tercerabut. Musik ini adalah anak dari sejarah: sejarah perbudakan, peminggiran, dan pencarian identitas dalam masyarakat Afrika-Amerika yang terpinggirkan. Maka, ketika kita menyebut “jazz”, sejatinya kita sedang menyebut sebuah ingatan kolektif tentang bagaimana bunyi bisa menjadi tempat tinggal ketika rumah telah dirampas.
Dalam tulisannya yang reflektif, Sri Hanuraga mengingatkan kita bahwa jazz bukan sekadar gaya musikal. Ia adalah kosmos nilai dan laku performance practice, interaksi sosial, dan mode eksistensi yang meminjam tubuh sebagai tempat bicara. Ia mengutip istilah “organ eksosomatis”, yang menggambarkan jazz sebagai perpanjangan tubuh sosial yang memungkinkan kelompok tertindas untuk tetap eksis, didengar, dan diingat.
Jazz juga bukan entitas yang beku. Sejarahnya adalah sejarah mutasi dan pembauran. Charlie Parker mengawinkan bebop dengan struktur klasik Eropa. Herbie Hancock membawa jazz ke ranah elektronik dan funk. John Coltrane mengisap esensi Stravinsky ke dalam idiom improvisasi. Bahkan hari ini, musisi seperti Mark Guiliana dan Steve Lehman menjalin jazz dengan drum machine, spectral music, dan hip-hop. Inilah watak dasar jazz: bergerak, menyerap, menolak dikurung.
Namun, mutasi bukan berarti kehilangan akar. Ia justru menguatkan dasar, karena ia tumbuh di atas sejarah perjuangan. Itulah mengapa banyak musisi jazz merasa resah ketika festival yang mengusung nama “jazz” tak lagi menyisakan ruang bagi mereka. Yang terganggu bukan semata giliran tampil, melainkan kehilangan legitimasi atas identitasnya sendiri. Ketika jazz dikaburkan menjadi “tema festival”, bukan “isi festival”, maka yang hilang bukan sekadar genre, tapi jejak dan ingatan budaya.
Di sinilah letak pentingnya memahami bahwa musik tidak pernah bebas nilai. Musik selalu membawa beban sejarah, tubuh sosial, dan relasi kuasa. Menempatkan musik hanya sebagai hiburan atau komoditas adalah mereduksi potensi terbesarnya: sebagai alat berpikir, bertahan, dan merawat dunia batin manusia. Dalam pengertian inilah, jazz menjadi contoh paling kuat dari “musik untuk musik”, yakni musik yang ada bukan untuk melayani pasar, tetapi untuk menghidupi makna. Dan ketika makna itu terancam oleh tuntutan sponsorship dan algoritma popularitas, muncul pertanyaan tak terhindarkan: bagaimana cara mempertahankan ruh jazz di ruang festival yang kini semakin digerakkan oleh logika pasar?
Festival sebagai Ruang Komodifikasi dan Negosiasi
Tak ada festival yang bebas dari logika ekonomi. Bahkan festival yang lahir dari semangat komunitas sekalipun, pada akhirnya harus berdamai dengan panggung, listrik, promosi, logistik, nasi kotak, refreshment artis, dan yang terberat ekspektasi pasar. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh banyak penyelenggara festival musik hari ini: bagaimana menjaga integritas artistik tanpa mengabaikan keberlanjutan finansial?. Prambanan Jazz bukan satu-satunya festival yang harus menapaki jalur ini. Tapi posisinya menjadi istimewa karena memilih membawa nama “jazz” dalam branding utamanya. Nama itu bukan sekadar istilah, melainkan warisan kultural. Maka ketika festival ini menampilkan lebih banyak musisi pop, nostalgia, hingga idol grup, kritik pun muncul bukan hanya dari persoalan lineup, melainkan dari kegelisahan akan makna dan identitas.
Dewa Budjana, musisi yang hidup dalam dua dunia—jazz dan industri—menyuarakan kegelisahan tersebut dengan suara tenang namun tajam. Ia menyayangkan minimnya ruang bagi musisi jazz muda yang justru sedang bertumbuh, dan menyoroti ketidakseimbangan dalam kurasi. Dalam catatannya, ia tidak mengutuk keterbukaan genre, tapi mengajak berpikir ulang tentang prioritas dan proporsi. Jazz, dalam ruang bernama jazz, mestinya tetap diberi tempat utama, atau setidaknya sejajar. Namun, dalam bayangan Anas, jazz adalah napas yang dihidupi. Bukan soal chord progresi yang rumit, melainkan apakah musik itu bisa menyentuh, meski hanya dalam tiga menit. Ia tahu bahwa festival butuh sponsor, artis besar, dan angka. Tapi ia percaya: jika kita setia pada mimpi, angka akan datang. Dan kalaupun tidak, biarlah. Asalkan suara tetap punya tempat dalam dunia yang makin bising.
Di sinilah kita melihat bahwa persoalan ini bukanlah pertentangan antara “yang tulus” dan “yang menjual”, tapi sebuah titik negosiasi antara idealisme artistik dan realitas produksi budaya. Festival musik hari ini berada dalam tegangan antara musik untuk musik dan musik untuk industri. Di satu sisi, ia ingin merayakan ekspresi. Di sisi lain, ia dituntut untuk laku. Dan keduanya, mau tak mau, harus berdialog dalam satu ruang yang sama. Pertanyaannya bukan lagi: “apakah festival ini murni jazz?”, tapi “apakah festival ini masih menyisakan ruang bagi suara yang tak populer, namun penting?” Apakah ia masih sanggup mengangkat musisi jazz muda yang tanpa manajer dan label, tapi punya suara yang pantas mengisi udara di atas panggung megah berlatar candi, dan langit malam yang syahdu aduaii?
Improvisasi yang Jujur dalam Ruang yang Berubah
Barangkali kita terlalu sering memaksa ruang budaya untuk tunduk pada satu definisi. Kita ingin festival yang murni, tapi juga ramai. Kita ingin musik yang jujur, tapi juga viral. Kita ingin panggung yang sakral, tapi juga menghibur. Kita berharap jazz tetap hidup, namun tidak selalu sanggup mendengarkan bisikannya di antara kebisingan industri.
Namun justru di dalam ketegangan inilah, makna sering kali lahir. Polemik Prambanan Jazz bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang lebih berhak atas nama jazz. Ini adalah refleksi bersama tentang apa arti “ruang” bagi musik hari ini. Apakah festival masih bisa menjadi rumah bagi suara yang tak selalu menjual, tetapi bermakna? Apakah kita masih punya keberanian untuk memelihara suara yang rapuh, minor, dan mungkin hanya dipahami oleh segelintir orang, tapi menyimpan kejujuran yang utuh?
Kita hidup di masa di mana algoritma lebih cepat dari sejarah, dan popularitas bisa membungkam substansi. Tapi justru karena itu, kita memerlukan ruang-ruang yang berani berdiri di tengah arus. Ruang yang tak hanya menjual bunyi, tapi menyediakan tempat bagi ingatan, keberagaman suara, dan kemungkinan baru dalam musik. Festival, dalam bentuk terbaiknya, bukan hanya tentang susunan penampil. Ia adalah medan tafsir budaya, di mana nilai-nilai lama dan baru saling bertemu. Di sanalah musik tak sekadar dimainkan, tapi dihidupi dengan peluh, debu, gerimis kecil, dan panasnya matahari.
Maka mungkin yang kita perlukan bukan festival yang sepenuhnya “jazz” atau sepenuhnya “pasar”, melainkan festival yang punya kejujuran kuratorial dan keberanian etis. Festival yang tahu akar sejarahnya, tapi juga mendengar detak zaman. Festival yang mau menjadi tempat bertemunya bunyi dan manusia, meski tak sempurna tapi tetap setia. Karena pada akhirnya, seperti jazz itu sendiri, festival adalah tentang improvisasi yang jujur dalam ruang yang terus berubah. Dan semoga, dalam Gong suwuk terakhir malam di antara candi dan bintang, kita masih bisa mendengar yang tersisa dari mimpi: bahwa musik, entah untuk seni atau untuk komersial, tetaplah bunyi yang mencari rumahnya.
—–
*Mukhlis Anton Nugroho. Mahasiswa Program Doktoral Pengkajian Seni Musik, Institut Seni Indonesia Surakarta.