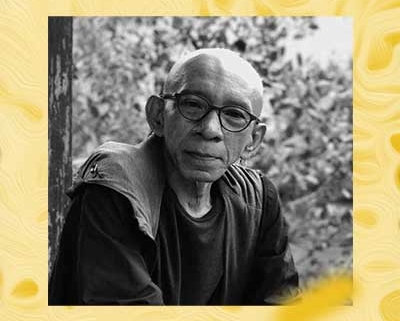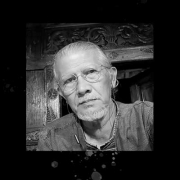Jangan Mengambil Nasi Dari Mulut Orang Lain
Epik dari Teater Kita Makassar
Oleh Afrizal Malna*

Ikan dalam mulut aktor. Pertunjukan kolaborasi Teater Kita Makassar: “Tragos Of Bagang”, Arts Festival Sanggar Merah Putih, 2013. (Foto: dokumentasi Teater Kita Makassar)
Generasi 70-an hingga 90-an merupakan jejak yang mewarnai tumbuhnya teater epik di Makassar. Generasi ini melibatkan kehadiran seniman-seniman teater Makassar seperti Rahman Arge, Aspar Paturusi, A.M. Mochtar, Yudhistira Sukatanya, Yacob Marala, dan Fahmi Syarif.1 Asia Ramli Prapanca yang menjadi fokus tulisan ini bersama dengan Teater Kita Makassar, merupakan generasi dekade 90-an yang ikut terbentuk dalam iklim ini. Merupakan periode cukup panjang di mana terjadi kolaborasi intens antara teater dan sejarah. Historiografi Bugis, Makassar, maupun La Galigo merupakan rujukan utama mereka, termasuk Orang Laut (Bajau) maupun pelaut Bugis sebagai representasi budaya maritim yang membentuk sejarah Sulawesi.
Tema sejarah ini pada masanya eksis, karena seolah-olah mampu mengisi kebutuhan hubungan antara teater dan politik pada masa rezim Orde Baru yang otoriter. Dua situs di Makassar, yaitu Benteng Somba Opu dan Benteng Fort Rotterdam, menjadi rujukan utama ruang sejarah sekaligus sebagai ruang pertunjukan bersama dengan gedung kesenian Societeit De Harmonie yang letaknya tidak terlalu jauh dari Benteng Fort Rotterdam. Ruang sejarah ini, yaitu Benteng Fort Rotterdam, Benteng Somba Opu, gedung kesenian Societeit De Harmonie, dan kemudian pantai Losari, ikut membentuk iklim kreativitas seni di Makassar. Masa di mana teater juga ikut memperjuangkan dikembalikan nama kota dari Ujung Pandang menjadi Makassar.
Ruang sejarah ini kini kian berubah setelah komersialisasi lahan di pantai Losari berlangsung ugal-ugalan. Memutus hubungan langsung antara Benteng Fort Rotterdam dengan laut serta dermaga tua masa Hindia Belanda. Seniman-seniman di Makassar, hingga kini, kehilangan ruang bersama mereka yang tak tergantikan. Ruang di mana sejarah Makassar pernah menopangnya. Dan membentuk ekosistem seni yang mempertemukan ruang kota dengan situs sejarah, alam (pantai Losari), dan aktivitas seni.
Teriakan, permainan silat dan tombak, serta gendang pakkanjara (Genderang Perang Mangkassara) banyak mengisi pertunjukan-pertunjukan teater epik ini. Alih-alih menjadikannya sebagai dapur budaya dimana tradisi Bugis, Makassar (musik maupun tari) mengalami revitalisasi melalui pertunjukan-pertunjukan teater epik ini. Mitos perlawanan pahlawan-pahlawan Gowa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang mempertahankan benteng dari serangan VOC, cukup luas bisa kita dengar dari seniman-seniman teater pada masanya.
Masih berbasis lingkungan kampus IKIP Ujung Pandang (kini Universitas Negeri Makassar), Asia Ramli Prapanca kemudian membentuk Teater Kita Makassar, tahun 1993. Kehadiran mereka membuka belokan baru dalam sejarah teater di Makassar, yaitu mulai menjadikan teater sebagai ruang eksperimentasi berbasis tradisi. Mereka membuat pertemuan unik antara tradisi Bugis maupun Makassar dengan kehidupan urban Makassar.

Ikan dalam mulut aktor. Dalam pertunjukan kolaborasi Teater Kita Makassar: “Tragos Of Bagang”, Arts Festival Sanggar Merah Putih, 2013. (Foto: dokumentasi Teater Kita Makassar)
Asia Ramli sendiri lahir dan dibesarkan dalam tradisi Bugis pesisir di desa nelayan, Usuku, Buton (Sulawesi Tenggara), bersama warisan sastra lisan yang kaya. Kemudian hidup berpindah-pindah di Banyuwangi, Pasuruan, Ambon, lalu mulai menetap di Makassar ketika mulai kuliah di Universitas Negeri Makassar.
Beberapa pertunjukan awal Teater Kita Makassar, Namaku Batu (1993), Etalase Bulan Sabit 1 (1993), Berdiam Dalam Batu (1994), Di Atas Puing-puing (1994), Namaku Batu II (1995), Nyanyian Kubur (1995), Manusia Dalam Karung (1996), Kavling 2M² (1996), Perempuan di Atas Piring (1996), Mungkin Tentang Kita (1997), BAH (Bah Atas Bah Bawah) (1997), Songka Bala Penghuni Pulau (1998), juga bisa dilihat di mana Teater Kita Makassar mulai mengusung politik identitas yang sangat penting dalam sejarah Bugis maupun Makassar.2 Material yang banyak digunakan dalam pertunjukan mereka juga khas, lokal seperti bambu, batu, api, daun kelapa, buah kelapa, kain sarung, maupun alat penangkap ikan terbuat dari bambu. Masa di mana Asia Ramli (sebagai sutradara) banyak melakukan kolaborasi dengan Is Hakim, Halilintar Lathief,3 maupun Malhamang Zamzam.

Pertunjukan Teater Kita Makassar: “Pelayaran Menuju Ibu (Jangan Lupakan Warna Merah)”, dalam Festival Teater Rakyat Indonesia, 7 November 2009, Gedung Teater Cak Durasim, Surabaya. (Foto: Dokumentasi Teater Kita Makassar)
Iklim eksperimentasi dalam seni pertunjukan ini, mendapat garis tebalnya melalui kehadiran perupa dan seniman performance art (Firman Djamil), kemudian Sanggar Merah Putih bersama Shinta Febriany membentuk Joma (Journal of Moment Art) tahun 2000, dan membawa warna lain dalam sejarah seni pertunjukan di Makassar.4
Reformasi, yang oleh Teater Kita Makassar ditandai melalui pertunjukan mereka, Songka Bala Penghuni Pulau, merupakan sebuah titik penting di mana tema Reformasi kemudian menghadapi isu baru dalam memasuki milenium baru dan globalisasi. Entah apa yang terjadi, pada masa ini pertunjukan-pertunjukan berbasis eksperimentasi dalam teater tampak mulai kehilangan suaranya. Tumbuhnya generasi baru, yaitu Gen Z, yang sebagian besar kemampuan, keahlian, dan juga momorinya mulai dilimpahkan kepada aplikasi teknologi digital maupun internet. Mereka menggunaan media sosial sebagai representasi dan distribusi identitas. Proses kreatif berbasis tubuh dan pengalaman mulai bergeser menjadi proses kreatif berbasis teknologi.
Tahun 2000-an, terutama setelah pertunjukan The Eyes of Marege (2007), yang dipentaskan dalam Festival OzAsia di Adelaide Festival Centre, dan di Studio Opera House Sydney, Teater Kita Makassar terkesan kembali menempuh jalan teater epik. The Eyes of Marege sendiri merupakan perpanjangan dari proyek pertunjukan sebelumnya, yaitu The Crocodile Hotel (2003). Pertunjukan yang membuat hubungan historis antara pelaut-peluat Bugis dengan Aborigin yang sudah berlangsung lama. Juga menandai kolaborasi Teater Kita Makassar dengan seniman Australia (Julie Janson dan Sally Sussman). Dan sebelumnya dengan seniman Perancis, Roland Ganamet.

Suasana pasar dalam pertunjukan Teater Kita Makassar: “Sultan Hasanuddin”. (Foto: dokumentasi Teater Kita Makassar)
Pertunjukan Sultan Hasanuddin (Ayam Jantan dari Timur), yang berlangsung 26 November 2024, di Kampus Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, kian mempertebal kehadiran Teater Kita Makassar dalam melanjutkan tradisi teater epik di Makassar. Pertunjukan ini, yang merupakan bagian dari program Kementerian Kebudayaan Fasilitasi Bidang Kebudayaan untuk Teater Kepahlawanan 2024, merupakan pertunjukan yang ke 53 Teater Kita Makassar. Sebuah kelompok teater yang usianya sudah memasuki tahun ke 31.
Pertunjukan menghadirkan dua realitas visual yang saling melengkapi. Pertama, panggung teater itu sendiri yang menjadi tatapan utama di mana penonton mengikuti pergerakan alur pertunjukan. Dan kedua, merupakan dua bidang datar putih di bagian belakang panggung yang disusun menyerupai tipografi benteng. Bagian kedua ini berfungsi sebagai layar video mapping maupun animasi, di mana representasi sejarah maupun arsip-arsip sejarah di sekitar Perang Makassar antara Kesultanan Gowa (Sultan Hasanuddin) dan VOC didistribusi sebagai arus visual pertunjukan.
Dalam sejarah Makassar, ada tiga kali serangan VOC terhadap Gowa: pertama tahun 1660, kemudian tahun 1667 di mana Sultan Hasanuddin akhirnya terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya yang merugikan Gowa. Lalu tahun 1669, di mana Sultan Hasanuddin wafat dan Benteng Somba Opu jatuh ke tangan VOC.

Adegan perang dalam pertunjukan Teater Kita Makassar: “Sultan Hasanuddin”. (Foto: dokumentasi Teater Kita Makassar)
Pertunjukan dibuka dalam suasana hening dan mistis. Kemudian mulai terdengar pembacaan sinrilik, yaitu kisah tentang Sultan Hasanuddin dalam bahasa Makassar, dinyanyikan oleh Angelita yang mengenakan busana perempuan Bugis. Pembukaan pertunjukan ini mempertegas performativitas sejarah sebagai sastra lisan, maupun sejarah Perang Makassar yang ditatap dalam sudut pandang perspektif lokal. Dalam babak pertama ini juga diperlihatkan bagaimana Sultan Hasanuddin dibentuk dalam tradisi Islam yang kuat. Di sisi lain tentang kehidupan pasar di pelabuhan, memperlihatkan ragaman budaya di mana Makassar tumbuh sebagai kota pelabuhan yang kosmopolit. Juga berlangsung hubungan setara antara perempuan dan lelaki.
VOC mulai tergoda untuk menguasai Makassar sebagai kota pelabuhan, terutama setelah pelabuhan Malaka diduduki Portugis pada tahun 1511, dan membuat banyak bangsa meninggalkan Malaka dan bermigrasi ke Makassar.5 Diwakili oleh Cornelis Speelman, VOC ingin menguasai Makassar. Menggunakan kota pelabuhan ini sebagai praktik perdagangan monopoli VOC. Terutama monopoli perdagangan rempah. Dan inilah yang ditolak Sultan Hasanuddin yang tetap menjaga Makassar sebagai kota pelabuhan yang terbuka untuk siapapun, tanpa ada monopoli. Apa yang akan dilakukan VOC terhadap Makassar, bagi Sultan Hasanuddin sama dengan “mencuri nasi dari mulut orang lain.”
Pertunjukan teater tari ini dikoreografi oleh Ridwan Aco dan Wahyu Youngdong. Di sini performance sejarah hadir lebih sebagai visual performatif. Tari, antara kelompok perempuan dan lelaki, keduanya berbasis silat lokal dan permainan tombak. Dan musik ditata oleh Arifin Manggau bersama Ahmad Nur. Para penari serta musik memiliki peran penting dalam menciptakan suasana di pelabuhan maupun di pasar, dan sebagai puncaknya dalam adegan perang yang berkecamuk, menjelang Gowa jatuh.

Sultan Hasanuddin dalam adegan akhir pertunjukan Teater Kita Makassar: “Sultan Hasanuddin”. (Foto: dokumentasi Teater Kita Makassar)
Teks pertunjukan lebih banyak didistribusi melalui peran Sultan Hasanuddin yang diperankan oleh Ferdinan, serta para Karaeng sebagai lingkungan terdekat Sultan Hasanuddin. Karaeng Galesong diperankan oleh Djamal Dilaga, Karaeng Karunrung olah Indra Kirana, Karaeng Bontomarannu oleh Djamal Kalam, Daeng Mangalle oleh Arga Batara, I Fatimah Daeng Takontu oleh Mirza, Syekh Yusuf oleh Wahyu Youngdong, Qadi oleh Chaeruddin Hakim. Sementara Cornelis Speelman diperankan oleh Ishakim.
Sebagian para Karaeng, terutama beranggapan bahwa Sultan Hasanuddin seharusnya tidak menyetujui Perjanjian Bongaya. Karena bagi mereka, “kita belum kalah, perang masih berlangsung”, seperti dinyatakan Karaeng Galesong dalam pertunjukan. Tombak dan badik telah menyatu bersama tubuh untuk perang total. Namun bagi Sultan Hasanuddin, tidak perlu lagi banyak korban yang jatuh dari pihak Gowa, karena teknologi perang yang tidak seimbang.
Pertunjukan yang melibatkan seratus lebih personel ini, termasuk seniman maupun tim produksi, disutradarai Asia Ramli Prapanca bersama Alif Anggara. Dramaturg oleh Bahar Merdhu, Azis Nojeng, dan Aco Muhammad. Tapi apa artinya sejarah Hasanuddin di masakini? Kenapa memilih sejarah Sultan Hasanuddin yang historiografinya terkesan telah definitif sebagai historiografi Makassar?
Baiklah.
Menghadirkan kembali epos Perang Makassar di masakini, sebenarnya sama dengan mengukuhkan kembali visi Sultan Hasanuddin bahwa Makassar merupakan kota terbuka untuk keberagaman, termasuk kesetaraan hubungan perempuan-lelaki. Perang Makassar terjadi, justru karena Hasanuddin berusaha mempertahankan visi kota yang akan diubah oleh VOC. Di sini kisah Hasanuddin jadi penting untuk membaca sejarah kota sebagai bagian dari tubuh masakini. Penggunaan teknologi dalam pertunjukan, seperti video mapping, ikut memiliki peran penting bagaimana menghadirkan arsip sejarah sebagai tubuh masakini.
Salah satu yang perlu dibaca ulang dalam pertunjukan ini adalah bagaimana pejabat-pejabat VOC diperankan oleh aktor. Sudut pandang lokal dalam memposisikan nilai-nilai ideologis sejarah perang, selalu membawa resiko di mana peran yang dimainkan sebagai representasi kehadiran VOC, cenderung menghasilkan stereotip bahwa pejabat maupun tentara VOC diperankan mirip preman-preman pasar. Penampilan mereka yang petantang-petenteng, seolah tidak memiliki etika dalam menghadapi seorang Sultan seperti Hasanuddin.
Performance VOC dalam representasi ini seolah-olah tidak memperlihatkan sisi sejarah yang harus dihormati dalam menghadapi lawan, terutama untuk membawa pihak lawan masuk ke dalam perangkap mereka. Kehadiran VOC di sini diperankan oleh Anjas Wirabuana sebagai Abraham Sterck, dan Zein sebagai De Vires. Peran stereotip seperti ini ikut mengurangi dinamika sejarah sebagai bagian bagaimana struktur pertunjukan menemukan arus dalam segi tiga peran teater realis antara protagonis, antagonis, dan deuteragonis yang batas-batasnya bisa dibuat kabur maupun tegas sebagai dinamika antara ilusi dan nalar. Naskah ditulis oleh Ram Prapanca bersama Faisal Yunus.
Video mapping yang digarap oleh Davidson Johns Carlos dan Reza Destavianto, sering kali kemudian harus berbagi ruang atau saling melengkapi dengan peran tata cahaya yang dilakukan oleh Sukma Sillanan. Sekaligus kadang ikut mengurangi peran artistik yang dilakukan oleh Ishakim, Brewok, dan Satriadi. Ruang artistik pada gilirannya memang terkesan lebih banyak hadir sebagai penopang keberadaan video mapping. Perlu semacam kerja kuratorial (alih-alih peran dramaturg) yang bisa membuat kompleksitas jaringan media dalam pertunjukan ini hadir sebagai lanskap pertunjukan dengan garis perubahan (gerak, ruang, maupun cahaya) bersama rasionalisasi artistiknya.
Peran paduan suara oleh Angelita, kemudian, Bicit, Sizi, Nadindah, dan Arya penting untuk membuat unsur audio pertunjukan membuat kategori suara antara suara alam, suara kebudayaan, dan suara politik.
Suara bahwa “Kita belum kalah” dari Karaeng Galesong terus terdengar bersama suara gendang pakkanjara yang ditabuh kian gemuruh menjelang pertunjukan berakhir. Meja tempat Perjanjian Bongaya ditandatangani, kini menjadi tempat untuk Sultan Hasanuddin masuk ke dalam keheningan yang paling dalam di luar suara gemuruh yang paling luar.
Pertunjukan seolah-olah dibiarkan berakhir dalam tegangan dua ruang ini: antara di luar dan di dalam; antara yang diam dan yang gemuruh.***
1 Fahmi Syarif, misalnya, banyak menulis naskah drama berbasis sejarah Bugis. Salah satu bukunya yang terbit, “Trilogi Drama Teropong dan Meriam”, Hasanuddin University Press, Makassar, 2005.
2 Dalam salah satu Lontaraq Luwu, misalnya, Karaengnge Matowae berkata: siapa saja yang negerinya ditaklukkan, maka niscaya tidak diketahui adat leluhurnya, pertanda ia takkan bangkit lagi. Dalam Ahmad Yunus (et. all), “Lontarak Luwu Daerah Sulawesi Selatan”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara 1991/1992.
3 Halilintar Lathief, misalnya, banyak menerbitkan buku. Antara lain: “Seni tari tradisional di Sulawesi Selatan”, Depdikbud, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan, 1995; “Bissu : pergulatan dan peranannya di masyarakat”, Desantara, 2004; “Tari-tarian daerah Bugis”, Institut Press Yogyakarta, 1983; “Orang Makassar”, Padat Daya, Yogyakarta, 2009.
4 Saya membuat catatan cukup panjang mengenai program Joma di Makassar, dalam buku saya: “Performance Art (dan Medan Pasca Seni)”, Diva Press, Yogyakarta, 2022.
5 Leonard Y Andaya, “Warisan Arung Palakka. Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke -17”, Makassar: Ininnawa, 2004; Lihat juga Singgih Tri Sulistiyono, “Dominasi Kolonial dan Diaspora Perdagangan: Pasang-Surut Jaringan Makassar Hingga Masa Akhir Penjajahan Belanda,” Makalah Seminar, Universitas Hasanuddin, 2008.
————
*Afrizal Malna termasuk penyair yang cukup banyak membuat performance puisi melalui media digital. sebagian tersebar dalam channelnya di youtube. Salah satu di antaranya serial “teater masker” yang dibuatnya pada masa pandemi. Sebagian lain diposting melalui akunnya di instagram (@malna.a). Sepanjang 2023 mengikuti forum “Temu Seni Performance Indonesia Bertutur” di Tubaba (Lampung), “Djakarta Theater Platform International“, “Panggung Pantura“ di Semarang, “Festival Kebudayaan Yogyakarta”, “Aruh Sastra Kalimantan Selatan” di Banjarmasin, “Flores Writing Festival” di Maumere, dan “Borobudur Writers & Cultural Festival” di Malang. Buku-buku terbarunya: Performance Art. Dan Medan Pasca-Seni (Diva Press, Yogyakarta 2023); Tiket Masuk Bioskop Autobiografi (JBS, Yogyakarta 2023); Revisi Telur Dadar Mentah (Diva Press, Yogyakarta. 2024); dan Document Shredding Museum. Terjemahan Daniel Owen (New York: World Poetry Books, 2024). Sebagai tokoh seni pilihan majalah Tempo 2020 untuk buku Prometheus Pinball. Sebagai anggota Akademi Jakarta (2020-2025). Afrizal lahir di Jakarta, 7 Juni 1957.