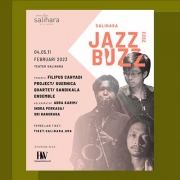Puisi-puisi Abdul Wachid B.S
BALADA BATANG PETUNG YANG HILANG
Di halaman itu
anak-anak bermain bayang sendiri
suara mereka seperti angin
mengejar bentuk yang tak jadi.
Dulu di tengah mereka
ada batang petung berdiri
menadah hujan
menampung cahaya pagi
dan mendengarkan burung jalak bertahlil
sebelum embun benar-benar pergi.
Tak hanya menadah hujan,
ia pernah jadi bende penanda waktu,
menggetarkan malam
ketika leluhur menyeru langit
dengan suara yang tak teriakan.
Tak ada yang mencatat
kapan ia lenyap dari halaman itu
yang pasti bayang anak-anak
tak lagi punya poros
suara pun hanya gema yang berlompatan
dari kaca ke kaca.
Aku pulang.
Tapi halaman itu seperti asing
tak ada yang menyambut selain angin
dan debu yang mengendap di ranting.
Wahai petung,
yang tubuhmu lapuk bukan karena waktu,
tapi karena lupa kami
pada arti tegakmu
yang tak pernah tunduk selain kepada-Nya.
Kini kami hanya punya reranting
dan kebun yang menganga.
Tanda-tanda tak lagi dipacak
langit bicara
tapi tak ada telinga.
Batang petung itu telah hilang
tapi bukankah kita pun tengah patah
di dalam surah-surah bumi
yang tak lagi kita baca?
Kitab pun diam,
sebab tangan kita tak sanggup lagi
menyentuh maknanya.
2025
BALADA AIR DI SELA BATU KARANG
(Untuk Perempuan yang Menyimpan Laut dalam Dadanya)
Ia datang sebelum bayang mentari
dengan langkah kecil seperti titik air
yang sabar memahat karang,
membawa ember dan harap
dari rumah papan
yang berdinding angin asin.
Tangannya adalah doa yang terus berjalan,
mengaduk umpan, mengurai jala,
membisikkan nama-nama Tuhan
ke dalam setiap simpul ikhtiar.
Suaminya telah lama kembali ke pasir
tanpa peluit atau kabar
dan laut tak pernah mengembalikan
selain sunyi yang tak bisa ia jual.
Tapi perempuan itu tak bertanya
mengapa rezeki kadang sembunyi
di balik riak yang tak bisa diraba.
Ia hanya mengulang langkahnya
seperti zikir yang tak butuh alasan.
“Ya Shabur…”
lirihnya kepada bebatuan
yang keras tapi mendengarkan.
“Ya Razzaq…”
bisiknya kepada angin
yang lewat sambil tersenyum asin.
Ia tahu:
air tak perlu memaksa batu
cukup datang berkali-kali
maka karang pun membuka jalan
seperti hati yang rela dititisi
oleh kasih-Nya yang tanpa suara.
Dan bila malam memanggil
dengan tangan gelapnya,
perempuan itu menyalakan pelita
dari dalam dadanya sendiri
karena ia tahu:
cahaya bukan barang jualan,
tetapi anugerah bagi yang sabar
memeluk gelap.
2025
BALADA TUNGGUL WULUNG DI TENGAH PASAR WAGE
Ada pohon tua di tengah pasar,
kulitnya mengelupas seperti cerita yang lupa ditulis.
Ia berdiri tak bernama,
tak pernah berbunga
namun menyimpan musim
dalam dengus hembus angin dan bau darah kambing qurban.
Orang-orang lewat tanpa menyapa,
namun tiap Jumat Wage
ada perempuan membawa daun sirih dan beras kuning
meletakkannya diam-diam di akar yang menggigil.
Anaknya sakit.
Suaminya minggat.
Langit tak memberi kabar.
Dari celah kayu yang retak,
keluar seekor capung hitam
terbang rendah,
mengitari kepala tukang sol sepatu
yang tiap pagi menggumam:
“Ya Allah, kuatna dodo kula…”
Pasar bergolak oleh tawar-menawar:
“telur e piro, Bu?”
“duwit receh, Pak?”
tapi tunggul wulung tak bergerak.
Ia mendengar suara
yang tak diucapkan.
Saat malam jatuh dengan suara sendok logam,
dan tikus-tikus berdoa dalam gelap,
seorang anak kecil memeluk batang pohon itu,
berharap mimpi ibunya yang meninggal
tidak datang lagi malam ini.
Pohon itu menangis tanpa suara.
Air matanya uap yang menyelinap
ke dalam angin,
ke dalam dengkuran penjaga parkir,
dan ke dalam tidur petani yang menjajakan ketela.
Ia pohon,
ia saksi,
ia mihrab tak bernama
yang mencatat istighfar
dalam aksara embun.
2025
BALADA DAUN JATI DAN BAYANGAN LANGIT
Di tanah perbukitan,
daun jati luruh satu per satu
seperti huruf-huruf gugur
dari kitab yang tak sempat disempurnakan langit.
Langit tak menangis,
tapi bayangannya mengalir
di punggung daun kering
yang meluncur ke bumi
dengan lirih yang hanya bisa didengar
oleh batu dan burung mati.
Ada anak gembala melintas,
kakinya telanjang, matanya bening
seperti sumur yang belum disentuh doa.
Ia memungut sehelai daun,
menyimpannya di saku
seperti menyimpan rahasia surga
yang tercipta dari sunyi dan pasir.
“Apakah semua yang gugur
akan kembali tumbuh?”
tanyanya pada angin,
namun angin berputar
seperti duka yang kehilangan kata,
mendekap senyap
dalam jubah gaib senja.
Seekor burung kutilang hinggap
di ranting yang nyaris patah.
Ia bernyanyi bukan karena musim,
melainkan karena ia tahu:
segala yang jatuh adalah dzikir,
segala yang kering menyimpan cahaya
dari langit yang ditutup kabut rahasia.
Sore hari,
daun-daun membentuk jalan
menuju padang lapang,
tempat seorang lelaki tua
bersujud lama sekali,
hingga tubuhnya menyerupai pohon
yang kehilangan seluruh daunnya,
dan bayangannya
menyatu dengan tanah
seperti akar yang sedang menghafal kematian.
Ia tak bicara.
Namun bumi mencatat doanya
dalam suara langkah daun
yang digerakkan takdir
dengan sepatu tak tampak.
Jati pun berdiri tanpa suara,
melihat bayangannya sendiri
menjalar ke dalam tanah:
tak lagi menjadi pohon,
namun menjadi waktu
yang menunggu
daun kembali hijau
dari musim yang belum lahir.
2025
BALADA TIKAR PANDAN YANG TERBAKAR
Di bawah rumah panggung
yang disangga tiang-tiang kenangan,
ada tikar pandan tua
menghampar sabar
seperti doa ibu
yang tak pernah rampung.
Ia tahu cerita setiap dengkur
dan tangis bayi yang pernah lahir di atasnya.
Ia menyimpan bau asin peluh ayah
dan remah jagung dari tangan-tangan kecil
yang kini merantau ke kota-kota.
Namun suatu malam
angin datang membawa bara.
Tak ada petir,
tak ada hujan,
hanya nyala dari mata yang tamak
dan tangan yang tak kenal dzikir.
Api menari di atas tikar itu
seperti ular lapar
menggigit akar rumah
dan menjilat dinding bambu
sampai seluruh langit
berbau arang.
Tikar pandan menangis
tanpa suara,
hanya anyamannya
yang berubah jadi abu
dan melayang
ke langit yang lupa caranya mendung.
Di luar rumah,
seorang nenek terpekur,
menggenggam sisa anyaman yang tak terbakar,
menyebut satu-satu nama cucunya
dalam gumaman yang hanya dimengerti
oleh api yang telah kenyang.
“Ini bukan sekadar rumah,”
katanya lirih.
“Ini tanah air.
Ini amanah bumi
yang telah kalian jual
dengan harga angkuh.”
Lalang pun diam.
Burung-burung menjauh.
Dan tikar pandan itu
menjadi syair terakhir
yang ditulis bumi
sebelum ia menggulung diri
dalam sunyi yang paling panjang.
2025
BALADA GUBUK DI UJUNG KEBUN KOPI
Di ujung kebun kopi
yang ditingkahi kabut dan desis jangkrik,
berdiri gubuk reyot
atapnya separuh langit,
lantainya daun gugur dan jejak ayam kampung.
Petani tua tiba menjelang asar,
membawa goni dan kepasrahan.
Ia duduk di atas tikar rajutan bulan lalu,
mengaduk kopi di cangkir retak
dengan doa yang tak bersuara.
Gubuk itu tak punya jam
namun tahu kapan matahari menunduk
dan angin mulai membaca ayat-ayat gelap.
Seekor tokek bersyahadat
setiap kali tubuh petani membungkuk,
mengusung sujud yang dalam
ke tanah yang dulu ditanami bapaknya
dan kelak diwariskan ke anaknya yang kini
entah di mana.
Tak ada pengeras suara.
Hanya desir daun dan suara kayu lapuk
yang mengeja alif–lam–mim
di sela-sela hembusan napas.
Ia menengadahkan tangan,
meminta bukan hujan
tetapi cahaya agar hatinya
tak menjadi ladang yang mati.
Malam turun perlahan
seperti sajadah hitam dibentangkan langit.
Di luar gubuk, kopi-kopi bermimpi
tentang tangan-tangan lembut yang memetiknya.
Di dalam, petani itu telah jadi angin,
melebur dalam nama-nama
yang disebutnya diam-diam
di balik dinding bambu yang mulai keropos.
Ia pulang tak pernah benar-benar pulang.
Sebab gubuk itu
adalah rumahnya yang terakhir
sebelum bumi menjadikannya
sebatang pohon kopi
yang tak pernah berhenti
berbuah doa.
2025
BALADA EMBUN DI UJUNG ALANG-ALANG
Embun jatuh diam-diam
di ujung alang-alang yang digerakkan sunyi,
seperti ayat pertama
yang gugur dari langit
sebelum semesta sempat mengeja.
Ia tak berteriak.
Hanya menggigil sejenak
di antara benang cahaya
dan desir angin yang kehilangan kampung.
Sehelai nyanyian Tuhan
yang ditulis dengan air
di atas rumput paling bening.
Seorang lelaki tua
melewati padang itu tiap pagi,
menyentuh embun dengan ujung jarinya,
lalu membasuh wajahnya
seperti mengambil wudu
dari telaga yang hanya muncul dalam mimpi para nabi.
“Ini bukan air biasa,” katanya,
“ini bisikan yang diturunkan sebelum fajar.”
Namun tak ada yang mendengar,
kecuali seekor burung hantu
yang menunduk dari batang lamtoro
seolah mengamini kesaksian
dari yang kerap dilupakan.
Anak-anak desa melintas,
menertawakan ujung celana yang basah.
Mereka belum tahu:
suatu hari nanti,
mereka akan mencari embun itu
untuk menyembuhkan luka
yang tak ada di tubuh.
Di balik pohon waru,
langit masih menjatuhkan airmata
yang bening dan tak beraroma.
Bumi menerimanya
tanpa banyak tanya,
seperti menerima maaf
dari seseorang yang hanya datang dalam sujud.
Alang-alang pun bersujud
tak dengan tubuhnya,
melainkan dengan bayangannya
yang merunduk pelan
dalam pelukan pagi.
Dan embun itu
ia akan lenyap
tanpa suara,
namun membawa serpih dzikir
ke singgasana cahaya.
2025
BALADA TALI JEMURAN DI PEKARANGAN LANGGAR
Ada seutas tali melintang
di pekarangan langgar yang sunyi,
menjadi jemuran kain sarung
dan sisa angin subuh
yang belum sempat dibawa burung pipit.
Tiap pagi,
perempuan tua menggantung cucian
sambil melafalkan satu demi satu
asma Allah
di antara helaian handuk dan sajadah basah.
Ia tak pernah tergesa.
Langkahnya sepelan waktu
yang menapaki doa-doa
berumur panjang.
Di ujung tali,
sebuah jepitan kayu menua dalam diam,
menyaksikan langit luntur
lalu kembali biru
seperti hati yang telah memaafkan dunia.
Kadang hujan turun tiba-tiba,
dan ia hanya tersenyum kecil:
“Allah sengaja menunda kering
agar aku belajar bersabar lagi.”
Seekor kucing mengendus sarung basah,
lalu duduk
di antara sandal jepit dan sepotong batu bata,
menyimak suara adzan
yang menyeruak dari corong langgar
bagai getar tali rebab
di malam syahdu.
Tali itu tak pernah putus,
meski kadang dihinggapi layang-layang
atau tersangkut ranting waru.
Ia tetap tegar
seperti hati orang miskin
yang menggantungkan seluruh hidupnya
pada Yang Maha Menatap.
Saat senja tiba,
dan jemuran telah diangkat,
tali itu tampak lengkung,
membentuk busur doa
yang mengarah ke langit
tanpa anak panah.
Malam pun datang,
dan perempuan tua itu menyandarkan tubuhnya
pada dinding langgar yang rapuh,
menggenggam ujung tali
seolah menggenggam
satu-satunya janji yang tak pernah ingkar.
Di atas sana,
bulan menggigil di antara reranting,
dan malaikat mendekat perlahan
seperti angin halus
yang mengeringkan air mata
tanpa suara.
2025
LANGIT DALAM GENGGAMAN IBU
Ibu,
tanganmu adalah akar
yang menyentuh bumi dalam diriku.
Engkau menggenggam bukan kulit
tetapi detak yang enggan tumbuh
tanpa suaramu.
Dalam lipatan telapakmu
ada langit yang patah
di sana aku pernah terbang
dengan sayap dari debu
dan doa yang kau lipat
dalam kantong seragamku.
Kita tak pernah benar-benar
berjalan berpisah.
Engkau tinggal di dalam
genggaman angin,
yang tiap pagi
menyusupi ruas jemariku
dengan rasa yang tak bisa dijelaskan
oleh musim,
oleh usia,
oleh waktu.
Di hari ketika aku lupa wajahku,
aku masih mengingat kulit tanganmu
yang menua bersama matahari
dan membisikkan namaku
pada bayang-bayang yang enggan pulang.
Aku pun berjalan,
dengan getar itu
menggigil di antara sela-sela doaku.
Tuhan tahu,
di tubuhku masih ada ibu
yang tak pernah pergi.
2024, 2025
ZIARAH MENUJU PELUKAN
Sejak kau pergi,
bantal ini menjadi perahu
yang selalu karam
di laut dadaku sendiri.
Aku menyebut namamu
dalam doaku yang gagap,
seperti anak kecil
belajar mengeja kehilangan
di antara jeda azan dan iqamah.
Ada sesuatu
yang dulu tak kukatakan:
bahwa aku lelah
menjadi kuat di hadapanmu,
dan pelukmu, yang tak sempat kupinta
telah lama kupahat
di ruang sepi antara dua waktu.
Kini aku tahu,
kehangatan bukan soal suhu,
melainkan ingatan
yang menyala di tulang belakang
setiap kali angin malam
membawa bau bajumu yang hilang.
Dan hidup,
adalah ziarah
menuju satu pelukan
yang tak pernah selesai.
2024, 2025
DUA SAJADAH SATU KIBLAT
Di kamar kecil ini
tak ada lukisan mewah
hanya dua sajadah
yang saling menatap dari arah kiblat.
Sajadahmu dan sajadahku
kadang berjarak sehelai sajadah,
kadang berhimpit
saat kita merunduk bersama
pada satu Nama
yang tak pernah memisahkan doa-doa kita.
Aku hafal lipatan sajadahmu
yang enggan diluruskan orang lain.
Engkau hafal sisa harum keningku
yang tertinggal tiap sujud malam.
Tak ada pelukan lebih mesra
selain saat kita diam dalam tahiyat akhir,
mengirim salam pada langit
dan saling menua dalam dzikir yang tak bersuara.
Sajadah-sajadah itu tak pernah bicara
tapi merekam seluruh cinta kita
yang tak terucap di meja makan
namun larut dalam wudhu yang setia.
Suatu hari nanti,
mungkin satu sajadah akan tergulung
lebih dulu dari yang lain
tapi jangan cemas,
satu sajadah yang tersisa
akan tetap menghadap kiblat yang sama
dengan kenangan akan lututmu yang hangat
dan takbirmu yang lirih
mengisi ruang ini
sepanjang hidupku.
2024, 2025
SETANGKUP MAAF
YANG TUMBUH
Kita bertengkar
seperti dua musim
yang datang terlalu cepat
di kalender yang retak.
Aku berjalan di dalam sunyimu
seperti angin
yang mencari pintu
di rumah yang kehilangan bayang-bayangnya.
Kau berkata dengan mata
lebih banyak daripada lidah,
dan aku menjawab dengan diam
yang tumbuh seperti rerumputan
di antara huruf-huruf yang patah.
Pertengkaran ini,
barangkali bukan luka
melainkan jeda
agar cinta menemukan kembali nadanya
di antara detak dan jarak.
Kita bertengkar
karena kita masih menyimpan nyala.
Jika tidak,
bukankah kita hanya akan diam
seperti batu
yang tak lagi mengenal gelombang?
Malam itu,
aku tidur di ranjang kata-kata
yang belum sempat kita saling ucapkan.
Dan subuh datang
membawa teh
dan setangkup maaf
yang tumbuh dari reruntuhan hari kemarin.
2024, 2025
PELUKAN
Dalam dekapanmu,
air mata tak lagi jadi beban,
melainkan kabut
yang menyimpan gema
dari malam-malam
yang belum sempat kita jamah dalam doa.
Ada sunyi
yang tak bisa dijahit dengan kata
ia hidup di sela nafas,
menumpuk perlahan
di rak-rak sepi
dalam kedua matamu.
Saat tubuhmu mendekapku,
aku mendengar
duka mengalir tanpa suara,
seperti sungai
menyusup ke akar pohon
dan lenyap, tanpa jejak
menuju asalnya.
Kita saling memeluk,
bukan untuk menghapus,
melainkan menyulam
agar luka tidak membeku
menjadi dingin
atau menjadi bayang
yang asing di kemudian hari.
Di tengah senyap,
aku pahami:
cinta yang tahan uji
menyimpan duka
seperti tanah menyimpan benih
tanpa perlu memberitahu dunia.
Dan pelukanmu,
adalah rahasia
yang kujaga dalam dada
seperti api kecil
yang menyala
meski tak terlihat siapa-siapa.
2024, 2025
RUMAH ITU TUMBUH
Aku membentang tubuhku
sebagai tanah yang kau pijak lembut,
dan membiarkan langkahmu menanam jejak
di antara bebatuan dan debu yang setia.
Aku bukan sekadar dinding,
tapi ruang tempat angin menyimpan rahasia,
tempat kau menitipkan rindu
yang tak pernah habis meski kau pergi.
Rumahku adalah pelukan yang sunyi
tanpa kata, tanpa janji,
hanya diam yang menunggu
agar kehadiranmu menjadi cahaya.
Setiap jendela adalah harapan yang terbuka,
mengundang pagi untuk menyelinap masuk,
menghangatkan malam yang pernah beku
di sudut-sudut hati yang kehilangan arah.
Aku tidak membangun tembok,
tapi membiarkan akar tumbuh dari sabar,
memeluk bumi dalam diam
dan menyimpan jejakmu
dalam cahaya yang tak pernah padam.
2024, 2025
CINTA YANG DATANG
TANPA PASPOR
Aku terbangun,
dan mimpiku masih menyisakan
jejak langkahmu
di halaman
yang belum selesai kutulis.
Engkau datang seperti musim
yang tak diundang,
namun selalu dinanti
oleh pepohonan.
Kau berjalan dalam mimpiku
seperti puisi
yang menghindari penyairnya,
seperti tanah air
yang hanya bisa kupeluk
dalam lagu.
Namamu menetes
di antara bintang dan luka,
dan aku mengumpulkannya
dalam botol kecil
yang kusembunyikan
di bawah bantal pengasinganku.
Kau bertanya:
apakah cinta masih hidup
di negeri
yang kehilangan dirinya?
Aku menjawab dalam diam:
cinta adalah engkau
yang datang tanpa paspor,
dan pergi
tanpa mengucap
selamat tinggal.
Mimpiku adalah kemah
yang selalu kupindahkan,
agar tak dijangkau
oleh rindu.
Namun kau
menemukannya setiap malam,
dan menyalakan pelita
di dalam mataku.
2024, 2025
RINDU DI BALIK KABUT
Rindu ini berjalan
di lorong-lorong sunyi
yang tak mengarah
ke sebuah pintu.
Ia membawa namamu
dalam kabut
dan dalam surat-surat
yang tak pernah tiba.
Aku duduk
di beranda mimpi,
menunggu detak langkah
yang kehilangan bayangan.
Sejak kau pergi,
langit malam seperti puisi
yang kehilangan larik terakhirnya.
Kukirimkan dinding-dinding doaku
agar menjadi pintu,
namun yang terbuka
hanyalah angin
membawa jejak
dari tanah
yang pernah disebut harapan.
Apakah cinta ini
adalah negeri
yang runtuh
karena peta
yang disobek oleh waktu?
Aku tetap di sini,
menyulam malam demi malam
dengan jarum patah,
mencari pintu
di tembok
yang dibangun oleh diam.
2024, 2025
DI BALIK SEPASANG MATA YANG DIAM
Sepasang mata itu
pernah memandangku dari ujung jalan
yang tak sempat kusebut namanya.
Ada daun gugur di sela-sela senyumnya,
dan angin yang membelai bahunya
membawa sesuatu yang nyaris kusebut pulang.
Aku berjalan
tanpa arah yang pasti,
menggenggam bayangan
seperti anak kecil
yang tak tahu harus memilih
antara riang dan kehilangan.
Sepasang mata itu
diam di antara rimbun waktu
seakan tak ingin dikenang,
namun tak pernah benar-benar pergi
dari lipatan pikiranku.
Jalan itu kini
tersamar dalam kabut,
dan aku kehilangan jejak
seperti hujan
yang tak tahu
kapan ia mulai menjadi air mata.
Tapi sepasang mata itu
masih menyinari malam-malamku
dengan kerlip
yang tak bisa kupadamkan
meski telah kupelajari
segala cara untuk melupakan.
2024, 2025
BAHASA BULAN DAN SEPI
Bulan menggantung seperti tanda tanya
di antara dua langkah yang ragu
kau di ujung angin,
aku di kaki senyap
yang baru saja selesai membaca doa.
Kita saling mencari
dalam malam yang tidak memberi tahu
ke mana ujung rindu harus kembali.
Aku membawa nama
yang tak sempat kau kenakan,
kau membawa senyum
yang pernah singgah di mimpiku
tanpa mengetuk pintu.
Langit diam seperti kitab yang tertutup,
tapi tanah menyimpan jejak
dua bayang
yang bersilang,
lalu hilang.
Kita tak pernah benar-benar bertemu,
tapi aku percaya:
ada gema dari langkahmu
yang menjawab detak jantungku
dengan bahasa
yang hanya dipahami
oleh bulan dan sepi.
2024, 2025
MENUNGGU DALAM HENING
Berapa banyak ciuman
yang tertunda
oleh detik yang terlalu angkuh
untuk berdetak?
Kita menunggu,
seperti gadis tua
di beranda yang
kehilangan alamat surat,
seperti puisi
yang tak jadi dibaca
karena nama kekasihnya
disembunyikan angin.
Aku duduk
di samping kursi kosong yang
kau tinggalkan,
mengaduk teh
dengan sendok rindu
yang tak pernah larut sepenuhnya.
Waktu di antara kita
adalah benang tipis
ditarik dari kedua ujungnya
kadang rapuh,
kadang nyaris tak terasa,
tapi selalu ada.
Cinta kita,
adalah percakapan yang
tak pernah selesai,
dengan jeda-jeda
yang menyimpan berjuta kata
yang tak sempat
menyentuh bibirmu.
2024, 2025
AIR MATA ITU MILIK SIAPA
DALAM TAHAJUD?
Dalam gelap yang paling sunyi,
aku mendengar detak jantung bumi
menyebut nama-Mu
seperti seorang pengembara
menyebut rumah yang
tak lagi ia ingat jalannya.
Air mata jatuh
bukan karena duka,
melainkan karena cahaya
yang terlalu terang
untuk disimpan dalam dada.
Aku sujud,
tapi tanah tak menahanku.
Ia membawaku melayang
ke antara huruf-huruf kuno
yang pernah Kau bisikkan
kepada nabi yang rindu.
Siapa pemilik air mata ini?
Aku (yang kehilangan kata)
untuk menyebut-Mu dengan sempurna?
Atau Engkau (yang mengajarkan)
bahwa cinta paling agung
tak perlu dijawab, cukup dirasakan
seperti malam yang percaya pada fajar?
Di antara rakaat,
aku mencium bayangan-Mu
pada lantai yang dingin,
pada detik yang menua,
pada aroma malam
yang melipat kesedihan menjadi sabda.
Dan dalam setiap bisik
“Ya Rahman, Ya Rahim,”
aku temukan namaku
terukir rapuh pada kelopak air mata
yang kembali ke langit
tanpa pamit.
2024, 2025
SELAMA MASIH BERNAFAS
Cinta ini belum habis,
meski waktu telah meluruhkan
segala yang bisa kutangisi.
Ia tinggal di sela helaan nafasku,
seperti bisikan lirih
yang enggan mati
meski badai telah lewat
dan sunyi bertahun menetap.
Aku telah menyerahkan banyak hal
kepada kehilangan
namun cinta ini tetap tinggal,
bersandar di dinding dada
seperti cahaya kecil
yang menolak padam
oleh luka, oleh dingin,
oleh kematian harapan.
Barangkali ini bukan tentang siapa,
bukan tentang masa lalu yang retak,
tapi tentang rasa yang
tak ingin pergi
karena masih ada Engkau
di setiap helaannya.
Dan selama aku masih bernafas,
cinta ini akan menoleh kepada-Mu
meski tubuhku lelah,
dan jalan kembali
terus dibungkus kabut malam.
2024, 2025
DI ANTARA BATU
DAN CAHAYA
Kubur adalah pusaran
di mana bisu dan doa bertaut
sebuah rongga gelap
yang menelan kata-kata terakhir.
Aku melangkah di antara bayang-bayang,
menghirup aroma tanah yang berdarah,
dan di sana, antara getar batu nisan
aku temukan wajahmu
bukan dalam bentuk yang kumengerti,
melainkan sebagai gema sunyi
yang menebarkan cermin di dadaku.
Doa adalah lampu yang tak pernah padam,
menyala dalam kabut kelam,
mengurai jarak antara
yang hidup dan yang hilang,
mengajarkan aku menulis namamu
di atas gelombang waktu yang runtuh.
Antara kubur dan doa,
engkau bukan bayangan atau jejak,
melainkan denyut abadi
yang melintasi tenggorok malam,
menggetarkan nafasku,
dan menyulamku menjadi suara
yang tak pernah lelah menunggu.
2024, 2025
SUARA DALAM TIDURKU
malam menjelma jendela
dan angin menyibak tirai mimpiku
aku mendengar sesuatu
bukan dari luar,
tetapi dari dalam suara yang
kukira telah lama padam
ia menyebut namaku
dengan bunyi lembut
seperti doa yang tak jadi dilisankan
karena air mata lebih dulu
mengetuk pintu langit
suara itu menyerupai bapakku
saat mengajari huruf demi huruf
dengan napas yang menyatu
pada setiap ayat yang
tak sempat kusempurnakan
aku terbangun,
namun tidur tetap bersamaku
ia menyimpan langkah-langkah
yang tak kutemui di siang hari
dan membisikkan jalan pulang
yang hanya bisa kulalui
dengan dada yang basah
malam pun kembali sunyi
tapi suara itu tinggal
di antara napas dan napasku
seperti restu
yang tak pernah selesai diucapkan
2024, 2025
LAUTAN YANG MENYIMPAN
NAMAMU
lautan itu masih sama
pasang surutnya menyimpan bisik
yang dulu kau kirim bersama angin
mengabarkan namamu
dalam aliran gelombang yang
tak lelah memanggil
aku berdiri
di tepi gelisah
menggenggam sisa-sisa senyummu
yang tertinggal di buih
dan jejak doa yang tak sempat kembali
namamu
seperti cahaya yang ditelan kedalaman
namun memantul di dada ombak
setiap kali aku mencoba melupakan
tapi angin memulangkannya
di lautan ini
aku belajar menyebutmu
tanpa suara
karena cinta, seperti samudra,
lebih luas dari kata
dan dalam sujudku
kupungut namamu
dari riak-riak
yang mengajarkan
bagaimana rindu
tak perlu sampai
untuk menjadi abadi
2024, 2025
KABAR DARI SAJADAH
di ujung malam
ketika seluruh lampu telah reda
dan langit menunduk dalam
sajadah mengirimkan kabar
yang tak bisa dibaca mata
ia bicara dari serat-seratnya
yang dulu menyerap air matamu
dan kini menyimpan suaramu
yang tak sempat kau ucapkan dalam zikir
ia berkata:
doamu belum selesai
rindumu masih bertahan
meski waktu telah berpaling
kupeluk sajadah itu
seperti memeluk jejakmu
yang tidak pergi,
hanya menyatu dengan bau subuh
dan suara yang memanggil tanpa suara
di sajadah,
ada kabar dari langit
yang menetes di ubun-ubun
seperti restu
yang tak pernah habis ditampung bumi
2024, 2025
RUANG KOSONG
DI DEKAT JENDELA
ada ruang kecil
yang tak pernah kau isi
di dekat jendela
tempat cahaya masuk pelan
dan angin menyampaikan salam
dari langit
di sanalah dulu kau duduk
memandang jalan
menunggu waktu
yang tak pernah menjanjikan apa-apa
selain perpisahan
yang datang dengan senyap
kursi itu masih ada
tapi tak lagi bersandar
pada punggungmu
hanya bayangan yang datang
sekali-sekali
seperti kabut yang enggan disebut nama
aku menyentuh dindingnya
dan menemukan hangat
yang belum pergi
bekas doa
yang sempat kau bisikkan
sebelum pagi menjelma jauh
ruang kosong itu
tak benar-benar kosong
ia menyimpan pertemuan
yang belum selesai
2024, 2025
SEBELUM KATA MENJADI HENING
aku ingin bicara
tapi suaramu lebih dulu tiba
dari sepi yang kau tinggalkan
di antara kelopak malam
dan lembaran kitab
yang belum selesai kubaca
aku masih menunggu
satu kata
yang bisa menampung air matamu
yang turun sebelum salam
kau ucapkan
tapi waktu telah berubah
menjadi kabut
dan doa-doa tinggal gema
yang memantul
dari dinding jiwaku
sebelum kata menjadi hening
aku ingin menyebut namamu
seperti menyebut cahaya
yang tidak pernah redup
di dalam dada
karena cinta yang benar
tak pernah memerlukan suara
cukup hadir
dalam diam yang bersujud
2024, 2025
—–
*Abdul Wachid B.S., lahir 7 Oktober 1966 di Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Wachid lulus Sarjana Sastra dan Magister Humaniora di UGM, dan menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Abdul Wachid B.S. lulus Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (15/1/2019). Buku terbarunya : Kumpulan Sajak Nun (2018), Bunga Rampai Esai Sastra Pencerahan (2019), Dimensi Profetik dalam Puisi Gus Mus: Keindahan Islam dan Keindonesiaan (2020), Kumpulan Sajak Biyanglala (2020), Kumpulan Sajak Jalan Malam (2021), Kumpulan Sajak Penyair Cinta (2022), Kumpulan Sajak Wasilah Sejoli (2022). Melalui buku Sastra Pencerahan, Abdul Wachid B.S. menerima penghargaan Majelis Sastrawan Asia Tenggara (Mastera) sebagai karya tulis terbaik kategori pemikiran sastra, pada 7 Oktober 2021 (tepat di ulang tahunnya yang ke-55).