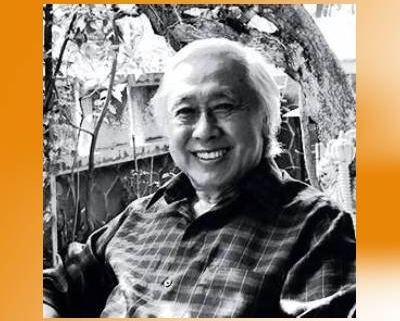Berakhirnya Orientalisme
Oleh : Agus Dermawan T
Pameran seni rupa Imlek yang tidak lagi menghadirkan dominasi unsur ketionghoaan. Isyarat berakhirnya Orientalisme, dan petunjuk berkembangnya Akulturasisme.
———-
PADA 22 sampai 29 Februari 2024 Bentara Budaya Jakarta menggelar pameran Merayakan Kebersamaan, yang berkait dengan keramaian Tahun Baru Imlek, 10 Februari.
Sebelum selebriti Olga Lydia membuka pameran, penggerak budaya Ilham Khoiri mengawali dengan pidato kesejarahan tentang nasib kebudayaan orang Tionghoa di Indonesia. Dari yang semula hadir sebagai budaya teraniaya, sampai akhirnya jadi budaya yang dipeluk dan dirindukan keberadaannya oleh siapa saja.
Pidato itu lalu dieratkan konteksnya dengan kurasi Frans Sartono atas pameran yang beraroma Tionghoa ini. Kita bisa melihat, betapa selain diikuti oleh seniman keturunan Tionghoa, pameran ini juga melibatkan pelukis bumiputera dari berbagai wilayah Indonesia. Di antara yang beragama Kristen dan Budha, ada yang beragama Islam, Hindu dan Kepercayaan Jawa.
Campursari peserta ini lalu berkorelasi dengan apa yang dikreasi.

Suasana kala pidato pembukaan pameran Merayakan Kebersamaan. Anak-anak juga terlibat.
Syakieb Sungkar melukis acara makan Imlek, dengan dihiasi lambaian amplop angpao (Bagi-bagi Angpao). Putu Sutawijaya melukis kemeriahan klenteng, seintens ketika ia merekam pura di Desa Angseri, Bali (Menjelang Imlek). Nisan Kristiyanto melukis bunga merah menyala di atas hamparan sawah yang siap panen raya (Memaknai Bunga-bunga – Menyambut Musim Semi). Fatih Jagad Raya Aslami melukis orang-orang yang girang melayang sambil membawa lampion dan gunungan wayang (Cultural Fortune Illuminating the Skies). Hanny Widjaja melukis pertemuan barong dan penari topeng Cirebon (Live in Harmony).

Lukisan Syakieb Sungkar, “Berbagi Angpao”.

Lukisan Putu Sutawijaya, “Menyambut Imlek”

Lukisan Nisan Kristiyanto, “Memaknai Bunga-bunga-Menyambut Musim Semi”.

Lukisan Hanny Widjaya, “Live in Harmony”.
Sidik Martowidjojo, ahli chinese painting itu, melukis berseminya bunga peoni Wuhan di tengah semesta dalam sapuan gaya Eropa (Keagungan Semesta). Vy Patiah melukis wanita tak berdaya di tengah tragedi Mei, dan berlindung di belakang sisik-sisik liong dan barong (Kembang Mati Yang Hilang Ditelan Zaman). Andre Tanama melukis anak Tionghoa yang tak lagi sipit matanya, namun belum berani bicara (The Art of Silence). Teguh Ostenrik membuat video tentang berbagai unsur budaya yang sudah menyatu dalam harmoni rupa (Alur Harmoni).

Lukisan Vy Patiah, “Kembang Mati Yang Hilang Ditelan Zaman”.
Pada dinding lain Sarnadi Adam mengenang tari cokek Betawi yang sangat dipengaruhi budaya Tionghoa, tapi kini tiada lagi terdengar gemanya (Dialog Tujuh Penari Cokek). Galuh Taji Malela merekam wajah Gusdur, guru bangsa yang memasukkan kembali budaya Tionghoa dalam kubah Nusantara (Behind The Scene of Imlek).
Jajaran lukisan itu, meski dalam balutan tema Imlek, tidak lagi menampakkan atmosfir visual seni rupa orientalis Tionghoa. Deretan lukisan itu, walau menggiring diri ke muara budaya Tionghoa, tidak pula memperlihatkan dominasi dari konten budaya Tionghoa. Bahkan karya seni mereka juga tidak lagi menghadirkan identifikasi: siapa perupa yang Tionghoa dan siapa yang bukan Tionghoa. Karya mana yang ciptaan perupa Tionghoa, dan mana yang garapan bumiputera.
Hal ini terjadi lantaran budaya Tionghoa (seperti Imlek) sudah begitu dekat dengan kehidupan para seniman yang bukan keturunan Tionghoa. Sementara seniman yang Tionghoa, sejak jauh hari telah melebur dalam kebudayaan tempat ia sekarang bermukim. Kedekatan kebudayaan dan peleburan ini jelas diberangkatkan dari semangat akulturasi (aculturation), atau spirit akulturasisme, yang ujungnya mengasimilasikan kebudayaan. Asimilasi ini pelan-pelan melahirkan turunan budaya baru, seperti yang terbaca dalam pameran Merayakan Kebersamaan.
Seni mata orientalis
Realitas budaya akulturasisme yang muncul sekarang ini sungguh berbeda dengan yang terjadi pada sejarah seni rupa Indonesia pada kurun-kurun sebelumnya. Yakni pada waktu para perupa masih melihat kebudayaan Tionghoa dengan mata orientalisme.
Kita tahu, Orientalisme adalah faham yang merujuk kepada penggambaran bangsa Barat atas unsur-unsur budaya Timur, seperti Afrika Utara, Asia Barat dan Asia Tengah. Istilah itu dipopulerkan sejak akhir abad 18 oleh para ilmuwan dan budayawan negeri-negeri Barat, yang notabene pernah menjajah atau mengunjungi negeri Timur.
Sampai pada akhirnya mereka ingin memakai kebudayaan Timur sebagai orientasi penelitian, untuk sekadar dicari kebedaannya dengan budaya Barat. Dari situ muncul kesimpulan ekstrim yang dituliskan sastrawan Inggris kelahiran India, Rudyard Kipling (1865-1936): “Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet, till earth and sky stand presently at God’s Great judgement seat…” (Oh, Timur adalah Timur, dan Barat adalah Barat, dan tak akan bisa dipertemukan, sampai bumi dan langit duduk di kursi penghakiman Tuhan Yang Agung).
Lantas kita simak contoh orientalisme seni rupa ini, di Indonesia.
Pada tahun 1940 Sudjojono (1913-1986) mencipta lukisan Cap Go Meh. Lukisan ini menggambarkan kegembiraan masyarakat Tionghoa dalam menyambut hari ke 15 setelah Tahun Baru Imlek. Hikayat menuturkan bahwa pada saat cap go meh, bulan diperhitungkan hadir bundar dan bersinar penuh. Bunga-bunga dipercaya mekar diam-diam di malam hari. Rejeki dan kebaikan konon akan datang bergerumbulan. Dalam purnama itulah pemuda dan pemudi berbondong pergi ke halaman klenteng untuk menonton pertunjukan barongsai atau wayang potehi, mendengarkan erhu (musik gesek bersenar dua) mengalun, atau menyaksikan pentas gambang kromong yang digelar alun-alun.
“Sebagai orang Indonesia yang hidup di tengah kelindan budaya Belanda, saya melihat perayaan cap go meh sebagai sekadar tradisi eksotik. Cap go meh itu obyek menarik bagi penganut orientalis seperti saya,” katanya.
Begitu pula Basoeki Abdullah ketika melukis pertunjukan liong di sejalur jalan di Singapura, pada 1988. Lukisan Pertunjukan Liong yang atraktif itu adalah hasil penglihatannya atas kebudayaan Tiongkok, dari mata seorang orientalis, atau mata (orang Indonesia) yang berkurun tahun hidup di antara orang-orang Barat di Belanda.
“Saya memandang pertunjukan liong adalah pertunjukan orang sana. Bukan atraksi orang kita,” tuturnya.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rusli (1912-2005) dan Affandi (1907-1990) yang sering melukis wihara. Mareka melihat wihara sekadar sebagai arsitektur yang unik, dari kacamata seorang orientalis.
Seni pasca modernisme
Pemisahan masif kebudayaan Timur (yang oriental) dengan kebudayaan Barat (yang modern) pelan-pelan berusaha dipertemukan oleh para pelaku budaya Barat sendiri, pada tengah abad 19. Yakni ketika para seniman di Eropa banyak memanfaatkan unsur-unsur budaya Timur, seperti Mesir, Maroko, Jepang dan Tiongkok sebagai perbendaharaan estetika.
Yang sastrawan menjumput kebudayaan oriental sebagai ilustrasi atau bahkan aksentuasi dalam puisi dan prosa. Panggung pertunjukan seperti teater Moulin Rouge di Paris mengusung arstistika pentas India dan Tiongkok. Sampai akhirnya unsur budaya oriental melekat dalam aneka desain grafis, desain busana, penciptaan patung dan lukisan.
Pada tahun 1972 Panitia Olimpiade 1972 Munchen, Jerman, mengadakan pameran seni rupa yang menegaskan asimilasi kebudayaan oriental dan budaya Barat itu. Buku besar yang menandai pameran ini adalah World Cultures and Modern Art (Bruckmann Publishers, Munich) yang disusun Prof Dr Siegfried Wichmann dan kawan-kawannya.
Dalam pameran (dan buku) tergelar karya Utamaro, Katsukawa Shunshe, Hirosige, yang “dinikahi” Claude Monet sampai Gustav Klimt. Kaligrafi Tiongkok yang “dikawini” Hans Hartung dan Franz Kline. Patung-patung Afrika yang “disunting” Picasso. Ornamentasi hiasan Polinesia yang dipeluk tiada henti oleh Paul Gauguin, dan seterusnya.
Asimilasi budaya Oriental dan Barat itu lalu menghasilkan keturunan mashab seni baru, yang pada tahun 1980-an dipopulerkan dengan sebutan Seni Pasca Modern, atau Post Modernism Art. Sampai di sini, seni oriental serta-merta hadir sebagai benda memorabilia. Dan Orientalisme tinggal ilmu yang diwariskan sejarah.
Dari paparan di atas kita bisa melihat pameran Merayakan Kebersamaan dengan sudut pandang yang lain. Dan sekaligus dengan kesimpulan yang mengerucut. Yakni, kebudayaan Tionghoa (yang dipelihara di Indonesia) telah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Tema dan konten boleh oriental, namun presentasinya akulturatif. Sebuah realitas yang menandai lahirnya Akulturasisme, dan berakhirnya Orientalisme. Setidaknya dalam pameran ini. *
—————-
Agus Dermawan T.
Kritikus Seni. Narasumber Ahli Koleksi Benda Seni Istana Presiden Republik Indonesia.