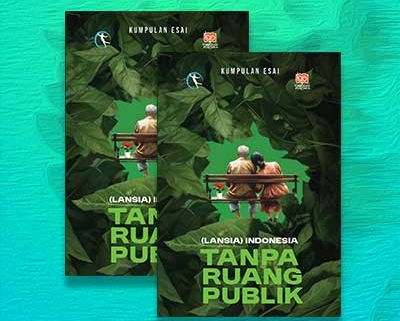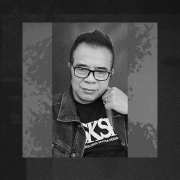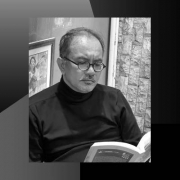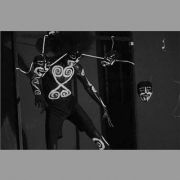Ruang Publik dan Jouissance dalam Pembentukan Subyek Lansia

Oleh Indro Suprobo & Ons Untoro*
The difficulty with talking about jouissance is that we cannot actually say what it is. We experience it rather through its absence or insufficiency. As subjects we are driven by insatiable desires. As we seek to realize our desires we will inevitably be disappointed – the satisfaction we achieve is never quite enough; we always have the sense that there is something more, something we have missed out on, something more we could have had. This something more that would satisfy and fulfil us beyond the meagre pleasure we experience is jouissance. We do not know what it is but assume that it must be there because we are constantly dissatisfied. As Fink puts it, eventually ‘we think that there must be something better, we say that there must be something better, we believe that there must be something better.
– Sean Homer dalam Jacques Lacan1
Secara filosofis, manusia lansia bukanlah subyek yang meredup dan menjadi layu. Ia tetap merupakan subyek yang terus-menerus merekah dan memancarkan auranya dari kedalaman dirinya. Meskipun dalam beberapa aspek barangkali mengalami perubahan dan penurunan, manusia lansia tetaplah merupakan vibrant subject yang berdampak kepada lingkungan hidup sekitarnya. Ia tetap merupakan subyek yang terus-menerus menjadi (continuously being), menggetarkan energi, nilai dan inspirasi dari kedalaman dirinya (vibrant subject). Gerak dan perubahan yang secara prinsipial terkandung di dalam dirinya, masih terus-menerus berlangsung tanpa henti. Ia senantiasa menjalani proses deteritorialisasi, melepaskan diri dari jerat kemapanan, kepastian dan fiksasi (segala bentuk pembekuan), dan terus melaju menemukan kreativitas pemaknaan baru di dalam kehidupan. Tak berhenti, sampai mati.
Kutipan awal tentang jouissance yang dicantumkan di awal tulisan ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya prinsip dasar dalam proses pembentukan subyek yang terus-menerus berlangsung tanpa henti, termasuk di dalam diri manusia lansia. Baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia belum memiliki kata yang mewakili untuk alih bahasa dari istilah jouissance ini. Secara agak mendekati meskipun tidak mewakili, istilah yang seringkali digunakan untuk mengalihbahasakannya adalah kenikmatan. Namun kata ini belum memadai karena di dalam istilah jouissance itu, selain ada unsur kenikmatan, terkandung pula unsur rasa sakit atau kepedihan mendalam (Jawa, nggrantes). Jadi semacam kenikmatan yang sekaligus menyisakan kepedihan mendalam (nggrantes). Pemikir dan psikoanalis Perancis, Jacques Lacan, menyatakan bahwa jouissance itu berisi kenikmatan (pleasure) sekaligus kepedihan (pain). Dinyatakan bahwa kepuasan atau kenikmatan yang kita peroleh tidaklah pernah cukup. Kita selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang telah terlewatkan, sesuatu yang terlepas, yang seharusnya bisa kita capai. Selalu tersisa residu yang tak tergapai, tak terengkuh, tak tertangkap. Dalam bahasa Jawa kita bisa mengatakan kenikmatan itu tak pernah sepenuhnya dapat digapai karena selalu saja ada yang “mrucut“, terlepas, atau hilang. Oleh karena itu, sesuatu yang senantiasa mrucut, terlepas atau hilang ini melahirkan kepedihan, sekaligus melahirkan undangan dan kerinduan abadi untuk senantiasa digapai lagi dan lagi, yang selalu melahirkan hasrat. Dengan demikian subyek manusia digambarkan senantiasa bergerak maju, merekah, menggetar (vibrant), menggapai yang lebih, dan terus-menerus melampaui (magis).
Dalam proses penghayatan hidup, jouissance ini barangkali boleh digambarkan sebagai suatu pencapaian pengalaman bermakna yang menyediakan kepenuhan dan kelegaan jiwa, namun senantiasa menyisakan kerinduan untuk terus-menerus menggapainya lagi secara lebih mendalam. Proses pencapaian makna ini, meskipun dialami sebagai semacam pengalaman yang memuncak, namun tak pernah mengarah kepada fiksasi atau pemadatan. Ia senantiasa mencair dan mengalir kembali. Ini adalah sebuah prinsip dinamis.
Penggambaran sederhana tentang sastrawan tua dan aktivitas memancing di laut berikut ini barangkali dapat membantu untuk memahami jouissance secara lebih baik. Seorang sastrawan yang sudah memasuki masa lansia, ketika mengalami kelelahan, kejenuhan dan kebuntuan ide, memiliki kebiasaan memancing di laut sebagai aktivitas refreshing sekaligus merefleksikan pengalaman.
Ketika memancing, ia mengalami nostalgia masa kecil, menemukan kegembiraan dan kegairahan, menyelami perasaan eksploratif mengarungi lautan, menemukan kesegaran dan keluasan karena memandang keindahan dan luasnya lautan, merasakan relaksasi mata karena bisa memandang kejauhan, merasakan hangatnya pertemanan dan persahabatan karena ia memancing bersama kelompok sebayanya, dan dapat berbagi cerita tentang masa lalu kepada generasi lebih muda karena ada beberapa remaja yang bergabung di dalamnya. Ia bisa merasakan perubahan alam dan ekosistem karena bisa menghitung keragaman burung di sekitar laut yang sudah banyak berkurang dari sisi jumlah maupun variasi jenisnya. Ia juga bisa mengidentifikasi perubahan lautan karena kejernihan air, keragaman dan jumlah ikan yang diperolehnya. Seluruh pengalaman yang ditemukannya ketika memancing di atas perahu di lautan itu, dalam hening di antara hutan-hutan bakau yang melindunginya dari terpaan angin dan gelombang, melahirkan pengalaman kepenuhan dan kenikmatan di dalam dirinya. Apalagi jika alat pancingnya dapat menarik ikan yang besar dan langka. Sungguh aduhai, kepenuhan yang tak terkira. Itu adalah pengalaman “aha!“. Ada kebanggaan karena kapasitas dan kompetensinya sebagai pemancing tetap terbuktikan. Ada kegembiraan karena terlepas dari beban pikiran harian. Semuanya itu dirasakan dalam satu kerangka sifat pengalaman yang disebut “intensitas“. Namun pada saat yang sama, tetap tersisa perasaan kehilangan dan kepedihan karena toh semua pengalaman itu hanya akan berlangsung beberapa saat. Paling lama berada dalam hitungan jam. Setelah itu ia musti kembali kepada aktivitas rutin keseharian. Kesadaran bahwa seluruh ketercapaian kepenuhan itu tak akan pernah selamanya, dan akan berakhir karena sifat kesementaraannya, melahirkan perasaan kehilangan dan kepedihan. Kesadaran bahwa ia musti kembali lagi memasuki rutinitas harian, telah menjadi celah di mana kepedihan dan perasaan kehilangan itu menyusup cepat di dalam dirinya. Pengalaman memancing di laut telah menyediakan kenikmatan dan kepedihan yang menggerakkan hasratnya untuk mengulanginya kembali pada kesempatan lain. Memancing di laut menjadi kerinduan yang selalu hadir pada saatnya. Dengan demikian pengalaman memancing di laut bersama kawan sebaya merupakan jouissance bagi sastrawan lansia itu.
Ruang Publik dan Jouissance
Ruang publik yang dalam buku ini dipaparkan sebagai ruang fisik yang aksesibel bagi manusia lansia, yang menyediakan kemudahan, kenyamanan, keamanan, kesempatan, serta pengalaman-pengalaman kepenuhan yang senantiasa melahirkan kerinduan untuk diulang kembali, merupakan ruang yang dinilai penting bagi seluruh proses pembentukan subyek lansia. Ruang publik yang aksesibel, produktif dan transformatif bagi pembentukan subyek lansia ini merupakan ruang yang senantiasa menyediakan perjumpaan dan penemuan “pengalaman berharga dan intens” yang mengaki-batkan ketergetaran batin, keterhubungan mendalam dengan lingkungan alam dan sesama, serta interkoneksi lintas generasi. Seluruh perjumpaan dan penemuan pengalaman berharga dan intens yang difasilitasi oleh ruang publik ini, memengaruhi seluruh proses pembentukan subyek lansia sebagai manusia yang senantiasa menjadi, memproduksi makna, melahirkan nilai, menyelami kualitas, menghadirkan integritas, memancarkan otentisitas, menginspirasi kreativitas, dan terus-menerus bergerak serta merekah tanpa batas.
Pengalaman ketercapaian kepenuhan dan kebermaknaan itulah yang pantas disebut sebagai jouissance karena bagaimanapun juga pengalaman ketercapaian itu tak pernah berlabuh pada titik akhir dan selalu menyediakan undangan, kerinduan serta kesempatan baru di depan. Ia bagaikan horison, yakni batas pandang dan pengalaman yang tak pernah tergenggam dan terlampaui. Ia senantiasa mundur di depan dan menyisakan jarak yang selalu mengundang hasrat dan kerinduan untuk ditempuh kembali.
Ruang publik yang melahirkan jouissance semacam ini merupakan ruang yang memengaruhi seluruh proses pembentukan dan kemenjadian subyek lansia. Ruang publik yang demikian senantiasa membuat manusia lansia menemukan dan mengalami peneguhan diri, mendapatkan pengakuan, menghayati kemartabatan dan pertumbuhan, menegaskan kepercayaan dan keyakinan, melahirkan inspirasi dan produktivitas, serta terus-menerus mengemukakan keraguan dan pertanyaan baru dan aseli yang mengundangnya untuk terus maju menggali dan menggali kembali. Jouissance yang difasilitasi oleh ruang publik yang aksesibel, produktif dan transformatif bagi lansia merupakan pengalaman kepenuhan dan kebermaknaan yang senantiasa mrucut dan mencair kembali. Ia tak pernah menjadi padat dan anti fiksasi. Ia senantiasa menanti dan mengundang untuk terus-menerus direngkuh kembali.
Ruang publik fisik bisa berupa taman atau bangunan, atau kombinasi keduanya. Artinya di tengah taman dapat disediakan bangunan sebagai bentuk ruang publik tertutup. Ruang publik memang diperuntukkan bagi semua kalangan tanpa diskriminasi. Dalam ruang publik seperti itu, lansia (dan difabel) sesungguhnya termasuk kalangan minoritas. Karena ruang publik terbuka untuk semua kalangan, maka lansia juga memiliki hak untuk mengakses, dan lebih dari itu perlu diberi ruang khusus, yang bisa digunakan oleh lansia dan difabel, terutama untuk lansia yang secara fisik memang memerlukan tempat dan fasilitas tersendiri.
Karena, kita tahu, ada lansia yang secara fisik masih kuat dan mampu berinteraksi dengan kelompok sosial lainnya, bahkan dengan kelompok sosial yang lebih muda. Lansia seperti ini diberi kebebasan melakukan aktivitas di ruang publik bersama kelompok sosial lainnya, dan tentu saja boleh berinteraksi di dalam ruang publik khusus lansia.
Ruang publik fisik menjadi pilihan bagi lansia, karena proses interaksi yang terjadi di dalamnya bisa melahirkan kehangatan, emosi dan seterusnya, sehingga rasa kemanusiaan antar lansia bisa terjaga. Di dalam interaksi itu, masing-masing lansia dapat saling belajar, sekaligus saling menghormati. Sebagai subyek, lansia dihormati dan sebagai kolektivitas, lansia semakin dikuatkan rasa kemanusiannya. Dalam konteks ini, lansia tidak merasa terasing dan kesepian, karena bertemu dengan sesama lansia di satu ruang bersama.
Jadi, ruang publik fisik bagi lansia sangat penting perannya untuk menjaga ingatan, bahwa ada lansia lain dalam kebersamaan. Karena secara personal, lansia cenderung merasa kesepian, bukan karena dijauhkan oleh keluarga, dalam hal ini oleh anak-anaknya misalnya, melainkan karena ingatannya merujuk pada kakak dan adik-adiknya, kawan-kawan seangkatan, teman-teman kerja seusia yang sudah lebih dahulu meninggal. Akibatnya secara personal lansia merasa sendirian dan kehilangan. Dengan demikian ruang publik merupakan tempat bagi lansia untuk mengisi ingatannya dengan lansia yang lebih berwarna dan kompleks, bukan hanya mereka yang sudah meninggal. Di dalam ruang publik fisik itu, pertemuan dengan sesama lansia yang melahirkan kehangatan, kegembiraan, dan kepenuhan kemanusiaan itu, menjadi jouissance.
Ruang Publik sebagai Subversi
Ruang publik yang aksesibel, produktif dan transformatif bagi lansia, yang menyediakan jouissance dalam proses pembentukan subyek lansia pada gilirannya dapat disebut sebagai subversi terhadap tatanan simbolis masyarakat yang pada umumnya berlaku, yakni tatanan simbolis yang berisi stereotype terhadap lansia sebagai manusia yang lemah, tidak produktif, menjadi beban sosial, dan pantas diisolasi.
Tatanan simbolis masyarakat dipahami sebagai struktur atau gramatika yang berada dalam ranah ketidaksadan sosial yang memengaruhi seluruh proses produksi makna. Ini seumpama bahasa sebagai sistem, struktur atau tatanan yang berada dalam ketaksadaran (langue), namun sangat memengaruhi bagaimana manusia berbicara (parole). Tatanan simbolis adalah sebuah sistem atau struktur yang berisi jejaring penanda yang seluruh relasinya memengaruhi proses pembentukan makna dalam pembentukan subyek manusia.2 Secara khusus, terkait dengan ruang publik dan subyek lansia, tatanan simbolis yang berisi stereotype tentang manusia lansia ini pada umumnya dianggap sebagai normalitas dan diyakini sebagai kebenaran dalam pandangan umum (common sense).
Tatanan simbolis masyarakat yang stereotipikal tentang manusia lansia ini berisi asumsi, anggapan, keyakinan, pengetahuan, dan sikap yang mengidentifikasi manusia lansia sebagai subyek yang lemah, tak lagi kompeten, kehilangan kapabilitas, tidak produktif, tak sanggup lagi berpartisipasi, mengganggu, merepotkan, menghalangi arus kecepatan dan kelancaran, tak lagi sanggup melahirkan kreativitas, sudah berhenti berproses, sudah menjadi subyek yang meredup, layu dan meranggas. Tatanan simbolis yang stereotipikal ini seringkali diterima sebagai normalitas, common sense dan kebenaran tanpa disertai sikap kritis.
Ketersediaan ruang publik yang aksesibel, produktif dan transformatif bagi lansia dengan demikian merupakan cerminan dari penjungkirbalikan (subversi) terhadap tatanan simbolis sosial yang stereotipikal itu. Ketersediaan ruang publik yang aksesibel, berfungsi sebagai kritik terhadap tatanan simbolis stereotipikal itu sekaligus menyediakan produksi makna, asumsi, pengetahuan, penilaian, dan keyakinan alternatif tentang manusia lansia.
Subversi terhadap tatanan simbolis yang stereotipikal itu memandang manusia lansia sebagai subyek bermartabat yang pantas mendapatkan ekosistem sehat dan produktif bagi seluruh proses pembentukan dan pertumbuhan dirinya. Akibatnya, subversi ini melahirkan praktik penyediaan ruang publik yang aksesibel, produktif dan transformatif.
Sebaliknya, tatanan simbolis yang berisi stereotype terhadap manusia lansia tidak memandang manusia lansia sebagai subyek yang bermartabat dan masih terus-menerus produktif melahirkan makna dan secara kreatif melahirkan inspirasi bagi sesama maupun lintas generasi. Tatanan simbolis yang bersifat stereotipikal terhadap manusia lansia ini pada gilirannya justru melahirkan alienasi terhadap subyek lansia. Tidak tersedianya ruang publik yang aksesibel, produktif dan transformatif bagi lansia, menjadikan lansia menghadapi pengalaman-pengalaman yang dapat melahirkan makna penolakan yang traumatis, tiadanya pengakuan (recognition), pemaksaan konsepsi atau citra diri bahwa ia merupakan subyek yang lemah, yang menghadapkan dirinya pada ruang-ruang yang menolak kehadiran dirinya sebagai manusia lansia, mengabaikannya dan menyingkirkannya.
Tiadanya ruang publik yang aksesibel dapat meruntuhkan martabat dan citra diri manusia lansia, menjadikan dirinya merasa sebagai manusia terbuang, lemah, terpinggirkan, tak berkapasitas, tak dihargai, teralienasi, dan merasa kehilangan. Tatanan simbolis yang alienatif terhadap manusia lansia ini dapat mengakibatkan manusia lansia menjadi subyek yang meredup, menjadi layu, dan tak pernah merekah lagi.
Tiadanya ruang publik yang aksesibel, atau tersedia ruang publik namun tidak aksesibel bagi lansia merupakan manifestasi dari struktur tak sadar masyarakat, terutama para pembuat kebijakan. Meminjam istilah dari Sigmund Freud, secara analogis, tiadanya ruang publik yang aksesibel atau seandainya ada, namun tidak aksesibel bagi lansia, itu seumpama suatu selip lidah atau guyonan yang mencerminkan atau memanifestasikan struktur ketaksadaran yang memengaruhi seluruh ekspresi dirinya.3 Struktur ketaksadaran inilah yang di bagian awal tadi disebut sebagai tatanan simbolis.
Dengan demikian pantas dinyatakan bahwa ruang publik yang aksesibel bagi lansia, meskipun merupakan ruangan fisik, ia tidak akan dipahami semata-mata sebagai ruang fisik melainkan juga sebagai teks, sebagai sistem tanda, yang dibaca oleh subyek lansia dan menyampaikan suatu pesan kepadanya. Semua bentuk aksesibilitas dalam rupa desain, fasilitas, rambu-rambu, kehadiran subyek lain serta kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalamnya akan dibaca oleh subyek lansia sebagai pesan yang meneguhkan citra dirinya, penerimaan, penghargaan, pengakuan, kesempatan untuk berpartisipasi, dan kebermaknaan. Ruang publik yang seperti ini menjadi subversi terhadap teks atau sistem tanda yang pada umumnya mengalienasi. Ruang publik yang aksesibel ini melahirkan momen-momen pengalaman yang benar-benar menganggu dan menjungkirbalikkan representasi stereotipikal tentang penuaan sebagai kemunduran dan keterbatasan. Sebagai subversi, ruang publik yang aksesibel bagi lansia seperti mau menyatakan bahwa manusia lansia bukanlah manusia lemah yang tak pantas mendapatkan perhatian dan bisa dilupakan, melainkan subyek yang masih terus meniti proses kehidupan, melahirkan kreativitas, memproduksi makna dan menggetarkan.
Aktivitas dan Komunitas sebagai Negosiasi
Beragam aktivitas yang dijalankan di dalam komunitas-komunitas lansia, baik itu komunitas seni dengan segala jenisnya, komunitas sastra-budaya, komunitas keterampilan dan ekonomi kreatif-alternatif, komunitas senam, jogging dan kesehatan, komunitas gowes, komunitas kuliner dan komunitas-komunitas hobi lainnya, semuanya itu merupakan hal yang penting. Semua aktivitas itu merupakan alat dan media serta langkah nyata untuk bernegosiasi demi merebut makna tentang lansia. Disebut sebagai alat dan media serta langkah nyata untuk bernegosiasi karena semuanya itu merupakan tawaran konstruksi makna tentang lansia, bahwa manusia lansia bukanlah kaum lemah tanpa kapasitas dan bukanlah subyek yang berhenti berproses memproduksi makna hidup, melainkan subyek yang masih terus bergerak, kreatif, memberdayakan diri, membagi inspirasi, aktif ber-partisipasi dan berkontribusi dalam beragam aspek kehidupan masyarakat, serta masih tetap merupakan subyek yang bermartabat dengan segala hak dan kebutuhan yang setara di tengah kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Manusia lansia adalah tetap merupakan bagian dari warga negara. Subyek lansia bukanlah setengah warga negara, apa-lagi setengah manusia. Manusia lansia adalah subyek utuh bermartabat dengan segala kompetensi, kapasitas, hak dan kewajibannya.
Sebagai analogi, melalui karya-karya arsitekturalnya, almarhum YB. Mangunwijaya melakukan negosiasi dengan negara untuk membela, mengadvokasi hak-hak masyara-kat bantaran kali Code untuk hidup dan berkomunitas di wilayah itu dalam segala keterbatasan dan kesulitan yang dihadapinya, agar negara yang memandang mereka sebagai sampah dan pencoreng citra keindahan kota, tidak menggusur dan menelantarkan mereka. Karya-karya arsitektural yang memungkinkan warga masyarakat bantaran kali Code itu menata lingkungan dan kehidupan mereka sendiri secara merdeka dan indah, pada akhirnya sanggup merebut makna tentang martabat warga negara, sehingga masyarakat bantaran kali Code tidak mengalami penggusuran, tak lagi dianggap sebagai sampah dan pencoreng keindahan kota, diakui (recognition) sebagai warga negara sehingga lingkungan pemerintahan terkecil, yakni kelurahan, memasukkan mereka sebagai bagian dari warga dan memberikan kartu tanda penduduk kepada mereka sesuai dengan hak dan martabatnya.
Dalam analogi itu, seluruh aktivitas yang dijalankan di beragam komunitas lansia, juga merupakan alat, media dan langkah negosiasi untuk merebut makna lansia sebagai warga negara yang bermartabat sehingga memiliki hak-hak yang harus dipromosikan, dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Melalui semua aktivitas di beragam komunitas itu, manusia lansia menunjukkan dan menawarkan bukti serta validasi makna bahwa manusia lansia adalah subyek bermartabat yang senantiasa berproses membentuk dirinya, memproduksi makna dalam kehidupan, melahirkan inspirasi kepada lintas generasi, menetaskan kreativitas dan bahkan masih tetap sanggup melahirkan teladan integritas.
Semoga manusia lansia semakin sanggup memenangkan konstruksi makna di tengah tatanan simbolis masyarakat sehingga meraih martabat dan hormat. Produksi kebijakan tentang ruang publik dan implementasi layanan ruang publik yang aksesibel dan ramah bagi manusia lansia, merupakan salah satu wujudnya. ***
1 Sean Homer, Jacques Lacan, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2005, hlm.90
2Lih Sean Homer, Jacques Lacan, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York 2005, hlm.43-44
3Lih. Sigmund Freud, Jokes And Their Relation To The Unconscious (1905), Free eBoook from www.SigmundFreud.net
—–
Indro Suprobo, Penulis, Editor, Penerjemah Buku, tinggal di Yogyakarta.
Ons Untoro, Penulis, Penyair, Pendiri dan Pengelola Sastra Bulan Purnama, Yogyakarta.