Dari Tubrukan ke Kebinekaan, Puisi Sunda Arip Senjaya

Oleh Deri Hudaya
Judul buku : Ceurik Arsénik Made in Nagara Komik
Penulis: Arip Senjaya
Gambar Sampul: “Serial Sapi Super Animal” Rudi ST Darma
Drawing Eusi: Rudi ST Darma, Ahmada Faisal Imran, Isa Perkasa,
Amran Japaring, Nandanggawae.
Disain Sampul & Eusi: Kaverboi
Diterbitkan: Penerbit Anak-Anak Rel
Cetakan: I, Maret 2021
Tebal: xiv+80 halaman: 12 x 18 cm
ISBN: 978-623-7820-09-03
1.
“… sampé kiwari di dieu mah euweuh nu aranna tradisi nulis sajak atawa carita basa Sunda nu makéan basa Sunda ti wewengkon belah dieu.”
“… sampai saat ini di sini tidak ada tradisi menulis
puisi atau cerita menggunakan bahasa Sunda dari daerah ini.”
—Niduparas Erlang
Jika benar apa yang ditulis Niduparas Erlang di penutup buku ini bahwa di Banten tidak ada tradisi menulis puisi dengan bahasa Sunda dialek Banten, maka antologi puisi karya Arip Senjaya ini merupakan tonggak. Mungkin itu sebabnya Rudi ST Darma, Ahmad Faisal Imran, Isa Perkasa, Arman Jamparing, hingga perupa Jawa Barat sekelas Nandang Gawe antusias menyambutnya. Para perupa itu ikut menyumbang drawing untuk sampul hingga ilustrasi buku yang diterbitkan oleh Anak-Anak Rel pada Maret 2021 silam. Jikapun bukan tonggak, saya tetap bahagia bisa membaca karya yang menawarkan alternatif pada khazanah puisi bahasa Sunda.

Drawing Rudi ST Darma di buku Ceurik Arsénik Made in Nagara Komik

Drawing Nandanggawe di buku Ceurik Arsénik Made in Nagara Komik
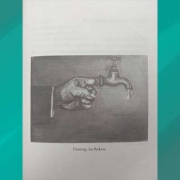
Drawing Isa Perkasa di buku Ceurik Arsénik Made in Nagara Komik
Mula-mula saya terkesan dengan waktu terbitnya, memilih terbit di masa krisis akibat pandemi, ketika sastra Sunda—bahkan sebelum pandemi—sudah mengalami masa krisis. Kritikus Hawe Setiawan1 ketika mengumumkan pemenang hadiah sastra Rancagé pernah menyebut sastra Sunda seperti ada sekaligus tidak ada. Uji coba mengubah teks sastra jadi konten digital adalah kecenderungan baru dari sastra, tak terkecuali dalam sastra Sunda. Ada harapan karya sastra bisa bertemu dengan orang baru, dengan jumlah penikmat lebih luas dari yang dapat dijangkau buku. Dengan kuatnya tendensi ini Afrizal Malna, di kanal Youtube Lampung Kultur, sambil ketawa-ketawa namun tetap serius, berpendapat bahwa di ekosistem sastra sekarang fungsi kritikus bahkan bisa digeser selebgram. Bagi saya, tetap menerbitkan buku, tidak membiarkan diri terlalu hanyut dengan kecenderungan zaman adalah sikap menarik juga.
Arip Senjaya tidak sepenuhnya ada di luar arus. Saya pertama kali mengenalnya justru melalui musikalisasi Panji Sakti atas puisinya di Instagram, juga melalui beberapa video pembacaan puisi yang dibuat oleh dirinya sendiri. Bahkan, saya tahu bukunya terbit lewat cerita (story) Instagram yang dibagikan seorang teman, yang bukan selebgram, yang bukan kritikus sastra. Yang membuat saya ingin segera memiliki bukunya adalah karena saat itu saya curiga akan bertebarannya frasa di kanal-kanal digital semacam “kampus merdeka”, “merdeka balajar”, “vaksin merah-putih”, “vaksin nusantara”, yang terasa aneh. Sementara buku puisi bahasa Sunda itu diberi judul seakan sengaja bertentangan: Ceurik Arsénik Made in Nagara Komik (tangis arsenik dari negeri komik).
Tentu saja saya kemudian membacanya tidak dengan sikap tanpa kepentingan. Saya ingin menemukan apakah kata “merdeka” bisa mendapat pengertian dari kata “ceurik”? Apakah frasa “merah-putih” akan mendapat referensi baru dari frasa “made in”? Apakah kimia yang kerap dikaitkan dengan misteri kematian Munir, yakni “arsenik”, ada relasinya dengan wacana “vaksin”? Apakah buku puisi ini dapat menciptakan jalan baru bagi perkembangan puisi bahasa Sunda? Dan pertanyaan-pertanyaan lain bermunculan begitu saja. Selebihnya saya membaca buku puisi sekedar untuk bersembunyi dari rasa asing yang nyaris tak tertanggungkan lagi di tengah pandemi, yang membuat segalanya absurd dan sulit dibahasakan.
2.
“Puisi adalah tentang sejarah kesulitan
pengucapan yang bersifat individualistik ….”
–Arip Senjaya
Dalam esai berjudul “Jalan Setapak Umat Ibrahim”2 itu, Arip Senjaya mengutarakan pengakuan bahwa ia pernah mengalami gegar bahasa. Setelah lulus sarjana ia pindah dari Bandung ke Banten oleh alasan pekerjaan. Di Bandung bahasa Sunda dikategorikan sebagai bahasa dialek Priangan dengan ciri lekatnya undak-usuk (tingkatan-tingkatan) bahasa, sementara dialek Banten tidak, sama seperti dialek-dialek lain di luar Priangan. Kepindahan itu di satu sisi membuat ia terpisah dari bahasa yang diajarkan lingkungan keluarganya, yang melekat dengan dirinya sejak masa kecil, dialek bahasa Sunda yang jadi bahasa baku sekaligus konvensi tradisi tulis, serta jadi acuan utama kesusastraan Sunda. Bahasa baru bagi Arip Senjaya, yaitu dialek Banten, di sisi lain membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi dengannya. Kesulitan itu ia bawa juga ke dalam puisi, genre sastra yang konon telah menarik minatnya sejak SMP.
Molotov
Ma, aing deuk balik deui ka diya, Ma!
Sono aing dibabuk ku céntong diya
Nepi ka pitakan hulu aing
Ma, aing deuk balik deui ka diya, Ma!
Hayang aing diusir deui ku diya
Ngarah bisa nyaba leuwih jauh ka luar nagara
Ma, aing can bisa balik ayeuna, Ma!
Loba pisan anjing ngahalangan jalan
Si Tumang geus dipodaran ku aing harita
Tapi balad-baladna, Ma, teu béak-béak ku aing dimolotov!
2008
Molotov
Mak, gue pengin balik menemuimu lagi, Mak!
Gue kangen pengin dipukul penanak nasi
Sampai palaku jadi pitak
Mak, gue nanti pasti balik, Mak!
Gue pengin diusir sekali lagi
Biar gue bisa pergi lebih jauh ke luar negri
Mak, gue belum bisa balik sekarang
Banyak anjing merintangi jalan
Si Tumang dulu sudah dibikin mampus
Tapi temen-temennya, Mak, gak habis-habis gue molotov!
2008
Puisi tersebut bagi saya adalah pengakuan lain dari alienasi bahasa yang dialaminya. Ada kemarahan akibat terpisah dari bahasa Ibu, dialek Priangan, lantas ia terseret petualangan bersama dialek Banten. Dua dialek bahasa Sunda di puisinya muncul sekaligus, bertabrakan, jadi penanda dari pertentangan batin dalam dirinya. Pertentangan itu lantas meruncingkan kelugasan nada (tone) dalam puisi, yang mula-mula direduksi dari nada bicara para pengguna dialek Banten. Kelugasan ini jarang terjadi jika puisi ditulis dengan dialek Priangan yang dilekati dan stereotip bahwa para penuturnya tidak biasa bicara lugas, alih-alih berbahasa lembut dan simbolik, bilang begini dengan maksud begitu agar tidak menyinggung lawan bicara.
Kita bisa membandingkan puisinya dengan puisi lain, karya Hadi AKS. Biografi Hadi AKS berbanding-terbalik dengan Arip Senjaya. Ia lahir di Pandeglang, Banten, lalu bekerja dan menetap di Bandung. Ia kerap menggunakan kosa kata dialek Banten, baik dalam puisi maupun dalam prosa.
Néangan Kentring
Kentring, ieu kami datang nyusul sora lisung
hawar-hawar. Kapireng dia ngawih ngalaeu
di saung lisung, di lamping Nagri Pakuan.
Trung-trung kelentrung. Aya tanda
ti karuhun. Ka nagri urang nu keur Liwung.
Teu kebat sora nu nembang, sabab dayeuh laju hurung
ngagugudag, diduruk punggawa Banten.
Biheung ka mana dia ngejat harita. Nya kami
terus nyusulan. Néangan teu eureun-eureun.
…
2015
Mencari Kentring
Aku datang mencari suara lesung
lamat-lamat. Terdengar ia lantunkan kawih
di saung lesung, di lereng Negeri Pakuan.
Trung-trung kelentrung. Ada tanda
dari moyang. Untuk negeri yang bimbang
Mesti terhenti dendang tembang, sebab kota terbakar
hebat, dibakar prajurit Banten.
Entah ke mana ia pergi. Aku
terus mencari. Terus mencari-cari.
….
2015
Dalam puisi Hadi AKS tersebut dunia Banten hadir bukan dalam wujud bahasa. Puisinya liris, tidak bernada lugas, tapi mengalun layaknya tembang atau nyanyian. Di puisi liris, ada kesan perfeksionis dalam memilih bunyi agar kata-kata tidak terdengar berantakan, agar nada di dalam puisi tidak bertabrakan. Puisi tersebut ada di buku puisi terbarunya berjudul Tembang Matapoe3 yang masuk nominasi hadiah sastra Rancagé. Adapun kosa kata dari dialek Banten muncul di puisinya sebagai penanda dari luasnya referensi bahasa penyair, untuk memainkan suasana, untuk mempertegas latar tempat. Dunia Banten hidup di puisinya terutama sebagai peristiwa, dalam hal ini asal-usul masyarakat adat Kanekes yang merujuk pada proses islamisasi Kerajaan Pajajaran oleh Kesultanan Banten di masa silam.
Jika Niduparas Erlang, yang menulis kata penutup di buku Arip Senjaya, di suatu ketika yang berbahagia pernah membacanya, wajar apabila ia mengambil simpulan bahwa Hadi AKS tidak menulis dengan dialek Banten, tapi mengangkat tema tentang Banten dengan bahasa dialek Priangan. Kemampuan Hadi AKS dalam penguasaan dialek Banten akan tampak lebih meyakinkan dalam karya-karya prosa berupa cerpen dan fiksimini berbahasa Sunda.
Selain Hadi AKS, pengarang yang sering menggunakan kosa kata dari dialek Banten, bahkan biografi dan latar kreatifnya perbijak di Banten, adalah Rohendi. Nama pena sekaligus nama akun Facebook-nya bahkan identik dengan Banten, yaitu Rohendi Pandeglang. Akan tetapi, tak ada puisinya yang bisa saya temukan, kecuali cerpen, terutama fiksimini bahasa Sunda dengan jumlah melimpah. Saya ada di antara mereka yang percaya bahwa bahasa puisi lebih proporsional jika dibandingkan dengan bahasa puisi lagi, bukan dengan prosa. Seandainya Rohendi pernah menulis puisi dengan dialek Banten, saya yakin puisi-puisinya belum dipublikasikan dalam antologi tunggal. Tidak ada buku puisi bahasa Sunda dengan nama penulis Rohendi ketika saya bertanya pada ia yang serba tahu itu, Google, rezim dokumentasi yang minimal bisa diandalkan untuk mencari tahu sampul atau sebatas deskripsi buku.
Sampai di bagian ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa tubrukan dialek Banten dan dialek Priangan dalam puisi Arip Senjaya adalah kearifan yang ia temukan secara autentik. Motif tubrukan itu berasal dari pengalamannya sendiri setelah mengalami kegamangan di antara dua dialek bahasa Sunda. Temuannya bisa dikatakan autentik sebab tidak ada penyair lain yang sama dalam memperlakukan kedua dialek tersebut dalam puisi berbahasa Sunda. Dua dialek yang digunakan sekaligus itu membuat bahasa Sunda bermakna jamak, plural, atau agar disebut pancasilais sebut saja: bineka.
Perjalanan menuju kearifan tersebut dapat ditelusuri melalui puisi “Molotov” yang merekonstruksi ulang Mitos. Sangkuriang terusir lalu menemukan betapa nikmat dan menantangnya petualangan di wilayah asing. Sangkuriang memang rindu dan ingin kembali pada ibunya (dialek Priangan), agar ia mengalami pengusiran lagi, agar dirinya bisa mengalami petualangan yang lebih jauh lagi keluar dari batas-batas dialek Priangan. Rindu Arip Senjaya pada bahasa ibu bukan kerinduan yang romantis dan bernada liris, tapi kerinduan yang mengandung motolov, sesuatu yang bisa diledakkan untuk menghancurkan aturan yang telah ada, pakem yang baginya terlalu didewakan semacam Si Tumang.
Pada satu diskusi di Forum Masyarakat Membaca4, Arip Senjaya mengaku jenuh dengan puisi bahasa Sunda umumnya di mana konvensi puisi liris terlalu luas pengaruhnya, membatasi bahasa selembut lagu sesuai stereotip terhadap dialek Priangan, yang nadanya tak berantakan, kesannya tak lugas, tak bisa mewakili keresahan manusia Sunda urban seperti dirinya yang bisa kehilangan hubungan romantis dengan bahasa ibu, juga dengan hal-hal lain di luar bahasa. Menurut Hawe Setiawan, awal mula sastra Sunda memang kental dengan lirik, menulis sastra berarti menggubah lagu.5 Barangkali tetap setia terhadap ukuran puisi Sunda tersebut tak hendak dipilih Arip Senjaya:
Aya Hiji Jalan
Aranna Jalan Di Tempat
…….
Aya hiji jalan aranna Jalan Di Tempat
Di jalan éta aing sina tamat
2017
Ada Satu Jalan
Namanya Jalan Di Tempat
…..
Ada satu jalan namanya Jalan Di Tempat
Di situ gue dibikin sekarat
2017
3.
Memang saya terkejut ketika di puisinya terjadi tubrukan antara dialek Priangan dan dialek Banten setiap muncul kosa kata “diya”, “doang”, “jasa” , “jing”6, dst. Tubrukan bahasa itu terus-menerus dipertahankan, seakan jadi pakem dari wilayah bahasanya Sundanya sendiri. Dan tubrukan itu tidak cukup. Ia melibatkan kosa kata berbau impor seperti “véri lovéli”, “émézing”, “snorkling”, “boéh kasteum”, “dipréng”, yang ditulis dalam tata tulis bahasa Sunda. Ada juga kata dari tradisi ilmiah yang sesekali turut menyeruak seperti “arsénik”, “abstrak” dll. Lalu ikut bertumbukan pula kosa kata pergaulan yang sering diumbar dan digunakan warganét asal Sunda ketika berkelakar di konten-konten digital seperti kata “bangké”, “modol”, “hitut”, “goblog”, “cingcay” atau cicing bari ngacay.
Tubrukan-tubrukan bahasa tersebut melampaui batas dua dialek bahasa Sunda, bahkan menerima serta mensejajarkan yang asing, yang murahan, yang intelek, yang slengean. Ada kesan serius untuk bermain-main dengan bahasa, kadang berhasil jadi humor (komikal) dalam puisinya.
Lebih lanjut, bahasa itu mengemas berbagai gagasan chaos dan satire, misalnya tentang cara berdoa agar tak sambil menjilat—tak menyamakan Tuhan dengan gubernur berwatak feodal—dalam puisi “Kawajiban Jalema Hirup”. Puisi “Cimol” bicara tentang cinta yang dipenggal jadi (ci)mol dan ko(ta).7 Puisi “Abstrak Karya Ilmiah Kabudayaan Bako” mengolok-olok tradisi penulisan ilmiah yang terlampau mengedepankan keseragaman. Puisi “Hipotesis Hayam Broiler” bicara tentang manfaat KB untuk mengurangi jumlah demonstran. Sementara puisi “Beko” bicara tentang beko yang rakus hingga semua orang dan semua benda dan seluruh tempat di sebuah negara habis dimakan olehnya.
Perpaduan antara gagasan dan kemasan (bahasa) itu mengesankan selera humor yang keras kepala. Humor adalah salah satu karakter khas masyarakat Sunda sejak lama, sebelum tradisi lisan mengisahkan si Kabayan yang berperilaku konyol namun filosofis, juga jadi alasan wayang golek mengedepankan tokoh-tokoh kocak seperti Cepot, Gareng, dan Dawala. Akan tetapi, humor bukan sesuatu yang dominan dalam puisi Sunda, kecuali dalam sebagian besar gagasan—bukan pada bahasa—karya Taufiq Faturohman,8 seperti dalam puisi berikut:
Tresna III
Asih téh lir qur’an butut
diaji teu bisa ditincak
doraka
Tresna III
Cinta serupa qur’an butut
dibaca sulit diinjak (dilakoni)
dosa
Sementara bahasa dalam puisi Arip Senjaya hadir sebagai humor itu sendiri. Di samping itu, bahasa puisinya yang memunculkan kosa kata beragam, yang selalu dipertahankan hampir dalam semua puisinya, diam-diam berubah jadi pesan itu sendiri: bahasa Sunda dalam kebinekaan. Pesan itu penting karena selama ini khazanah puisi Sunda khususnya, sastra Sunda umumnya, masih terlalu didominasi oleh pengaruh dialek Priangan, tidak dengan dialek Banten, tidak dengan dialek Kawarang, tidak dengan dialek Baduy, dan dialek lainnya. Jika muncul kosa kata dari dialek-dialek di luar Priangan, para kritikus atau akademisi lazim menandainya dengan sebutan “basa wewengkon”. Wewengkon artinya daerah, bukan pusat. Istilah itu menegaskan bahwa dialek Priangan masih utama sementara dialek lainnya pinggiran.

Arip Senjaya
Selebihnya, kebinekaan itu mereduksi bahasa asing yang datang dari luar batas bahasa Sunda, bahkan berani menyerap bahasa dari pergaulan di dunia digital yang selalu temporer. Motif ini menunjukkan sebuah kesadaran terhadap percampuran (akulturasi) sebagai yang alamiah, saling memengaruhi dengan kebudayaan lain bukan kesalahan. Kebinekaan bukan katak dalam tempurung. Arip Senjaya dengan motif tersebut seperti membuat satire terhadap politik identitas di negara yang selalu gamang memasuki pergaulan dunia, yang senang menghasilkan gimik tentang keaslian dan kemandirian seperti dalam frasa: “vaksin nusantara”, “belajar merdeka”, “vaksin merah-putih”, dst. Gimik-gimik itu bisa membungkam suara-suara kritis yang beroposisi terhadap mapannya kekuasaan, semacam kimia arsenik untuk melenyapkan Munir di masa Orba.
Sajak Saayana
……….
Mun sia teu bogoh kénéh kana sajak aing ieu
sia jeung aing jelas pisan lain jodo
Jodo sia mah jorok, ayana dina sajak-sajak capruk
Sajak-sajak bangké pinuh rambetuk!
………
2019
Sajak Apa Adanya
……
Kalo elo masih nggak cinta sama sajak gue ini
gue dan elo pastinya bukah jodoh
Jodohmu cetek, ada di sajak-sajak ngaco
Sajak-sajak bangke penuh lalat!
2019
Dua larik awal dari puisi yang saya kutip tersebut memperlihatkan sikap terbuka, sesuai dengan motif kebinekaan yang ditawarkan Arip Senjaya. Pembaca dipersilakan untuk menerima atau menolak puisinya. Semua itu seakan tergantung selera. Sekalipun menarik, puisi yang ditulis Arip Senjaya tidak akan pernah diterima atau sebaliknya ditolak secara total oleh pembaca puisi Sunda. Puisi sama seperti perempuan cantik bagi laki-laki, tidak ada perempuan cantik bagi semua laki-laki, kecuali dalam utopia Miss Universe di televisi. Namun dua larik akhir ternyata membalik sikap terbuka tersebut dengan ekstrim. Pembaca di luar selera puisinya dianggap hanya akan berjodoh dengan puisi: jorok, capruk, bangké. Artinya, puisi ini menyatakan penolakan terhadap perbedaan, anti-kebinekaan.
Dalam esai “Setapak Jalan Umat Ibrahim”, Arip Senjaya menyatakan bahwa penyair tidak perlu memuja pencapaian atas karyanya sendiri. Penyair harus membuat puisi yang baik dan tak perlu segan untuk kemudian menghancurkannya. Jika tidak, penyair itu Firaun sekali. Lalu dengan menulis “Sajak Saayana” apakah ia tengah berusaha menghancurkan kebinekaan yang telah ia bangun dalam puisi-puisinya di antologi ini agar kebinekaan itu tidak berpeluang menjadi berhala bagi pembacanya? Saya pikir terlalu buru-buru. Arip Senjaya mestinya menghancurkan pencapaiannya, nanti, di antologi puisi berikutnya, dengan cara menghadirkan esetetika yang berbeda dan tak melakukan pengulangan.
Dalam tafsiran lain, bisa saja puisi tersebut dialamatkan pada sebuah rezim yang dalam pandangannya telah memberhalakan puisi-puisi tertentu sekaligus menghalangi terciptanya kebinekaan dalam khazanah puisi berbahasa Sunda. Arip Senjaya datang dengan puisinya, serasa Ibrahim dan kapaknya, ingin menghancurkan berhala-berhala itu.
—-
1 Baca artikel Hawe Setiawan di Facebook (03/01/2021), berjudul “Terasa Ada, Terlihat Tidak”.
2Esai ini dipublikasikan di web Borobudur Writers Cultural Festival (29/07/2021)dalam rangka menyambut Hari Puisi. Saya kira pernyataan yang saya kutip, lebih layak dijadikan kredo kepenyairannya dibandingkan dengan bagian puisi “Banyumas” yang menurut Ujianto Sadewa dalam diskusi di Forum Masyarakat Belajar mengandung kredo.
3 Tembang Matapoé (Geger Sunten, 2018). Judul ini mengingatkan saya pada antologi tunggal Acep Zamzam Noor, Dayeuh Matapoé.
4 Diskusi tersebut bertajuk Wabah, Sajak dan Kemerdekaan (18/08/2021). Catatan ini sebetulnya disusun untuk diskusi tersebut, namun nyatanya baru bisa diselesaikan beberapa hari setelah diskusinya selesai.
5 Masih mengacu pada artikel Hawe Setiawan di Facebook, berjudul “Terasa Ada, Terlihat Tidak”.
6 Awalnya saya kira “jing” adalah singkatan dari umpatan “anjing”, ternyata bukan. “Jing” merupakan fatis, sejenis dengan “duh”, “sih”, dll.
7 Dalam diskusi sastra di Komunitas Rawayan, puisi “Cimol” ditafsirkan oleh Tedi Muhtadin dan Dian Hendrayana sebagai puisi yang teknik bahasanya bertolak dari teori formalisme sastra.
8 Puisi Taufik Faturohman ini diambil dari bunga rampai Sajak Sunda Indonesia Emas (Geger Sunten, 1995).
*Deri Hudaya lahir di Garut, 3 September 1989. Menulis dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Saat ini mengajar di Ilmu Komunikasi, Universitas Garut. Buku terakhirnya bertajuk Puisi Sunda 18+ (Kenja Press, 2021) dan antologi puisi Lawang Angin (Langgam Pustaka, 2021).













