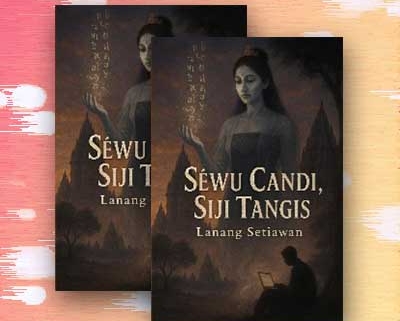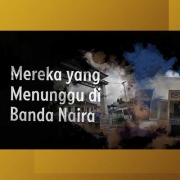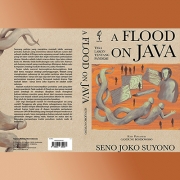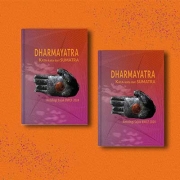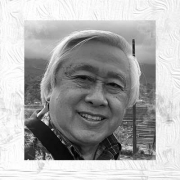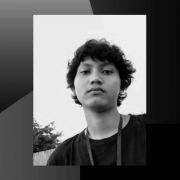Cinta yang Tak Selesai, Sejarah yang Terlupakan: Membaca Sewu Candi Siji Tangis karya Lanang Setiawan

Oleh Kang Du
“Candi-candi itu menyimpan lebih banyak air mata daripada dupa. Tapi hanya sedikit orang yang mendengarnya.”
— Raswadi Utomo
SETIAP bangsa menyimpan sejarah dalam bentuk monumen, dan setiap monumen menyimpan narasi yang dipahat dalam diam. Namun sejarah resmi terlalu sering ditulis oleh mereka yang menang. Maka suara-suara kecil—jerit tukang batu, tangis perempuan yang ditinggal, keluh para petani yang sawahnya diambil untuk candi agung—luruh tanpa tapak. Di sanalah novel Sewu Candi Siji Tangis hadir, sebagai perlawanan naratif terhadap pelupaan kolektif.
Novel ini bukan sekadar fiksi sejarah. Ia adalah gugatan yang dilapisi cinta, kritik sosial yang dibalut dalam puisi, dan rekonstruksi budaya yang lahir dari luka-luka kolektif masyarakat kecil. Lanang Setiawan, sang pengarang, tidak menulis dari menara gading akademik, melainkan dari bumi: dari tanah yang diinjak petani, dari pasar yang dijejaki pengamen, dari laku ziarah sunyi seorang penyair yang ingin memahami ulang kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso.
Tokoh sentral novel ini, Raswadi Utomo, adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara dunia gaib dan dunia realis. Ia seorang penyair tua yang manggon di penginapan murah, hidup dari pembacaan puisi, tetapi menyimpan peti-peti sejarah dalam ingatannya. Lewat matanya, kita menyaksikan bukan hanya candi yang menjulang, tetapi juga tangisan-tangisan yang membangunnya.
Raswadi mengembara dari desa ke desa, dari kota ke kota, bahkan dari dunia ke dunia—mengalami pertemuan mistis dengan roh-roh leluhur, mendengar suara-suara perempuan yang dikorbankan demi obsesi kekuasaan. Di suatu malam, ia menyaksikan pertemuan puncak antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, namun bukan dalam suasana romantis, melainkan dalam ruang perenungan dan permohonan maaf.
“Aku tidak ingin jadi arca. Tapi kalau dunia ini tetap keras kepala, mungkin lebih baik aku jadi batu daripada jadi manusia yang dipaksa tunduk.”
— Roro Jonggrang
Kutukan itu, yang sering dianggap mitos, dalam novel ini ditafsir ulang sebagai bentuk perlawanan terhadap kuasa maskulin dan kekuasaan yang memaksa. Roro Jonggrang bukan korban, tapi simbol. Simbol dari perempuan yang ingin menentukan nasibnya sendiri. Dan Bandung Bondowoso, dalam tangan Lanang Setiawan, bukan sekadar pangeran sakti, tapi potret penguasa yang harus belajar mencinta tanpa menaklukkan.

Puisi sebagai Perlawanan
Ciri khas naratif yang menjadikan novel ini berbeda adalah hadirnya bentuk puisi Tegalan yang disebut “puisi Tegalerin”. Ini adalah bentuk puisi lokal, pendek, dan padat, yang muncul sebagai ekspresi spontan Raswadi dalam menghadapi situasi sosial dan spiritual. Seperti dalam bait berikut:
Ngadeg candi,
Ati nyawang jalmo mati.
Swara lumpur,
Kaya tangis sing disilih.
Puisi ini tak hanya menambah kedalaman emosi, tetapi juga menjadikan bahasa daerah sebagai medium utama untuk menyampaikan kedalaman batin dan realitas sosial. Raswadi tidak menulis puisi untuk dikenal, tapi sebagai upaya mencatat yang tidak bisa dicatat sejarah.
Maka novel ini juga menjadi dokumen budaya. Sebuah upaya pengarsipan rasa dan ingatan dari perspektif Tegal dan wong cilik. Dalam sebuah adegan, Raswadi tampil membaca puisi di alun-alun Tegal:
“Wong-wong nglumpuk. Ora ana panggung megah. Mung saben tembung saka lambeku, nempel ning langit-langit alun-alun. Kaya swara leluhur sing mudik njaluk didangu.”
Adegan ini mencerminkan semangat akar rumput: bahwa suara rakyat bukan ditunggu tampil di istana, tapi dilahirkan di ruang publik rakyat. Inilah simbol penting dari novel ini: bahwa sejarah dan seni tak harus agung dan elit—cukup jujur dan dari rakyat.
Sewu Candi, Siji Tangis
Judul Sewu Candi Siji Tangis bisa dibaca dalam banyak lapisan. “Sewu candi” merujuk pada peradaban, pada prestasi, pada kebesaran bangsa. Tapi “siji tangis”—satu tangis—adalah pusat dari semuanya. Tangis itu bisa berasal dari korban yang dikorbankan demi kejayaan. Bisa dari ibu yang kehilangan anak. Bisa dari seorang penyair tua seperti Raswadi, yang menyadari bahwa seluruh kebesaran itu kadang hanya berdiri di atas luka yang tak pernah sembuh.
Novel ini bukan tentang membalik sejarah, tetapi mengisinya dengan suara yang hilang. Ia tidak menawarkan narasi pasti, tapi mengajak kita bertanya: siapa yang sesungguhnya kita banggakan? Penguasa yang membangun? Atau rakyat yang memikul batu dengan tangis diam-diam?
Dan dari pertanyaan itulah, novel ini menjadi penting. Sebab di tengah zaman yang makin melupakan sejarah rakyat kecil, karya seperti ini menjadi penyeimbang. Ia bukan hanya novel. Ia adalah peringatan.

Penutup
Novel Sewu Candi Siji Tangis layak dibaca sebagai bagian dari upaya kita memulihkan narasi sejarah lokal dan membongkar mitos yang terlalu lama dianggap suci tanpa digugat. Raswadi, Roro Jonggrang, bahkan Bandung Bondowoso, semuanya adalah simbol dari dunia lama dan dunia baru yang terus bernegosiasi.
Melalui novel ini, Lanang Setiawan bukan hanya menulis cerita, tapi menaburkan kembali benih kesadaran: bahwa di balik tiap tumpukan batu, selalu ada tangis yang layak diingat.
“Tangisku dudu merga kalah. Tapi merga aku ngerti, sing menang ora mesti bener.”
— Raswadi Utomo
Selamat membaca, dan selamat menyelami kembali suara-suara yang telah lama dibungkam. (*)
—–
*KANG DU adalah Pimred Panturapost.com