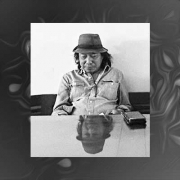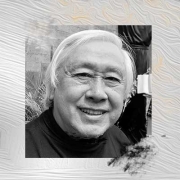Wayang, Anak dan Politik Kebudayaan
Oleh Purnawan Andra*
Festival Dalang Anak Nasional yang digelar di Gedung Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah, pada 3-5 November 2025 ini mungkin tampak seperti kegiatan rutin – sekumpulan anak memainkan wayang dengan menyajikan teknik estetika untuk melestarikan tradisi.
Namun di balik layar pertunjukan itu, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih mendesak. Dalam kebudayaan yang kian diseret oleh logika algoritma dan kepentingan politik jangka pendek, apa arti pendidikan estetik dan moral melalui wayang bagi anak-anak masa kini?
Ruang Diskursif
Wayang pernah menjadi medium paling canggih dalam menyampaikan nilai, kritik, dan pengetahuan di Nusantara. Dalam tangan dalang, ia menjadi ruang diskursif yang lentur yang memadukan mitos dan realitas, tatanan dan subversi.
Clifford Geertz menyebut wayang sebagai bentuk “teater moral” masyarakat Jawa. Ia bukan sekadar tontonan, tapi laku tafsir atas hidup, kuasa, dan kebenaran. Di panggung wayang, tak ada tokoh yang mutlak jahat atau benar; yang ada adalah pertarungan kesadaran, perebutan makna, dan tegangan antara dharma dan nafsu.
Ironisnya, ketika logika simbolik ini seharusnya memberi inspirasi bagi cara berpikir bangsa, kebijakan kebudayaan justru kerap menjauh dari ruhnya. Politik kebudayaan kita masih sering berhenti pada tataran seremonial. Ia memuliakan warisan, tapi tidak memelihara kehidupan simboliknya.
Wayang diangkat sebagai ikon nasional, namun para dalang dan komunitasnya hidup di tepi subsistensi. Negara memamerkan “identitas budaya” dalam upacara dan festival, tapi lupa bahwa kebudayaan tak hidup dari seremoni, melainkan dari ekosistem makna yang tumbuh sehari-hari di masyarakat.
Kita sering menyebut wayang sebagai “warisan dunia”, tapi warisan itu kini bergeser menjadi artefak. Ia dihidupkan kembali hanya ketika dibutuhkan, seperti pada saat peringatan, kampanye, atau diplomasi budaya. Sementara itu, generasi muda dibanjiri logika citra dan kecepatan yang menyingkirkan kedalaman simbolik. Anak-anak tumbuh dengan gestur digital yang instan, bukan dengan refleksi naratif yang mendidik batin.
Maka, ketika Festival Dalang Anak Nasional digelar, pertanyaannya bukan sekadar bagaimana melestarikan wayang, tapi bagaimana menghadirkan kembali kemampuan tafsir dan kesadaran moral sebagai esensi nilai yang terkandung di dalamnya?
Jean Baudrillard pernah menulis bahwa di era simulakra, representasi menggantikan realitas. Kita hidup di dunia bayangan yang kehilangan tubuh. Ironisnya, wayang—yang secara literal memang bayangan—justru menawarkan cara membaca ulang realitas itu.
Di tangan seorang dalang (anak), bayangan menjadi ruang untuk menafsirkan dunia. Bukan untuk menipu, tapi untuk memahami. Ia belajar bahwa di balik setiap sosok heroik ada keraguan. Di balik perang ada hasrat dan keserakahan. Pendidikan macam ini, yang mengajarkan ambiguitas dan refleksi, justru lenyap dalam sistem pendidikan formal yang kian teknokratik.
Festival ini seharusnya bukan hanya ruang regenerasi dalang, melainkan juga simbol perlawanan terhadap penyederhanaan makna dalam budaya digital. Anak-anak yang memainkan wayang sebenarnya sedang mengajarkan ulang kepada kita bahwa imajinasi tak bisa digantikan oleh algoritma.
Mereka melawan logika visual yang datar dengan dunia simbol yang berlapis. Di tengah banjir konten yang instan dan dangkal, kehadiran mereka adalah kritik yang halus tapi telak – bahwa manusia tidak cukup hanya menjadi konsumen gambar, melainkan harus menjadi pencipta makna.
Politik Kebudayaan
Sayangnya, politik kebudayaan belum sampai ke tingkat kesadaran seperti itu. Panggung wayang anak mungkin dikunjungi pejabat, diberi sambutan, dan difoto media, tapi begitu lampu padam, kebijakan kembali berpihak pada industri dan proyek mercusuar. Bukan pada ruang-ruang kecil yang menumbuhkan daya tafsir dan kebijaksanaan lokal.
Padahal, seperti diingatkan filsuf kebudayaan Franz Magnis-Suseno, moralitas politik hanya mungkin hidup jika berakar pada “kebijaksanaan lokal yang meneguhkan kemanusiaan.” Wayang adalah salah satu bentuknya: ia menyampaikan kebenaran tanpa dogma, mengajarkan etika melalui dialog dan tawa.
Dalam konteks bangsa majemuk, fungsi wayang jauh melampaui ritual tradisi. Ia adalah model berpikir tentang kebhinekaan. Tokoh-tokohnya berasal dari lintas dunia, narasinya memadukan India, Jawa, Islam, hingga modernitas.
Dunia wayang adalah dunia intertekstual, seperti Indonesia itu sendiri, yang berlapis, penuh pertemuan dan pergeseran sehingga dengannya penuh dinamika. Maka ketika anak-anak memainkan wayang, mereka sebenarnya sedang memerankan identitas bangsa – yang terbentuk dari dialog antartradisi, bukan dari pemurnian tunggal.
Pertanyaan besarnya adalah: apakah negara melihat potensi ini sebagai energi strategis untuk memperkuat kebangsaan, atau sekadar nostalgia budaya? Jika politik kebudayaan terus berorientasi pada citra, maka wayang hanya akan hidup sebagai “maskot pluralisme”. Tapi bila ia ditempatkan sebagai ruang produksi makna dan refleksi, maka ia bisa menjadi fondasi baru bagi pendidikan karakter, politik etik, dan kreativitas nasional.
Dalam kerangka ini, pemajuan kebudayaan seharusnya dibaca sebagai politik pengetahuan, bukan sekadar pelestarian bentuk. Menghidupkan wayang berarti menghidupkan cara berpikir simbolik yang peka terhadap perbedaan dan paradoks. Ia menumbuhkan kemampuan menafsir, bukan sekadar menghafal; ia mengajarkan empati, bukan hanya teknik presentasi.
Seperti diingatkan filsuf Paul Ricoeur dalam The Symbolism of Evil (1969), simbol selalu “memberi untuk dipikirkan.” Wayang mengajarkan bahwa makna tak pernah tunggal. Selalu ada ruang bagi tafsir dan negosiasi. Inilah yang dibutuhkan dalam masyarakat digital yang terpolarisasi oleh kebenaran instan dan algoritma kebencian. Dengannya, wayang bukan sekadar artefak budaya. Ia adalah model epistemologi, bagaimana memahami dunia melalui perenungan, bukan hanya reaksi.
Anak-anak dalang hari ini adalah penjaga pengetahuan semacam itu. Mereka tumbuh di antara dua dunia: dunia bayangan yang sarat makna dan dunia digital yang serba cepat. Tugas kita bukan memilih salah satu, tapi menumbuhkan jembatan di antaranya. Jika politik kebudayaan mampu membaca potensi ini, maka festival semacam ini bukan sekadar ajang pelestarian, melainkan laboratorium masa depan kebudayaan bangsa.
Mungkin inilah paradoks yang justru menyelamatkan. Di tengah dunia yang kehilangan kedalaman, anak-anak dengan boneka kulit dan layar kelir justru mengajarkan ulang makna refleksi, kesabaran, dan pengetahuan simbolik. Mereka mengingatkan bahwa bayangan, sejauh dipahami dan diolah, bisa menjadi cahaya.
Dan mungkin, di tengah hiruk-pikuk digital dan politik pencitraan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan bangsa ini adalah kemampuan untuk kembali menafsir. Seperti dalang membaca dunia: dengan hati, bukan hanya sorotan layar.
—-
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, penerima fellowship Governance & Management of Culture di Daegu Catholic University Korea Selatan.