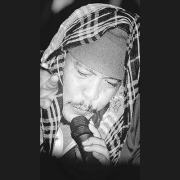Topografi Kesadaran: Membaca Politik Keheningan di Blora
Oleh: W. Sanavero*
Blora tidak hanya dapat dibaca sebagai entitas administratif di timur Jawa Tengah, tetapi sebagai medan makna — sebuah teks terbuka yang menyimpan lapisan sosial, politik, dan spiritualitas yang terjalin di dalam ruang geografisnya. Jika lambang Blora kita perlakukan sebagai representasi semiotik dari identitas ruang, maka ia bukan semata perwujudan estetika heraldik, melainkan artikulasi kesadaran kolektif: tentang tanah yang keras sekaligus subur, tentang manusia yang hidup di antara kelangkaan dan kelimpahan.
Secara topografis, Blora terbelah secara alami menjadi dua wajah: utara dan selatan. Blora Utara hidup di atas tanah kapur yang kering, di mana minyak bumi dan industri menguasai lanskap sosial. Di wilayah ini, logika yang tumbuh adalah logika rasional dan produktivistik: efisiensi, eksploitasi sumber daya, dan modernisasi ekonomi menjadi ide dominan. Sementara itu, Blora Selatan yang dipenuhi hutan jati, sawah, dan dataran tinggi menumbuhkan logika ekologis dan spiritual: kesabaran, gotong royong, dan relasi harmoni dengan alam menjadi orientasi hidup yang lebih kuat daripada rasionalitas ekonomi.
Dua wajah ini tidak berlawanan, tetapi berdialog. Ia seperti kutub yin dan yang dalam filsafat Timur—saling menegasikan sekaligus melengkapi. Utara adalah cahaya rasionalitas, selatan adalah bara spiritualitas. Ketegangan dan keseimbangan di antara keduanya menciptakan ekologi sosial yang unik: masyarakat yang keras tapi halus, modern tapi tetap menyimpan tradisi. Blora berdiri sebagai ruang liminal, di mana modernitas dan kesunyian tradisi hidup dalam satu tubuh.
Namun, keseimbangan itu tak selalu bebas dari politik kuasa. Secara historis, Blora merupakan wilayah periferal dari kerajaan besar Jawa: di masa Mataram, wilayah ini menjadi frontier, penjaga batas kekuasaan yang diisi dengan fungsi-fungsi penyangga. Ketika kolonialisme datang, peran itu tidak berubah—Blora kembali ditempatkan sebagai wilayah penghasil sumber daya: kayu jati, minyak bumi, dan tenaga kerja murah. Dalam kerangka ekonomi politik, Blora adalah contoh klasik dari extractive periphery: wilayah kaya sumber daya, tetapi kemakmurannya ditarik ke pusat.
Kondisi ini terus berlangsung hingga hari ini. Dalam narasi pembangunan nasional, Blora seolah disimpan di ruang abu-abu, tidak sepenuhnya maju, tapi juga tidak cukup tertinggal untuk diprioritaskan. Kota ini tampak sengaja dibiarkan “sunyi”, seperti underdeveloped city yang fungsinya adalah menyediakan legitimasi bagi keberlanjutan eksploitasi energi. Di sini muncul hipotesa yang lebih politis: bahwa kekuasaan dan modal justru menemukan stabilitasnya dalam keterdiamannya. Ketika masyarakat sibuk bertahan hidup di antara harga kayu dan tanah tandus, maka kekuasaan dapat bekerja tanpa gangguan suara.
Paradoks inilah yang menjadikan Blora menarik sebagai teks sosial-politik. Ia bukan sekadar contoh ketertinggalan, melainkan refleksi tentang bagaimana kekuasaan beroperasi di balik narasi pembangunan. Dalam terminologi Michel Foucault, Blora dapat dilihat “ruang kuasa yang tersembunyi”: wilayah yang dikontrol bukan melalui represi terang-terangan, tetapi melalui reproduksi keterbatasan. Jalan rusak, infrastruktur lambat, dan fasilitas publik yang minim bukan semata akibat ketidakefisienan birokrasi, tetapi bagian dari ekonomi politik yang menjaga agar Blora tetap menjadi ladang, bukan kota.
Namun, dari sudut pandang spiritual dan kultural, keterbatasan ini justru melahirkan bentuk kesadaran lain—kesadaran ekologis dan reflektif. Masyarakat Blora hidup dengan nalar sabar: sebuah nalar yang tidak inferior, tetapi merupakan hasil internalisasi atas ruang yang keras. Di selatan, hutan jati menanamkan filosofi ketahanan; di utara, tanah kapur mengajarkan kejujuran terhadap kekeringan. Dari sini lahir manusia yang terbiasa menunggu, mengelola waktu seperti mengelola harapan.
Lambang Blora, bila dibaca dalam konteks ini, menjadi simbol dialektika antara realitas dan cita-cita. Ia mengandung bayangan keseimbangan antara pusat dan pinggiran, antara manusia dan tanah. Bahwa kejayaan bukan hasil dari dominasi, tetapi dari kemampuan menjaga harmoni. Cacana Jaya Kerta Bhumi—kejayaan berasal dari bumi yang tertata—dapat dibaca bukan sebagai semboyan administratif, tetapi sebagai etika politik ekologis: pembangunan sejati harus lahir dari penataan yang adil atas sumber daya dan kesadaran manusia.
Blora dan Politik Keheningan
Secara politis, Blora adalah “wilayah penyangga” yang tidak diberi otonomi penuh atas kekayaannya sendiri. Industri migas di Cepu, misalnya, lebih banyak dikelola oleh jaringan nasional dan internasional daripada oleh masyarakat lokal. Akibatnya, yang tersisa di tingkat daerah hanyalah sisa pendapatan dan kerusakan lingkungan. Dalam logika ekonomi ekstraktif, hal ini adalah konsekuensi yang “normal.” Namun secara moral dan sosial, ini adalah bentuk pengingkaran terhadap janji pembangunan.
Pertanyaannya kemudian: apakah kondisi ini diciptakan secara sengaja? Apakah Blora dijaga dalam status “underdeveloped” sebagai bagian dari desain politik energi nasional? Jika ditelaah secara struktural, hipotesis ini bukan tanpa dasar. Pemerintah pusat memiliki kepentingan menjaga stabilitas pasokan energi, sementara para pemodal memiliki kepentingan mempertahankan ruang eksploitasi yang minim resistensi sosial. Maka, membiarkan Blora tetap “diam” berarti menjaga legitimasi ekonomi politik yang sudah mapan.
Dalam kerangka ini, keheningan Blora bukanlah akibat alamiah dari ketertinggalan, melainkan produk politik dari penguasaan sumber daya. Kota ini seperti tubuh yang diberi anestesi: hidup, tapi tidak berdaya. Ia berfungsi, tapi tidak bersuara. Dan di sanalah tragedi itu berlangsung secara halus—kekuasaan berjalan tanpa perlawanan karena masyarakatnya sudah terlalu terbiasa mengelola kesunyian.
Namun, justru di ruang sunyi itulah muncul kemungkinan lain. Keheningan di Blora juga dapat dibaca sebagai potensi—bukan hanya politik, tapi eksistensial. Di tengah dunia yang semakin bising oleh wacana pembangunan, Blora menyimpan ruang refleksi tentang bagaimana sebuah daerah dapat mendefinisikan kemajuannya sendiri. Jika pembangunan modern diukur dari pertumbuhan, maka Blora mengajarkan pertahanan: tentang bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam tanpa kehilangan martabatnya.
Keheningan di sini bertransformasi menjadi kesadaran: bahwa tidak semua kemajuan harus berisik, dan tidak semua keterlambatan berarti kegelapan. Blora, dalam diamnya, sedang merumuskan cara lain untuk hadir di dunia. Sebuah cara yang tidak didikte oleh logika modal, tetapi oleh ritme alam dan sejarah lokalnya sendiri. Mungkin inilah politik sejati dari keheningan: kemampuan untuk menunda bukan karena lemah, tetapi karena tahu kapan harus tumbuh. Seperti akar jati yang bergerak tanpa suara, Blora membangun dirinya dari bawah, perlahan, menembus batu waktu dan sistem. Ia mungkin tidak tampak dalam statistik pembangunan, tetapi tumbuh dalam kesadaran kultural: kesadaran bahwa kekuasaan yang sejati bukan milik mereka yang berkuasa atas tanah, melainkan mereka yang mampu menjaga napasnya tetap hidup di dalam tanah itu sendiri.
Maka Blora, dalam segala kesunyiannya, adalah ruang perenungan tentang makna kemajuan itu sendiri. Ia menantang paradigma pembangunan yang serba bising dan mengajukan alternatif: kemajuan yang berakar pada keseimbangan, bukan kecepatan. Dalam keheningan hutan jati dan kilau pipa minyak yang berdampingan, Blora memperlihatkan wajah ganda Indonesia—sebuah negara yang kaya tapi tidak merdeka sepenuhnya dari logika kuasa modal.
Pada akhirnya, membaca Blora adalah membaca tubuh Indonesia dalam bentuk kecil: kontradiksi antara kekayaan alam dan kemiskinan struktural, antara spiritualitas lokal dan kekuasaan global, antara tanah yang subur dan masyarakat yang haus. Namun, justru dari kontradiksi itu lahir ruang refleksi: bahwa mungkin, kekuatan sejati Blora bukan pada minyak atau kayu jatinya, tetapi pada kemampuan warganya untuk bertahan, merenung, dan terus hidup di tengah sistem yang berusaha membuat mereka diam.
Keheningan itu juga tampak dalam cara masyarakat menginternalisasi keterbatasan. Ia bukan pasrah dalam arti negatif, melainkan bentuk kearifan ekologis: semacam silent resistance yang tidak frontal, tapi konsisten. Dalam setiap hutan jati dan sumur minyak, ada kesadaran bahwa tanah ini menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada yang diizinkan oleh sistem. Di sinilah politik dan spiritualitas bertemu. Keheningan menjadi bentuk doa, tetapi juga bentuk perlawanan.
***
Blora, 13 November 2025
—-
*W. Sanavero, penulis dan peneliti kebudayaan, menjembatani sastra, kearifan lokal, dan tata kelola. Ia meneliti diplomasi budaya bersama Keraton Yogyakarta dan JNU India. Penerima ASEAN Scholarship jurusan Magister Sastra Dunia di Nalanda University ini menulis dengan pendekatan etnografi, mengeksplorasi hubungan sastra, kekuasaan, dan identitas dalam karya dan risetnya.