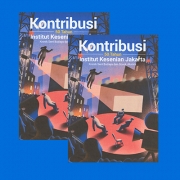Tarekat Syattariyah di Bumi Nusantara
Menyambut Borobudur Writers and Cultural Festival 2025
Oleh: Gus Nas Jogja*
Tarekat Syattariyah di bumi Nusantara bukan sekadar rantai transmisi ajaran sufi; ia adalah sebuah “arkeologi spiritual” yang mengakar, sebuah matarantai keilmuan yang membentuk fondasi kosmologi keagamaan di Asia Tenggara. Ia tiba bukan sebagai ajaran asing yang kaku, melainkan sebagai senandung filosofis yang mampu berdialog dengan kearifan lokal, menawarkan jawaban atas pertanyaan eksistensial mengenai asal dan tujuan wujud. Dari Barus yang mistis hingga Keraton Mataram Islam yang agung, Syattariyah telah menorehkan jejaknya sebagai tarekat yang fleksibel, mendalam, dan transformatif.
Esai ini akan menggali historiografi Tarekat Syattariyah, menelusuri silsilah keilmuannya, dan mendiskusikan filsafat eksistensialnya, terutama melalui konsep kunci Martabat Tujuh, yang menjadi struktur batin peradaban Nusantara. Puncaknya, kita akan menelaah bagaimana struktur spiritual ini diaktivasikan menjadi panggilan jihad yang menggerakkan ribuan pengikutnya, –yang paling dramatis tercermin dalam Perang Diponegoro (1825–1830),– menjadikannya Tarekat Pejuang yang menentang cengkeraman kolonialisme.
Historiografi dan Rihlah Agung Sanad
Akar Syattariyah terentang jauh melintasi benua, dari alirannya di Persia yang dikenal sebagai ‘Ishqiyyah atau Tayfuriyyah, hingga India yang melahirkan nama Shattar –kecepatan atau kilat– [1]. Tarekat ini tiba di Nusantara pada puncak rihlah atau perjalanan intelektual ulama-ulama Melayu yang kembali dari Haramain –Mekkah dan Madinah– pada abad ke-17. Namun, penyemaian dan konsolidasinya di Nusantara secara luas tak terpisahkan dari satu pilar sentral: Syekh Abdul Rauf Singkil (w. 1693 M), atau yang dikenal dengan gelar yang penuh penghormatan, Teungku Syiah Kuala.
Syekh Singkil menghabiskan hampir dua dekade (sekitar 1642–1661 M) menimba ilmu di pusat-pusat keilmuan Islam global [2]. Selama rihlah ini, ia secara khusus menerima sanad Syattariyah dari guru utamanya, Syekh Ahmad al-Qushashi (w. 1661 M) di Madinah. Al-Qushashi adalah mursyid yang menjembatani Syattariyah dari India ke Dunia Melayu. Melalui Syekh Singkil, rantai spiritual (silsilah) ini tertanam kokoh, menjadi sebuah sumbu batin yang legal dan otentik di Aceh, yang saat itu menjadi pusat kekuasaan dan keulamaan Kesultanan Islam [3].
Penting untuk dicatat bahwa Syattariyah datang setelah gelombang ajaran wujudiyyah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani, yang sempat mengalami masa kontroversi dan penindasan oleh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Singkil, dengan posisinya sebagai Mufti Besar Kesultanan Aceh, berhasil mengoreksi dan merekonsiliasi pemahaman wujudiyyah dengan batas-batas syariat melalui penyebaran Syattariyah yang lebih berhati-hati dan terstruktur. Ini adalah tugas filosofis Syattariyah di Nusantara: merangkul esensi hakikat sambil menjaga benteng syariat.
Filsafat Eksistensial: Kosmologi Martabat Tujuh
Jantung filosofis Tarekat Syattariyah di Nusantara terletak pada doktrin Martabat Tujuh –seven grades of existence–, yang diuraikan secara rinci oleh Syekh Singkil dalam karyanya yang monumental, Daqā’iq al-Hurūf (Kelemahlembutan Huruf) dan ‘Umdah al-Muhtajin (Sandaran Orang-Orang yang Membutuhkan) [4]. Martabat Tujuh adalah kosmologi eksistensial yang menjelaskan proses tajalli –penampakan atau emanasi– dari Wujud Mutlak (Tuhan) hingga terbentuknya alam semesta, dan sebaliknya, proses ruju’ (kembali) ruh manusia kepada Asal.
Martabat Tujuh bukanlah sekadar taksonomi, melainkan sebuah peta batin yang memandu para salik –penempuh jalan spiritual. Tujuh tingkatan tersebut, yang dibagi menjadi tiga kelompok utama, memiliki makna filosofis yang mendalam:
Aḥadiyyah atau Tingkat wujud mutlak yang tersembunyi {Lā Ta’ayyun. Titik keesaan yang belum terbagi.
Waḥdah atau Tingkat penampakan Sifat-Sifat secara potensial {Ta’ayyun Awwal}. Kesadaran Tuhan akan Diri-Nya sendiri.
Wāḥidiyyah atau Tingkat manifestasi Asma’ (Nama-Nama) Ilahi {Ta’ayyun Thānī}. Tempat prototipe segala sesuatu (A’yan Tsabitah) eksis dalam Ilmu-Nya.
’Ālam al-Arwāḥ atau Alam Ruh, manifestasi pertama wujud murni yang sederhana.
’Ālam al-Mitsāl atau Alam Contoh semacam Imajinasi, perantara antara ruh dan jasad.
’Ālam al-Ajsām atau Alam Jasad, dunia material, tempat ruh mengalami keterbatasan fisik.
’Ālam al-Insān al-Kāmil –Manusia Sempurna sebagai puncak penciptaan. Manusia yang berhasil merealisasikan kembali seluruh tujuh martabat dalam dirinya.
Filsafat ini menekankan bahwa tujuan manusia adalah mencapai Martabat Ketujuh, yaitu menyadari bahwa ia adalah mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos [5]. Konsep ini menjadi landasan etis dan spiritual: jika manusia adalah pantulan sempurna dari Tuhan, maka eksistensi ini memiliki nilai dan tanggung jawab yang suci. Mempertahankan kesucian eksistensi, baik pribadi maupun kolektif, menjadi tugas batin yang sakral, termasuk tanggung jawab untuk melawan ketidakadilan.
Jika Syekh Abdul Rauf Singkil adalah pintu masuk Syattariyah ke Nusantara, maka para khalifah dan mursyid lokalnya adalah akar yang menjalar ke seluruh kepulauan, mengawinkan ajaran tersebut dengan tradisi lokal di Minangkabau, Jawa, dan Palembang.
Syekh Burhanuddin Ulakan: Konsolidator di Ranah Minang
Salah satu murid Syekh Singkil yang paling berpengaruh adalah Syekh Burhanuddin Ulakan (w. 1692 M). Setelah menyelesaikan studi di Aceh, Syekh Burhanuddin kembali ke tanah kelahirannya, Minangkabau, dan menginstitusionalkan Syattariyah melalui sistem Surau sebagai pusat spiritual di Ulakan, Pariaman. Surau Ulakan menjadi universitas spiritual yang mencetak ribuan khalifah (guru pengganti) yang menyebar ke seluruh pedalaman [6].
Di Minangkabau, Syattariyah Syekh Burhanuddin menjadi jembatan teologis yang kuat antara Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah. Ajaran Martabat Tujuh diserap sebagai pemahaman yang mendalam tentang asal-usul, memberikan legitimasi spiritual pada sistem niniak mamak (pemimpin adat).
Di Jawa, sanad Syattariyah mencapai kedalaman struktural dan konflik filosofis melalui figur kontroversial Syekh Mutamakkin (w. Abad ke-18) dari Kajen, Pati [7]. Kasus Mutamakkin, yang terekam dalam Serat Cebolek, adalah drama filsafat antara ulama fiqih dan ulama hakikat. Kemenangannya melegitimasi Syattariyah sebagai tarekat yang aman dan mendalam di lingkungan pesantren Jawa, membuka jalan bagi integrasinya ke dalam struktur sosial dan politik Mataram.
Syattariyah, Kyai Istad, dan Panggilan Jihad: Epistemologi Perang Diponegoro
Ketika kolonialisme Belanda (dengan segala intrik politik dan eksploitasinya) mencapai puncaknya di Jawa pada awal abad ke-19, struktur Syattariyah yang telah mengakar di kalangan kiai dan santri di pedalaman menjadi titik api perlawanan. Jaringan ini bukan hanya tempat zikir, tetapi komando batin yang siap diaktifkan.
Kyai Istad Wonokromo: Mursyid di Balik Sumpah
Di lingkungan Kesultanan Kraton Yogyakarta, tarekat Syattariyah memiliki sanad kuat yang berpusat di beberapa pesantren kuno yang berada di kawasan Pathok Negoro. Salah satu figur paling krusial dalam kaitan spiritual Pangeran Diponegoro adalah Kyai Istad, seorang Mursyid Syattariyah terkemuka dari Wonokromo [8].
Kyai Istad tidak hanya seorang guru agama formal; ia adalah pembimbing spiritual Diponegoro, yang mengajarkan disiplin Tarekat dan filsafat wujud atau Martabat Tujuh yang mendalam. Kyai Istad, bersama dengan kiai lain seperti Kyai Mojo, menjadi penjamin otentisitas spiritual bagi Pangeran.
Melalui ajaran Syattariyah, Diponegoro memandang dirinya bukan hanya sebagai pangeran yang kehilangan hak, tetapi sebagai alat Ilahi, Insan Kamil yang diutus untuk membersihkan bumi Jawa dari fāsad –kerusakan dan kezaliman– yang diakibatkan oleh Belanda dan elite keraton yang korup. Kyai Istad dan jaringan Syattariyah-nya memberikan fatwa spiritual dan mandat profetik ini, mengubah pemberontakan politik menjadi Perang Suci atau jihad.
Aktivasi Struktural dan Disiplin Perang
Ajaran Tarekat Syattariyah secara filosofis mempersiapkan pengikutnya untuk Jihad Akbar –perjuangan melawan hawa nafsu– melalui zikir yang intens dan khalwat. Proses ini menanamkan integritas spiritual yang mutlak. Ketika Diponegoro, yang disokong Mursyid seperti Kyai Istad, mengeluarkan seruan jihad pada tahun 1825, Jihad Akbar secara otomatis memicu Jihad Ashghar –perang fisik– [9].
Jaringan Syattariyah yang terstruktur—dari Kyai Istad ke khalifah di desa-desa—memberikan Diponegoro struktur komando alternatif yang efisien, loyal, dan tidak terdeteksi Belanda. Setiap kiai adalah mursyid dan komandan perang bagi ribuan santri dan petani.
Pengikut Syattariyah, yang terbiasa dengan disiplin Zikir Nafi Itsbat (Lā Ilāha Illallāh) dan wird harian, dengan mudah mengadopsi disiplin militer. Perang ini adalah Epistemologi Spiritual yang diterjemahkan menjadi aksi perlawanan kolektif, di mana Martabat Tujuh menjadi blueprint moral perlawanan.
Warisan Syattariyah tidak hanya terukir pada batu nisan atau tersimpan di keraton, tetapi hidup dalam literatur sastrawi dan kitab kuning yang tersebar luas, memastikan kesinambungan sanad.
Syekh Singkil adalah seorang sastrawan agung. Karyanya, terutama terjemahan dan tafsir al-Qur’an berjudul Tarjuman al-Mustafid –Penerjemah Pemberi Manfaat, merupakan kitab tafsir lengkap pertama dalam bahasa Melayu. Proyek sastra ini secara strategis memastikan bahwa ajaran Islam, termasuk nuansa sufistik Martabat Tujuh, dapat diakses oleh masyarakat luas. Sastra Syattariyah sering menggunakan estetika spiritual yang mengalir, di mana diksi-diksi tentang air, cahaya, dan cermin digunakan untuk menjelaskan kesatuan wujud.
Tradisi Kitab Kuning dan Kesinambungan Sanad. Di pesantren-pesantren, manuskrip Syattariyah menjadi materi utama. Kitab ‘Umdah al-Muhtajin menjadi rujukan wajib, memastikan bahwa silsilah keilmuan –rantai guru– dan silsilah spiritual –rantai wirid– tetap terjaga [10]. Syattariyah mempromosikan pemahaman bahwa ilmu agama tidak terbagi; syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat adalah empat tingkat yang harus ditempuh secara berurutan. Filsafat ini menawarkan paradigma holistik dalam pendidikan Islam, mencetak ulama yang fasih dalam fikih sekaligus mendalam dalam tasawuf.
Warisan Wujud yang Abadi
Tarekat Syattariyah di Nusantara adalah monumen filsafat eksistensial yang berbasis pada ajaran Martabat Tujuh. Ia berhasil menancapkan tiang spiritual yang kokoh, mengintegrasikan kosmologi Islam universal dengan struktur budaya lokal. Melalui rihlah agung Syekh Abdul Rauf Singkil, jaringan mursyid lokal seperti Syekh Burhanuddin, Syekh Mutamakkin, dan Kyai Istad Wonokromo, Tarekat ini menjadi matarantai spiritual yang abadi.
Figur Kyai Istad adalah bukti nyata bahwa Syattariyah tidak hanya beroperasi dalam lingkup batin (khalwat), tetapi mampu menjadi kekuatan struktural yang menggerakkan sejarah. Perang Diponegoro adalah puncak manifestasi filosofi ini: sebuah gerakan massal yang didorong oleh kesadaran Insan Kamil dan tanggung jawab spiritual untuk menegakkan keadilan. Warisan Syattariyah adalah sebuah kesadaran kosmik yang abadi, memberikan kedalaman spiritual, disiplin moral, dan semangat perlawanan yang terus bersemi hingga hari ini.
Wallahu A’lam.
***
Catatan Kaki
[1] Sumber historis menunjukkan bahwa Syattariyah dikembangkan oleh Syekh Abdullah as-Shattar di India pada abad ke-15.
[2] Syekh Singkil belajar di berbagai pusat keilmuan seperti Doha, Yaman, dan Mekkah, sebelum menetap lama di Madinah di bawah Syekh Ahmad al-Qushashi.
[3] Azyumardi Azra, dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, menempatkan Syekh Singkil sebagai salah satu ‘Ulama Kunci’ dalam transmisi tarekat.
[4] Syekh Abdul Rauf Singkil, Daqā’iq al-Hurūf, merupakan salah satu risalah terpenting yang membahas Martabat Tujuh.
[5] Pencerahan ini, atau mencapai martabat Insan Kāmil, adalah tujuan puncak yang secara filosofis membawa manusia pada kesempurnaan moral dan spiritual, yang menjadi landasan untuk aksi di dunia nyata.
[6] Dobbin, Christine. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784–1847. Minangkabau memiliki struktur Surau yang sangat mendukung penyebaran Syattariyah oleh Syekh Burhanuddin.
[7] Drewes, G.W.J. dan Rinkes, D.A. adalah peneliti awal yang banyak meneliti manuskrip Syattariyah. Kasus Syekh Mutamakkin diuraikan rinci dalam Serat Cebolek sebagai konflik antara syariat dan hakikat.
[8] Data historis (termasuk Babad Diponegoro dan sumber-sumber Jawa lainnya) mencatat Kyai Istad dari Wonokromo sebagai salah satu tokoh spiritual utama yang memberikan restu dan bimbingan tasawuf kepada Pangeran Diponegoro, menunjukkan peran Syattariyah dalam mobilisasi perang.
[9] Konsep ini sejalan dengan ajaran sufi klasik: Jihad Akbar adalah prasyarat untuk Jihad Ashghar. Peperangan melawan ketidakadilan eksternal (penjajah) adalah tugas bagi jiwa yang telah dimurnikan secara internal.
[10] Bruinessen, Martin van. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat. Konsistensi ajaran Syattariyah di Jawa dibuktikan melalui manuskrip yang seragam dan metode pengajaran yang turun-temurun.
Daftar Rujukan Ilmiah Pilihan
Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004.
Bruinessen, Martin van. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Bandung: Mizan, 1995.
Dobbin, Christine. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784–1847. London: Curzon Press, 1983.
Fathurahman, Oman. Manuskrip dan Keilmuan Islam di Nusantara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Ricklefs, M. C. A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Stanford: Stanford University Press, 2008. (Mengulas latar belakang sosial dan agama di Jawa pada masa Diponegoro).
Singkel, Syekh Abdul Rauf. ‘Umdah al-Muhtajin ila Suluk Masalik al-Mufridin. (Manuskrip sebagai sumber primer).
—-
*Gus Nas Jogja, budayawan.