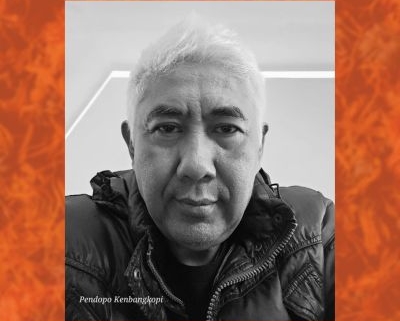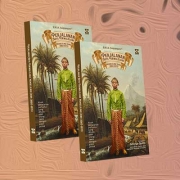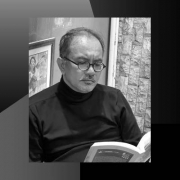Takengon Kota Seribu Kafe Kopi
Oleh: Pietra Widiadi*
Di Banyuwangi, ada istilah seribu cangkir yg disandingi seribu Gandrung. Jombang dijuluki kota santri dan Lamongan kota seribu pesantren. Saya ingin mengenalkan Takengon kota seribu kafe kopi. Julukan yg mengoda dan bisa menggelora, bukan karena gimik pasar wisata tp memang begitu adanya.
Mari kita telusuri daerah-daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2023 adalah Sumatera Selatan, diikuti oleh Lampung dan Sumatera Utara. Sumatera Selatan memproduksi sekitar 198 ribu ton kopi, sementara Lampung dan Sumatera Utara masing-masing sekitar 108,1 ribu ton dan 87,9 ribu ton, menjadikannya provinsi-provinsi kunci dalam produksi kopi nasional, terutama untuk jenis kopi Robusta. Mereka ini lumbung kopi, komoditi perkebunan-pertanian unggulan keren. Di daftar ini tidak ada Nangro Aceh Darusalam, meski dataran tinggi Gayo, ada di sana.
Lebih jauh, kita coba telusuri juga Kabupaten penghasil kopi terbesar di Indonesia, yang bergantung pada kategori yang dinilai. Secara umum, Lampung dan Sumatera Selatan (terutama OKU Selatan) adalah provinsi penghasil kopi terbesar, dengan fokus pada Robusta dan Arabika secara luas. Sementara daerah Aceh Tengah (Dataran Tinggi Gayo) dan Jawa Timur (seperti Malang, Jember, Bondowoso) juga dikenal sebagai penghasil utama.
Dari gambaran di atas, selain Aceh Tengah di dataran tinggi Gayo ada Bener Meriah dan Gayo Lues. 3 kabupaten dg prestasi tinggi sebagai produsen kopi. Secara khusus, Takengon, saya menyebutnya sebagai kota kecil, small is beautiful sebagai pusat industri kopi. Menyitir mas Gibran, Wapres yang senang menyampaikan terminologi hilirisasi. Dia, harusnya mengunjungi Takengon, sebagai bagian dari hilirisasi produksi kopi.
Takengon, kopi dan kafe
Tidak ada catatan yg pasti berapa jumlah kafe kopi di Malang, di Jakarta atau di Bandung atau Gresik, meski mustinya kalau negara berpihak pada produksi dalam negeri punya catatan. Sama juga di Takengon, tidak ada catatan pasti soal jumlah. Jangankan yang besar, apalagi yang kecil, pasti gak akan nampak.
Luas Takengon, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, adalah 4.521,70 km², sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022. Wilayah ini mencakup berbagai kecamatan di dataran tinggi Gayo dan menjadi lokasi Danau Lut Tawar, yang terkenal dengan airnya yang tawar. Kota menara air dan pusat menikmati minuman dari kopi.
Ibu kota dari Kabupaten Aceh Tengah ini, memiliki kekhasan yg tidak sama dg kota-kota kabupaten di Indonesia. Terutama dalam pembangunan bertumpu pada pertanian-perkebunan. Boleh saja OKU Selatan atau Jember-Bondowoso, Jatim punya produksi biji kopi, atau Malang. Tapi soal selera minum kopi murni, Takengon sepertinya adalah puncak.
Misalnya di kafe Buar, atau Rumah Nenek di mana kamu muda berkreasi menciptakan minuman dari kopi, dan tidak meninggalkan kopi yang diseduh dari metode V60. Atau ngopi Black di mobil kopi di bang Andre yang asli Gayo, di perempatan batas kota ke Benet Meriah – Takengon, kopinya nendang.
Tidak kalah nendangnya dengan coldbrew racikan Kopi Seladang, bang Gembel yang terletak di jalan antar Takengon – Bener Miriah. Ada juga kopi alay-alay kesukaan GZ, manis dan berasa buahnya, fruitynya. Atau bisa di Nusantara dan SMEA yang menyajikan kopi saring dengan layanan pasar. Nikmat pula kopi tubruk di hotel Parkside, atau di tetangganya cafe Pastho. Atau ke arah danau ada Harsaya atau di Teluk Mandale.
Hampir setiap penggal jalan, di jalanan Takengon, ada kafe kopi. Di warung makan khas Aceh, Padang atau Gayo, sajian kopi tak terpisahkan. Dengan luasan kota yang relatif kecil dan tempat ngopi ada di mana-mana adalah sesuatu banget. Inilah kota seribu kafe Kopi.
Kota industri paripurna
Perkebunan kopi memang sumbernya, sekalipun merambah ke kawasan Taman Nasional Lauser di mana Gajah dan Harimau bermukin sejak dulu kala. Luas Taman Nasional Gunung Leuser 1.094.692 hektar, sebagian besar wilayahnya terletak di Provinsi Aceh dan sebagian di Provinsi Sumatera Utara. Angka ini merujuk pada penetapan di tahun 1997 dan merupakan hasil penggabungan beberapa kawasan suaka margasatwa dan hutan wisata.
Sebuah perpaduan yang eksotik, di mana keindahan alam, kekayaan semesta berpadu jadi satu. Makhluk hidup berkelidan dengan cuaca yang panas dan dingin pada malam hari. Menjaga ekosistim kehidupan tidak hanya dalam satu atau dua tahun, tapi bisa satu generasi atau satu masa kehidupan di bumi ini.
Kopi tidak sekedar di tanam tetapi juga diseduh untuk dinikmati. Bukan hanya petani yang disebut pekerja kopi. Dari titik awal yaitu membudidaya kopi termasuk membibit dan menjualnya pada pedagang, untuk diangkut ke kota dan penjuru negeri. Bahkan dipakai bahan minum kopi di negeri Paman Sam dengan merek yang mendunia. Gayo hanya tersemat kecil dalam bungkusnya tapi tak pernah muncul di cangkir atau muk kopi dalam hidangan.
King Gayo, bukan hanya nama yang dikenal di sana. Setiap kafe di pelosok negeri ini mengenalnya. Samapun di sini, di Takengon. Seduhan kopi, tidak meninggalkan bijinya. Menjadi barista dalam gimik dunia kopi, bisa jadi kebanggaan. Meramu dan meracik, mencoba moctail, membuat seduhan kopi nikmat, jadi andalan.
Menikmati V60, dengan saringan yang sempurna secara manual. Dari kopi yang diproses secara alami, natural atau difermentasi dengan pencucian yang hati-hati, adalah rasa dan karsa menuju kenikmatan. Back kopi atau biasa juga dikenal dengan tubruk, masih jadi hidangan bagi kalangan laleki tua yang menghirup kretek sambil ngobrol seru soal politik, apakah mas Gibran akan berkunjung mempromosikan hilirisasi kopi seperti di Kedai Horas.
Tanaman kopi adalah kenyataan dan sekarang dibangun kebanggaan yang menyertainya, yaitu peracik minuman dari kopi. Petani dan pedagang kopi relasinya masih seperti dulu, belum juga beranjak, kadang mutualis dan tak sedikit yang ekploitatif. Harga kopi glondongan, istilah untuk bahasa indah kopi yang disebut dg Cherry, perliter, atau perbambu Rp 22.00 – 30.000 tergantung kualitas. Kalau 1 Ha ladang kopi menghasilkan 3 ton setiap panen tahunan, maka duit diterima sebesar adalah Rp 75.000.000 kotor dg harga Rp 25.000/liter/perbambu.
Sedangkan harga beras saat ini Rp 14.000, dan kebutuhan pokok lainnya beranjak naik. Maka penghasilan pertahun dari kopi, katakan Rp 35.000.000 bersih, tetap saja kebuhan lainnya belum bisa dipenuhi. Ini bisa dilihat bentuk rumah yg cukup sederhana, meski dari batu bata namun umumnya tidak dipelur temboknya. Rumah-rumah dari kayu masih mendominasi, karena hangat pada malam hari di cuaca dingin dan bisa dilihat di mana-mana, bahkan rumah-rumah yg muncul di sepanjang Danau laut Tawar Takengon.
Menelaah prosesing kopi, juga suatu keasyikan. Memetik, mengumpulkan dan kemudian mengupas kulitnya dengan pulper, dan mencuci lalu menjemurnya. Atau kopi yang baru dipetik di cuci bersih, dipisahkan dan disortir untuk diambil yang berkualitas. Menyingkirkan butiran yang mengapung dan kulit kopi di air rimbangan, hal yang selalu dilakukan.
Merendam butiran kopi yang disebut gelondongan itu untuk diproses jadi berasan yang manis dan cantik. Perendaman bisa saja antara 3 – 7 hari. Bahkan ada yang melakukan itu sampai dengan 21 hari dan mencampurnya dengan ragi atau bahan-bahan lainnya supaya menghasilkan butiran yang patut jadi bahan hidangan.
Maka perjalanan dari kebun, sampai dengan meja kafe, bukan proses yang sederhana dan pendek. Kopi yang sudah jadi berasan itu, tidak serta-merta langsung diroasting dan digrinder untuk diseduh. Tetapi perlu ditunggu setidaknya satu tahun, meski ada yang bilang cukup 3 bulan untuk menghilangkan getah dr berasan. Berasan ini, bahasa kopi di di kota disebut green bean.
Inilah perjalanan paripurna, dari butiran kopi menjadi minuman yang dinimati pada pagi atau sore hari, yang berdampingan dengan pisang goreng krispi. Dampingan kopi itu, bisa juga dengan ubi krispi dan tahu krispi, dipertegas dengan sambal kecap atau sambal kecombrang atau sambal terong Belanda.
Maka kalau kita boleh menggambarkan, komoditi kopi di mulai dengan berbudi daya, membibit di kebun kopi, yang secara regular dikelola atau diganti secara bersulam bibit kopi baru. Kopi varietas Ateng atau Timtim akan sehat kalau mendapat peneduh yang sesuai, seperti Petai Cina lama dibandingkan dengan Petai Gung, atau Lamtoro Gung yang rentan jamur upas dan ikut merusak tumbuhan kopi. Selain Petai, peneduh yang umum adalah Alpukat. Alpukat aligator, panenan Jagungjagad di Bener Meriah, bisa mudah ditemukan di pasar Kramatjati, Jakarta atau di gerai buah moderen di kota-kota besar di Indonesia.
Kopi dan peneduh adalah pasangan yang sulit bisa dipisahkan. Maka Durian atau jeruk dan jambu biji, adalah pasangan yang serasi dibandingkan dengan Kemiri atau Mindi atau mahoni di ketinggian yang merupakan penghasil kayu. Rindangnya daun pohon kayu ini bukan sahabat bagi kopi, mereka menutupi kehangatan yg diingin oleh para kopi.
Ada gejala baru bertautnya pasangan ini, saat ini ada varietas kopi yang tidak membutuhkan pasangan peneduhnya. Seperti Liberika dan Excelsa, yang ennggan berteduh. Sebagian besar kopi tetap butuh pelindung, yang terbagus katanya adalah Petai karena rimbun daunya basuh bisa diintip matahari dan mencegah jamur di kelembaban.
Pada kelola perkebunan ini, menghasilkan sebuah paduan konsevasi yang indah. Betapa tidak pohon peneduh, selain melindungi kopi juga akan menjaga pasokan air dari hujan dan melindungi kebun dari erosi. Khusus di Lauser, berkelidan juga gajah yang kadang singgah ke kebun-kebun kopi. Tidak hanya ingin menikmati kopi yang ada bersama pisang yang ditanap oleh para pekebun. Tetapi kehadiran gajah-gajah itu seperi sedang menginspeksi rumah dan halaman mereka, yang dipinjam oleh warga yang menetap di sana.
Sebenarnya tidak ketinggalan dengan Datuk Harimau Sumatra, kadang juga hadir, menengok pekarangan mereka. Perpaduan pelestarian alam yang musti dijaga. Meski saat ini, pembersihan hutan, bahkan bagian dari Taman Nasional diubah menjadi kebun kopi baru yang diselingi dengan cabe yang ditanam secara vertikal dari ketinggian dan kemiringan lebih dari 45°. Atau mulai ditumbuhkannya sawit di bukit-bukit yang mustinya dirawat dan dilindungi.
Maka setelah proses budidaya, kopi dipetik dan dipanen yang dibawa ke gudang besar berikutanya. Di bak-bak atau di kolam-kolam pencucian dan bentang jemuran kopi di penggilingan kopi. Proses di mulai, kenikmatan kopi dimulai dari budidaya menuju area prosesing. Setelah biji kopi, atau berasan atau greenbean, dientas dari jemuran, proses sortir kedua dilakukan untuk memisahkan ukuran yang berbeda, atau biji kopi yang pecah menjadi satu ukuran.
Setelah itu, penyimpanan dalam karung goni dimulai, yang dilapisi dengan kantung kopi untuk menghindarkan kelembaban ketinghian bukit dan gunung di pegunungan Lauser dan Bukit Barisan. Setelah satu tahun, berasan ini mulai masuk pada penggorengan, roasting untuk diproses menjadi bubuk kopi dengan berbagai model cara mengolah dan menyajikan jadi minuman.
Dari perjalanan panjang yang hampir ditempuh selama 2 tahun dalam 1 masa panen sebuah kopi, melibatkan begitu banyak tenaga kerja dan teknologi mempertahankan kopi. Ini seperti dengan lembah Kanyon, di mana light industry berkembang. Di Takengon, rentetan proses produksi dari petani/pekebun di kebun, ibu dan anak muda membersihkan gulma di ladang kopi. Menuju ke para pengolahan kopi, tenaga sortir dan tenaga prosesing, sampai kepenyaji kopi dan para barista. Ini deretan proses sebuah industri yang ada di masyarakat. Mereka tidak butuh hamparan gedung besar sebagai pabrik packing kopi bubuk.
Ini lah paripurna sebuah industri yang membentang panjang yang dikelola oleh masyarakat. Meski pada penggal paling awal, mereka tidak mendapatkan keuntungan yang cukup. Jadi melihat Takengon, terbangun sebuang bangunan budaya yang melegenda. Namun sering dianggap bukan apa-apa, bukan tradisi yang menjadi bagian budaya masyarakat karena di sana tidak ada tarian, tidak ada kreasi yang dipertontonkan di panggung-panggung hiburan.
Ada yang menarik, pada satu kala terjadi sebuah ritual perkawinan kopi, di mana putik dan serbuk bertemu. Matra ditapakkan supaya mereka segera mengandung dan melahirkan kopi yang disenandungkan bahagia, karena sebentar lagi kopi memerah.
Usaha mikro kecil berpadu
Industri besar pemilik modal diujung akhir sebuah kopi menjadi minuman sepertinya adalah ultimate produksi. Pada hal ultimate itu terjadi dalam bagian-bagian proses menjadi minuman kopi. Tidak ada yang paling ultimate. Tetapi karena sering tidak ada keberpihakan pada budidaya kopi, karena dianggap orang desa, orang udik maka tidak perlu mendapatkan duit yang cukup.
Kondisi ini tidak berimbang dgn harga setengan kelas kecil 350 ml dari olahan kopi yang disebut dengan mochi, yang harganya Rp 60.000. Ini ironi bagi pemetik kopi glondongan, yang berpanas dan ditimpuk matahari. Namun demikian perjuangan yang ada menunjukkan olah danulah daei golongan usaha kecil dan mikro. Bukan usaha skala menengah dan besar.
Ini seperti kebalikan dengan kopi saset, yang belum tentu diproduksi dari kopi pilihan dan proses yang jempolan. Bagaimana kopi rasanya bisa distandartisasibkecuali dari olahan kopi yang diberi esen atau campuran standart rasa. Mana ada kopi yang beda hamparan rasanya sama, gak pernah ditemukan budidaya kopi olahan pak Rosiki akan sama dengan Pak Riga.
Koperasi berkembang, tetapi sejatinya adalah usaha dagang dengan nama koperasi. Bukan kumpulan orang yang bersekutu untuk meningkatkan kan produksi atau olahan kopi. Itu adalah unit simpan pinjam, yang menjual dana pada pelaku usaha pertanian.
Organisasi petani kopi sering berjuang sendiri-sendiri, sehingga petani budidaya selain membibit, mengolah lahan juga sekaligus berjuakan kopi. Pembagian peran dalam usaha kopi skala kecil ini berkembang dengan sendiri dan alami. Meski sebuah rangkaian produksi sebuah komodi kopi, tetapi rangkaiannya tidak benar-benar dijalin dengan cermat dan tepat.
Budaya berkembang dari penghidupan
Pola-pola relasi antar bagian dalam proses produksi kopi, adalah rangkaian interaksi sosial yang berlangsung cukup lama. Pola tanam yang mapan, proses mengawinkan putik dan serbu, juga masih sama. Tak ketinggalan ritual petani, pedagang dan penyeduh kopi masih satu jalinan yang sama.
Memang gawai sudah jadi bagian yang sulit dibendung tapi ini mendukung membangun relasi yang lebih cepat, mengetahui harga kopi glondongan dan berasan yang standar asalan. Pemahaman harga yang agak lebih mahal karena kopi diproduksi dengan cara-cara yang menghasilkan kualitas.
Hari-hari libur nyaris tidak ada, kecuali ritual lingkaran hidup dari kelahiran – kematian dan kembali ke kelahiran. Adat istiadat pernikahan yang masih sama model dan aksesori yang sudah berubah. Tapi semua bertumpu dan bersumber pada mengelola, mengolah kopi untuk penghidupan mereka.
Ini sebuah keindahan tapi sering dianggap bukan aset yang bisa dikembangkan, aset yang menjadi kekuatan bermasyarakat. Jangan sampai budaya kopi ini hilang karena sawit datang, atau karena sirup makin banyak di pasaran. Jangan sampai kopi Takengon ini sepeti olahan kulit di Tanggulangin di Sidoarjo yang kehilangan arwah atau gerabah di Kasongab Jogja yang mati degan, hiduppun enggan.
Berbudaya itu adalah sebuah karya bersama yang terus berkembang yang harusnya melestarikan, dan bukan sebaliknya, yaitu memusnahkan.
——–
*Pietra Widiadi. Petani kopi, tinggal di Desa Sumbersuko, Wagir – Malang; Ph.D candidate dari Unmer – Malang; sosiolog praktisi.