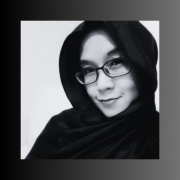“Surat Wasiat” dan Etika Ingatan: Membaca Agus R. Sarjono dari Puisi yang Mengikat Puisi-Puisinya
Oleh Abdul Wachid B.S.*
I. Masuk Melalui Pertanyaan Estetik
Ada satu pertanyaan yang selalu terasa mengganjal setiap kali kita berhadapan dengan penyair yang puisinya banyak, beragam, dan (yang terpenting) saling berbicara satu sama lain: bagaimana mungkin kita memilih satu puisi terbaik tanpa mengkhianati puisi-puisi yang lain? Pertanyaan ini bukan perkara selera, apalagi soal peringkat. Ia lebih dekat pada kegelisahan estetik sekaligus etis: ketika puisi-puisi itu saling menyahut, saling menyimpan gema sejarah, bahkan saling mewariskan luka, adakah satu teks yang layak dijadikan pintu masuk tanpa menutup lorong-lorong yang lain?
Cara baca yang lazim sering kali terlalu tergesa. Kita cenderung menunjuk puisi yang paling terkenal, yang paling sering dikutip dalam forum akademik, atau yang paling memancing emosi pembaca. Kriteria-kriteria semacam itu memang tidak sepenuhnya keliru, tetapi kerap berhenti di permukaan. Ketokohan puisi direduksi menjadi soal visibilitas, keindahan diukur dari intensitas perasaan sesaat, sementara kerja ingatan yang lebih dalam, yang diam-diam mengikat puisi ke puisi, justru terlewatkan. Dalam konteks penyair seperti Agus R. Sarjono, cara baca semacam ini terasa kurang memadai, bahkan berisiko menyederhanakan medan estetik yang sesungguhnya kompleks.
Saya ingin mengajukan satu tawaran pembacaan yang barangkali lebih lambat, tetapi (saya kira) lebih adil. Puisi terbaik tidak selalu yang paling lantang menyuarakan diri, melainkan yang paling sanggup menampung kesadaran puisi-puisi lain. Ia bekerja sebagai simpul, sebagai ruang temu, tempat berbagai suara, tema, dan sejarah saling berkelindan tanpa harus kehilangan ketegangannya. Puisi semacam ini tidak meniadakan yang lain; sebaliknya, ia justru memungkinkan puisi-puisi lain dibaca ulang dengan cahaya yang berbeda.
Di titik inilah esai ini bermula. Bukan dari keinginan menetapkan pemenang dalam lomba imajiner, melainkan dari hasrat memahami bagaimana satu puisi dapat berfungsi sebagai pusat etika ingatan dalam semesta kepenyairan tertentu. Nama puisi itu belum perlu disebut sekarang. Cukuplah dikatakan bahwa kita sedang menyiapkan sebuah modus pembacaan: modus yang percaya bahwa puisi, seperti sejarah, tidak pernah berdiri sendirian. Ia selalu mengikat, dan terikat.
II. Posisi Seorang Penyair Saksi Zaman
Agus R. Sarjono lahir di Bandung, 27 Juli 1962. Ia dikenal luas sebagai penyair, tetapi kiprahnya tidak pernah berhenti pada puisi semata. Esai, kritik sastra, drama, dan kerja kebudayaan menjadi bagian dari medan hidup yang ia jalani secara bersamaan. Latar intelektualnya bertumpu pada sastra dan teater, namun arah perhatiannya sejak awal bergerak ke wilayah yang lebih luas: bahasa sebagai medan kuasa, ingatan sebagai persoalan etis, dan kebudayaan sebagai ruang pertarungan makna.
Dalam perjalanan panjangnya, Sarjono menempati berbagai posisi kultural yang strategis. Ia pernah menjadi redaktur majalah Horison dalam waktu yang tidak singkat, memimpin Dewan Kesenian Jakarta, serta mengajar teater di ISBI Bandung. Di luar negeri, ia hadir sebagai sastrawan dan peneliti tamu di berbagai pusat kajian sastra dan budaya: dari Leiden hingga Bonn, dari Langenbroich hingga berbagai forum sastra internasional. Namun deretan posisi ini tidak serta-merta menjadikannya penyair institusional yang berjarak dari denyut sosial. Justru sebaliknya: pengalaman berada di dalam dan di luar institusi itu membentuk kepekaan ganda: sebagai pelaku budaya sekaligus pengamat yang waspada.
Yang menarik, Sarjono tidak memanfaatkan posisi-posisi tersebut untuk membangun suara kepenyairan yang menara gading. Puisinya tidak lahir dari jarak aman, melainkan dari persentuhan langsung dengan sejarah, kekuasaan, dan luka kolektif. Ia menulis Marsinah tanpa mengubahnya menjadi slogan. Ia berbicara tentang perang, pengasingan, dan penindasan tanpa meninggikan suara. Bahkan ketika puisinya menjelajah dialog dengan tokoh-tokoh sastra dunia (Breytenbach, Sartre, Cervantes, Pamuk), yang hadir bukan kekaguman kosong, melainkan kesadaran bahwa luka sejarah bersifat lintas batas dan lintas bahasa.
Dalam pengertian ini, Sarjono dekat dengan gambaran intelektual yang tidak sekadar menjelaskan dunia, tetapi bersedia tinggal di dalam kerumitannya. Ia tidak berdiri sebagai juru bicara kekuasaan, juga tidak mengklaim diri sebagai pahlawan moral. Ia memilih posisi yang lebih sunyi: menjadi saksi yang terus-menerus bertanya, mengingat, dan menulis dengan kewaspadaan etis. Bahasa baginya bukan alat pembelaan diri, melainkan medan tanggung jawab.
Posisi estetik inilah yang kemudian menentukan bentuk puisinya. Banyak sajak Sarjono tampil sebagai “surat”: alamat kepada seseorang, kepada tokoh sejarah, kepada pembaca, bahkan kepada sejarah itu sendiri. Puisi-puisi itu tidak berdiri sendiri sebagai luapan emosi, melainkan saling menyapa, saling menaut, dan saling mengingatkan. Dari sini menjadi jelas bahwa membaca puisi Agus R. Sarjono tidak cukup dilakukan secara terpisah-pisah. Ia menuntut cara baca yang relasional; membaca satu puisi dari puisi-puisi lain yang mengitarinya, hingga akhirnya tampak bahwa di antara jejaring itu ada simpul kesadaran yang bekerja lebih dalam.
Bagian inilah yang kelak menuntun kita pada satu pertanyaan penting: adakah satu puisi yang tidak sekadar mewakili tema, tetapi merangkum etika dan kesadaran seluruh semesta kepenyairannya?
III. Membaca Puisi Secara Intraestetik
Setiap pembacaan puisi, sadar atau tidak, selalu membawa asumsi. Ada yang membaca puisi sebagai peristiwa tunggal, ada yang menempatkannya dalam urutan kronologis, ada pula yang terlalu cepat mengaitkannya dengan biografi penyair. Cara-cara ini sah, tetapi tidak selalu memadai; terutama ketika berhadapan dengan penyair yang puisinya saling berbicara, saling menyahut, dan saling menyimpan jejak ingatan bersama. Pada titik inilah diperlukan strategi baca yang tidak sekadar melihat puisi sebagai unit terpisah, melainkan sebagai bagian dari satu semesta estetik.
Yang saya maksud dengan pembacaan intraestetik adalah cara membaca yang bergerak dari puisi ke puisi, dari teks ke teks, tanpa tergesa-gesa keluar menuju penjelasan luar. Fokusnya bukan urutan waktu penciptaan, bukan pula kisah hidup penyair, dan bukan sekadar pengelompokan tema. Pembacaan ini berangkat dari asumsi sederhana tetapi penting: bahwa puisi-puisi tertentu diciptakan dalam kesadaran akan puisi-puisi lain, dan karena itu maknanya baru tampak utuh ketika dibaca secara relasional.
Dalam kerangka ini, saya mengajukan dua istilah kerja: puisi poros dan puisi orbit. Puisi poros adalah puisi yang menjadi pusat etika dan kesadaran puitik; bukan karena ia paling terkenal atau paling emosional, melainkan karena di sanalah berbagai kecenderungan estetik bertemu dan menemukan bentuknya. Sementara itu, puisi orbit adalah puisi-puisi yang mengitari poros tersebut: menjelaskan dari sudut lain, menegaskan dengan nada berbeda, atau bahkan menyimpang secara tematis, tetapi tetap berada dalam medan kesadaran yang sama. Relasi ini bukan hierarki nilai, melainkan relasi fungsi.
Gagasan semacam ini sebenarnya tidak sepenuhnya asing dalam sejarah kritik sastra. T.S. Eliot, dalam esainya Tradition and the Individual Talent, pernah menegaskan bahwa kehadiran satu karya baru tidak hanya menambah daftar karya, tetapi juga mengubah cara kita membaca karya-karya yang sudah ada (Eliot, London: Faber & Faber, 1920). Tradisi, dalam pengertian Eliot, bukan latar pasif, melainkan medan dinamis yang terus bergeser. Dalam konteks ini, satu puisi dapat berfungsi sebagai simpul yang membuat puisi-puisi lain (baik yang mendahuluinya maupun yang mengitarinya) terbaca ulang secara berbeda. Logika inilah yang memungkinkan kita berbicara tentang poros tanpa terjebak pada subjektivitas semata.
Sementara itu, bentuk puisi-puisi Agus R. Sarjono yang kerap tampil sebagai “surat” membuka kemungkinan pembacaan dialogis. Di sini, pemikiran Mikhail Bakhtin tentang dialogisme menjadi relevan, meskipun tidak perlu dihadirkan secara terminologis. Bagi Bakhtin, bahasa selalu beralamat; ia selalu ditujukan kepada yang lain, selalu mengandung respons, dan selalu berada dalam relasi (Bakhtin, Moscow: Progress Publishers, 1981). Puisi-puisi Sarjono tidak berbicara ke ruang hampa. Ia menyapa: tokoh sejarah, penyair lain, pembaca, bahkan sejarah itu sendiri. Dengan demikian, makna puisinya lahir dari relasi antar-suara, bukan dari monolog liris yang tertutup.
Dimensi lain yang tak kalah penting adalah soal ingatan. Puisi-puisi Sarjono berulang kali berurusan dengan sejarah, tetapi bukan sebagai kronik peristiwa. Di sini, pemikiran Paul Ricoeur tentang memori dan narasi membantu menjernihkan posisi puisi. Ricoeur membedakan antara sejarah sebagai rekaman fakta dan ingatan sebagai kerja etis untuk memberi makna pada masa silam (Ricoeur, Chicago: University of Chicago Press, 2004). Dalam kerangka ini, puisi tidak bertugas membuktikan apa yang benar atau salah secara faktual, melainkan menjaga agar ingatan tidak membeku menjadi angka, data, atau slogan. Puisi bekerja pada wilayah yang lebih rapuh: luka, kelalaian, dan tanggung jawab.
Dengan menggabungkan ketiga garis pemikiran tersebut secara fungsional (tanpa menjadikannya beban teoritis) kita memperoleh satu pijakan metodologis yang cukup kokoh. Puisi dapat dibaca sebagai jejaring kesadaran; satu puisi dapat berfungsi sebagai pusat; dan makna sejarah dalam puisi bukan dokumentasi, melainkan kerja ingatan. Dari sini, pembacaan terhadap Agus R. Sarjono tidak lagi bergerak dari puisi ke dunia luar secara tergesa-gesa, tetapi berputar di dalam semesta puisinya sendiri, hingga akhirnya menemukan satu simpul yang menahan dan mengikat semuanya.
Kerangka inilah yang akan digunakan untuk membaca puisi-puisi Sarjono secara relasional, dan pada akhirnya, untuk menetapkan satu puisi yang dapat dibaca sebagai poros etika dan kesadaran puitiknya.
IV. Pemetaan Semesta Puisi Agus R. Sarjono
Sebelum menentukan satu puisi sebagai poros, kita perlu terlebih dahulu menyadari keluasan semesta puisi Agus R. Sarjono. Keluasan ini bukan semata jumlah puisi atau ragam temanya, melainkan medan kesadaran yang dibangun dari beragam alamat: sejarah, sastra dunia, kebudayaan Indonesia, hingga ruang personal yang paling domestik. Puisi-puisinya bergerak lintas waktu dan lintas ruang, tetapi tetap berada dalam satu napas etis yang sama.
Pertama, terdapat puisi-puisi yang secara langsung berhadapan dengan sejarah dan kekuasaan. “Surat Marsinah” adalah contoh paling nyata bagaimana puisi berfungsi sebagai ruang pengadilan moral ketika hukum dan negara gagal menjalankan tugasnya. Marsinah tidak dihadirkan sebagai simbol abstrak, melainkan sebagai alamat konkret: seseorang yang kepadanya penyair berbicara, sekaligus seseorang yang melalui namanya sejarah ditanyai. Demikian pula puisi-puisi yang menyebut figur seperti Gorky, yang tidak sekadar menjadi nama besar sastra Rusia, tetapi hadir sebagai simpul antara penderitaan, perlawanan, dan tanggung jawab intelektual. Dalam puisi-puisi ini, sejarah tidak tampil sebagai latar, melainkan sebagai luka yang terus terbuka.
Kedua, terdapat puisi-puisi yang membangun dialog intens dengan sastra dunia. Nama-nama seperti Sartre, Cervantes, Pamuk, Breytenbach, Singer, hingga Saint-Exupéry tidak dipanggil untuk pamer referensi, melainkan sebagai mitra percakapan. Agus R. Sarjono seolah menulis dari ruang yang sama dengan mereka: ruang pertanyaan tentang kemanusiaan, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Puisi-puisi ini menunjukkan bahwa kesusastraan dunia bukan etalase yang dikagumi dari kejauhan, melainkan medan dialog tempat penyair Indonesia menempatkan dirinya secara setara; bertanya, menyahut, bahkan berbeda pendapat.
Ketiga, ada puisi-puisi yang menoleh ke dalam tradisi dan kebudayaan Indonesia sendiri. Ketika nama Ranggawarsita atau Chairil Anwar muncul, yang dipertaruhkan bukan nostalgia atau penghormatan seremonial, melainkan pertanyaan tentang keberlanjutan suara. Apa arti menjadi penyair setelah zaman keruntuhan, setelah zaman revolusi, setelah bahasa mengalami kelelahan oleh slogan dan kekuasaan? Puisi-puisi ini memperlihatkan kegelisahan yang khas: antara warisan dan keterputusan, antara hormat dan kritik, antara melanjutkan dan menyimpang.
Keempat, terdapat pula puisi-puisi yang bergerak ke wilayah liris personal dan domestik, seperti “Surat Emily” dan “Surat Lamaran”. Namun, personal di sini tidak jatuh menjadi sentimental. Relasi personal justru menjadi ruang ujian etika yang paling dekat dan paling rapuh. Dalam surat-surat semacam ini, cinta, harapan, dan kecemasan hadir bukan sebagai perasaan privat semata, melainkan sebagai bagian dari cara manusia berelasi secara jujur dan bertanggung jawab. Yang domestik menjadi politis dalam pengertian yang paling sunyi.
Dari keempat wilayah tersebut (sejarah, sastra dunia, budaya Indonesia, dan ruang personal) muncul satu ciri bentuk yang menonjol: mayoritas puisi Agus R. Sarjono hadir sebagai “surat”. Bentuk ini bukan pilihan estetika yang kebetulan. Surat meniscayakan alamat, tujuan, dan tanggung jawab. Ia menolak monolog liris yang hanya sibuk dengan suara sendiri. Dalam surat, selalu ada yang disapa, selalu ada yang diharapkan menjawab, meskipun jawaban itu mungkin tidak pernah datang.
Dengan demikian, semesta puisi Agus R. Sarjono dapat dipahami sebagai jaringan alamat etis. Puisi-puisi itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dan saling menegaskan medan kesadaran yang sama. Pemetaan ini penting bukan untuk mengklasifikasi secara kaku, tetapi untuk menunjukkan bahwa ketika nanti satu puisi dipilih sebagai poros, pilihan itu lahir dari keluasan, bukan dari penyempitan. Puisi poros hanya mungkin dikenali setelah kita melihat betapa luas dan padat orbit yang mengitarinya.
V. Penetapan Puisi Poros: “Surat Wasiat”
Pada titik inilah pembacaan perlu mengambil risiko: memilih satu puisi sebagai poros, sambil sadar bahwa pilihan itu bukan penobatan mutlak, melainkan keputusan metodologis. Dalam semesta puisi Agus R. Sarjono yang luas dan saling berkelindan, “Surat Wasiat” tampil bukan karena ia paling sering dikutip atau paling mudah menggetarkan emosi, melainkan karena ia menampung (dengan cara yang dingin dan sadar) tegangan etis yang bekerja di hampir seluruh puisinya.
Alasan pertama terletak pada persona yang berbicara. “Surat Wasiat” tidak disampaikan oleh aku-liris yang personal, melainkan oleh sebuah suara kolektif yang bisa disebut sebagai Sejarah Silam. Suara ini tidak meminta simpati, tidak pula mengajukan pembelaan. Ia berbicara seolah dari jarak waktu yang sudah melewati penyesalan dan kemarahan, tetapi belum sampai pada pengampunan. Dalam posisi ini, puisi menjadi ruang tempat sejarah menyampaikan pesan terakhirnya; bukan kepada individu tertentu, melainkan kepada kemanusiaan yang masih berlangsung.
Kedua, pilihan bahasa administratif dalam puisi ini menjadi kunci penting. Wasiat, sebagai dokumen, biasanya bersifat legal, dingin, dan fungsional. Agus R. Sarjono justru memanfaatkan bahasa semacam ini untuk membalik arahnya: dari administratif menjadi etis. Kata-kata yang lazim kita temui dalam arsip, laporan, atau dokumen resmi, dihadirkan kembali sebagai alat untuk menyingkap tanggung jawab moral. Di sini, bahasa tidak berfungsi untuk menutup jejak, melainkan untuk membuka ingatan. Puisi bekerja seperti berkas yang akhirnya berbicara setelah terlalu lama dibungkam.
Ketiga, skala ruang yang dibangun “Surat Wasiat” memperlihatkan kesadaran global yang jarang hadir secara tenang dalam puisi Indonesia. Penyebutan tempat-tempat seperti Jüterbog, Aceh, Papua, Afghanistan, hingga Syria tidak disusun sebagai daftar tragedi yang bersaing dalam penderitaan. Semua ruang itu hadir setara, seolah diikat oleh satu benang sejarah kekerasan yang sama. Puisi ini tidak menunjuk satu pusat dunia; justru ia memperlihatkan bahwa luka kemanusiaan tidak pernah lokal. Dengan cara ini, “Surat Wasiat” mengikat puisi-puisi Agus R. Sarjono yang lain (tentang Marsinah, tentang perang, tentang pengasingan) ke dalam satu horison etis yang luas.
Keempat, yang paling menentukan, adalah nada puisi yang dingin. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada retorika kemarahan, tidak pula lirisisme yang memohon air mata pembaca. Justru dalam ketiadaan emosi yang demonstratif itulah kekuatan puisi ini bekerja. Ia memaksa pembaca untuk bertahan di hadapan kata-kata, tanpa perlindungan empati instan. Dingin di sini bukan ketiadaan rasa, melainkan bentuk kedewasaan etis: kesadaran bahwa sejarah tidak selalu bisa disikapi dengan ratapan, tetapi harus dihadapi dengan tanggung jawab.
Secara konseptual, penempatan “Surat Wasiat” sebagai puisi poros dapat dipahami melalui gagasan Northrop Frye tentang mythic atau structural center. Dalam setiap sistem estetik, menurut Frye, selalu ada pusat simbolik yang tidak harus paling indah, tetapi paling menentukan arah makna keseluruhan. Pusat ini bekerja seperti poros roda: tidak bergerak mencolok, tetapi memungkinkan seluruh bagian lain berputar dan terbaca sebagai satu kesatuan (Frye, Anatomy of Criticism, Princeton: Princeton University Press, 1957).
Dalam kerangka itu, “Surat Wasiat” berfungsi sebagai pusat simbolik puisi-puisi Agus R. Sarjono. Ia tidak meniadakan puisi lain, justru membuat puisi-puisi tersebut saling terbaca. Puisi sejarah menemukan fondasi etisnya, puisi dialog sastra dunia memperoleh konteks kemanusiaannya, dan puisi-puisi personal mendapatkan bayangan tanggung jawab yang lebih luas.
Maka, perlu ditegaskan sejak awal: “Surat Wasiat” bukan puisi paling indah, melainkan puisi paling sadar. Kesadarannya bukan hanya kesadaran bentuk, tetapi kesadaran akan posisi puisi di hadapan sejarah, kekerasan, dan ingatan kolektif. Dari titik inilah, pembacaan terhadap puisi-puisi Agus R. Sarjono dapat bergerak; bukan sebagai kumpulan teks yang terpisah, tetapi sebagai satu medan etika yang terus menuntut jawaban.
VI. Pembacaan Vertikal: Struktur dan Etika “Surat Wasiat”
Ada puisi yang memanggil pembaca untuk terharu. Ada puisi yang mengundang kekaguman. Dan ada puisi yang meminta tanggung jawab. “Surat Wasiat” termasuk jenis yang terakhir. Ia tidak datang dengan metafora yang berkilau atau letupan emosi. Ia hadir seperti sebuah berkas, dingin, administratif, nyaris tanpa daya tarik retoris yang lazim kita harapkan dari puisi. Justru di situlah etika puisinya bekerja.
Sebelum ditafsirkan, puisi ini perlu dihadirkan utuh, sebab ia bukan sekadar rangkaian larik, melainkan sebuah arsip kesadaran.
Surat Wasiat
Dengan sadar dan tanpa paksaan
Saya, Sejarah Silam, mewasiatkan:
Bahwa sisa-sisa senjata yang tersebar
di sekitar Jüterbog, Banda Aceh, Papua
maupun tempat-tempat di antara
keduanya, harap rapat di simpan. Bahkan
dipamerkan pun sebaiknya jangan.
Karena anak-anak yang belum dewasa
suka tergoda main perang-perangan
agar disebut pahlawan. Jangan tertawa!
Jangan diabaikan! Ini sudah pernah kejadian
yakni saat ayah saya, Sejarah Silam Sr, lupa
mewasiatkan hal serupa di Afganistan,
Yaman, Syria dan segala tempat
di antaranya, hingga dunia kembali
dan kembali lagi dengan rajin
memproduksi janda dan anak yatim.
Adapun sisa harta simpanan: sedu-sedan,
debu bakaran, erang luka,
jerit ketakutan di zaman perang,
harap digunakan sebagaimana mestinya
bagi kemashalatan umat manusia,
khususnya mereka yang papa
dan tak putus dirundung derita.
1. Persona: Sejarah sebagai Subjek yang Berbicara
Puisi ini tidak dibuka oleh aku-liris, melainkan oleh sebuah persona kolektif: “Saya, Sejarah Silam.”
Ini keputusan estetik yang menentukan. Sejarah tidak diperlakukan sebagai latar, korban, atau hakim, melainkan sebagai subjek yang telah belajar, dan kini berbicara. Ia tidak menuntut, tidak menjerit, bahkan tidak mengutuk. Ia hanya mewasiatkan.
Dengan menyebut dirinya Sejarah Silam, puisi ini menolak ilusi bahwa sejarah sudah selesai. “Silam” di sini bukan selesai, melainkan tersimpan, dan sewaktu-waktu bisa terulang bila kelalaiannya diwariskan.
Menariknya, Sejarah juga memiliki “ayah”: Sejarah Silam Sr. Ini ironi halus sekaligus pahit bahwa sejarah pun lahir dari sejarah sebelumnya, lengkap dengan kelupaannya.
2. Bahasa Administratif sebagai Bahasa Etika
Diksi-diksi kunci dalam puisi ini sangat sederhana dan nyaris teknokratis:
“… harap rapat di simpan. Bahkan
dipamerkan pun sebaiknya jangan
…
harap digunakan sebagaimana mestinya”
Tidak ada metafora rumit. Tidak ada hiperbola. Yang ada justru bahasa prosedur: bahasa yang biasa kita jumpai dalam surat resmi, laporan, atau instruksi lembaga.
Namun di tangan Sarjono, bahasa administratif ini berbalik menjadi bahasa etika. Ia menunjukkan bahwa kejahatan dan kekerasan tidak selalu lahir dari kebencian besar, melainkan dari kelalaian kecil yang dilegalkan bahasa netral.
Di sinilah gema pemikiran tentang banalitas kejahatan terasa, tanpa perlu disebutkan. Senjata yang “dipamerkan” dan perang yang “dimainkan” oleh anak-anak bukan tragedi besar yang tiba-tiba, melainkan hasil dari arsip yang dibiarkan terbuka.
3. Logika Wasiat: Antisipasi Trauma, Bukan Nostalgia
Sebagai wasiat, puisi ini tidak berbicara ke masa lalu, melainkan ke masa depan. Ia bersifat antisipatif.
Larangan “Jangan tertawa! Jangan diabaikan!” bukan ekspresi emosi, melainkan alarm etis. Sejarah tahu bahwa manusia gemar menertawakan masa lalu sebagai sesuatu yang tidak akan terulang, padahal justru di situlah pengulangan bekerja.
Repetisi daftar wilayah (Jüterbog, Aceh, Papua, Afganistan, Yaman, Syria) tidak disusun untuk efek globalisme puitik, melainkan untuk menunjukkan pola: di mana pun, kelalaian etis selalu berujung sama.
4. Harta Warisan yang Terbalik
Bagian paling sunyi sekaligus paling tajam dari puisi ini terletak pada konsep “harta simpanan”:
“… sedu-sedan,
debu bakaran, erang luka,
jerit ketakutan di zaman perang”
Inilah pembalikan radikal atas makna warisan. Sejarah tidak mewariskan kejayaan, monumen, atau pahlawan, melainkan sisa-sisa penderitaan. Dan bahkan penderitaan ini pun tidak boleh dipuja, melainkan:
“harap digunakan sebagaimana mestinya
bagi kemashalatan umat manusia”
Artinya, penderitaan hanya sah secara etis bila ia menghalangi penderitaan berikutnya, bukan bila ia diperingati sambil mengulang kesalahan yang sama.
5. Sejarah yang Belajar, Bukan Menghakimi
Yang paling menentukan: puisi ini tidak menuduh siapa pun. Tidak ada kata “penjahat”, “tirani”, atau “rezim”. Sejarah di sini tidak menjadi jaksa, melainkan arsip yang berbicara dengan suara datar.
Justru karena itu, tanggung jawab berpindah ke pembaca.
“Surat Wasiat” tidak meminta simpati. Ia meminta kedewasaan: kesediaan untuk menyimpan, mengingat, dan menggunakan ingatan secara etis.
Di titik ini, puisi ini menegaskan posisinya sebagai pusat kesadaran dalam semesta puisi Agus R. Sarjono. Ia bukan puisi paling indah, bukan pula yang paling retoris. Ia adalah puisi yang paling tahu apa yang harus ditahan agar dunia tidak kembali mengulang luka yang sama.
VII. Pembacaan Horisontal: Puisi-Puisi Orbit
Menetapkan “Surat Wasiat” sebagai puisi poros berarti membaca keseluruhan perpuisian Agus R. Sarjono sebagai satu semesta kesadaran yang saling berkelindan. Puisi-puisi lain bergerak sebagai orbit, bukan sekadar mengitari, melainkan menguji daya tahan etika yang sama dari berbagai medan pengalaman: sejarah lokal, tragedi global, keretakan ekologis, luka batin, hingga keintiman domestik. Pembacaan horisontal ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan bobot seluruh puisi, melainkan untuk memperlihatkan bagaimana satu kesadaran puitik diuji terus-menerus oleh kenyataan yang berlapis. Dengan cara inilah “Surat Wasiat” terbaca bukan sebagai teks tunggal, melainkan sebagai simpul tempat pengalaman-pengalaman itu saling mengendap, mengeras, dan menemukan rumah etikanya.
1. “Surat Marsinah”: Sejarah yang Ditutup, Luka yang Dibiarkan Terbuka
Puisi “Surat Marsinah” adalah orbit terdekat yang paling keras. Di sini, sejarah tampil bukan sebagai narasi heroik, melainkan sebagai kelelahan yang berulang. Repetisi kalimat “Ah sudahlah” bukan sekadar refrain retoris, tetapi ekspresi kepasrahan struktural: suara korban yang sadar bahwa
“… perkara hukum dan keadilan
tentu saja semua milik majikan.”
Demokrasi justru hadir sebagai ironi prosedural: ruang sidang yang “nyaman,” perdebatan “seru di koran dan tivi,” sementara tubuh buruh terus
“didera kerja serupa mesin:
merana, kuyu, pucat, miskin.”
Nada datar dan dingin ini menemukan resonansi ekstremnya dalam “Surat Wasiat”. Tragedi tidak lagi ditangisi, karena tangis telah kehilangan alamat. Yang tersisa adalah bahasa administratif yang nyaris impersonal: bahasa sisa yang memanggil etika. Di sinilah “Surat Marsinah” menemukan simpul etikanya dalam “Surat Wasiat”: keduanya berbicara tentang kegagalan sejarah belajar dari dirinya sendiri. Bedanya, “Surat Wasiat” berbicara dari atas (dari suara sejarah), sementara “Surat Marsinah” berbicara dari bawah, dari tubuh yang dikorbankan oleh kelupaan kolektif.
2. “Surat Breyten Breytenbach”: Luka Global dan Ibu yang Sama
Orbit selanjutnya bergerak ke horison global. Dalam “Surat Breyten Breytenbach”, puisi melampaui batas geografis dan nasional. Afrika Selatan dan Indonesia tidak disandingkan secara politis, melainkan secara afektif dan etis: keduanya memiliki “ibu yang sama,” yakni air mata. Metafora sederhana ini menegaskan bahwa Agus membangun solidaritas luka, bukan ideologi.
Puisi ini beresonansi kuat dengan “Surat Wasiat”: perang, penindasan, dan trauma selalu melahirkan generasi “anak-anak air mata” yang belajar membisu, hampa, dan sangsai. Jika “Surat Wasiat” mengingatkan agar senjata tidak diwariskan pada anak-anak, “Surat Breytenbach” menunjukkan akibat ketika peringatan itu diabaikan. Sejarah global tampil sebagai sistem yang memproduksi kebisuan dan trauma struktural.
3. “Surat Pembaca”: Etika Ekologis sebagai Metafora Sosial
Dari luka manusia, orbit bergerak ke etika alam. “Surat Pembaca” tampak jauh dari kekerasan sejarah dan perang global. Namun justru di sinilah strategi orbit bekerja halus. Bahasa surat keluhan kepada “redaksi” adalah parodi terhadap bahasa administratif; bahasa yang juga ditemukan dalam “Surat Wasiat”.
“… Burung bangau
di tepi danau itu sudah sembilan malam
mencangkung sendirian …”
“Juga di tepi padang, sekuntum kembang
tersedu-sedu sendirian, …”
hingga rusa yang kehilangan pasangan, bukan sekadar citraan alam, melainkan tanda retaknya relasi. Bahkan,
“… sepasang kupu-kupu
yang terjebak di kaca jendela kamar,”
menjadi metafora dunia yang terperangkap oleh kenyamanan manusia. Etika di sini bukan slogan aktivisme, melainkan kepekaan (jenis kepekaan yang menopang moral “Surat Wasiat”): bahwa korban sejarah tidak hanya manusia, tetapi juga alam yang ikut mewarisi luka.
4. “Surat Lamaran”: Bahasa Administratif dan Luka Batin
“Surat Lamaran” adalah miniatur ironis dari “Surat Wasiat”. Jika “Surat Wasiat” menggunakan bahasa legal untuk mengatur warisan sejarah global, “Surat Lamaran” menggunakan bahasa formal untuk menawarkan jasa mengelola “sendu”, “kehampaan”, dan “melankolia.” Di sini, luka tidak lagi berskala geopolitik, tetapi berskala batin.
Namun keduanya bertemu pada satu kesadaran: bahasa administratif, yang biasanya dingin dan impersonal, justru dapat menjadi alat pengakuan luka. Luka tidak ditangisi, tetapi diajukan, dilampirkan, dan ditandatangani. Dengan cara ini, “Surat Lamaran” menjadi orbit intim dari “Surat Wasiat”.
5. “Surat Emily”: Residu Kemanusiaan yang Bertahan
Jika “Surat Wasiat” berbicara tentang sejarah besar dan “Surat Marsinah” tentang korban struktural, “Surat Emily” bergerak ke wilayah paling rapuh: cinta, ingatan, dan kehidupan domestik. Detail tentang bulu hidung, dengkur, dan sarapan bukan sekadar liris personal, melainkan perlawanan halus terhadap sejarah yang mereduksi manusia menjadi angka.
Di hadapan perang dan kekuasaan, puisi ini seperti berkata: masih ada yang tersisa, masih ada yang layak dijaga. “Surat Emily” menjadi orbit yang mengingatkan bahwa tujuan akhir dari semua wasiat sejarah adalah menyelamatkan kemungkinan hidup yang sederhana dan manusiawi.
6. Ranggawarsita dan Chairil: Dialog dengan Sejarah Sastra
Orbit “Surat Wasiat” tidak hanya mencakup sejarah politik, tetapi juga sejarah sastra Indonesia. Ranggawarsita hadir sebagai simbol “zaman edan,” sementara Chairil hadir sebagai kegelisahan eksistensial dan estetika. Keduanya menegaskan bahwa sejarah sastra pun menyimpan warisan dan wasiatnya sendiri: kewaspadaan, keberanian, dan luka.
Dialog ini diperluas oleh interaksi dengan sastra dunia (Saint-Exupéry, Singer, Sartre, Cervantes, Gorky, Pamuk) sehingga orbit etika “Surat Wasiat” menjadi refleksi global tentang kehilangan, kekuasaan, dan ingatan. Dari anak-anak yang kehilangan warna, ksatria gelak tawa yang dianggap berbahaya oleh negara, hingga identitas yang remuk
“Antara timur yang mendengkur
dan barat yang berkarat,”
semuanya mengarah pada satu simpul kesadaran: ingatan manusia selalu terancam amnesia struktural.
7. Simpul Horisontal
Dari “Surat Marsinah” hingga “Surat Emily”, dari bangau yang kesepian hingga senjata yang harus disembunyikan, satu benang etis mengikat semuanya: sejarah yang gagal belajar akan terus mewariskan luka, dan puisi hadir sebagai alamat agar luka itu tidak dibungkam.
Di titik inilah “Surat Wasiat” bekerja bukan sebagai puisi yang menggurui, melainkan sebagai pusat kesadaran. Semua puisi orbit tidak menirunya, tidak menjelaskannya, tetapi menemukan dirinya sendiri di bawah bayang-bayang etika yang sama. Dan barangkali, di situlah kekuatan utama semesta puisi Agus R. Sarjono: bukan pada keindahan retorika, melainkan pada kesetiaan untuk terus mengingat, meski ingatan itu dingin, getir, dan tak pernah selesai.
VIII. Posisi “Surat Wasiat” dalam Perpuisian Indonesia: Dari Puisi Nilai ke Puisi Ingatan
Menilai posisi “Surat Wasiat” dalam perpuisian Indonesia tidak dapat dilakukan dengan ukuran kepahlawanan subjek, keterkenalan penyair, atau intensitas emosional semata. Puisi ini justru memperoleh bobot estetiknya karena memilih berdiri di luar kategori-kategori yang lazim dipakai untuk mengukur “puisi besar”. Ia bukan puisi heroik, bukan puisi slogan politik, dan bukan pula puisi lirih-romantik. Posisi estetiknya bergerak ke wilayah lain: puisi sebagai etika ingatan dan kewaspadaan moral.
Jika ditarik ke periode Balai Pustaka, puisi Indonesia masih berfungsi sebagai medium penanaman nilai dan harmoni. Dalam puisi-puisi Sanusi Pane, subjek berbicara sebagai wakil kebijaksanaan dan ketertiban moral. Sejarah belum hadir sebagai luka; ia masih berupa latar ideal yang harus dijaga. Puisi berfungsi sebagai penuntun budi, bukan sebagai saksi kehancuran. Dalam kerangka ini, nilai mendahului pengalaman; etika hadir sebelum tragedi. Puisi belum menanggung beban sejarah, melainkan mengukuhkan tatanan.
Kesadaran tersebut mengalami pergeseran penting pada masa Pujangga Baru. Dalam “Padamu Jua” karya Amir Hamzah, puisi bergerak ke wilayah kontemplasi spiritual dan relasi vertikal manusia dengan Yang Ilahi. Sejarah dan kekerasan tidak tampil sebagai peristiwa konkret, melainkan disublimkan ke dalam bahasa cinta dan pengabdian:
“Pulang kembali aku padamu
Seperti dahulu
Kaulah kendi kemerlap
Pelita jendela di malam gelap”
Bahkan kegelisahan batin dan kegilaan eksistensial:
“Nanar aku, gila sasar”
tetap diarahkan kembali ke pusat cinta ilahiah. Sejarah, dalam puisi ini, larut menjadi pengalaman ruhani. Luka dunia dilebur ke dalam keintiman metafisik. Dibandingkan dengan itu, “Surat Wasiat” justru lahir dari kesadaran bahwa sejarah tidak bisa sepenuhnya diselamatkan melalui sublimasi spiritual. Ia menolak melarutkan luka ke dalam metafisika; ia memilih menahannya sebagai ingatan duniawi yang belum selesai.
Ledakan besar dalam perpuisian Indonesia terjadi pada Angkatan 45 melalui Chairil Anwar. Dalam “Aku”, subjek tampil sebagai pusat energi sejarah:
“Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang”
Tubuh, luka, dan keberanian individual menjadi medan perlawanan:
“Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang”
Puisi menjadi teriakan eksistensial yang menantang maut dan waktu:
“Aku mau hidup seribu tahun lagi”
Dalam konteks ini, keberanian subjek menjadi nilai utama. Sejarah dihadapi dengan vitalitas personal. “Surat Wasiat” memperlihatkan pergeseran drastis dari paradigma tersebut. Subjek tidak lagi berada di pusat, bahkan nyaris menghilang. Yang berbicara bukan “aku” yang menantang sejarah, melainkan sejarah itu sendiri:
“Saya, Sejarah Silam, mewasiatkan:”
Keberanian individual digantikan oleh beban kolektif yang tidak dapat diselesaikan oleh satu suara. Puisi tidak lagi berdiri di hadapan sejarah, melainkan berbicara dari dalam reruntuhannya.
Pada periode 1950–1960-an, melalui Sitor Situmorang, puisi Indonesia memperlihatkan kesadaran eksistensial yang lebih reflektif. Dalam puisi “Rumah”, keterasingan sejarah hadir sebagai kegelisahan batin:
“Laut dan darat tak dapat lagi didiami
Benahilah kamar di hatimu”
Dunia menjadi tidak layak huni, dan puisi menawarkan ruang batin sebagai tempat berlindung. Namun, kegelisahan ini tetap berakar pada subjek personal. “Surat Wasiat” melampaui kegelisahan tersebut dengan menggeser pusat puisi dari “aku yang mencari rumah” menjadi “sejarah yang meninggalkan reruntuhan”. Yang disorot bukan lagi tempat berdiam, melainkan sisa-sisa yang tak boleh diabaikan.
Angkatan 66 menghadirkan puisi sebagai alat perlawanan moral yang lantang. Dalam “Karangan Bunga” karya Taufiq Ismail, sejarah tampil sebagai tragedi konkret:
“Bagi kakak yang ditembak mati
Siang tadi”
Nada serupa hadir dalam puisi Rendra “Aku Mendengar Suara”:
“Orang-orang harus dibangunkan.
Kesaksian harus diberikan.”
Puisi ingin menggugah dan menggerakkan. Bahasa bersifat langsung, deklaratif, dan menuntut perubahan. “Surat Wasiat” memilih jalan berbeda. Ia berbicara setelah semua teriakan itu usai, ketika tragedi telah menjadi kebiasaan sejarah. Karena itu nadanya dingin, hampir administratif, seperti arsip yang menolak dilupakan:
“… Jangan tertawa!
Jangan diabaikan! Ini sudah pernah kejadian”
Etika puisi bergeser dari perlawanan menuju pertanggungjawaban ingatan.
Pada dekade 1970-an, puisi Indonesia bergerak menjauh dari sejarah konkret. Sutardji Calzoum Bachri, dalam “Walau”, membebaskan kata dari beban makna referensial:
“walau huruf habislah sudah
alifbataku belum sebatas allah”
Sementara Abdul Hadi W.M., dalam “Tuhan, Kita Begitu Dekat”, menegaskan keintiman spiritual melalui metafora metafisis:
“Aku panas dalam apimu”
Puisi bergerak ke wilayah ontologis dan sufistik. “Surat Wasiat” melakukan gerakan sebaliknya. Ia memanggil kembali sejarah konkret (senjata, tempat, korban) bukan sebagai ideologi atau mistik, tetapi sebagai fakta yang menuntut kewaspadaan:
“Bahwa sisa-sisa senjata yang tersebar
di sekitar Jüterbog, Banda Aceh, Papua”
Memasuki 1980-an, puisi Indonesia melalui D. Zawawi Imron dan K.H. A. Mustofa Bisri menghadirkan lirisme religius dan kearifan kultural yang meneduhkan. Dalam puisi “Agama”, Gus Mus mengingatkan agar manusia tidak bertikai dalam perjalanan menuju Tuhan. Puisi menjadi ruang kebijaksanaan. “Surat Wasiat” menolak keteduhan yang terlalu cepat. Ia tidak mengajak berdamai, melainkan mengingatkan bahwa perdamaian tanpa ingatan justru berbahaya. Karena itu ia menutup dengan nada getir:
“… dunia kembali
dan kembali lagi dengan rajin
memproduksi janda dan anak yatim”
Jika dibandingkan dengan penyair sezaman, perbedaan posisi “Surat Wasiat” semakin tegas. Soni Farid Maulana, dalam puisi “Bintang Mati”, masih mengolah kehancuran peradaban melalui lirisme personal dan empati emosional. Joko Pinurbo, dalam “Kepada Puisi”, mereduksi pengalaman ke dalam ironi domestik:
“Kau adalah mata,
aku air matamu.”
Agus R. Sarjono memilih jalur lain. Ia menghapus lirisme personal dan ironi keseharian, lalu menghadirkan bahasa yang menyerupai arsip moral. Puisi tidak menghibur, tidak menghangatkan, tetapi menjaga.
Dengan demikian, “Surat Wasiat” menempati posisi estetik yang khas dalam perpuisian Indonesia. Ia bukan kelanjutan langsung satu periode tertentu, melainkan hasil pendewasaan lintas generasi. Setelah puisi nilai, puisi heroik, puisi perlawanan, pembebasan kata, dan keheningan spiritual, “Surat Wasiat” menandai satu fungsi baru puisi Indonesia: menjadi penjaga ingatan.
Dalam pengertian inilah “Surat Wasiat” memperoleh bobot estetiknya. Ia tidak menyelesaikan sejarah, tetapi memastikan sejarah tidak dilupakan. Puisi menjadi wasiat bahasa, tanda bahwa perpuisian Indonesia telah sampai pada kesadaran etis yang matang: bahwa setelah tragedi, keindahan saja tidak cukup, dan keberanian saja tidak memadai. Yang dibutuhkan adalah kesediaan untuk mengingat, menjaga, dan bertanggung jawab.
IX. Refleksi: Puisi sebagai Tanggung Jawab Sejarah
Pada tahap ini, puisi memang tidak pernah ditugasi untuk menyelesaikan sejarah. Ia tidak membangun kembali kota yang hancur, tidak menghidupkan kembali yang mati, dan tidak mengoreksi keputusan politik yang keliru. Puisi tidak bekerja di wilayah solusi. Justru karena itu, ia memiliki wilayah tanggung jawab yang lain, wilayah yang sering luput dari kalkulasi pragmatis: menjaga agar sejarah tidak menjadi lupa.
Dalam dunia yang bergerak cepat, sejarah mudah direduksi menjadi angka, laporan, atau arsip. Tragedi dipadatkan menjadi statistik, penderitaan disederhanakan menjadi data, dan luka manusia berubah menjadi catatan kaki. Bahasa semacam itu efisien, tetapi sekaligus menghapus kehadiran manusia. Di titik inilah puisi mengambil peran yang tak tergantikan. Ia menolak percepatan itu. Ia memperlambat ingatan, menahan makna, dan memaksa kita berhenti: untuk sungguh-sungguh menghadapi apa yang ingin segera kita lewati.
“Surat Wasiat” bekerja persis di wilayah tersebut. Ia tidak menawarkan penghiburan, tidak pula menjanjikan penebusan. Ia hanya meninggalkan pesan yang sederhana sekaligus berat: ada sesuatu yang pernah terjadi, dan sesuatu itu tidak boleh lenyap begitu saja. Sejarah, dalam puisi ini, berbicara bukan sebagai pahlawan atau korban, melainkan sebagai pewaris luka yang lelah melihat dirinya terus diulang.
Namun, kesadaran semacam ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam satu puisi. Ia berakar dalam keseluruhan perpuisian Agus R. Sarjono. Dalam “Surat Marsinah”, misalnya, sejarah tampil sebagai ironi yang pahit: suara buruh yang dilemahkan oleh bahasa kekuasaan dan prosedur hukum yang dingin. Puisi itu tidak berteriak, melainkan mendesah lirih dengan kalimat-kalimat yang seolah sudah kehabisan harapan. Di sana, sejarah bukan peristiwa lampau, melainkan luka yang belum selesai bekerja.
Sementara itu, dalam “Surat Pembaca” dan “Surat Lamaran”, tanggung jawab puisi terhadap sejarah mengambil bentuk yang lebih sunyi dan domestik. Kesepian makhluk-makhluk kecil, kehampaan personal, dan melankolia sehari-hari ditulis bukan sebagai curahan perasaan semata, melainkan sebagai gejala dunia yang makin kehilangan empati. Yang retak bukan hanya individu, tetapi cara manusia saling memperhatikan. Sejarah, di sini, bekerja dalam skala mikro, di ruang-ruang yang kerap dianggap sepele.
Dalam “Surat Breyten Breytenbach”, kesadaran sejarah bahkan melampaui batas nasional. Ingatan kolektif dipertautkan lintas bangsa, lintas pengalaman penindasan. Airmata menjadi metafora bersama; bukan untuk menyamakan tragedi, melainkan untuk menegaskan bahwa sejarah manusia saling berkelindan, dan bahwa puisi dapat menjadi ruang dialog etis antar-ingatan.
Semua itu menemukan bentuknya yang paling telanjang dalam “Surat Wasiat”. Di puisi inilah bahasa dilepaskan dari lirisisme personal dan disederhanakan hingga nyaris administratif. Nada dingin, struktur seperti dokumen resmi, dan persona “Sejarah Silam” bukanlah permainan stilistika, melainkan keputusan moral. Bahasa dipaksa menahan diri agar luka tidak berubah menjadi tontonan. Metafora ditarik mundur agar tragedi tidak terestetisasi secara berlebihan.
Dengan demikian, bahasa puisi di tangan Agus R. Sarjono bukan sekadar alat ekspresi, melainkan medium etika. Cara mengatakan menjadi sama pentingnya dengan apa yang dikatakan. Ada peristiwa yang tidak layak diteriakkan, tidak patut dipoles, dan tidak boleh dirayakan sebagai keindahan. Yang bisa dilakukan bahasa hanyalah menjaga jarak yang hormat; cukup dekat untuk mengingat, cukup jauh untuk tidak mengeksploitasi.
Maka, ketika puisi tidak lagi menjadi ruang aku-liris memamerkan perasaan, atau penyair mendeklarasikan sikap secara langsung, ia justru menemukan fungsinya yang lebih dalam: menjadi ruang titipan. Di sanalah sejarah diletakkan, bukan untuk dipuja, tetapi untuk dijaga. Bukan agar dendam diwariskan, melainkan agar kelalaian tidak terulang. Puisi tidak menyembuhkan luka, tetapi memastikan luka itu tidak disangkal.
Dalam konteks ini, “Surat Wasiat” bukan penutup pembacaan, melainkan awal kewaspadaan. Ia tidak menjanjikan masa depan yang lebih baik, tetapi menjaga agar masa lalu tidak dihapus begitu saja. Ia tidak menawarkan harapan, tetapi menegaskan ingatan sebagai tanggung jawab bersama. Dan barangkali, di situlah puisi menemukan martabatnya yang paling sunyi sekaligus paling berat: menjadi saksi yang tidak pergi.
Jika sejarah adalah sesuatu yang terus berusaha melupakan dirinya sendiri, maka puisi (dalam bentuknya yang paling jujur) adalah usaha kecil manusia untuk berkata: tunggu sebentar, jangan hilang dulu.
Dan mungkin, sejauh itulah bahasa masih bisa memikul tanggung jawabnya.
X. Penutup
Menempatkan “Surat Wasiat” dalam keseluruhan perpuisian Agus R. Sarjono bukanlah usaha untuk mengukuhkan satu teks sebagai puncak pencapaian estetik, melainkan untuk membaca pola kesadaran yang bekerja secara konsisten di dalam karya-karya tersebut. Puisi ini tidak hadir sebagai karya yang “lebih unggul” dari yang lain, tetapi sebagai titik temu dari kecenderungan tematik, pilihan bahasa, dan sikap puitik yang telah lama dibangun. Ia berfungsi sebagai simpul pembacaan, tempat berbagai arah puisi itu bertaut dan memperlihatkan orientasi etiknya secara paling jelas.
Dengan demikian, pembacaan ini tidak berangkat dari asumsi bahwa satu puisi dapat mewakili keseluruhan karya secara total, melainkan dari keyakinan bahwa dalam setiap semesta kepenyairan terdapat teks-teks tertentu yang bekerja sebagai pengendapan. “Surat Wasiat” memungkinkan hal itu karena ia tidak mengedepankan ekspresi personal, tidak menggantungkan diri pada momen emosional tertentu, dan tidak menempatkan penyair sebagai pusat wacana. Justru melalui sikap menahan diri itulah puisi ini membuka ruang bagi pembacaan yang lebih luas terhadap keseluruhan kerja puitik Agus R. Sarjono.
Pendekatan semacam ini menggeser cara membaca puisi dari pencarian intensitas estetis menuju pengujian konsistensi sikap bahasa. Puisi tidak lagi diperlakukan sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari jaringan teks yang saling menerangkan. Dalam konteks tersebut, “Surat Wasiat” tidak memusatkan makna, tetapi membantu memperlihatkan bagaimana puisi-puisi lain, baik yang bersifat politis, domestik, maupun reflektif, bergerak dalam horison kesadaran yang sama.
Implikasi dari pembacaan ini tidak berhenti pada satu penyair. Ia menawarkan kemungkinan cara membaca puisi Indonesia secara lebih relasional dan bertanggung jawab: tidak tergesa-gesa mengagungkan satu teks, tidak pula memisahkan puisi dari konteks etis yang melingkupinya. Puisi, dalam pengertian ini, dipahami sebagai kerja jangka panjang (bukan ledakan sesaat), yang menuntut ketekunan membaca dan kehati-hatian menilai.
Akhirnya, “Surat Wasiat” menunjukkan bahwa kekuatan puisi tidak selalu terletak pada daya pikat bahasa atau keberanian gestur, melainkan pada keteguhan sikapnya terhadap apa yang ditulis. Ia tidak menawarkan jawaban, tidak pula menutup perbincangan. Justru dengan sikap itulah puisi ini tetap terbuka: sebagai teks yang terus dapat dibaca ulang, dipertanyakan, dan diuji relevansinya, seiring perubahan zaman dan cara kita memandang sejarah itu sendiri.
Di titik inilah pembacaan dapat dihentikan, bukan karena persoalan telah selesai, tetapi karena ruang tafsir telah cukup disiapkan. Puisi tidak ditinggalkan sebagai monumen, melainkan sebagai teks yang siap dimasuki kembali, dengan kesadaran yang mungkin berbeda, namun dengan kehati-hatian yang sama. ***
—-
Daftar Pustaka
Anwar, Chairil. 1949. Deru Campur Debu. Jakarta: Pustaka Rakyat.
Bachri, Sutardji Calzoum. 1981. O Amuk Kapak. Jakarta: Sinar Harapan.
Bakhtin, Mikhail M. 1981. The Dialogic Imagination: Four Essays (C. Emerson & M. Holquist, Trans.). Moscow: Progress Publishers.
Bisri, Mustofa. 2016. Aku Manusia. Rembang: MataAir.
Eliot, T. S. 1920. Tradition and the Individual Talent. London: Faber & Faber.
Eneste, Pamusuk (Ed.). 2009. Chairil Anwar: Yang Terampas dan Yang Putus. Jakarta: Gramedia.
Frye, Northrop. 1957. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton University Press.
Hadi W.M., Abdul. 2012. Tuhan, Kita Begitu Dekat. Depok: Komodo Books.
Hamzah, Amir. 1985. Nyanyi Sunyi. Cet.X. Jakarta: Dian Rakyat.
Imron, Zawawi. 2017. Segugus Percakapan Cinta di Bawah Matahari. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
Ismail, Taufiq. 1992/1993. Tirani dan benteng. Jakarta: Yayasan Ananda.
Maulana, Soni Farid. 2000. Kita Lahir Sebagai Dongengan. Bandung: Pustaka Jaya.
Pinurbo, Joko. 2004. Kekasihku. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Rendra. 2013. Potret Pembangunan dalam Puisi. Jakarta: Pustaka Jaya. (Cetakan Pertama, Jakarta: PT Pembangunan, 1980).
Ricoeur, Paul. 2004. Memory, History, Forgetting (K. Blamey & D. Pellauer, Trans.). Chicago: University of Chicago Press.
Sarjono, Agus R. 2010. Suatu Cerita dari Negeri Angin. Cet. III. Depok: Komodo Books.
Sarjono, Agus R. 2011. Lumbung Perjumpaan. Depok. Komodo Books.
Sarjono, Agus R. 2013. Kopi, Kretek, Cinta. Depok: Komodo Books.
Sarjono, Agus R. 11-2-2014. Sajak-sajak: 1. Ranggawarsita, 2. Saint-Exupery, 3. Singer, 4. Sartre, 5. Cervantes, 6. Gorky, 7. Pamuk, 8. Chairil. Sumber : https://www.jendelasastra.com/dapur-sastra/dapur-jendela-sastra/lain-lain/puisi-puisi-agus-r-sardjono
Sarjono, Agus R. 26-2-2021. Sajak-sajak: 1. Surat Pembaca, 2. Surat Lamaran, 3. Surat Marsinah, 4. Surat Breyten Breytenbach, 5. Surat Wasiat, 6. Surat Emily. Sumber: https://borobudurwriters.id/sajak-sajak/puisi-puisi-agus-r-sarjono/
Situmorang, Sitor. 1953. Surat Kertas Hijau. Jakarta: Pustaka Rakyat.
Suryadi AG, Linus. 1987. Tonggak: Antologi Puisi Indonesia Modern, Jilid 1–4. Jakarta: Gramedia.
—–
*Penulis adalah penyair, Ketua Sekolah Kepenulisan Sastra Pedaban (SKSP) dan Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.