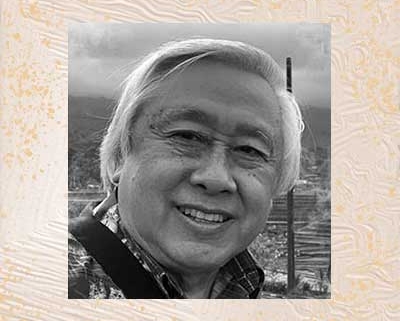Sepi Sunyinya SEKOLAH KAMI
Oleh Agus Dermawan T.
Pada 60 tahun silam para pemerhati pendidikan di Rogojampi mendorong pemerintah untuk mendirikan Sekolah (Negeri). Kini sekolah “penampung siswa” yang dulu sangat berperan : kesepian dan merana.
—————————
PADA minggu-minggu terakhir dunia pendidikan SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) di Indonesia dihebohkan oleh kasus penerimaan siswa di sekolah baru.
Kebijakan pemerintah yang memilah domisili siswa dalam zonasi, ternyata melahirkan skandal. Sementara proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang diselenggarakan secara online lewat halaman web juga menyediakan kesempatan untuk kecurangan. Pada bagian lain juga ditemukan tindakan penyuapan, pemerasan dan paksaan gratifikasi kepada orangtua Peserta Didik Baru (PDB). Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi harus menerbitkan Surat Edaran Nomer 7 tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB.
Yang jadi pertanyaan: mengapa persoalan zonasi menjadi biang kekisruhan? Jawabannya ternyata berkait dengan penilaian para PDB atas sekolah favorit. SMAN yang relatif istimewa kualifikasinya memang selalu diperebutkan bangkunya dengan segala cara. Meski SMAN itu tidak berada di zonasi tempat tinggal PDB.
Lalu mengapa pula yang diperebutkan hanya SMAN, padahal SMAS (Sekolah Menengah Atas Swasta) yang bereputasi hebat juga banyak jumlahnya? Alasannya adalah ekonomi: SMAN tidak memungut biaya. Ini selaras dengan peraturan ulang pemerintah yang tertuang dalam Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas No 20/2003. Sementara SMAS (yang favorit, maupun yang agak favorit) alamak mahal biaya masuk dan biaya sekolahnya!
Sekitar 60 tahun silam
Melihat kisruh yang berulang dalam beberapa tahun belakangan, saya jadi teringat hikayat Sekolah Negeri di desa saya, Rogojampi. Desa kecamatan (pernah berstatus kawedanan), 15 kilometer sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Teringat benar! Meski hikayat itu hanya menyangkut SR atau Sekolah Rakyat (yang kemudian menjadi SD atau Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Ajang ajar yang dua atau satu level di bawah SMA.
Dahulu, sebelum tahun 1960 di Rogojampi hanya ada dua SD yang dikelola oleh Negeri, atau Negara. Sementara SMP Negeri sama sekali tidak ada. Jumlah sekolah yang dua gelintir ini sungguh tidak mencukupi untuk menampung anak-anak peserta didik yang tersebar di banyak wilayah kecamatan. Seperti desa Gladak, Bubuk, Mangir, Watukebo, Macanputih, Blimbingsari. Dusun Aliyan, Karangbendo, Lemahbang, Mangir, Kaotan, Pengantigan sampai Gintangan. Padahal kala itu, menurut statistik, jumlah anak-anak yang butuh sekolah lebih dari 400. Dan mereka tidak hanya membutuhkan SD, tapi sekolah yang berketerusan.

Kecamatan Rogojampi dalam peta, yang bernoktah merah, di ujung timur Pulau Jawa. (Sumber: Dokumentasi Agus Dermawan T.)
Syahdan ada beberapa orang pemerhati pendidikan prihatin dengan keadaan itu. Lalu mereka – kita sebut saja Tim P (prihatin) – mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun minimal satu sekolah di setiap desa dan dusun.
Selain mengeluhkan ketiadaan Sekolah Negeri, Tim P juga memperhatikan situasi sosial yang ada kala itu. Karena diam-diam di Rogojampi muncul gap pendidikan antara masyarakat bumiputera dan masyarakat Tionghoa yang berstatus WNA (warga negara asing). Di desa ini sebelum 1960 sudah ada beberapa sekolah Tionghoa Asing.
Gedung sekolah Tionghoa Asing ini apik berdiri di beberapa tempat, dan guru-gurunya pun siap. Sekolah ini bahkan menyediakan bus khusus untuk antar-jemput peserta didik. Maka pada setiap jam di beberapa desa di Rogojampi bersliweran bus sekolah mereka. Sementara para pelajar bumiputera dan Tionghoa WNI (warga negara Indonesia) yang “sempat bersekolah”, sebagian kecil naik sepeda dan lainnya cuma berjalan kaki saja. Yang “ironis”, pemerintah Indonesia (justru) melarang peserta didik WNI (bumiputera atau keturunan Tionghoa) masuk ke sekolah Tionghoa Asing.
Usaha Tim P dalam mendorong pemerintah untuk mendirikan Sekolah Negeri ternyata mentok. Lalu Tim P – di antaranya Tjeng Siauw Kien, Kho Tjing Lok, Nyoo Siok Tjwan, Tan Ik Khoen (ayah saya) – berinisiatif mendirikan sekolah swasta, untuk SD dan SMP. Tim tersebut lantas mendekati Yayasan Karmel di Malang. Sebuah yayasan milik Katolik yang khusus bergerak di bidang pendidikan.

Para pendiri SR dan SMP Katolik Bakti Rogojampi berpotret bersama Monsinyur dari Yayasan Karmel, Malang, 1958. Tampak Tan Ik Khoen, Kho Tjing Lok, Tjeng Siauw Kien dan Nyoo Siok Tjwan di situ. (Sumber: Dokumentasi Agus Dermawan T.)

Logo Yayasan Karmel, Malang dan logo SMP Katolik Bakti Rogojampi. (Sumber: Dokumentasi Agus Dermawan T.)
Tim P menjelaskan bahwa Rogojampi adalah daerah yang bagus untuk pendidikan, karena lokasinya tepat di tengah himpitan beberapa desa dan kota. Seperti Srono, Benculuk dan Jajag di selatan; Banyuwangi dan Kabat di utara, serta Genteng dan Gambor di barat. Letak yang memusat ini terbukti pernah menstimulasi pemerintah Hindia Belanda untuk membuat Rogojampi sebagai desa percontohan, sehingga harus diatur oleh seorang wedana. Maka di desa ini sejak sebelum kemerdekaan telah ada stasiun kereta api, kantor pos, lapangan luas untuk jaarbeurs (pasar malam tahunan), gedung pertemuan, gereja, masjid, toko buku, pasar, bahkan kantor telpon.
Pada tahun 1930-an Ki Hajar Dewantoro juga terpikat Rogojampi, sehingga menugaskan Sindudarsono Sudjojono untuk jadi guru di situ sambil mengembangkan lembaga Taman Siswa. (Kita tahu, Sudjojono pada kemudian hari menjadi tokoh besar seni lukis Indonesia).
Menilik sejarah yang menarik, Yayasan Karmel setuju untuk mendirikan sekolah di Rogojampi. Pada akhir 1957 Keuskupan Malang, dengan dukungan organisasi Tiong Hoa Hwee Kwan, membeli sebidang tanah luas di Kampung Baru. Pada 1 Agustus 1958 berdirilah SD dan SMP Katolik Bakti.
Meski di bawah payung yayasan Katolik, sekolah ini menerima siswa yang berasal dari berbagai agama. Bahkan yang terdaftar mayoritas beragama Islam. Dan biaya sekolah juga dilakukan dengan prinsip gotong-royong. Yang punya uang membayar sesuai kewajiban. Yang kurang berada membayar sekadarnya saja. Lalu SD dan SMP Katolik Bakti pun punya banyak siswa yang datang dari mana-mana. Mereka yang tidak tertampung di Sekolah Negeri, berbaris masuk ke sini. Problem kekurangan Sekolah Negeri pun sedikit tertambal, meski tentu jauh dari ideal.
Untuk memaksimalisasi peran sekolah, dalam setiap tahun Monsinyur (monsignor – Itali, yang artinya “Tuanku”) dari Yayasan Karmel selalu datang ke Rogojampi untuk meninjau. Dalam kesempatan itu beliau selalu mampir di rumah ayah. Saya ingat benar ketika mobil sedan Chevrolet Monsinyur yang hitam mulus berkilau-kilau itu dirubungi kami – anak-anak sekampung. Dan ketika kami berusaha mendekat, si sopir menggusah dengan halus. Hhusss…

Mobil mengkilat Monsinyur Yayasan Karmel, dalam ingatan. (Sumber: Dokumentasi Agus Dermawan T.)
Ilustrasi, guru tak pandang bulu
Karena dianggap berperan dalam pendirian sekolah, ayah kemudian diangkat sebagai wali sekolah. Atas jabatan itu, saya, kakak dan adik-adik, yang semuanya sekolah di situ, punya posisi yang “diperhatikan”. Namun jangan dikira perhatian itu sama dengan peng-anakemas-an. Guru-guru di sekolah tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturannya, termasuk terhadap kami. Adik saya pernah dua kali tidak naik kelas, tanpa ampun. Ayah mendukung keputusan itu.
Pada suatu kali sejumlah teman sekelas berusaha menghindari pelajaran dari guru yang tidak kami sukai. Guru itu mengajar setelah jam istirahat. Maka pada jam istirahat itu kami berenam (semuanya lelaki) bersepakat melincur dengan pergi ke Waduk Bunder yang tak terlalu jauh dari sekolah. Setelah satu jam bermain-main di situ kami semua balik. Dan ohooi!, di depan pintu kelas telah menunggu sang kepala sekolah. Hukuman pun dijalankan. Caranya: rambut di depan telinga sebelah kiri kami dijumput, lalu dipelintir dan dibetot ke atas dengan keras. Hukuman yang “halus tanpa suara” ini menghasilkan sakit yang nyelekit. Bahkan sampai dua hari panas pada kulit kepala masih terasa.
Apakah saya sebagai anak wali sekolah juga kena ganjaran? Guru ternyata sama sekali tidak pandang bulu! Sepupu saya, Tjeng Ie Tiong, anak salah satu pendiri sekolah, juga kebagian. Maka, meski terposisi sebagai anak wali sekolah dan anak pendiri sekolah, kami tidak pernah aman. Saya tak bisa membayangkan apabila hukuman itu dilakukan pada masa sekarang. Cerita kiamat Pak Guru jadi berita di televisi dan koran!
Tidak populer
Pada tahun 1960 ayah dan teman-temannya mendirikan SMP Teratai yang dibiayai para donatur Tionghoa yang berafiliasi di bawah organisasi Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). SMP Teratai menerima murid dari kalangan mana saja, dengan biaya yang lagi-lagi gotong royong. Lulusan SD Negeri yang tak punya sekolah lanjutan, dipersilakan bersekolah di sini.
Peristiwa Gerakan 30 September meletus pada 1965. SMP Teratai ditutup. Pada tahun ini pula akhirnya, – ya akhirnya! – berdiri SMP Negeri Rogojampi (sebagai titipan SMP Negeri Banyuwangi), dengan lokasi ala kadarnya. Pada tahun 1966 SMP Negeri ini (oleh ayah dan teman-temannya) dipindah ke gedung sekolah SMP Teratai yang ditutup setahun sebelumnya itu.
Tahun-tahun terus berjalan, dan dekade demi dekade dilalui. Sekolah Negeri bertumbuhan di mana-mana. Sehingga para siswa SMP menyebar di berbagai sekolah di banyak wilayah.
Bayangkan, apabila sekitar 60 tahun lalu SMP Negeri di Rogojampi hanya satu, sekarang sudah ada lima. Itu pun ditambah dengan SMP Muhamadiyah, SMP NU Shafiyah, SMP Plus Al Hidayah, SMP Wahid Hasyim, SMP Roudlotussalam, dan SMPLB PGRI. Jajaran sekolah yang semuanya berbiaya rendah, seperti Sekolah Negeri. Begitu juga siswa SD-nya, yang kini menyebar di Sekolah Negeri di banyak desa dan dusun.
Dengan moncernya Sekolah Negeri – “senjata makan tuan” – sekolah swasta seperti SMP Katolik Bakti yang dulu berperan sebagai “penampung siswa”, menjadi tidak populer. Bahkan tidak laku. Ihwal ketidak populeran tersebut Anda bisa fahami lewat jumlah siswa SMP ini sekarang.

Foto suasana Dies Natalis SMP 1 Negeri Rogojampi. (Sumber: Dokumentasi Agus Dermawan T.)
Pada tahun ajaran 2024, peserta didik SMP Katolik Bakti Rogojampi hanya 24 siswa, dengan diasuh lima guru. Siswa lelaki berjumlah 13, dan yang perempuan 11. Jumlah secuil itu tentu terbagi dalam tiga kelas. Yakni kelas 7 dengan delapan siswa, kelas 8 dengan sembilan siswa, dan kelas 9 dengan tujuh siswa. Sangat sedikit! Bandingkan dengan enam dekade lalu sampai sebelum tahun 2000, yang dalam setiap tahun mengasuh sekitar 80-90 siswa.

Siswa SMP Katolik Bakti Rogojampi sedang beraktivitas olahraga karate. (Sumber: Dokumentasi Agus Dermawan T.)

Sekolah SD dan SMP Katolik Bakti Rogojampi sekarang, yang memiliki kelengkapan fasilitas ajar, seperti laboratorium. (Sumber: Dokumentasi Agus Dermawan T.)
Tapi apa pun yang terjadi, sungguh, SMP Katolik Bakti Rogojampi tak pernah berkecil hati. Apalagi setelah melihat kenyataan betapa Sekolah Negeri di desa-desa dan dusun-dusun yang dulu sangat diperjuangkan dan didorong untuk didirikan, kini tumbuh subur, bahkan beberapa jadi primadona, atau sekolah unggulan.

Aktivitas kesenian SMP Negeri 3 Rogojampi. (Sumber: Dokumentasi Agus Dermawan T.)
Maka sungguh sayang apabila keprimadonaan dan keunggulan ini dinodai berbagai kasus manipulasi domisili, zonasi, suap, pemerasan, gratifikasi dan seterusnya, seperti yang dilakukan Sekolah Negeri di berbagai kota. ***
*Agus Dermawan T. Penulis buku-buku budaya dan seni. Siswa SMP Katolik Bakti Rogojampi 1965 -1967.