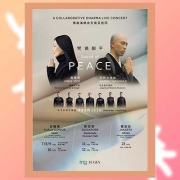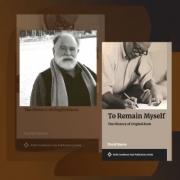Rumah Puisi Adalah Hati
Oleh Gus Nas Jogya*
Di sebuah kota bernama Partitur Rindu, segalanya adalah bunyi, namun tanpa makna. Jalan-jalan terbuat dari bisikan yang kosong, bangunan-bangunan berdiri dari teriakan yang hampa, dan manusia saling berbicara dengan frasa yang sudah aus, diucapkan bukan untuk menyampaikan, melainkan untuk mengisi kehampaan di antara mereka. Di kota ini, puisi telah mati, dikubur di bawah lapisan rutinitas yang membosankan. Namun, ada sebuah proverb kuno yang masih dikutip dengan nada misteri: “Rumah Puisi adalah Hati. Maka, berhati-hatilah dalam Berpuisi.”
Kalam adalah nama seorang penjaga perpustakaan di kota itu, seorang penyaksi dari kealpaan. Namun, tidak seperti orang lain, Kalam tidak kosong hatinya. Di dalam dadanya, bersemayam sebuah rumah yang sebenarnya, rumah yang terbuat dari jiwa, rumah yang ia sebut Rumah Puisi. Ia adalah satu-satunya yang mengetahui keberadaan rumah ini, sebuah rahasia yang begitu berat untuk dipikul. Rumah itu bukanlah sebuah bangunan fisik, melainkan sebuah lanskap metafisik, sebuah semesta miniatur di dalam dirinya. Masing-masing ruangan rumah ini berkorespondensi dengan sebuah emosi, sebuah memori, sebuah keinginan. Ia hidup dalam ketakutan konstan akan kekuatan yang terpendam di dalamnya.
Rumah Puisi di dalam hati Kalam adalah sebuah koleksi surreal yang tidak terduga. Ada sebuah ruang tamannya, namun bunga-bunga yang tumbuh di sana terbuat dari kesepian yang mengering. Daunnya terukir dengan huruf-huruf yang tak terbaca, sebuah puisi yang terlalu pribadi untuk diucapkan. Di seberang ruang taman, ada sebuah dapur di mana api tidak pernah menyala, namun selalu ada aroma dari masakan yang tidak pernah dimasak, aroma dari cinta yang tidak terbalas. Dindingnya tertutup oleh kertas-kertas resep yang kosong.
Paling menakutkan adalah dua ruangan di sisi lain rumah. Yang satu adalah ruang tidur, namun ranjangnya terbuat dari kekecewaan yang mengeras, dan di atas bantalnya, tergeletak mimpi-mimpi yang telah mati sebelum sempat terlahir. Yang satu lagi adalah ruang baca, namun buku-buku di sana semuanya kosong, terbuat dari janji-janji yang tak terpenuhi. Kalam selalu berhati-hati ketika ia berjalan melalui rumah ini. Setiap langkahnya adalah sebuah negosiasi yang halus dengan jiwanya sendiri. Ia tidak berani mengucapkan sebuah kalimat penuh yang terlalu otentik, karena ia tahu betapa rapuhnya rumah ini.
Filosofi di balik Rumah Puisi ini adalah sebuah kontradiksi abadi: bahwa keindahan terlahir dari kerapuhan, bahwa makna tercipta dari kekosongan. Kalam mengerti ini. Ia hidup dengan sangat minimalis, baik di dunia nyata maupun di dalam hatinya. Ia berbicara dalam frasa-frasa pendek, menulis sebaris kalimat tanpa emosi di atas kertas kosong. Ia adalah seorang penyair yang tidak pernah berani berpuisi, sebuah rumah yang memilih untuk tetap sepi.
Suatu siang, saat Kalam sedang menata buku di perpustakaan, ia melihat sebuah pemandangan yang tak terduga. Seorang anak kecil yang duduk di sudut ruangan, menggambar sesuatu di atas kertas. Gambar itu begitu sederhana, namun begitu penuh dengan makna. Sebuah matahari yang terbuat dari api, seekor burung yang terbuat dari air, dan sebuah tanah yang terbuat dari kata-kata yang tulus. Anak itu tidak mengetahui proverb tentang puisi dan hati, ia hanya menggambar dengan segenap jiwanya.
Melihat gambar itu, sesuatu di dalam hati Kalam pecah. Bukan seperti pecahnya kaca, melainkan seperti pecahnya sebuah sumur yang telah lama kering. Gelombang emosi mengalir, mengisi ruangan-ruangan yang telah lama kosong di Rumah Puisinya. Aroma masakan dari dapur tiba-tiba menjadi begitu nyata, bunga-bunga kesepian di taman mulai bergetar, dan buku-buku di ruang baca mulai terisi dengan kata-kata yang mengalir tanpa henti. Kalam merasa pusing, seolah-olah seluruh dunia di dalam dirinya berputar dengan cepat.
Ia memegang dadanya, merasakan denyut jantungnya yang begitu kencang. Ia tahu ini adalah saatnya. Rumah Puisi menuntut untuk diekspresikan. Bukan sekadar bisikan, bukan sekadar baris kosong, tapi sebuah puisi yang lengkap, sebuah puisi yang terbuat dari darah dan air mata. Tangannya terasa dingin, namun otaknya terasa panas. Ia mencoba untuk menulis sebuah baris, namun tangannya mengkhianatinya. Ia menulis bukan dengan kesadaran, melainkan dengan getaran jiwanya. Kata-kata mengalir dari ujung penanya seperti sebuah air bah, sebuah puisi yang panjang, yang penuh dengan citra yang surreal dan absurd.
Ia menulis tentang matahari yang menangis, tentang burung yang tidak bisa terbang, tentang rumah yang takut pada penghuninya. Itu adalah puisi tentang dirinya, tentang Kota Bunyi Gema, tentang manusia yang terjebak dalam kehampaan. Ia menulis dengan cepat, tanpa henti, tanpa pemikiran. Ia menulis bukan sebagai penulis, tapi sebagai saksi. Ia adalah saluran dari sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri.
Sesaat setelah ia selesai, dunia di sekitarnya mulai bergetar. Sebuah gedung di seberang jalan mulai menghilang, bukan runtuh, melainkan menjadi transparan, seperti bayangan yang memudar. Angin bertiup, membawa bau kopi yang tidak ada, bau dari kenangan yang hilang. Di dalam ruangan perpustakaan, buku-buku mulai terbuka sendiri, dan kata-kata di dalamnya mulai terukir dengan cahaya yang memudar, sebuah bahasa yang telah lama dilupakan. Kekacauan ini adalah refleksi langsung dari puisinya. Setiap baris puisinya adalah sebuah perintah kepada realitas, sebuah mantra yang mengubah dunia.
Puisinya adalah sebuah pengkhianatan terhadap kemapanan. Ia mengungkapkan semua yang tidak terucap, semua yang tersembunyi, semua yang mati. Tiba-tiba, Kota Bunyi Gema bukan lagi sebuah kota yang penuh dengan bunyi tanpa makna. Ia adalah sebuah kota yang penuh dengan makna tanpa bunyi, sebuah kota yang telah terbuka tabirnya. Orang-orang di jalanan mulai berhenti berbicara, mereka hanya berdiri di sana, menangis tanpa suara, sebuah pengakuan terhadap kekosongan diri mereka selama ini.
Kalam terkejut. Ia telah mengerti sepenuhnya makna dari proverb kuno itu. “Berhati-hatilah dalam Berpuisi” bukanlah sebuah larangan, melainkan sebuah peringatan akan konsekuensi. Puisi sejati tidak dapat diciptakan tanpa risiko. Ia adalah sebuah tindakan radikal, sebuah pemberontakan yang dapat menghancurkan dirimu dan dunia di sekitarmu. Ia membuatmu bertanggung jawab atas seluruh eksistensimu, atas setiap emosi yang kau rasakan, atas setiap keinginan yang kau pendam.
Kalam melarikan diri dari perpustakaan, dari puisinya sendiri. Ia berlari ke luar kota, meninggalkan kekacauan yang telah ia ciptakan. Namun, ia tidak bisa melarikan diri dari Rumah Puisi di dalam hatinya. Rumah itu telah terbuka penuh, sebuah samudra emosi mengalir di dalam dirinya. Ia merasa sakit, merasa terlalu penuh dengan kebenaran. Ia telah menjadi sebuah paradoks yang hidup, sebuah jiwa yang menemukan makna di tengah kekacauan yang ia ciptakan sendiri.
Di pinggir kota, ia menemukan seorang tua buta yang duduk di bawah pohon yang tumbuh dari kerapuhan. Pria tua itu adalah seorang penyair legendaris yang telah lama menghilang. Matanya buta, namun hatinya begitu terang, begitu penuh dengan puisi. Ia berbicara tanpa suara, melalui getaran hati.
“Kau takut,” bisik penyair itu. “Kau telah membiarkan Rumah Puisimu berbicara, dan sekarang kau takut akan kekuatannya.”
Kalam menangis tanpa suara, air matanya terbuat dari frasa yang pecah.
Penyair itu melanjutkan, “Berhati-hati bukanlah tentang menghindari bahaya, tetapi tentang menguasai bahaya itu. Hati bukanlah sebuah tempat yang aman, melainkan sebuah tempat yang suci. Puisi sejati tidak dapat diciptakan dari tempat yang aman. Ia tercipta dari api dan kerapuhan, dari keberanianuntukmenghadapi dirimu sendiri seutuhnya`.”
Kalam terdiam. Ia memahami semuanya. Ia berhenti melarikan diri. Ia duduk di samping penyair itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menjadi penghuni yang berani di Rumah Puisinya. Ia membiarkan badai emosi berlalu, ia membiarkan gelombang kata mengalir. Ia menjadi satu dengan Rumah itu, satu dengan puisinya. Ia bukan lagi seorang penulis, ia adalah sebuah puisi yang berjalan, sebuah bukti bahwa kebenaran terdalam kita adalah hal yang paling indah dan paling berbahaya yang kita miliki.
—–
*Gus Nas Jogya, Budayawan.