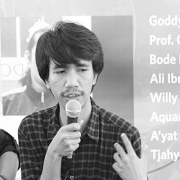Romo Kirjito
Oleh Riwanto Tirtosudarmo
Buku bersampul warna agak keungu-nguan itu sudah lecek. Bekas lipatan disana-sini membekas jelas di sampul depan-nya. Nampaknya, buku itu sudah lama dibaca berkali-kali. Ada beberapa catatan dan coretan kecil di beberapa halamannya. Tidak tahu pasti apa alasannya, buku yang sudah kelihatan lecek itu diberikan kepada saya oleh Romo Kirjito.
Buku itu berjudul “Sastra dan Religiositas”, diterbitkan oleh Penerbit Kanisius pada tahun 1988. Sebelumnya buku yang mendapatkan penghargaan Hadiah Pertama dari Dewan Kesenian Jakarta ini pertama kali diterbitkan oleh Penerbit Sinar Harapan pada tahun 1982. Mungkin, Romo Kir, begitu beliau biasa dipanggil, memberikan buku kumpulan tulisan Romo YB Mangunwijaya itu karena merasa bahwa dari obrolan-obrolan singkat dengan saya sebelumnya, melihat ketertarikan saya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan agama dan relijiusitas. Mungkin juga Romo Kirjito berpikir daripada sulit-sulit menjelaskan kepada saya soal-soal pelik itu lebih baik kalau saya langsung saja membaca buku Romo Mangun itu yang menurutnya sangat bagus untuk menjelaskan soal relijiusitas yang menjadi perhatian saya itu.
Dalam sebuah esai yang saya tulis beberapa waktu lalu tentang Mas Sitras Anjilin yang saat ini memimpin padepokan Tjipto Budojo, saya menyebut nama Romo Kirjito yang saya katakan dalam esai itu sebagai pastur Jesuit. Beberapa teman yang membaca esai itu mengatakan bahwa Romo Kirjito bukan dari Ordo Jesuit tapi dari Ordo Projo, seperti Romo YB Mangunwijaya. Maka dengan esai ini saya ingin mengoreksi kekeliruan saya itu sekaligus memohon maaf kepada Romo Kir atas kecerobohan saya tersebut.

Gambar 1: Romo Kirjito, koleksi foto pribadi.
Tapi memang harus saya akui bahwa pengetahuan saya tentang kepasturan dan kekatolikan nol besar. Saya tidak tahu tentang ordo-ordo itu apalagi membedakannya satu dengan lainnya. Setahu saya kebanyakan romo-romo Jawa yang saya kenal ada SJ dibelakangnya. Memang, jika saya sedikit mengenal Romo Kir melalui pertemuan dan diskusi-diskusi pendek dengan beliau sama sekali tidak terpikir dalam benak saya sedang berdiskusi dengan seorang Romo tapi bagi saya seperti berdiskusi dengan seorang intelektual atau aktifis lingkungan saja.
Mungkin bagi seorang romo dari Ordo Projo, seperti Romo Kir dan Romo Mangunwijaya, kiprahnya dalam masyarakat diwujudkan dalam praxis yang langsung berada ditengah masyarakat, agak mirip memang dengan praxis yang dilakukan oleh para aktifis LSM. Ketika itu Romo Kir misalnya terlibat langsung dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh warga desa di lereng Merapi yang berusaha mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan pasir.
Tapi Romo Kir juga dikenal sebagai romo yang berani menyelenggarakan prosesi perayaan paskah dengan menggunakan atribut-atribut yang ada di umumnya masyarakat desa Jawa. Semacam pribumisasi paskah. Belakangan, apalagi setelah tidak lagi aktif sebagai romo yang memimpin sebuah paroki, semacam purna tugas bagi para profesor di universitas, Romo Kir kemudian menggeluti kegiatan yang berkaitan dengan satu kebutuhan pokok dari mahluk hidup yaitu air.
Melalui sebuah teknologi sederhana yang berkaitan dengan kelistrikan, Romo Kir membuat air hujan menjadi air yang tidak saja layak dikonsumsi tanpa dimasak, tetapi juga menjadikan air hujan itu, dalam istilah saya sebagai air kesehatan. Baik dari Romo Kir sendiri maupun “murid” Romo Kir, Mas Bambang AW, teman baik saya yang memiliki Galeri Dialektika, di Jl. Sumbing, Malang; khasiat air kesehatan itu dalam menyembuhkan penyakit, sudah terbukti.
Di tempat kediamannya sekarang, di sebuah komplek Katolik di Muntilan, Romo Kir seperti memiliki sebuah laboratorium sekaligus perusahaan air minum kecil. Di tempat itu dengan peralatan yang cukup besar, Romo Kir memproduksi air kesehatan yang saya lihat bisa dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya secara gratis. Saat saya bertandang ke kediaman Romo Kir ada saja orang yang datang meminta air kesehatan itu. Saya sendiri selalu dihadiahi berbotol-botol air kesehatan itu ketika pamit pulang. Rasanya segar dan kerongkongan terasa bersih setelah dialiri air kesehatan itu.
Tidak mudah mencari waktu yang senggang untuk berdiskusi dengan Romo Kir karena para tamunya datang silih berganti dengan berbagai agendanya masing-masing. Dalam hal ini saya kira penilaian saya bahwa Romo Kir pada dasarnya seorang intelektual tidaklah keliru. Dengan cara dan gayanya sendiri Romo Kir terus memikirkan dan terlibat dalam upaya-upaya untuk mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan, seperti warga desa pada umumnya.
Meskipun memilih jalan yang tidak sekontroversial Romo Mangun misalnya, Romo Kir jelas melakukan kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Konon sempat ada kabar bahwa perusahaan air kemasan merasa terancam dengan upaya Romo Kir mempopulerkan proses pembuatan air hujan menjadi air minum gratis dan menyehatkan itu.
Kekhawatiran semacam ini sesungguhnya tidak mengherankan. Melimpahnya air hujan di Indonesia kecuali di beberapa tempat di Indonesia bagian timur melalui teknik sederhana yang ditemukan Romo Kir sebetulnya bisa dipraktekkan oleh banyak orang dengan biaya yang murah. Romo Kir juga tidak segan membagikan alatnya yang sederhana itu kepada siapa saja yang mau mempraktekkan sendiri temuannya itu.
Ketika kebutuhan pokok mahluk hidup seperti air telah menjadi komoditas yang diperjual belikan dengan harga yang bagi sebagian besar anggota masyarakat cukup mahal, teknologi pembuatan air minum dari air hujan adalah sebuah terobosan cerdas dan kreatif yang bisa menyelamatkan warga masyarakat dari keterpaksaan harus membeli air. Ketika tanah dan air di negeri yang sesungguhnya indah dan damai ini telah menjadi barang dagangan, masihkah kita memiliki tanah-air?
Ketertarikan saya untuk mendengarkan lebih lanjut tentang air ini sesungguhnya dipicu oleh sebuah pembicaraan yang terputus antara saya dengan Romo Kirjito. Dalam pertemuan yang terakhir di kediamannya di Muntilan, sambil makan nasi goreng yang sering dia pesan dari sebuah warung langganannya, Romo Kir mengungkap sedikit makna air secara relijius. Samar-samar saya menangkap air sebagai pengejawantahan dari yang ilahi. Sebagai orang yang baru mulai belajar menjalani hidup dalam jalur spiritual saya sungguh tergelitik untuk mencari lebih jauh apa sebetulnya yang dipikirkan dan direnungkan oleh Romo Kirjito tentang air.
Bagi yang mengetahui dunia pewayangan ada yang disebut sebagai Air Perwitasari, atau air kehidupan. Alikash, Bima, nama lain dari Bratasena atau Werkudara; adalah tokoh yang disuruh oleh Durna, guru yang sebenarnya ingin mencelakakannya, untuk mencari Air Perwitasari yang terletak di dasar samudra. Saat itulah, di dasar samudra, Bima bertemu dengan Dewa Ruci, yang bentuknya mirip dengan dirinya hanya sangat kecil. Dalam kisah itu Dewa Ruci mengajarkan bahwa apa yang sedang dicari itu ada di dalam diri Bima sendiri.
Dewa Ruci meminta Bima yang bertubuh tinggi besar itu masuk ke lubang telinga Dewa Ruci. Sesuatu yang mustahil tetapi terjadi, Bima menelusup melalui lubang telinga masuk kedalam tubuh Dewa Ruci, disitulah saya kira metafora Air Perwitasari atau air kehidupan menemukan maknanya. Manunggaling Kawulo lan Gusti, bersatunya manusia dengan sang khalik, sang maha kuasa, sang moho suci, sang moho agung, penciptanya. Inilah mungkin inti relijiusitas dari keseluruhan ajaran spiritual Jawa yang secara populer dikenal sebagai Kejawen.

Gambar 2: Suasana tempat tinggal sekaligus laboratorium air Romo Kirjito di Muntilan, koleksi foto pribadi.
Saya kembali membolak balik buku yang sudah agak lusuh berisi kumpulan tulisan Romo Mangunwijaya itu. Saya percaya Romo Kirjito memberikan buku itu dengan maksud tertentu. Di buku itu saya menyaksikan Romo Mangunwijaya, seorang pastur Katolik Jawa melalui pengetahuan keagamaannya yang mendalam, menelisik karya-karya sastra, terutama novel dan cerpen, dari berbagai belahan dunia terutama barat tetapi juga timur tengah dan Indonesia sendiri, dalama bahasa asli yang dikuasainya, Jerman, Perancis dan Inggris berusaha menemukan apa makna relijiusitas itu. Relijiusitas ini jelas bukan agama, meskipun merupakan elemen spiritualitas dan bisa menjadi nilai tertinggi dari agama, agama apapun. Karena dalam relijiusitas itulah manusia menemukan makna spiritualitas dari kemanusiaannya yang hakiki, sesuatu yang membebaskan bukan yang terbelenggu oleh hal-hal yang bersifat lahiriah dan serba wadag. Esai ini adalah tentang Romo Kirjito, bukan tentang Romo Mangun, yang saya berjanji akan menuliskannya dalam esai tersendiri nanti.
Membaca buku Romo Mangun ini saya bersyukur dan berterimakasih pada Romo Kirjito yang telah memberikannya kepada saya. Saya seperti mendapatkan peneguhan dari apa yang selama ini saya yakini. Melalui Romo Mangun yang telah menjelajah sastra barat, maupun sastra Indonesia sendiri; saya kira sebagai orang Jawa diapun mendapatkan peneguhan tentang apa yang selama ini dia yakini sebagai inti ajaran spiritual Jawa, Manunggaling Kawulo lan Gusti. Sebuah enigma yang menjadi pusat perhatian sekaligus keresahan seorang Romo Belanda yang kemudian memutuskan menekuni bahasa dan sastra Jawa karena tanpa kemampuan membaca bahasa Jawa tidak mungkin memahami sastra yang memuat ajaran Jawa yang sangat penting itu.
Romo Zoetmulder, seorang Romo Jesuit, yang kemudian memilih menjadi warganegara Indonesia, boleh dikatakan telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memahami inti spiritualitas Jawa. Beliau selama bertahun-tahun kemudian membuat kamus bahasa Jawa-Inggris. Sebelumya Romo Zoetmulder menuliskannya sebagai disertasi doktornya di Universitas Leiden. Disertasi doktor Romo Zoetmulder ini kemudian diterjemahkan Romo Dick Hartoko, romo Jesuit yang lain, dengan judul: Manunggaling Kawulo-Gusti: Panteisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa (Gramedia, 1990).
Kepada Romo Kirjito, sekali lagi saya ingin mengucapkan terimakasih atas persahabatan yang dibukakan kepada saya dan saya masih harus mencari waktunya untuk melanjutkan perbincangan tentang air yang belum tuntas ini.
Kampung Limasan Tonjong, 7 Maret 2023
*Riwanto Tirtosudarmo adalah peneliti