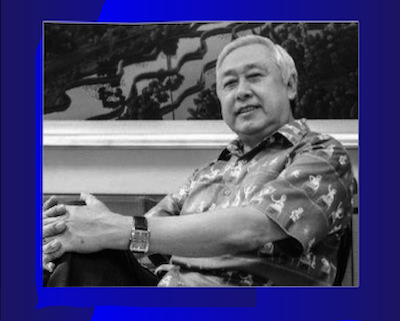Roman Asisten Rumah Tangga : Cenderamata dari Dusun Kunir
Oleh Agus Dermawan T.
Setiap menjelang hari raya seperti Idul Fitri, banyak orang membicarakan ART (Asisten Rumah Tangga). Dan setiap muncul pembicaraan mengenai ART saya selalu terkenang Tini. Dia adalah perempuan yang bekerja di rumah Ibu selama lebih dari 25 tahun. Sikapnya yang seperti anggota keluarga ada dalam ingatan. Kesetiaannya yang unik senantiasa tersimpan dalam kenangan.
Suatu ketika Ayah berselisih dengan rekan kerjanya, Ruut Rijken. Tini membela Ayah dengan sebentar-sebentar menyanyikan lagu penyemangat yang melodinya meminjam “Keroncong Sapu Lidi” : Waterpokken, si cacar aer… Maminya Rijken… Papinya Rijken ikanlah mujaer... Selantun dendang “militan” yang meledek keluarga Ruut Rijken sebagai ikan bermulut besar.
Kala menjelang tua Tini pulang ke Lasem untuk hidup bersama anaknya. Tapi ia balik lagi ke rumah Ibu dan berdiam sampai akhir hayatnya. Tini dimakamkan dengan khidmat oleh keluarga kami.
ART di zaman yang berubah
Tahun berganti, zaman berubah, jagad asisten rumah tangga tidak lagi sama. Namun meski berubah, isteri dan saya tetap memposisikan ART sebagai teman yang setara. Termasuk anak dan menantu saya, yang mengkursuskan bahasa Inggris ART-nya yang masih remaja, Nor dan Tri.
Dalam 44 tahun berumah tangga, isteri saya telah ditemani oleh banyak ART. Biasanya mereka bekerja dalam duet. Hampir semuanya rukun, jujur, baik dan bahkan sangat baik. Ada yang bekerja 14 tahun. Ada yang 5 tahun. Tapi ada yang hanya di bawah 3 tahun.
Di rumah kami mereka bekerja sesuai dengan tugas dan kemampuannya. Di luar gaji yang standar-standar saja, mereka kami senangkan dengan wajar dan apa adanya. Meski rumah tidak besar, mereka kami usahakan punya “living room” sendiri, televisi sendiri, dengan pintu keluar-masuk sendiri. Dalam beberapa minggu sekali mereka kami ajak bertamasya kuliner, mencoba rasa makanan warung-warung baru. Tentu saja saya sopirnya. Sekali-sekali ke pasar malam atau nonton film. Jangan lupa, para ART juga mengidolakan Nicolas Saputra! Kami mengapresiasi ART yang setiap pagi semaunya menghias rumah dengan bunga-bunga gugur yang mereka pungut dari taman. Seperti yang dilakukan Mila dan Iyai setahun ini.
Tapi di sela-sela ART yang menyenangkan, ada pula yang membuat kami kecewa. Suatu kali ada perempuan yang memohon-mohon minta jadi ART, sambil mengaku bahwa ia adalah sahabat ART kami yang dulu. Lantaran terlihat sangat ingin bekerja, dia kami terima. Tapi seminggu kemudian ia menghilang sambil menggondol sesuatu. Beberapa belas tahun lalu ada yang kesurupan asmara sehingga tabungan uang gajinya mengalir ke lelaki bergajul yang entah dari mana datangnya. Ia pun menangis menderu-deru.
Ada pula ART yang mendadak pamit dengan alasan klasik : ibunya sakit. Ternyata ia hanya dipindahkan ke majikan lain yang mengiming-imingi gaji sedikit lebih besar. Yang memindahkan adalah “pacar” baru, yang tak lain adalah “household servant scouting” alias calo ART pemetik komisi. Ada juga yang mengaku sekadar mudik (Jawa : mulih disik, pulang untuk segera balik lagi). Namun mudiknya diteruskan selamanya. Bahkan ada ART yang bilang ayahnya meninggal mendadak. Beberapa hari kemudian beredar foto di gawai para temannya : ia berdiri di depan rumah bersama Ayahnya yang ”meninggal” itu.
Berkunjung ke kampung
Tapi setitik dua titik kekecutan itu sama sekali tidak mengurangi penghargaan kami kepada para ART yang pernah bekerja baik di rumah. Dulu sebelum ada gawai, para alumni ART kadang menulis surat kepada isteri saya untuk sekadar berkabar. Ketika gawai menjadi alat komunikasi, dan WhatsApp jadi sarana jumpa bicara dan rupa, sejumlah alumni ART juga berunjuk-ria.
Kebaikan para ART itu menyebabkan isteri saya berhasrat mengunjungi mereka di kampung. Dan saya tentu saja ikut, sekalian tamasya.

Sebelum masuk ke Dusun Kunir, banyak pemandangan indah di Gumelem Kulon.
Maka pada tengah 1995 kami ke rumah Sugini di dusun Alas Tengah, Desa Sukodono, Sragen. Sesuai dengan nama tempatnya : “hutan bagian tengah”, kampung itu nun jauh dari kota. Kami melewati jalan desa belasan kilometer. Kemudian mobil harus diparkir di pinggir kali, dan dilanjutkan dengan jalan kaki di area ladang. Kami pun disambut di rumahnya yang masih beralas tanah, di dekat sawah. Ketika kami menyeruput teh manis hangat yang disuguhkan, dalam gelap rumah terdengar suara sapi melenguh. Sugini tertawa. “Itu sapi saya, Bapak. Hasil tabungan dari gaji yang diberikan Ibu.” Jawaban itu menyenangkan isteri saya. Tapi saya lebih tertarik kepada kenyataan : ada sapi yang dipersilakan berdiam di dalam rumah!

Untuk menuju Dusun Kunir, Gumelem Kulon, harus melewati jalan kecil berliku-liku dan menyusup hutan. Sebagian jalan lumayan bagus seperti terlihat dalam foto (19 Februari 2023). Tapi sebagian lain jalanannya buruk dan berbahaya.
Pada waktu yang lain kami mengunjungi Nenti, di pedalaman Leuwiliang, Bogor. Dalam pertemuan yang gembira itu kami diperkenalkan kepada segenap keluarganya, juga kepada pamannya, yang ternyata seorang pengrajin biola. Saya agak terkejut. Di kampung begini ada pengrajin biola! Untuk mengapresiasi, saya beli satu biola. “Biola Nenti” itu – yang lebih bernilai dibanding “Biola Stradivarius” – sampai sekarang masih tersimpan di rumah, dan sekali-sekali digesek kedua cucu saya.
Ketika memasuki dekade ke dua abad 21, beberapa ART saya ada yang lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Ada yang jurusan fikih (fiqh). Ada pula yang jurusan boga. Lia, ART yang lulusan jurusan multi media di Bogor, sering membantu saya dalam urusan zoom meeting di kala pandemi.
Setelah melakukan sejumlah kunjungan sejak 30 tahun lalu, pada Februari 2023 kami bertandang ke kediaman Simi, Nurhasanah dan Laeli. Mereka mantan para ART kami yang kebetulan dari satu kampung : Dusun Kunir, Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam banyak percakapan mereka mengatakan bahwa rumahnya di Gumelem gampang dicapai, dan pemandangannya indah. “Saya mengundang Ibu dan Bapak ke sini. Nanti kita bersama menikmati kelapa muda,” tulis salah satunya lewat WA.
Minat kami datang ke Gumelem semakin terdorong oleh foto-foto mereka. Laeli yang menikah dengan mengenakan busana pengantin gemerlap, serta Nurhasanah yang sumringah dalam upacara meriah. Juga Simi yang bahagia dengan tiga anak hasil pernikahannya dengan tukang ojek pengkolan di Kelapa Gading. Kami pun berangkat, dengan mengambil Banjarnegara sebagai kota persinggahan.
Gumelem Kulon ternyata sungguh tidak mudah dijangkau oleh kami yang sudah terlanjur berurat orang kota. Lantaran desa itu ternyata berjarak 25 kilometer dari Banjarnegara. Lalu untuk menuju Dusun Kunir mobil harus melalui jalan hutan berkelok-kelok mendaki dan menukik, sekitar 7 kilometer. Jalannya kecil, dengan salah satu sisinya lereng yang dalam, yang harus saya sebut sebagai jurang. Sesampai di satu persimpangan mobil saya berhenti, karena jalannya menurun sampai sekitar 60 derajat. Kami pun jalan kaki. Di dusun berhutan itulah anak-anak kami berumah-rumah, dengan tempat tinggal yang dipisahkan rimbun pepohonan. Saat menyambut kami mereka menggendong anak balitanya masing-masing.
“Kalian anak-anak hebat. Dari dusun seperti ini kalian berani sendirian atau berdua menuju Jakarta, mencari kerja. Kami kagum.”
“Kami juga kagum, Ibu dan Bapak bisa sampai ke sini. Seperti mimpi!” kata Simi, yang kadang bekerja sebagai ART infal di kala hari raya.
Mereka sepertinya tidak perduli bahwa ketika kami ke sana, para elit politik di Jakarta sedang debat soal RUU PPRT (Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). Para ART sadar bahwa masalah ART ujungnya kembali kepada nilai hubungan privat antara majikan dan pekerja. Tapi para ART tahu benar bahwa kaum elit pembuat undang-undang itu tak pernah menyentuh kampung, rumah, hutan, serta pikiran dan perasaan ART yang mereka undang-undangkan. Sehingga UU PPRT tidak terlampau diprioritaskan, dan penetapannya molor sampai kapan-kapan. Padahal problem perampasan hak manusia yang satu oleh manusia lain, exploitation de l’homme par l’homme versi majikan terhadap para ART, terus terjadi tanpa pernah henti.

Demo para asisten rumah tangga sambil membentangkan serbet raksasa. Serbet adalah lambang ART. (Foto : Antara).
Di rumah yang sederhana kami disambut dengan sukacita. Cimplung (kelapa setengah muda terbalut gula aren) yang merupakan penganan khas Gumelem, disuguhkan. Ketika pulang kami disangoni sekantung besar gula kelapa. Juga beberapa plastik keripik bikinan mereka sendiri. Mereka lantas mengantar kami di tepian jalan yang mulai dihiasi rintik hujan. Mereka lalu ramai-ramai melambaikan tangan.

Cimplung kelapa, penganan gurih manis kebanggaan para ART dari Desa Gumelem. Daging kelapa dibalut gula aren.

Setelah menyambut kami dengan hangat, para mantan ART dari Dusun Kunir, Desa Gumelem Kulon, melepas kami untuk pulang.
Saat mobil kami sudah berada di dekat hotel di Kota Banjarnegara, ada yang mengirimkan WA di gawai. “Ibu dan Bapak… sekarang sudah sampai di mana? Aman ya. Di sini hujan deras!”
Ah, anak-anak baik itu selalu mendoakan kami. Kapan saja dan di mana saja! Sementara pihak nyonya dan tuan hanya mengingat mereka sekali-sekali saja, ketika sangat membutuhkan tenaganya.
Saya pun teringat ucapan Sudjojono kala seniman besar ini memaknai lukisannya tentang Rose Pandanwangi (isterinya) mencuci setumpuk pakaian di perigi. “Pembantu itu bukan tangan kiri keluarga. Bukan pula tangan kanan keluarga. Tapi tangan kiri, tangan kanan dan sekaligus dua kaki sebuah keluarga!” *

Karya pelukis besar Sudjojono tahun 1960, Rose Pandawangi sedang mencuci pakaian.
*Agus Dermawan T. Penulis Buku-buku Budaya dan Seni.