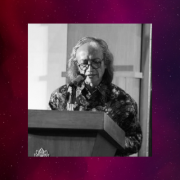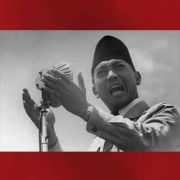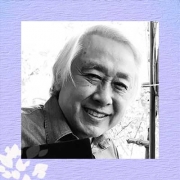Puisi dan Masa Pakai Kata
Oleh Gus Nas Jogja*
Puisi adalah pertarungan melawan waktu, dan setiap kata di dalamnya adalah upaya untuk mencapai keabadian. Di era analog, masa pakai kata diuji oleh keausan cetak dan memori kolektif; di era Literasi Digital, tantangannya jauh lebih kompleks: banalitas yang diinduksi oleh algoritma, kebisingan platform, dan kedangkalan interaksi. Kata-kata dalam bait-bait puisi itu kini hidup dalam siklus viral dan usang yang dipercepat. Mempertajam kajian tentang Puisi dan Masa Pakai Kata memerlukan elaborasi kritis yang mengintegrasikan Epistemologi, Silogisme, dan Linguistik dengan realitas digital.
Epistemologi Digital: Pengalaman Kata di Tengah Banjir Informasi
Epistemologi digital mengkaji bagaimana pengetahuan dihasilkan dan dikonsumsi di ruang daring. Kata dalam puisi harus berjuang melawan dua musuh epistemologis utama di internet: kecepatan skena dan volatilitas konteks.
Di ruang digital, pembaca didorong untuk melakukan scanning (pemindaian cepat) daripada close reading (membaca mendalam). Pengetahuan yang dihargai adalah yang instan, ringkas, dan mudah dibagikan.
Kata-kata yang sarat makna, kaya metafora, dan membutuhkan kontemplasi (seperti yang ada dalam puisi) memiliki masa pakai yang sangat singkat dalam feed media sosial. Mereka gagal memenuhi algoritma efisiensi yang menuntut immediate gratification (kepuasan segera).
Puisi digital yang berhasil justru menggunakan linguistiknya yang padat untuk mengganggu ritme scanning. Penyair harus menyuntikkan kerumitan epistemologis yang cukup untuk memaksa jeda. Puisi digital yang memperpanjang masa pakai kata adalah yang mampu menciptakan ‘lubang hitam’ makna di tengah arus, memaksa pembaca untuk berhenti dan menyelam. Inilah yang saya namakan “jihad epistemologis” puisi di era digital.
Dalam tradisi dokumentasi puisi (seperti yang dicontohkan HB. Jassin), epistemologi teks menuntut sanad—otentisitas dan mata rantai periwayatan pengetahuan. Di ruang digital, sanad sering kali terputus; kutipan dimutilasi, konteks ditiadakan, dan atribusi dikaburkan.
Puisi yang ditulis dengan kesadaran digital harus menguasai seni otentisitas visual-tekstual. Penyair harus menggunakan fitur digital (format, desain, layout) untuk mempertahankan integritas kata dan makna aslinya, bahkan ketika dihadapkan pada volatilitas berbagi (share). Masa pakai kata diperpanjang ketika identitas penulis dan konteks penciptaannya berhasil dipertahankan secara digital, melawan epistemologi anonimitas dan reposting tanpa sumber.
Silogisme Digital: Logika Koherensi di Tengah Fragmentasi Narasi
Silogisme (struktur logika) dalam puisi tradisional mengandalkan koherensi citra batin yang dibangun secara berurutan. Di ruang digital, narasi didominasi oleh fragmentasi, multitasking, dan ekspresi reaktif. Silogisme puisi harus beradaptasi tanpa mengorbankan kedalaman.
Silogisme hyperlink dan kepadatan makna. Literasi digital mengajarkan otak manusia untuk berpikir dalam jaringan hyperlink—melompat dari satu ide ke ide lain. Silogisme puitis di era ini tidak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan alur linear; ia harus berfungsi sebagai titik fokus padat yang mencakup banyak tautan makna sekaligus.
Puisi yang sukses memiliki masa pakai terlama adalah yang mampu memuat premis, minor, dan kesimpulan dalam beberapa baris atau satu citra tunggal yang padat. Ini adalah silogisme implosif yang bekerja seperti kode QR makna: ringkas di permukaan, tetapi membuka semesta informasi ketika dipindai dengan perhatian.
Silogisme puisi berisiko runtuh ketika dibaca tanpa konteks (context collapse). Penyair harus membangun koherensi yang intrinsik pada kata itu sendiri, bukan pada konteks visual atau caption yang menyertainya. Kata harus “berdiri sendiri” meskipun di share di platform yang berbeda-beda.
Ruang digital sering didominasi oleh simulasi emosi (emoji, caption yang dramatis, clickbait). Silogisme puitis menawarkan logika akal-akal (genuine logic) yang membongkar kepalsuan emosi digital.
Masa pakai kata “sedih” di media sosial sangat pendek; ia hanya berfungsi sebagai tag. Puisi, melalui silogisme batiniah yang runcing, mengembalikan beban ontologis pada kata sedih, memaksa pembaca untuk mengikuti urutan logis perasaan dan pengalaman yang autentik, bukan sekadar respons cepat. Puisi memperpanjang masa pakai kata dengan menjadikannya serius di tengah gelombang trivialitas.
Linguistik Digital: Arkeologi Kata dan Ekologi Bahasa
Linguistik dalam puisi digital berfokus pada bagaimana kata berinteraksi dengan teknologi dan bagaimana ia bertahan dalam ekologi bahasa yang didominasi oleh meme, slang instan, dan hashtag.
Puisi, seperti yang diajarkan oleh prinsip defamiliarization, sering melakukan arkeologi kata—menggali kembali kata-kata kuno, kosa kata yang terpinggirkan, atau tata bahasa yang unik. Ini adalah perlawanan linguistik terhadap glosarium trending yang didorong oleh search engine optimization (SEO) dan popularitas.
Ketika penyair menggunakan kata yang tidak populer, ia sebenarnya sedang melakukan tindakan konservasi linguistik. Masa pakai kata diperpanjang karena ia dibebaskan dari lingua franca algoritma yang homogen. Puisi menjadi cagar alam linguistik di mana keragaman kata dilindungi dari kepunahan digital.
Literasi digital menuntut sinkretisme bahasa: perpaduan teks, gambar, audio, dan video. Puisi yang sukses dalam konteks ini adalah puisi yang berani melampaui batas leksikal dengan merangkul multi-moda secara cerdas.
Puisi digital yang memperpanjang masa pakai katanya adalah yang mengubah kata menjadi kode visual atau kode audio. Misalnya, penggunaan spacing yang disengaja, font yang unik, atau kolaborasi dengan medium audio (spoken word) yang memanfaatkan ritme dan intonasi.
Dalam Linguistik digital, fonem (bunyi kata) menjadi penting. Pengalaman kata kini juga melibatkan mendengar (melalui video pendek atau podcast). Penyair harus memastikan bahwa kata tidak hanya kuat di mata, tetapi juga kokoh di telinga, sehingga masa pakainya meluas melintasi kanal indera.
Puisi, Deep Reading, dan Masa Depan Keadaban
Literasi Digital mengajukan tantangan eksistensial bagi masa pakai kata. Kata-kata yang tidak memiliki kedalaman filosofis, silogisme yang runcing, dan keunikan linguistik akan dengan mudah tersapu oleh arus informasi.
Puisi adalah Benteng Literasi Mendalam (Deep Reading). Ia adalah tindakan yang melawan epistemologi kecepatan, silogisme kepalsuan, dan linguistik banalitas.
Inisiatif HB. Jassin dalam mendokumentasikan pengetahuan secara fisik (PDS) adalah refleksi dari perjuangan yang sama di era analog. Di era digital, perjuangan itu diteruskan oleh puisi: memastikan bahwa kata-kata yang membawa keadaban, keadilan, dan kebenaran spiritual memiliki masa pakai yang tak kendor-kendornya—selalu tersedia, selalu relevan, dan selalu mampu menembus kebisingan untuk membebaskan jiwa pembacanya. Ruwet!
——
*Gus Nas Jogja, Budayawan.