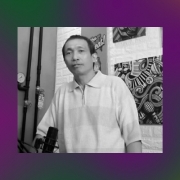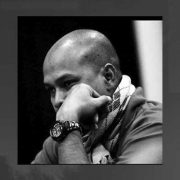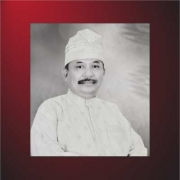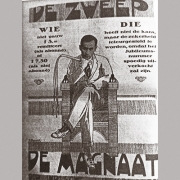Menegaskan Makna Pemajuan Kebudayaan
Oleh: Purnawan Andra*
Setelah sewindu berlalu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kini bangsa Indonesia memiliki Hari Kebudayaan yang diperingati setiap 17 Oktober.
Penetapan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 tanggal 7 Juli 2025, yang merujuk pada momen bersejarah 17 Oktober 1951—ketika Presiden Soekarno menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara Garuda Pancasila beserta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Secara simbolik, tanggal ini dimaknai sebagai peneguhan bahwa kebudayaan adalah dasar identitas bangsa, sumber nilai yang menyatukan keberagaman.
Hari Kebudayaan karenanya bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi ruang reflektifuntuk meninjau kembali bagaimana negara memahami, merawat, dan menumbuhkan kebudayaan di tengah perubahan zaman.
Ekosistem Kebudayaan
Dalam kerangka UU Pemajuan Kebudayaan, visi utama yang ditegaskan ialahpembangunan ekosistem kebudayaan. Yaitu sebuah sistem hidup yang menempatkan kebudayaan sebagai jaringan relasional antara pelaku, pranata, pengetahuan, ekspresi, serta lingkungan hidupnya.
Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa kebudayaan tidak bisa lagi diperlakukan sebagai benda mati yang dikoleksi, tetapi sebagai sistem yang terus bergerak, dinegosiasikan, dan dihidupi masyarakat. Risalah Rapat Komisi X DPR tahun 2017 menekankan bahwa undang-undang ini dihadirkan agar kebudayaan tidak lagi ditempatkan di pinggiran pembangunan nasional, melainkan menjadi fondasi etis dan intelektual bagi arah pembangunan itu sendiri.
Namun, seperti diingatkan Raymond Williams, “kebudayaan adalah medan pertarungan makna.” Dalam arti ini, politik kebudayaan selalu berada dalam tarik-menarik antara nilai dan kuasa, antara upaya pelestarian dan proyek representasi.
Bila pemahaman ini tak dihayati secara mendalam, kebijakan kebudayaan berisiko kembali pada pola lama: menonjolkan ekspresi puncak, kegiatan seremonial, dan pendataan administratiftanpa menghidupkan proses kultural yang sebenarnya. Kebudayaan akhirnya menjadi bagian dari daftar program, bukan paradigma yang menjiwai arah pembangunan.
Padahal, semangat awal UU Pemajuan Kebudayaan bukanlah administratif, melainkan paradigmatik, yaitu mengubah cara pandang negara terhadap kebudayaan. Ketika kebijakan dijalankan tanpa kesadaran reflektif, kebudayaan mudah terperangkap dalam logika pembangunanyang serba kuantitatif. Ia dinilai dari banyaknya kegiatan, bukan dari kedalaman relasi sosial yang dihasilkan. Dalam bahasa Pierre Bourdieu, kebudayaan direduksi menjadi modal simbolik—alat legitimasi dan citra, bukan proses pembentukan kesadaran.
Dalam praktiknya, banyak daerah masih menilai keberhasilan bidang kebudayaan darijumlah festival yang digelar, jumlah peserta yang hadir, atau besaran dana yang terserap. Penekanan berlebih pada hasil yang terukur ini menciptakan kesan seolah kebudayaan tengah tumbuh subur, padahal banyak pranata sosial yang menopang kehidupan budaya justru melemah. Lembaga adat kehilangan otoritasnya, sanggar-sanggar tradisi sulit bertahan tanpa dukungan berkelanjutan, dan pendidikan budaya di sekolah masih sering terpinggirkan.
Salah satu contoh ialah kebijakan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) yang dimandatkan oleh undang-undang. Gagasan ini sejatinya baik, niatnya untuk membangun basis data nasional untuk memperkuat perencanaan kebudayaan.
Namun, dalam pelaksanaannya, sistem tersebut belum sungguh menjadi “jantung ekosistem” karena masih lebih banyak berfungsi sebagai perangkat teknokratis daripada instrumen pemberdayaan budaya. Data dihimpun, tetapi belum menumbuhkan praksis; kebudayaan didaftarkan, tetapi belum dihidupi.
Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan utama kita bukan sekadar pada tataran teknis, melainkan pada cara pandang. Gayatri Spivak pernah mengingatkan bahwa representasi dari atassering kali menyingkirkan suara yang di bawah. Dalam konteks kebijakan budaya, hal itu terjadi ketika negara berbicara atas nama masyarakat adat, pelaku seni, atau komunitas budaya, tanpa memberi ruang yang cukup bagi mereka untuk menafsir dan menentukan arah kebudayaan mereka sendiri.
Meng-kebudayaan-kan Pembangunan
Dalam konteks inilah relevan untuk mengingat gagasan Nurcholish Madjid dalam Kebudayaan dan Pembangunan (1988) bahwa pembangunan sejati bukanlah memodernisasi kebudayaan, tetapi meng-kebudayaan-kan pembangunan. Artinya, kebijakan publik harus tumbuh dari nilai, etika, dan pengetahuan lokal; bukan sekadar menempelkan unsur budaya ke dalamprogram ekonomi. Dengan pandangan demikian, kebudayaan tidak lagi menjadi alat bantupembangunan, melainkan menjadi orientasi moral dan intelektual yang menuntun arahpembangunan itu sendiri.
Kini, di era pasca-pandemi yang diwarnai percepatan digitalisasi, krisis ekologi, dan ketimpangan sosial, tantangan kebudayaan menjadi semakin kompleks. Dunia berubah cepat, nilai bergeser, dan ruang-ruang hidup tradisional makin terdesak oleh logika pasar dan teknologi. Dalamsituasi ini, kebijakan kebudayaan dituntut tidak hanya melestarikan, tetapi juga mengantisipasiperubahan, menjadi ruang dialog antara masa lalu dan masa depan, antara tradisi dan inovasi.
Politik kebudayaan masa depan perlu menumbuhkan kesadaran ekosistemik: bahwakebudayaan bukan hanya urusan ekspresi, tetapi juga keberlanjutan hidup. Ia harus berakar pada komunitas, berpijak pada nilai kemanusiaan, dan terbuka terhadap perkembangan pengetahuan. Untuk itu, paradigma kelembagaan perlu diperbarui. negara berperan bukan sebagai pengaturtunggal, melainkan sebagai fasilitator yang mempertemukan jejaring antar pelaku budaya, akademisi, dan masyarakat.
Hari Kebudayaan dapat menjadi momentum penting untuk memulai pembaruan arahtersebut. Alih-alih menambah seremonial baru, peringatan ini bisa menjadi ruang dialog dan pembelajaran bersama, tentang bagaimana kebijakan dapat memberi ruang yang lebih partisipatif bagi komunitas, bagaimana SPKT dapat dirancang ulang agar interaktif, dan bagaimana pranatabudaya lokal dapat diperkuat sebagai mitra sejajar negara.
Dalam pidatonya Kebudayaan, Kebangsaan, dan Pembangunan (1951), Soekarno pernah berkata, “Kebudayaan adalah hasil perjuangan manusia untuk menundukkan alam dan dirinya sendiri.” Kalimat ini kini terasa kembali relevan. Menundukkan alam dan diri bukan berarti menguasai, melainkan memahami batas dan keseimbangan. Dalam konteks hari ini, itu adalah panggilan untuk membangun kebudayaan yang berkelanjutan, yang sadar ekologis, sosial, dan spiritual.
Maka, peringatan Hari Kebudayaan bukan hanya selebrasi, melainkan refleksi untukmenjaga kebudayaan agar tetap hidup dan menghidupi masyarakat, agar bangsa ini tidak hanyatumbuh secara material, tetapi juga matang secara kultural.
Dalam keheningan reflektif semacam itu, mungkin kita bisa memahami kembali maknapemajuan kebudayaan. Bukan sebagai proyek jangka pendek, tetapi sebagai perjalanan panjanguntuk merawat kehidupan bersama. Sebuah perjalanan di mana negara dan masyarakat berjalan bersama, bukan dalam hubungan kuasa, melainkan dalam kesadaran bersama bahwa kebudayaanadalah denyut yang membuat kita tetap menjadi manusia Indonesia.
—
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, penerima fellowship Governance & Management of Culture di Daegu Catholic University Korea Selatan.