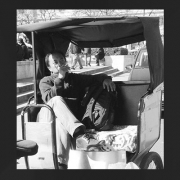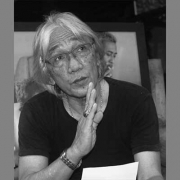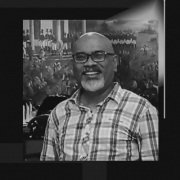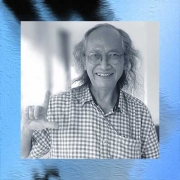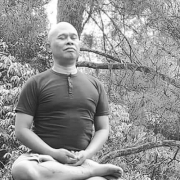Kedaulatan Narasi: Resolusi BRICS dalam Pencarian Jati Diri Sastra Indonesia
Oleh: Gus Nas Jogja*
Ketika sebuah negara anggota baru dalam aliansi geopolitik sebesar BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan anggota baru) diminta untuk mengajukan wakil sastranya, momen tersebut bukanlah sekadar proses administrasi. Ini adalah tindakan eksistensial kolektif. Panggung BRICS adalah medan di mana narasi bangsa diadu, diperbandingkan, dan diakui. Resolusi tentang Pembentukan Panitia Independen bukanlah dokumen prosedural, melainkan sebuah Manifesto Pertanggungjawaban Kultural yang mendesak.
Mengapa Resolusi ini perlu? Filsafat Eksistensialisme, yang dipelopori oleh pemikir seperti Jean-Paul Sartre, mengajarkan bahwa “eksistensi mendahului esensi.” Artinya, Indonesia, sebagai subjek budaya, tidak terlahir dengan esensi (nilai bawaan) yang tetap; sebaliknya, Indonesia harus menciptakan esensinya sendiri melalui pilihan dan tindakan nyata. Pilihan untuk mengirim karya sastra yang semenjana (medioker), sebagaimana disinggung Resolusi, adalah pilihan untuk mendeklarasikan diri sebagai bangsa dengan esensi budaya yang setengah hati—sebuah pengabaian tanggung jawab yang fatal.
Resolusi ini menegaskan bahwa kita tidak boleh melarikan diri dari kebebasan memilih ini. Kita harus memilih dengan otentisitas. Memilih sastrawan terbaik berarti memilih diri kita yang paling ideal untuk dilihat dunia. Sebaliknya, penolakan terhadap karya semenjana (Poin 1 Resolusi) adalah penolakan terhadap kepalsuan, sebuah tindakan otentik untuk menegakkan muruah kesusastraan dan kebudayaan Indonesia (Tujuan 1). Muruah (dignity atau kehormatan) dalam Filsafat Nusantara adalah fondasi etika dan estetika; ia adalah sumbu yang menjaga keseimbangan antara adiluhung (luhur) dan kapitalisme kultural yang cenderung pragmatis.
Argumen kedua Resolusi ini sangat strukturalis. Sastra Indonesia bukanlah kumpulan buku yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem tanda (sign system) yang terstruktur, mencerminkan gramatika budaya dan psiko-sosial kolektif bangsa.
Claude Lévi-Strauss, bapak strukturalisme, mengajarkan bahwa budaya beroperasi melalui struktur yang dalam (deep structure), yang seringkali tersembunyi di balik permukaan (surface structure). Karya sastra yang diajukan ke BRICS bukan hanya sebuah novel atau puisi, tetapi sebuah metonimi—sebuah bagian yang mewakili keseluruhan.
Obyektivitas dan Daya Ungkap Bahasa
Poin 2. Resolusi menuntut pengusulan sastrawan yang merepresentasikan kekayaan sosial-budaya dan kedalaman daya ungkap bahasa Indonesia secara kreatif. Secara struktural, ini berarti karya yang dipilih harus mampu memecahkan kode (decode) struktur yang dalam dari keindonesiaan:
1. Ekspresi Kebudayaan (Struktur): Karya harus mampu memetakan kontradiksi, mitos, dan nilai-nilai yang membentuk collective unconscious bangsa, dari Sabang hingga Merauke.
2. Daya Ungkap Bahasa (Sistem Tanda): Sastrawan tersebut harus telah mengeksplorasi batas-batas bahasa Indonesia—menciptakan sintaksis, metafora, atau gaya naratif baru yang belum pernah ada, seperti upaya dilakukan oleh sastrawan angkatan 45. Kualitas ini memastikan bahwa bahasa Indonesia (linguistic system) dilihat sebagai bahasa yang hidup dan mampu berdialektika dengan isu-isu global, bukan sekadar alat komunikasi.
Resolusi menuntut Panitia harus bertindak sebagai linguistik sastra, menganalisis struktur karya, dan memastikan bahwa signifier (karya) benar-benar terhubung secara valid dengan signified (makna kolektif Indonesia). Kegagalan dalam pemilihan, apalagi yang memicu kontroversi (Tujuan 2), berarti terjadi disonansi struktural yang serius: publik melihat karya yang diajukan sebagai tanda yang salah (misrepresentation), sehingga merusak keutuhan sistem sastra nasional.
Kriteria yang ditetapkan (kiprah, kontinuitas, produktivitas, capaian, dan kontribusi) adalah tuntutan historisitas sastra. Dalam tradisi pemikiran Jerman, sastra diakui sebagai Geist (roh zaman). Panitia harus melihat sastrawan bukan sebagai produk instan, tetapi sebagai vektor yang telah membawa kontribusi struktural melalui berbagai fase kesusastraan Indonesia.
1. Kontinuitas dan Produktivitas: Menunjukkan bahwa sastrawan tersebut adalah poros yang konsisten, sebuah institusi naratif yang terus-menerus memberikan kontribusi pada corpus sastra.
2. Autentisitas: Dalam konteks ini, berarti kemampuannya untuk tetap setia pada visi kreatifnya sendiri, bukan mengikuti tren pasar atau kepentingan politis. Ini adalah tuntutan otentisitas eksistensial yang berakar pada integritas etis seorang seniman.
Musyawarah dan Kepercayaan Publik
Inti dari Resolusi ini, terutama desakan untuk membentuk panitia independen yang kredibel, objektif, dan transparan, berakar pada etika Filsafat Nusantara, khususnya konsep Musyawarah dan Keterbukaan.
Dalam tradisi politik dan budaya Indonesia, keputusan yang sah harus dicapai melalui proses kolektif yang jujur. Panitia independen adalah representasi ideal dari Musyawarah di bidang kebudayaan. Panitia tidak hanya harus memilih, tetapi juga harus menyampaikan argumentasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Poin 5).
Pembentukan Panitia bukan hanya untuk alasan praktis, tetapi untuk alasan epistemologis moral. Sastra seringkali rentan terhadap subyektivitas dan konflik kepentingan. Hanya dengan menempatkan individu-individu yang berwawasan luas (menunjukkan keilmuan) dan kredibel (menunjukkan integritas moral) , maka keputusan yang dihasilkan dapat diklaim sebagai keputusan yang obyektif—atau setidaknya, inter-subjektif yang disepakati oleh otoritas keilmuan.
Jika prosesnya transparan, maka ia akan menumbuhkan kepercayaan publik pada karya sastra bangsa sendiri (Tujuan 3). Kepercayaan publik ini sangat penting. Sastra tidak dapat hidup jika ia terpisah dari pembacanya. Kepercayaan adalah jembatan yang mengubah buku menjadi khazanah (harta karun) budaya.
Tujuan tertinggi Resolusi ini adalah agar karya yang diajukan dapat menjadi kebanggaan dan anutan masyarakat serta mampu menyampaikan diplomasi budaya yang efektif.
Diplomasi budaya adalah perwujudan soft power suatu negara. Sastra yang diakui secara global tidak hanya membuka pasar, tetapi juga membuka pikiran. Ketika sastrawan Indonesia berbicara di panggung BRICS, ia tidak hanya mewakili dirinya, ia menjadi vektor narasi yang membawa gagasan, sejarah, dan nilai-nilai etis bangsa.
Karya sastra yang luhur memiliki fungsi paedagogis (pendidikan). Ia harus menginspirasi masyarakat untuk berani menjadi otentik dan kritis, selaras dengan cita-cita intelektual bangsa.
Jika karya yang dipilih memenuhi semua kriteria struktural dan eksistensial—bermutu tinggi, otentik, dan merepresentasikan kedalaman budaya—maka diplomasi budaya kita akan tegak di atas fondasi yang kokoh, bukan di atas pasir kebohongan.
Mandat Sastra: Kejujuran!
Resolusi tentang Pengajuan Calon Penerima Penghargaan Sastra BRICS adalah sebuah seruan mendasar untuk menghormati proses kreatif dan keilmuan di atas pragmatisme politik. Ia adalah pengakuan bahwa sastra adalah infrastruktur kebudayaan, dan pengabaian terhadap kualitasnya adalah pengabaian terhadap masa depan peradaban.
Ini adalah pertempuran melawan semenjana yang melanda banyak sektor budaya. Dengan menegakkan Resolusi ini, pemerintah Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga melakukan tindakan filosofis yang krusial: mengukuhkan eksistensi nasional melalui pilihan naratif yang otentik, menjamin koherensi struktural karya sastra sebagai tanda budaya, dan menegakkan etika keterbukaan dan tanggung jawab kolektif.
Mandat sastra kita harus abadi, luhur, dan jujur. Hanya dengan Panitia Independen yang berintegritas, pilihan tersebut akan menjadi adiluhung, mengubah BRICS dari sekadar panggung politik menjadi gerbang pengakuan bagi Kedaulatan Narasi Indonesia.
——–
Gus Nas Jogja. Budayawan.