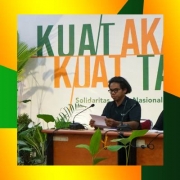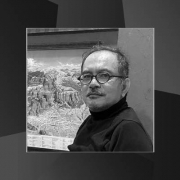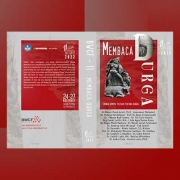Ke Madiun, Membaca Onghokham, Menyisir Politik Jawa/Indonesia
Oleh Riwanto Tirtosudarmo*
Ketika Mas Bambang Adrian Wenzel, Direktur Eksekutif NBS (New Book Store) Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), meminta saya menjadi narasumber acara peresmian Ruang Plate AE di cabang NBS di Madiun dengan mendiskusikan buku karya Onghokham, ‘Madiun Dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani”, saya menduga dia mengira karena saya secara pribadi dekat dengan Pak Ong, jadi bukan karena saya seorang sejarawan, seperti Pak Ong. Memang saya bukan sejarawan, tetapi saya juga bukan orang yang secara pribadi dekat dengan Pak Ong, seperti halnya David Reeve, penulis biografi Pak Ong yang memperoleh banyak pujian. Jika kemudian saya menerima permintaan Mas Bambang menjadi narasumber acara ini, karena saya melihat ini adalah kesempatan saya belajar, tentang Madiun dan tentang Pak Ong dan bagaimana Pak Ong melihat Jawa dan politiknya. Oleh karena itulah saya beri judul esai ini ” Ke Madiun, Membaca Onghokham, Menyisir Politik Jawa/Indonesia”.
Rencananya acara diskusi buku Onghokham ini akan dilakukan tanggal 11 September 2025 di Madiun, lokasi wilayah penelitian sejarah Onghokham untuk disertasi doktornya di Universitas Yale Amerika Serikat. Onghokham mulai menjadi mahasiswa di Universitas Yale tahun 1968 dan selesai tahun 1975. Saya mengenal Pak Ong sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UI awal tahun 1970an. Memang sedikit aneh. Saya mahasiswa psikologi sementara Pak Ong saat itu adalah dosen sejarah di Fakultas Sastra UI. Saya tidak tahu persisnya kapan, mungkin sekitar tahun 1976 setelah beliau pulang dari studi di Universitas Yale di Amerika. Di kampus UI Rawamangun ada sebuah taman, tempat mahasiswa kongkow dan jajan, namanya Taman Sastra, karena milik Fakultas Sastra. Di taman itulah saya sering berpapasan dan sedikit ngobrol dengan Pak Ong. Kebetulan saya tinggal di Asrama Mahasiswa UI Daksinapati, tidak jauh dari taman itu. Ekosistem kampus saat itu sangat menyenangkan dan hubungan dosen dan mahasiswa jauh lebih egaliter dibandingkan yang saya amati sekarang. Hubungan saya dengan Pak Ong meskipun terpaut jauh dari segi umur dan senioritas dalam dunia akademik, berlangsung secara egaliter.

Penulis dengan Pak Onghokham di ISEAS 1980. (Foto: Dokumentasi Penulis)
Setelah lulus dari Fakultas Psikologi UI, sejak awal tahun 1980an saya bekerja sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Para senior saya tidak sedikit yang sejarawan, seperti Taufik Abdullah, AB Lapian, Thee Kian Wie dan Abdurahman Suryomiharjo. Di LIPI ekosistim ilmu-ilmu sosial berbeda dengan yang ada di kampus-kampus yang cenderung terkotak-kotak berdasaran jurusan atau fakultas. Di LIPI yang saya alami di kedeputian ilmu sosial dan kemanusiaan, terbiasa bekerja secara multi dan inter-disiplin. Seorang sejarawan seperti Pak Abdurahman Suryomiharjo misalnya tidak canggung bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi yang dipimpin oleh Pak Thee Kian Wie, seorang ahli sejarah ekonomi tapi memiliki wawasan yang luas dalam bidang ekonomi, termasuk ekonomi kontemporer.
Selain ekosistim akademis dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang bersifat multi dan inter-disiplin, LIPI juga merupakan lembaga penelitian yang pada tahun 1980an memiliki jumlah peneliti sosial yang barangkali terbesar dan bisa dikatakan cukup berpengaruh pada zamannya. Lembaga penelitian lain diluar LIPI yang juga berpengaruh saat itu adalah CSIS (Center for Strategic and International Studies) sebuah think tank semi pemerintah yang pendirinya antara lain Jendral Ali Moertopo dan Sudjono Humardani, keduanya pernah menjadi Aspri Presiden Suharto. Selain CSIS bisa disebut disini LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerbitan Ekonomi dan Sosial) yang menerbitkan jurnal pemikiran Prisma.
Dalam ekosistim dunia akademik dan intelektual yang semarak itulah Onghokham bisa dikatakan sebagai seorang sejarawan publik yang penting. Mengapa penting? Karena Onghokham yang masih tercatat sebagai dosen sejarah UI dengan pangkat 2D karena tidak pernah mengurus kepangkatannya merupakan seorang akademisi yang mampu secara reguler menerbitkan tulisan-tulisannya yang bisa disebut sebagai esai-esai populer namun tetap didasari oleh pengetahuannya yang mendalam tentang sejarah, tidak hanya sejarah Indonesia tetapi dunia. Dalam menulis tentang Sukarno misalnya Ong bisa menggambarkan Sukarno sebagai orang Jawa sekaligus Sukarno sebagai tokoh yang kosmolitan. Dalam kaitan dengan pengetahuannya yang mendalam tentang Jawa inilah buku yang sedang kita bicarakan ini menjadi sangat relevan untuk mengetahui sejarah yang tampaknya lokal namun sesungguhnya dapat menjadi pelajaran yang penting bagi kita sebagai warga sebuah bangsa dan negara yang masih hidup hari ini.
Hari-hari ini Indonesia seperti sedang memasuki kembali sebuah fase perpolitikan yang penuh guncangan, atau dalam bahasa Jawa ontran-ontran, atau dalam bahasa anak gaulnya, sedang tidak baik-baik saja. Akhir bulan Agustus yang lalu Jakarta dan berbagai kota lain terguncang karena rangkaian demonstrasi massa yang memprotes berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memperdulikan nasib orang banyak yang sejak beberapa tahun terakhir ini kehidupan ekonominya dirasakan semakin sulit, antara lain dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja karena banyak pabrik dan perusahaan yang mulai bangkrut. Dalam situasi yang menekan perekonomian orang banyak ini pemerintah dan DPR dinilai hanya memikirkan kepentingannya sendiri atau kelompok elitnya tanpa memiliki empati terhadap nasib orang banyak. Kemarahan orang banyak itulah yang memicu rangkaian demonsrasi dan protes yang berlangsung di akhir bulan Agustus 2025 bersamaan dengan ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang ke -80. Sebuah ironi sejarah tapi itulah kenyataannya.
Pada saat Mas Bambang AW meminta saya menjadi narasumber diskusi buku karya Onghokham tentang Madiun kami samasekali tidak menduga bahwa perpolitikan negeri ini akan gonjang-ganjing pada akhir bulan Agustus itu. Buku yang oleh penerbitnya Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) diberi judul “Madiun Dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani di Karesidean Madiun Abad XIX” aslinya adalah disertasi doktoral Onghokham di Departemen Sejarah Universitas Yale di Amerika Serikat. Disertasi itu diselesaikannya pada tahun 1975 setelah melewati masa perjuangan yang cukup panjang, antara lain karena pembimbing utamanya Harry J Benda wafat pada tahun 1971. Onghokham kemudian dibimbing secara silih berganti oleh para ahli Indonesia yang bisa dikatakan tidak ingin Ong gagal menuliskan disertasinya. Dua orang bisa disebut disini sebagai penyelamat dari kegagalan meraih doktor, yang pertama adalah Bernhard Dahm, ahli Indonesia berkewarganegaraan Jerman yang menulis secara mendalam tentang Sukarno dan Anthony Reid, seorang yang ahli tentang sejarah Asia Tenggara, berkebangsaan New Zealand.
Secara kebetulan saya telah memiliki fotokopi disertasi Onghokham yang masih diketik secara manual dan disana-sini ada bagian yang sulit terbaca karena tintanya sudah pudar. Fotokopi itu saya peroleh dari Saiful Hakam alumni Jurusan Sejarah FIB UGM anggota tim penelitian yang saat itu saya koordinir tahun 2015-2016 tentang masyarakat Samin di Kabupaten Pati, Blora dan Kudus. Disertasi Onghokham itu kami perlukan karena selain Ong sendiri menulis tentang Samin untuk skripsi Sarjana Muda-nya di Juusan Sejarah UI, dalam disertasinya, Onghokham menyinggung tentang masyarakat Samin yang meperlihatkan karakter komunitas yang berbeda dengan masyarakat petani Jawa pada umumnya. Istilah “sedulur sikep” yang dipakai oleh masyarakat Samin sekarang dapat diketemukan asal usul-nya dalam disertasi Ong yang menunjukkan ada golongan petani Jawa yang disebut sebagai kelompok sikep yang merupakan kelas petani yang cukup independen dan menguasai tanah, biasanya dibantu oleh kelompok “numpang” dan “bujang”, kelas petani sebagai buruh dan pembantu buruh yang tak bertanah. Jadi sebelum saya menerima kiriman buku terjemahan terbitan KPG beberapa hari yang lalu, saya sudah terlebih dahulu membaca dengan agak susah payah fotokopi disertasi Pak Ong.
Dalam kata pengantar di disertasinya Ong mengatakan pengaruh besar dari guru pertamanya, Profesor Harry J Benda, seorang sejarawan yang menaruh minat pada masyarakat Jawa, yang menulis tentang Islam ketika masa pendudukan Jepang, juga mengapa kemudian Ong memilih sejarah Madiun sebagai fokus penelitiannya. Harus diingat bahwa Ong melakukan riset arsip-nya pada awal tahun 1970an tentang sebuah masyarakat di Jawa pada abad ke 19. Ong yang fasih berbahasa Belanda dan Jawa itu tenggelam dalam penelitian arsip Madiun pada masa kolonial terutama di Belanda. Karena memang disanalah arsip tentang Jawa boleh dibilang paling lengkap. Onghokham dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 1 Mei 1933 dari keluarga Tionghoa yang tergolong kaya pada zamannya. Pendidikan dasar menengahnya diselesaikan di Surabaya. Kecintaannya tentang Jawa, antara lain kegemarannya menonton wayang kulit, membuatnya paham betapa besar arti wayang tidak saja sebagai ekspresi kesenian namun juga sebagai referensi politik dan ideologi bagi masyarakat Jawa.
Melalui cara pandangnya yang kritis berbagai sumber yang ditulis tentang Jawa baik oleh orang Jawa sendiri seperti berbagai serat dan babad, maupun hasil studi penulis barat terutama Belanda, oleh Ong dibaca dengan perspektif baru, dan hasilnya adalah sebuah tafsir tentang Jawa yang bagi saya mencerahkan. Disertasinya yang berjudul “The Residency of Madiun: Pryayi and Peasant in the Nineteenth Century”, yang kemudian diterjemahkan menjadi buku yang sedang kita bicarakan ini, bisa dikatakan karya tulis paling cemerlang dari karya-karya Ong lainnya yang umumnya berupa artikel atau esai populer.
Sebagai seorang yang mempelajari demografi saya baru tahu dari buku Ong kalau di Jawa pada masa raja-raja Jawa berkuasa dan pada zaman kolonial penduduk lebih dihargai daripada tanah, alasannya waktu itu tanah cukup melimpah. Seorang raja, atau penguasa akan ditentukan tingkatnya dari jumlah penduduk yang menjadi kawulo-nya. Penduduk menjadi berharga karena dilihat sebagai pekerja yang bisa menggarap tanah. Setelah perang Diponegoro, atau Perang Jawa (1825-1830) Belanda memberlakukan sistim tanam paksa (1830-1870) di Jawa, mengubah sawah menjadi perkebunan dan rakyat dikenai pajak. Pajak itu diwujudkan dalam bentuk kerja paksa (corvee labor). Tekanan terhadap kehidupan para petani di Jawa sejak itu meningkat, dan berujung pada penurunan kesejahteraan tetapi juga berbagai bentuk resistensi dan perlawanan. Salah satu bentuk resistensi, menurut kajian Onghokham adalah migrasi penduduk. Perpindahan penduduk juga disebabkan oleh karena keharusan untuk ikut pindah jika rajanya kalah perang. karena itulah menurut Ong ada semacam pola perpindahan komunitas petani yang bersifat semi permanen. Pola ini menurut Ong juga bisa ditemukan di berbagai wilayah lain d seluruh Asia Tenggara. Ong membuktikan mitos orang Jawa enggan pindah dengan ugkapan “Mangan Ora Mangan Asal Ngumpul” sebagai persepsi yang salah tentang Orang Jawa.
Membaca disertasi Ong, sebagai seorang yang pernah belajar psikologi saya menemukan dari studi Ong semacam psikologi politik Jawa. Menurut Ong, pengalaman sejarah tentang keteraturan (order) dan ketidakteraruran (disorder) dalam kehidupan “bernegara” di Jawa, meninggalkan dua warisan budaya – saya menamakannya sebagai psikologi politik – yang penting bagi orang Jawa. Pertama, berkembangnya sebuah visi dari elit politik, kedinastian, perang antar “negara” persaingan dan intrik diantara elit penguasa, represi dan meningkatnya beban yang kesemuanya itu telah menciptakan tingginya sensitivitas terhadap politik. Kedua, sebagai kontras dari warisan pertama yang memperlihatkan keadaan ketidakstabilan dan penuh guncangan adalah terbentuknya angan-angan atau mimpi dalam psikologi orang Jawa tentang kehidupan bermasyarakat yang “tata tentrem kertaraharja”, teratur-tertata-damai-sejahtera dalam sebuah negara yang stabil dan dibawah raja yang bijaksana (Ratu Adil). Saya jadi ingat suatu saat di Taman Sastra Pak Ong yang tahu saya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi UI mengatakan mengapa saya tidak menulis skripsi tentang Ratu Adil. Saat itu sekitar pertengahan tahun 1970an apa yang dikatakan oleh Pak Ong tentang Ratu Adil betul-betul diluar imajinasi saya. Menjadi pertanyaan kita bersama apakah Orang Jawa hari ini masih mengimpikan Ratu Adil?
Madiun penting, berdasarkan studi Onghokham, karena sebagai wilayah/masyarakat pinggiran yang menjadi bagian dari pusat kekuasaan di Surakarta dan setelah Perjanjian Gianti (1755) juga dengan Jogyakarta, selalu menerima imbas dari apa yang terjadi di pusat kekuasaan, dan dalam hal ini tidak terlepas pada masa itu dari kehadiran pemerintah kolonial Belanda. Melalui perubahan sosial politik yang terjadi di Madiun, khususnya yang terjadi pada golongan priayi dan petani, dua komunitas di Madiun yang diteliti Ong, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang hampir sempurna tentang karakter politik Jawa, yang imbasnya cukup kuat kemudian terhadap perpolitikan (polity) Indonesia. Membaca buku hasil studi Ong di Madiun kita bisa mengetahui bagaimana politik kelas berjalan, tingkat penggunaan bahasa antar kelas, sistim perpajakan, penguasaan dan pengelolaan tanah, dan juga dengan demikian sistim dan hirarki kekuasaan melalui berbagai institusi seperti karesidenan, bupati, wedana, mantri, desa perdikan, pesantren dan sebagainya yang sebagian masih dipakai hingga hari ini.
Dari bukunya kita bisa mengetahui bagaimana proses penyebaran Islam berlangsung di sebuah wilayah yang penduduknya kuat memeluk agama Hindu dan Budha. Disana kita membaca bagaimana intrik dan politik penaklukan dan konversi agama itu berlangsung melalui peran tokoh legendaris Batara Katong, dan juga kemudian Kyai Kasan Besari. Secara kritis Pak Ong menggunakan Babad Ponorogo dan terutama Babad Pacitan disamping buku dan disertasi ilmuwan-ilmuwan Belanda seperti Drewes, HJ de Graf, Th Pigeaud dan lain-lain. Kemampuannya berbahasa Jawa dan Belanda menjadi sejarawan yang sulit dicari tandingannya. Tapi yang menurut saya patut diteladani sebagai ilmuwan sosial adalah perspektifnya yang kritis dan tidak sekedar mengutip apa yang dikatakan oleh ilmuwan Belanda. Sebagai contoh Onghokham menilai pendapat PJ Zoetmulder seorang pastor Jesuit yang meneliti tentang “agama Jawa” yang menurut Ong tidak mempertimbangkan konteks perkembangan sosial politik Jawa pada masanya. Ong juga mengkritik pendapat Cornelis van Vollenhoven tentang konsep masyarakat adat dan menganggap desa-desa di Jawa sebagai kesatuan sosial yang otonom.
Sebuah pelajaran penting yang bisa dipetik dari buku Ong adalah bagaimana secara bertahap Belanda bisa menguasai tanah Jawa dan menjadi basis kekuasaannya dalam proses penaklukan selanjutnya menguasai Indonesia. Dalam proses ini bisa dilihat kelemahan dari raja-raja Jawa yang pada dasarnya hanya saling berebut kekuasaan, wilayah dan penduduknya, satu sama lain. Sejarah Jawa bisa dilihat sebagai sejarah politik elit dari para raja dan kaum priayi yang tidak pernah terlihat memiliki niat untuk bekerjasama karena selalu saja ada alasan, baik itu alasan yang bersifat politis, ekonomis maupun agama, untuk saling menaklukkan. Salah satu referensi penting, kalau tidak bisa dikatakan terpenting dalam memahami kehidupan bernegara raja-raja Jawa adalah monografi Soemarsaid Moertono yang semula merupakan tesis master di Universitas Cornell (State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century).
Sebuah konsep yang penting dalam disertasi Ong adalah tentang kekuasaan. Kekuasaan, dalam konsep Jawa, sebagaimana dikemukakan oleh Ben Anderson, dan diamini oleh Onghokham, berbeda dengan yang ada di masyarakat barat yang bersifat kongkrit; dalam konsepsi Jawa bersifat abstrak yang memiliki dasar spiritual dan mistis. Baik saya kutip pendapat Ben Anderson, sebagaimana dikutip dalam disertasi Onghokham (hal. 4-5):
Power exists independent of its users…an existential reality. Power is that intangible, mysterious and divine energy which animates the universe. It is manifested in every aspect of the natural world. In stones, trees…This conception of the entire cosmos being suffused by a formless, constantly creative energy provides the basic link between the “animism” of the Javanese villages and the high metaphysical pantheism of the power centres. Thus, the well-known mystical formula Tuhan adalah Aku (God is I) expresses the concreteness of the Javanese Idea of Power. The divine power is the essence of I, of the self.
Dalam kaitan dengan konsep kekuasaan Jawa, Ong mengemukakan hal yang menarik tentang bagaimana persepsi para petani atau orang kebanyakan pada umumnya tentang kekuasaan pada tingkat desa, yaitu yang dia sebut sebagai “jago”. Dalam kata-kata Ong: “People expected an activist role from their leader whether he be king, priyayi, or village headman. The leader was likened to a jago (lit. fighting cock). Melalui para jago yang dilihat oleh orang desa sebagai perantara atau “power broker” antara rakyat dan penguasa; petani dan wong cilik pada umumnya menggantungkan nasibnya. Para jago menurut Ong tidak selalu yang memiliki jabatan resmi dalam hirarki kekuasaan tetapi juga mereka yang berada diluar lembaga kekuasaan, misalnya pemimpin pesantren atau bahkan para guru silat yang menguasai ilmu kanuragan dan dianggap memiliki kekebalan bahkan terhadap peluru tajam sekalipun. Kekuasaan yang dijembatani oleh para jago bisa bersifat kekuatan yang berwujud kongkrit maupun yang bersifat kosmologis.
Peran para jago yang berada diluar hirarki kekuasaan resmi ini penting sekali ketika orang kebanyakan mengalami tekanan dari para raja atau priayi karena merekalah yang kemudian bisa menggalang para petani dan rakyat banyak melakukan resistensi dan perlawanan terhadap kelas pryayi atau bangsawan. Dalam kaitan ini Ong menyinggung peran para warok yang merupakan pemimpin dari seni pertunjukan rakyat yang sangat populer di daerah Ponorogo, Reog. Warok dianggap memiliki kesaktian disamping kekebalan yang antara lain diperoleh dari hidup selibat menjauhi perempuan, dan memilih hidup bersama laki-laki muda sebagai gemblak-nya. Dalam konteks ini Ong melihat “anarkisme” sebagai bagian penting dari terjadinya perubahan sosial, ketika tatanan lama yang represif ingin ditumbangkan untuk menciptakan tatanan baru yang lebih baik. Munculnya Diponegoro sebagai representasi dari perlawanan rakyat terhadap penindasan yang dilakukan oleh para bangsawan dan kaum priayi bisa dilihat dalam konteks ini. Para bangsawan yang kemudian meminta Belanda untuk membantu menumpas pemberontakan Diponegoro terbukti kemudian menjadi pihak yang justru harus mengambil peran utama dalam perang Diponegoro, dan bukan para bangsawan atau kelas priayi yang hanya bersembunyi dibalik Belanda.
Onghokham menurut hemat saya melakukan terobosan dalam studi tentang perubahan sosial di Jawa, disamping tentu saja sejarawan pendahulunya Sartono Kartodirdjo yang menulis tentang pemberontakan petani di Banten 1888. Menurut hemat saya Sajogyo seorang ahli sosiologi pedesaan dari IPB yang menulis disertasi doktornya tentang Masyarakat Way Sekampung di Lampung bisa disejajarkan disini dengan Onghokham yang menekankan pentingnya melihat stratifikasi sosial dalam sebuah masyarakat. Jika Onghokham dibimbing oleh Harry J Benda, Sartono dan Sajogyo dibimbing oeh W.F Wertheim, ahli sosiologi dari Universitas Amsterdam, Belanda. Buku Ong, seperti terlihat dari judulnya, dengan jelas mengajak pembaca untuk melihat dua kelas sosial-ekonomi yang utama di Jawa yaitu kelas priayi dan kelas petani, kelas penindas dan kelas tertindas. Yang menarik, tanpa menggunakan slogan-slogan Marxisme, Onghokham sesungguhnya telah secara jeli melakukan analisis kelas pada masyarakat Jawa, melalui kasus Madiun pada abad 19. Fokusnya pada peran pajak sebuah konsep barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, menjadi menarik ketika diterapkan pada masyarakat petani Jawa yang belum mengenal hak milik atas tanah sebagaimana dialami di barat. Melalui kemampuan imajinasinya yang kreatif berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri sebagai orang Jawa Timur yang meskipun mengenyam pendidikan barat namun menghayati berbagai kepercayaan lokal seperti Tuyul, Danyang dan Nyai Loro Kidul beserta ritual-ritualnya, Onghokham berhasil menyajikan sebuah studi sejarah dengan perspektif struktural namun diracik dengan bumbu pengetahuan lokal yang sangat mengagumkan.
Onghokham, bukan Orang Jawa dan bukan Orang Belanda/Eropa. Dilihat dari posisinya, ia “outsider” yang mengamati interaksi antara Orang Belanda dan Orang Jawa, di Madiun. Meskipun bukan Orang Jawa, Ong dibesarkan di Jawa Timur dan oleh sebab itu dia mengalami hidup sebagai orang Jawa Timur. Ong, pada saat yang sama dididik, baik di lingkungan rumahnya, maupun di lingkungan sekolahnya, secara Belanda. Ong orang yang hidup dalam dua tegangan, antara Jawa dan Belanda. Ketika menulis skripsi S1 nya di UI, Ong memilih menulis sejarah runtuhnya Hindia Belanda, yang membuatnya mengenal dengan baik politik kolonialisme Belanda. Ong memilih Madiun sebagai bahan disertasinya, yang memungkinkan dia secara mendalam menganalisis politik Jawa.
Membaca disertasi Ong kita akan merasakan bagaimana Ong memahami Jawa yang kompleks melalui babad dan cerita-cerita rakyat (folklore) terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis dan spiritual yang memang menjadi bagian yang masih kuat melekat pada Orang Jawa pada masa itu. Namun membaca disertasinya yang tentu saja ditulis dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa maupun bahasa Belanda, kita dapat merasakan posisinya sebagai”outsider’ tadi. Kategorisasi “insider-outsider” ini tentu saja sebuah fiksi karena pada akhirnya apakah seorang ilmuwan sosial mampu melakukan empati terhadap nasib orang banyak yang tertindas atau tidak. Ong dengan caranya sendiri yang dikenal sebagai nyentrik (kritis, skeptis, sinis) itu merupakan orang yang tidak mungkin dibatasi dalam kategori-kategori itu. Ong adalah seorang pelintas batas sejati: lokal, nasional sekaligus kosmopolitan. Kenyentikannya bukan gaya inteketual salon atau kegenitan akademisi.
Ketika proklamasi dideklarasikan 80 tahun yang lalu, negara bekas jajahan Belanda yang bernama Indonesia itu memilih menjadi sebuah republik yang mengakui bahwa semua warganegara berkedudukan setara. Hari-hari ini ketika Indonesia kembali diguncang krisis kepemimpinan dan orang banyak melakukan demonstrasi dan protes kita sesungguhnya sedang menyaksikan sebuah masyarakat yang sedang dilanda kesenjangan dan ketimpangan antara kelas elit yang berkuasa dan kelas bawah yang marah karena diperlakukan tidak adil. Disertasi Onghokham yang sekarang telah diterjemahkan dengan baik dan menjadi buku dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit KPG isinya menurut hemat saya masih sangat relevan dan perlu menjadi bahan refleksi bersama, terutama ketika kita sebagai sebuah bangsa kembali sedang mengalami guncangan politik.
Sebagai penutup, saya ingin mengutip paragraph terakhir dari buku “Madiun Dalam Kemelut Sejarah” ini (halaman 318):
Untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang masyarakat Indonesia, kita harus memperhatian tidak saja seruan Benda (Harry J Benda, gurunya – catatan tambahan dari saya) untuk melihat masalah keberlanjutan dan perubahan, tetapi juga tuduhan Wertheim (WF Wertheim, ahli sosiologi Belanda yang sampai pertengahan tahun 1950an masih meneliti di Lampung – catatan tambahan dari saya) bahwa kita telah mengabaikan strutur kelas dalam masyarakat itu sendiri. Tidakkah kita seharusnya lebih melihat pada institusi kelas, hubungan mereka satu sama lain dan menginterpretasikan, misalnya keterkaitan antara santri, priayi, dan abangan dengan cara ini? Pandangan tentang masyarakat yang tidak terdiferensiasi terlalu sering menuju pada usaha menciptakan despotisme. Pandangan ini menggoda para pembuat kebijakan untuk membentuk masyarakat sesuai dengan kepentingan mereka sendiri atau orang lain. Kita tidak boleh nelupakan harga yang harus dibayar umat manusia dalam kondisi seperti ini; penindasan kepentingan kelompok dan kelas di dalam masyarakat, dan terhambatnya kemajuan manusia dan masyarakat di masa depan.
Tonjong Bogor 10 September 2025
*Riwanto Tirtosudarmo, Peneliti Sosial Independen