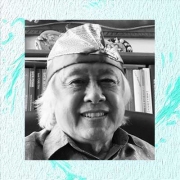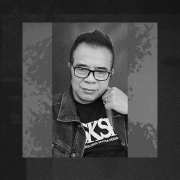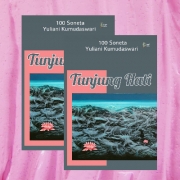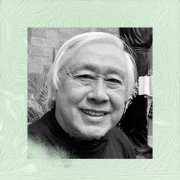Jejak Arkeologi Para Peziarah: Batu Nisan Sebagai Manifestasi Aletheia, Sanad, dan Perlawanan Spiritual
Oleh: Gus Nas Jogja*
Batu nisan di situs-situs keramat Nusantara berdiri bukan sekadar sebagai penanda akhir, melainkan sebagai Artefak Ontologis—sebuah titik material di mana dimensi Being (Kebenaran Abadi) yang tersembunyi berinteraksi dengan dimensi Becoming (Perwujudan Fana’) yang terlihat. Dalam tradisi spiritual, makam wali adalah Locus Theologicus—tempat yang disucikan dan dipenuhi makna, yang secara fisik menandai Gerbang antara dunia profan kehidupan sehari-hari dan dunia transendental Ruh dan Alam Barzakh.
Batu nisan, dalam kesunyiannya yang abadi, mengeluarkan sebuah tantangan filosofis terhadap Algoritma Kecepatan modern yang mendewakan keterlihatan, likes, dan hasil instan. Ia adalah Akar Spiritual yang menuntut Kearifan Kelambatan (wisdom of slowness) dan kontemplasi mendalam. Peziarah datang, bukan untuk meratapi kematian, melainkan untuk menyerap Hayatun Ba’da al-Mamat—kehidupan ruhaniyah yang abadi (Baqa’) dari ruh wali yang telah mencapai maqam Wushul bagi pencapaian tertinggi di sisi Hadirat Ilahi.
Telaah komprehensif ini bertujuan untuk menggali lapisan-lapisan makna tersembunyi pada jejak arkeologi peziarah: dari tipologi material batu nisan hingga jejak ritual (laku) yang didokumentasikan dalam manuskrip dan dibedah melalui kacamata Antropologi Agama. Kami akan membuktikan bahwa setiap sentuhan, setiap ukiran, dan setiap jejak keausan adalah naskah Sastrawi yang terukir dari sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, sebuah Ode kepada fondasi yang tak terlihat.
Ketersembunyian dan Struktur Sanad Kosmis. Bentuk fisik dan inskripsi –epigrafi– pada batu nisan adalah Dokumen Filsafat Material yang mencerminkan pemahaman teologis suatu komunitas dan struktur sanad atau rantai transmisi yang mereka yakini. Arkeologi tipologi mengungkapkan bagaimana Akar spiritual telah tumbuh dan beradaptasi di tanah Nusantara. Nisan adalah Pusaka Sunyi yang menyimpan sejarah batin peradaban.
Dialektika Tanzih dan Tasybīh dalam Batu. Tipologi nisan di Nusantara menunjukkan dua arus filosofis yang berdialektika: Tanzih dan Tasybīh. Dialektika ini bukan pertentangan, melainkan dua cara dalam memandang Diri Tuhan atau Dzatul Haq.
Gaya Tanzih atau Transendensi. Ode Ketinggian Dicirikan oleh nisan silindris, tebal, dengan kaligrafi monumental Arab murni, seperti di Makam Sultan Malikussaleh (Aceh). Gaya ini secara spiritual menekankan Tanzih—menjauhkan Tuhan dari segala kemiripan makhluk. Ia adalah Ode Ketinggian, sebuah seruan untuk memandang Tuhan sebagai Yang Mutlak, melampaui segala bentuk fana. Filosofi ini berakar pada Akar Disiplin syariat.
Gaya Tasybīh atau Imanensi/Inklusif. Meditasi Kedalaman Dicirikan oleh nisan berundak, pipih, dengan hiasan sulur, flora, dan unsur lokal yang disamarkan (stilisasi). Gaya ini mencerminkan Tasybīh—bahwa Tuhan hadir dalam manifestasi alam semesta (filosofi Manunggaling Kawula Gusti atau Wahdatul Wujūd).
Contoh Puncak Tasybīh bisa ditemukan pada Makam Sunan Sendang Dhuwur di Lamongan, Jawa Timur. Makam ini adalah monumen filosofis arsitektur Islam Nusantara. Batu nisan yang suci ditempatkan di dalam kompleks yang menggunakan gerbang (gapura) dan atap limasan bersusun—struktur yang secara visual mengadopsi tatanan kosmologis Hindu-Jawa. Gapura Paduraksa yang sangat tinggi dan nisan yang terintegrasi di dalamnya adalah pernyataan bahwa Imanensi Ilahi harus ditemukan dan dirayakan di dalam bingkai budaya yang sudah ada. Batu nisan di sini menjadi Pusat Sinkretisme, tempat peziarah secara spiritual menegaskan bahwa menerima Tauhid tidak berarti harus menolak Budaya Akar leluhur. Ziarah ke sini adalah sebuah laku untuk mencapai Akar yang Inklusif, mencari barakah yang telah tersintesis secara harmonis.
Peta Kosmis Sanad dan Narasi Maqam. Gelar-gelar spiritual pada nisan secara filosofis menegaskan Maqam (Kedudukan Spiritual) wali. Wali diyakini telah mencapai tahap Insan Kamil (Manusia Sempurna), yang ruhnya menjadi khalifatullah di bumi.
Inskripsi nisan adalah titik simpul fisik dalam jaringan Sanad Kosmis. Bagi murid Tarekat, menyentuh nisan adalah tindakan filosofis untuk menarik kembali sirr (rahasia batin) mereka yang terhubung pada ruh wali. Mereka memastikan bahwa Akar spiritual mereka tidak terputus.
Makam Syekh Panjalu di Ciamis, Jawa Barat dan Syekh Haji Abdul Muhyi di Pamijahan, Tasikmalaya misalnya, sering dikaitkan dengan penyebaran Tarekat Syattariyah di Jawa Barat. Makam Syekh Panjalu di sekitar Situ Lengkong adalah titik fokus spiritual yang berakar kuat pada geografi Sunda kuno. Sanad di sini tidak hanya diwariskan melalui teks, tetapi juga melalui tanah dan air. Nisan Syekh Panjalu menjadi Pancer baru, yang mengislamisasi dan menyucikan pundèn (tempat keramat) leluhur. Peziarah datang untuk menyambung sanad yang menautkan Tasawuf Timur Tengah dengan tradisi karuhun (leluhur) Sunda.
Seorang Mursyid dari Tarekat Khalwatiyah Yusuf (Gowa, Sulawesi Selatan) [3] berpesan:
“Ruh Awliya adalah Akar yang hidup. Makam hanyalah cangkang. Ketika engkau datang, niatkanlah untuk meletakkan sirr-mu di hadapan sirr mereka. Sebab, di antara dua sirr yang jujur, tidak ada lagi jarak yang diciptakan oleh lautan atau waktu. Itulah makna sejati dari Rabitah—pengikatan hati.”
Manuskrip Tarekat: Legitimasi Eksistensial dan Peta Sulūk
Kekuatan spiritual batu nisan diperkuat oleh tradisi manuskrip, yang membentuk kesadaran dan praktik para peziarah. Naskah-naskah ini menjadi blueprint bagi The Great Spiritual Tour di Nusantara.
Dalam manuskrip
Serat Centhini yang ditulis abad ke-19, [2] kemunculan naskah ini mengubah makna perjalanan fisik ziarah menjadi Sulūk atau Perjalanan Spiritual yang menolak kecepatan modern. Centhini merinci ritual tirakat atau (bertapa) dan kungkum (berendam). Ritual ini secara filosofis mengajarkan Fana’—peleburan diri melalui penyiksaan fisik dan mental untuk membuang ego. Nisan menjadi titik akhir dari laku yang keras, tempat barakah diterima sebagai imbalan atas usaha.
Dharma adalah laku yang mengajarkan bahwa Hikmah atau Kearifan hanya diperoleh melalui proses yang lambat, penuh penderitaan. Ini adalah perlawanan eksistensial terhadap janji kebahagiaan instan yang ditawarkan oleh Algoritma Kecepatan.
Kitab Manāqib: Doktrin Hayatun Ba’da al-Mamat dan Karamah
Manuskrip Kitab Manāqib, yang berisi riwayat hidup para wali, adalah fondasi teologis ziarah. Doktrin Baqa’ dalam Manāqib menegaskan bahwa wali mencapai Baqa’ (Keabadian Ruhani) melalui Fana’ total. Mereka berada dalam keadaan Hayatun Ba’da al-Mamat (kehidupan setelah kematian) dan mampu memberi syafaat. Makam adalah locus di mana karamah ini tetap aktif.
Dalam tradisi Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, keyakinan ini dilegitimasi:
“Jangan kau kira ruh para Awliya atau wali itu wafat. Mereka hanya berpindah dari alam mulk (fisik) ke alam malakūt (spiritual). Makam mereka adalah pintu gerbang. Ketika engkau memanggil ruh mereka dengan adab (etika), mereka akan menjawabmu dengan barakah dari sisi Hadirat Ilahi.”
Kajian Antropologi Agama membedah perilaku peziarah sebagai ekspresi pietas mendalam yang didorong oleh kebutuhan eksistensial untuk mentransfer energi spiritual. Batu nisan adalah konduktor utama dalam ritual ini.
Menurut Victor Turner [4], ziarah menciptakan keadaan Liminalitas, di mana status sosial duniawi dilepas. Tindakan melepas alas kaki, berwudu, dan memasuki kompleks nisan adalah ritual filosofis untuk melepaskan ego yang sombong (Nafs Ammarah) sebelum berhadapan dengan kebenaran hakiki.
Nisan sebagai Simbol Kematian Ego dan makam menjadi ruang yang memaksa peziarah untuk menghadapi kefanaan diri mereka sendiri, sebelum mencari Akar yang abadi.
Syekh Panjalu Di Makam Syekh Panjalu di Ciamis, ritual liminalitas seringkali diakhiri dengan mengambil air dari Situ Lengkong atau melakukan kungkum (berendam/bersuci) di dekatnya. Air, sebagai elemen pembersih kosmis, menandai akhir dari fase liminal. Secara antropologis, ini adalah upaya membersihkan energi profan sebelum secara formal menerima barakah dari nisan. Peziarah percaya bahwa air dari danau keramat tersebut adalah manifestasi dari kemurnian sirr Syekh yang abadi.
Perilaku peziarah terhadap batu nisan (tabarruk) didorong oleh Metafisika Sentuhan; keyakinan filosofis bahwa energi spiritual dapat meresap dan ditransfer melalui materi padat. Mengusap nisan (tabarruk) dan mengusapkan tangan ke wajah adalah ritual Kontaminasi Positif [6]. Peziarah secara sadar mengontaminasi diri dengan Akar kebajikan wali. Secara arkeologis, pola keausan yang sangat halus pada nisan keramat –seperti di Makam Pangeran Diponegoro, Makassar– adalah jejak kumulatif dari ribuan tindakan tabarruk.
Arsitektur di Sendang Dhuwur sengaja dirancang untuk memaksimalkan tabarruk. Kompleks nisan dibuat bertingkat dan berundak, mendorong peziarah untuk melakukan laku fisik menaiki tangga sebelum mencapai batu nisan. Setiap anak tangga, setiap ukiran gapura, adalah objek tafakkur. Peziarah yang menyentuh relief-relief sebelum mencapai nisan secara spiritual melakukan penyucian diri bertahap melalui Form yang disucikan. Ini adalah Arsitektur sebagai Meditasi.
Ritual laku di sekitar makam berfungsi sebagai Terapi Eksistensial kolektif bagi peziarah. Di tengah alienasi modern, laku (seperti mengelilingi makam atau berdiam diri) memberikan struktur dan makna yang hilang. Dengan melakukan ritual di tempat yang suci, peziarah secara efektif menyucikan ruang dan waktu mereka sendiri. Mereka menarik diri dari waktu linear ke dalam Waktu Siklus yang abadi, yang diatur oleh ritual spiritual.
Dalam tradisi Tarekat Sammaniyah atau Tarekat Khalwatiyah, adab (etika) ziarah sangat ditekankan:
“Pergi ke makam Awliya bukanlah pergi meminta, tetapi pergi memberi hormat. Bersihkan hati (Qalb) sebelum menyentuh batu. Ruh mereka akan memberimu futuhat (pencerahan) tanpa kau pinta, jika adab-mu benar. Jika niatmu hanya urusan dunia, engkau hanya akan menyentuh batu yang dingin.”
Batu nisan dan jejak peziarah adalah narasi agung tentang pencarian keabadian. Ia adalah penolakan tegas terhadap dunia modern yang absurd dan tercerabut [10]. Makam-makam seperti Syekh Panjalu dan Sendang Dhuwur membuktikan bahwa spiritualitas Nusantara adalah filsafat Kontinuitas Akar. Islam tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menyucikan dan mengisi wadah yang sudah ada.
Di Makam Panjalu, para peziarah mengambil air Situ Lengkong adalah tindakan filosofis untuk menyambungkan spiritualitas Islam dengan ruh alam Sunda. Nisan menjadi Titik Mediasi antara langit dan bumi, antara syariat dan karuhun.
Di Makam Sendang Dhuwur, para peziarah yang menggunakan gerbang Hindu-Jawa adalah deklarasi arsitektural bahwa Form lama dapat digunakan untuk menopang Esensi baru, sebuah model Filosofis Inklusi yang menjadi ciri khas Walisongo.
Kedua makam ini menantang konsep modern yang menuntut diskontinuitas total dari masa lalu. Sebaliknya, mereka menunjukkan bahwa Akar spiritual harus ditarik dari kedalaman sejarah untuk menghadapi masa depan. Martin Heidegger [5] mencari Aletheia—kebenaran sebagai ketidak-tersembunyian—yang telah dilupakan oleh filsafat Barat. Batu nisan adalah artefak yang memaksa Aletheia untuk muncul. Ia adalah kebenaran yang tersembunyi (Akar), yang hanya dapat diakses melalui tindakan penyingkapan (ziarah).
Di era Kecerdasan Palsu (AI), yang bekerja pada kecepatan Algoritma dan lapisan data (fenomena), ziarah dan nisan menawarkan jawaban:
1. AI vs. Sirr: AI bekerja pada informasi; nisan bekerja pada Sirr (Esensi). AI tidak memiliki sanad (asal-usul spiritual otentik). Peziarah mencari Akar yang otentik, yang hanya dapat ditemukan melalui koneksi spiritual yang lambat dan mendalam.
2. Kontemplasi vs. Komputasi: Batu nisan mengajarkan bahwa Hikmah (Kearifan) hanya tumbuh pada kecepatan kontemplasi, bukan kecepatan komputasi. Ia menuntut peziarah untuk mematikan noise digital dan mendengarkan bisikan Akar di dalam hati mereka.
Batu Nisan: Monumen Kesunyian yang Abadi
Batu nisan adalah monumen yang mengajarkan nilai Kesunyian yang Produktif. Ia diam, tetapi ia adalah sumber kehidupan spiritual bagi ribuan orang. Ia menerima beban sentuhan, doa, dan nazar tanpa pernah mengeluh atau menuntut pengakuan.
Secara sastrawi, batu nisan adalah Puisi Epik yang tidak pernah selesai. Setiap peziarah yang datang adalah satu baris baru dalam narasi keabadian. Pola keausan yang diakibatkannya adalah tinta yang tak terlihat, membuktikan bahwa kebenaran terbesar manusia terletak pada ikatan spiritualnya, bukan pada pencapaian materialnya.
Batu nisan adalah sebuah janji, sebuah silsilah, sebuah Akar Keabadian di Malam Eksistensi. Ia mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kita kumpulkan di atas, melainkan pada kedalaman spiritual yang telah kita tanam di bawah.
***
Catatan Kaki dan Rujukan Ilmiah
[1]. Lombard, Denys. Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. (Mengulas tipologi nisan dan jalur peradaban Islam).
[2]. Padmosoekotjo, S. Serat Centhini: Kandha Laku Jati. Jakarta: Balai Pustaka, 1992. (Analisis Serat Centhini sebagai panduan sulūk dan perjalanan).
[3]. Bruinessen, Martin van. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia. Bandung: Mizan, 1995. (Kajian tentang legitimasi Manāqib dan peran sanad, khususnya Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah).
[4]. Turner, Victor. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Ithaca: Cornell University Press, 1969. (Konsep Liminalitas, societas, dan communitas dalam ziarah).
[5]. Heidegger, Martin. Being and Time. Terj. John Macquarrie & Edward Robinson. New York: Harper & Row, 1962. (Konsep Aletheia dan Being).
[6]. Geertz, Clifford. The Religion of Java. Chicago: University of Chicago Press, 1960. (Menggambarkan praktik tabarruk dan sintesis kepercayaan, termasuk Metafisika Sentuhan).
[7]. Ismanto, FX. “Arkeologi dan Perkembangan Islam di Jawa.” Jurnal Sejarah 1, no. 2 (2018): 1-15. (Kajian arkeologis material, termasuk wear patterns).
[8]. Sunyoto, Agus. Atlas Walisongo. Depok: Pustaka IIMaN, 2017. (Analisis tipologi nisan Walisongo).
[9]. Nasr, Seyyed Hossein. Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man. London: George Allen & Unwin, 1976. (Dasar-dasar Eko-Sufisme).
[10]. Camus, Albert. The Myth of Sisyphus. Terj. Justin O’Brien. New York: Vintage Books, 1991. (Kajian tentang absurditas eksistensial).
[11]. Plato. Republic. (Konsep Ide/Form yang abadi).
[12]. Nietzsche, Friedrich. Thus Spoke Zarathustra. (Filosofi Will to Power).
[13]. Hasbullah Bakry, H. Ilmu Tasawuf. Jakarta: Widjaja, 1986. (Materi tentang Sirr, Qalb, dan Rabitah dalam Tarekat).
[14]. Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah. Bandung: Salamadani, 2009. (Kajian historis tentang peran ulama dan makam keramat).
[15]. Hasan, Noorhaidi. Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 2005. (Memberikan konteks tentang kontestasi teologis atas situs keramat).
[16]. Tijab, A. M. Panjalu dan Jejak Islam di Tatar Sunda. Bandung: Yayasan Laswi, 2012. (Kajian tentang Syekh Panjalu dan integrasi Islam dengan tradisi Sunda).
[17]. Daud, Idrus. Arsitektur Islam di Jawa. Jakarta: Pustaka Jaya, 2005. (Analisis arsitektur Makam Sendang Dhuwur).
—-
*Gus Nas Jogja, budayawan.