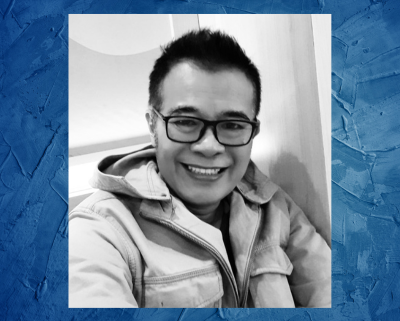Hakikat Suluk dalam Tradisi Tasawuf
Oleh Abdul Wachid B.S.*
1. Kekosongan Manusia Modern di Tengah Kelimpahan Hidup
Di era layar bercahaya dan sentuhan jari yang mudah, manusia justru semakin sering merasa hampa. Paradoks ini nyata: kebutuhan materi mudah dipenuhi, namun makna hidup terasa jauh. Kita dikelilingi informasi, hiburan, pilihan, dan peluang, tetapi batin sering kehilangan arah pulang. Pertanyaan tentang makna hidup bukan sekadar sosiologis, melainkan menyentuh inti keberadaan manusia.
Viktor Frankl menegaskan bahwa penderitaan terbesar manusia modern bukanlah kemiskinan, melainkan kehampaan eksistensial: hidup tanpa tujuan yang jelas (Frankl, Man’s Search for Meaning, Boston: Beacon Press, 1959). Kehampaan ini sering tersembunyi di balik kesibukan: orang bergerak dari satu target ke target lain tanpa menanyakan; untuk apa semua ini dijalani? Aktivitas sehari-hari menjadi rangkaian gerak, bukan perjalanan kesadaran.
Dalam perspektif tasawuf, kondisi ini mencerminkan keterputusan antara lahir dan batin. Dunia modern menekankan penguasaan ruang luar, tetapi melupakan penataan ruang dalam. Seyyed Hossein Nasr menyebut krisis ini sebagai akibat hilangnya dimensi spiritual dalam peradaban materialistis (Nasr, Knowledge and the Sacred, New York: Crossroad, 1989). Manusia bergerak cepat, namun tidak tahu kemana arah hidupnya.
Kehampaan sering muncul sebagai kelelahan psikis, kecemasan tanpa sebab, atau rasa jenuh yang sulit dijelaskan. Erich Fromm mengamati bahwa manusia modern lebih menekankan “memiliki” daripada “menjadi”, sehingga identitas diukur dari kepemilikan, bukan kedalaman batin (Fromm, To Have or To Be? New York: Harper & Row, 1976). Ketika kepemilikan tak lagi memberi kepuasan, tersisa kekosongan yang sulit diisi.
Di sinilah sastra, terutama sastra sufistik, hadir sebagai cermin batin. Puisi sufi tidak berbicara tentang kemewahan dunia, melainkan kerinduan pulang. Jalaluddin Rumi menulis bahwa manusia bagaikan seruling bambu yang merintih karena terpisah dari asalnya (Rumi, The Mathnawi of Jalaluddin Rumi, London: Luzac, 1926). Ratapan seruling itu adalah ratapan jiwa manusia yang jauh dari sumber makna. Kegelisahan malam hari adalah bahasa lain dari kerinduan yang sama.
Menariknya, kekosongan dapat menjadi pintu kesadaran. Dalam tasawuf, hampa bukan selalu musibah; ia bisa menjadi tanda panggilan bagi jiwa. Saat kenikmatan dunia tak lagi memuaskan, manusia mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Di sinilah suluk bermula, bukan dari kepastian, tetapi dari kegelisahan yang jujur. Jalan spiritual lahir dari pertanyaan sederhana: adakah makna yang lebih luas dari hidup yang berulang?
Perjalanan menuju kesadaran tidak mudah. Dunia modern menawarkan pelarian instan: hiburan tanpa jeda, konsumsi tanpa batas, distraksi yang terus-menerus. Semua menenangkan sesaat, tapi tidak menyembuhkan. Seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Tasawuf mengajarkan bahwa penyembuhan sejati datang dari dalam: penataan hati melalui tazkiyah, penyucian jiwa. Tanpa ini, kelimpahan luar justru mempertebal kekosongan batin.
Kehampaan manusia modern sebaiknya dilihat dengan empati, bukan penghakiman. Ia bukan kelemahan moral, melainkan konsekuensi sejarah peradaban yang bergerak cepat. Suluk bukan pelarian dari dunia, melainkan cara baru memaknainya. Jalan pulang bukan meninggalkan kehidupan, tetapi menemukan pusat makna di dalamnya.
Di sinilah pentingnya hening. Bukan hening kosong, tetapi hening yang mendengarkan. Dalam keheningan, manusia menyadari kegelisahan yang selama ini dihindari adalah undangan: untuk berhenti sejenak, menengok ke dalam, dan bertanya: di manakah rumah sejati jiwa? Pertanyaan sederhana ini mampu mengubah arah hidup.
Suluk berangkat dari kesadaran akan kekosongan itu sendiri. Tanpa hampa, manusia mungkin tidak pernah mencari makna. Tanpa kehilangan arah, ia mungkin tidak pernah menemukan jalan pulang. Paradoks manusia modern menyimpan rahasia: di balik kelimpahan melelahkan, tersembunyi pintu menuju kedalaman. Hanya mereka yang berani memasuki keheningan yang dapat melihat pintu itu perlahan terbuka. Di titik sunyi itu, perjalanan baru dimulai: perjalanan pulang yang telah lama dicari jiwa.
2. Definisi Suluk, Tazkiyah, dan Perjalanan Menuju Allah
Di tengah kegelisahan yang mulai disadari manusia modern, muncul pertanyaan yang lebih tenang namun mendalam: ke manakah jiwa ingin kembali? Pertanyaan ini sering tidak terucap, tetapi diam-diam bekerja di sela kesibukan dan keberhasilan yang terasa kosong. Tradisi tasawuf memberi nama bagi gerak batin ini: suluk, perjalanan yang diukur bukan oleh jarak ruang, tetapi oleh kedalaman kesadaran.
Secara etimologis, suluk berasal dari bahasa Arab salaka, “menempuh jalan.” Dalam pengertian spiritual, maknanya meluas menjadi proses mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian batin dan penataan hati. Para ulama menjelaskan bahwa perjalanan seorang salik adalah perpindahan dari sifat manusiawi yang terbatas menuju penyaksian kehadiran Ilahi yang melampaui batas (al-Qusyairi, al-Risalah al-Qusyairiyyah, Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1966).
Suluk selalu terkait dengan tazkiyat al-nafs, penyucian jiwa. Tanpa penjernihan batin, perjalanan spiritual hanya menjadi simbol kosong. Al-Ghazali menegaskan bahwa hati manusia ibarat cermin: ia memantulkan kebenaran hanya ketika dibersihkan dari kesombongan, hasrat berlebihan, dan keterikatan duniawi (al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983). Masalah utama manusia bukan kurangnya pengetahuan, tetapi keruhnya hati yang menerima pengetahuan itu.
Suluk bukan sekadar memahami ketuhanan, tetapi mengalami transformasi hidup. Seyyed Hossein Nasr melihat tradisi spiritual Islam sebagai jalan untuk keluar dari krisis makna menuju kesadaran akan Yang Sakral: pusat yang memberi arti pada seluruh keberadaan (Nasr, 1989). Dengan demikian, suluk mengembalikan orientasi hidup dari yang tercerai-berai menuju terpadu.
Perjalanan menuju Allah tidak instan. Para sufi menggambarkannya sebagai proses bertahap yang membutuhkan perjuangan batin, kesabaran, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Jalan ini sering sunyi, terasa asing bagi logika dunia cepat. Justru di situlah maknanya: kedalaman lahir dari kesediaan berjalan perlahan sambil memahami setiap langkah.
Tasawuf tidak memandang dunia sebagai musuh. Dunia tetap ruang kehidupan, tetapi bukan pusat keterikatan. Ibn ‘Athaillah al-Sakandari menekankan bahwa keterikatan berlebihan pada selain Allah menimbulkan kegelisahan, sementara ketergantungan kepada-Nya mendatangkan ketenteraman batin (Ibn ‘Athaillah, al-Hikam, Kairo: Dar al-Salam, 2004). Masalah bukan dunia itu sendiri, tetapi posisi hati manusia terhadapnya.
Dalam praktiknya, suluk dimulai dari kesadaran akan keterbatasan diri. Pengetahuan, kekuasaan, atau pencapaian tidak mampu menjawab seluruh pertanyaan batin. Kesadaran ini membuka kemungkinan baru: mencari makna yang lebih dalam daripada sekadar keberhasilan lahiriah. Di sinilah suluk menyentuh pengalaman universal manusia: kebutuhan untuk memahami diri sendiri dan asal kerinduan jiwa.
Sastra sufistik menggambarkan perjalanan ini dengan bahasa lembut dan menembus. Rumi, misalnya, menulis manusia sebagai pengembara yang mencari rumah asalnya, digerakkan oleh cinta yang kadang tak dipahami akal (Rumi, 1926). Metafora pengembaraan ini bukan sekadar puitik, tetapi cerminan kesadaran bahwa hidup memiliki arah batin yang lebih dalam daripada permukaan terlihat.
Pada akhirnya, suluk adalah proses mengingat; bukan masa lalu, tetapi asal keberadaan manusia dari Tuhan. Manusia yang menempuh suluk sedang merespons panggilan lama yang bersemayam di kedalaman jiwa.
Kesadaran ini memberi makna baru pada aktivitas sehari-hari. Bekerja, belajar, dan berinteraksi dapat menjadi bagian perjalanan spiritual ketika dijalani dengan hati yang terarah. Suluk bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi menghadirkan keheningan batin di tengah kehidupan. Dari situ, perjalanan menuju Allah berlangsung tanpa harus terlihat, namun nyata bagi jiwa yang bersedia mendengarkan panggilan terdalam.
3. Pandangan Tasawuf Klasik tentang Perjalanan Batin Manusia
Dalam tasawuf klasik, perjalanan batin selalu digambarkan sebagai proses internal, bertahap, dan penuh tantangan. Bagi para sufi, batin bukan sekadar wilayah psikologis, tetapi medan sakral untuk menyaksikan kehadiran Ilahi. Dengan demikian, suluk adalah penataan diri yang mengarah pada kesadaran total akan Tuhan, bukan sekadar ritual atau kepatuhan lahiriah.
Al-Qusyairi menegaskan bahwa seorang salik harus melewati tingkatan spiritual yang menata hati dan akal, agar cahaya Ilahi dapat masuk tanpa terhalang keserakahan, hawa nafsu, atau keterikatan duniawi (al-Qusyairi, 1966). Tingkatan ini menuntut latihan kontinu dan kesadaran penuh terhadap diri sendiri. Seorang sufi menyadari bahwa perjalanan batin diukur bukan oleh dunia, melainkan oleh kedalaman hati.
Al-Ghazali menekankan pentingnya menyingkirkan sifat negatif seperti marah, tamak, dan kesombongan. Hati yang bersih memungkinkan manusia memahami hakikat penciptaan dan menempatkan dunia di posisi yang tepat: bukan pusat, tetapi medium mendekat kepada Tuhan (al-Ghazali, 1983). Dengan demikian, suluk selalu terkait praktik etis dan moral, karena kesucian hati menjadi jembatan menuju pengalaman ilahi.
Perjalanan batin juga dibedakan melalui maqāmāt dan aḥwāl. Maqāmāt adalah tahapan objektif yang ditempuh seorang salik, seperti taubat, sabar, tawakal, ridha, dan mahabbah. Sebaliknya, aḥwāl adalah keadaan spiritual yang muncul secara tiba-tiba: ekstase, kedamaian, atau pengalaman batin yang melampaui akal. Ibn ‘Ata’illah menegaskan bahwa maqāmāt harus diiringi kesadaran bahwa aḥwāl adalah karunia Tuhan, bukan hasil usaha manusia semata (Ibn ‘Athaillah, 2004).
Rumi memperkaya pemahaman ini dengan bahasa metaforis. Bagi Rumi, perjalanan batin manusia seperti sungai yang mengalir menuju laut hakikat. Arusnya kadang tenang, kadang deras, tetapi setiap pengalaman (kesedihan, kerinduan, atau cinta) menjadi dorongan untuk mendekat pada sumber (Rumi, 1926). Metafora ini menegaskan bahwa perjalanan spiritual tidak linear, tetapi dinamis dan terarah.
Tasawuf klasik menekankan keseimbangan antara praktik batin dan kehidupan nyata. Dunia bukan musuh, melainkan laboratorium latihan: setiap interaksi, pekerjaan, dan tantangan menjadi cermin kualitas hati. Nasr menekankan bahwa spiritualitas Islam klasik memandang dunia sebagai arena pengalaman, bukan objek penolakan total (Nasr, 1989). Kedekatan dengan Tuhan muncul dari integrasi hidup dengan kesadaran ilahi, bukan pelarian.
Para sufi juga menekankan peran guru spiritual (murshid). Guru membimbing secara personal, mengenali titik lemah dan kuat murid, serta menuntun melalui maqāmāt dan aḥwāl dengan bijak. Hubungan ini sakral, karena pengalaman batin tidak cukup dipelajari dari teks; ia harus dialami dan dipandu dengan kesadaran mendalam (al-Qusyairi, 1966).
Secara keseluruhan, tasawuf klasik memberikan kerangka sistematis bagi perjalanan batin: transformasi dari keterikatan duniawi menuju kesadaran akan Yang Maha Esa. Perjalanan ini menuntut keberanian menatap kekosongan, menerima tantangan internal, dan menyucikan diri melalui tazkiyah. Memahami tasawuf klasik berarti menyadari posisi diri dalam perjalanan batin, dan menjadikan setiap tindakan sehari-hari sarana mendekat kepada Allah.
4. Krisis Makna, Kelelahan Psikis, dan Percepatan Zaman
Manusia modern hidup dalam arus percepatan yang tak henti. Informasi berdatangan setiap detik, tuntutan produktivitas meningkat, dan waktu terasa semakin sempit. Di tengah kelimpahan ini, banyak orang mengalami krisis makna: meski segala sesuatunya tampak tersedia, hidup tetap terasa hampa. Viktor Frankl menekankan bahwa manusia haus akan arti; ketika makna itu hilang, muncul kehampaan eksistensial yang mendalam (Frankl, 1959).
Kelelahan psikis menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Orang berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain, tetapi batin tetap kosong. Erich Fromm menunjukkan bahwa orientasi modern yang menekankan “memiliki” ketimbang “menjadi” membuat identitas diukur dari kepemilikan, bukan kedalaman keberadaan (Fromm, 1976). Sehingga materi tercukupi, tetapi jiwa tetap letih, dan kepuasan terasa jauh.
Percepatan zaman juga menimbulkan fragmentasi sosial. Komunikasi instan sering mengorbankan kedalaman percakapan, membuat hubungan manusia dangkal. Nasr menegaskan bahwa hilangnya dimensi spiritual menimbulkan krisis nilai, sehingga manusia kehilangan pusat dan arah (Nasr, 1989). Dunia yang serba cepat memaksa manusia bergerak refleks, tanpa jeda untuk menata batin.
Dalam perspektif tasawuf, krisis makna bukan sekadar gejala sosial, tetapi panggilan batin. Ia adalah tanda bahwa jiwa tersesat, menunggu diingatkan kembali pada asalnya. Al-Ghazali menggambarkan hati manusia seperti cermin yang kotor; hanya ketika dibersihkan, cahaya kebenaran dapat memantul dengan jelas (al-Ghazali, 1983). Kelelahan psikis dan kehampaan menjadi “pintu masuk” bagi suluk, tanda kesiapan batin menata diri dan menemukan arah kembali.
Sastra sufistik merespons fenomena ini dengan metafora halus namun menohok. Rumi menulis bahwa jiwa sering terombang-ambing di lautan dunia, gelisah karena kehilangan rumah asalnya (Rumi, 1926). Kegelisahan itu mencerminkan pengalaman manusia universal: di tengah percepatan zaman, kita mencari titik hening yang menegaskan makna hidup.
Suluk menawarkan cara menghadapi dunia yang bergerak cepat tanpa terseret olehnya. Jalan batin menekankan kesadaran saat ini, latihan batin untuk menenangkan kegelisahan, dan penataan hati agar tidak terjebak hiruk-pikuk dunia. Ibn ‘Athaillah menegaskan bahwa ketergantungan pada Allah menyembuhkan kegelisahan batin, sedangkan keterikatan berlebihan pada dunia memperkuat kelelahan (Ibn ‘Athaillah, 2004).
Dengan demikian, krisis makna dan kelelahan psikis bukan sekadar masalah individu, tetapi undangan untuk merenung. Mereka yang mampu menghadapi percepatan zaman dengan kesadaran batin menemukan makna di balik kekacauan: bahwa hidup tidak hanya tentang kecepatan dan pencapaian, tetapi juga tentang kesediaan berhenti, menata batin, dan menapaki jalan pulang menuju kesadaran yang lebih tinggi.
5. Puisi Sufi tentang Kerinduan Pulang
Di tengah kegelisahan manusia modern, puisi sufistik hadir sebagai cermin batin, lembut, namun tajam. Ia berbicara tentang rindu yang tak terucap, dorongan batin yang mengajak jiwa kembali pada asalnya. Kerinduan ini bukan romantisme duniawi, melainkan panggilan spiritual yang muncul di sela kesibukan dan kelelahan psikis.
Rumi menggambarkan manusia sebagai seruling yang merintih karena terpisah dari rumah asalnya:
“Setiap seruling yang menangis adalah jiwa yang mencari rumahnya; setiap napas adalah perjalanan pulang.”(Rumi, 1926)
Metafora seruling menegaskan bahwa kerinduan pulang adalah bahasa jiwa universal, hadir tanpa tergantung budaya atau pendidikan. Puisi sufi menuntun manusia menyadari panggilan batin menuju yang sakral.
Ibn ‘Arabi melihat kerinduan sebagai perjalanan “mengingat yang hilang”:
“Hati yang tersesat dalam dunia adalah rindu yang menunggu disentuh cahaya Ilahi.”
(Ibn ‘Arabi, Futuhat al-Makkiyah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1982)
Kerinduan ini membawa makna transformatif, menandai kesadaran manusia akan keterpisahan diri fana dari pusat hakikat. Puisi sufistik menjadi peta batin, menyingkap jalur pulang yang tersembunyi namun terasa di setiap detak kehidupan.
Dari Persia hingga Anatolia, puisi sufi menegaskan bahwa kerinduan pulang lahir dari pengalaman batin, dari rasa kehilangan yang dihayati sepenuh hati. Hafiz menulis:
“Aku haus, dan setiap tetes dunia hanya menambah dahagaku; pulang hanya bisa kutemukan di laut keabadian.”(Hafiz, Divan-e Hafiz, Teheran: Amirkabir, 1978)
Kutipan ini menunjukkan paradoks manusia modern: semakin mengejar dunia, semakin terasa kekosongan. Puisi sufistik mengingatkan bahwa inti pencarian adalah kedamaian batin, rumah yang selalu menunggu di dalam diri.
Kerinduan pulang tidak mengasingkan manusia dari dunia, tetapi menata relasi antara dunia dan batin. Ia hadir untuk membangun kesadaran: menjalani hidup dengan orientasi batin yang benar. Rumi menegaskan bahwa jiwa yang merindukan pulang menemukan dirinya dalam setiap peristiwa hidup bila mampu mendengar bahasa batin (Rumi, 1926).
Sastra sufistik menunjukkan bahwa puisi bukan sekadar kata, melainkan jalan batin. Setiap metafora (seruling, laut, cahaya, rumah) adalah peta menuju kesadaran diri dan kehadiran Ilahi. Bagi yang merenung, kerinduan pulang menjadi isyarat spiritual, menuntun hidup agar selaras antara perjalanan lahiriah dan batin.
Dengan demikian, puisi sufi berfungsi sebagai instrumen suluk, menghubungkan kesadaran estetis dengan pengalaman spiritual. Kerinduan pulang bukan kemewahan batin, tetapi kebutuhan fundamental manusia, panggilan diam-diam di tengah kesibukan, yang mengingatkan bahwa perjalanan lahiriah sebaiknya selaras dengan perjalanan batin.
6. Suluk sebagai Kebutuhan Universal Manusia
Manusia pada hakikatnya selalu mencari jalan untuk memahami dirinya sendiri. Terlepas dari budaya, zaman, atau kondisi sosial, ada dorongan batin universal: kembali pada pusat makna. Suluk, dalam perspektif tasawuf, bukan sekadar tradisi religius, melainkan manifestasi kebutuhan eksistensial manusia untuk menemukan orientasi hidup yang lebih dalam.
Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa peradaban yang sehat selalu menyertakan dimensi spiritual; tanpa itu, manusia mudah tersesat dalam materialitas dan kehilangan arah batin (Nasr, 1989). Suluk hadir sebagai sarana pemulihan jiwa, menegaskan bahwa kesadaran batin adalah fondasi kebahagiaan sejati.
Kebutuhan akan suluk tampak dalam pengalaman manusia sehari-hari: gelisah menghadapi rutinitas yang menekan, pencapaian yang tidak memuaskan, atau hidup yang terasa terlalu cepat. Viktor Frankl mencatat bahwa manusia modern sering mengalami “kehampaan eksistensial” karena kehilangan pusat makna hidupnya (Frankl, 1959). Kebutuhan untuk kembali pada pusat itu (melalui refleksi, meditasi, atau perjalanan spiritual) merupakan bentuk konkret kebutuhan universal akan suluk.
Al-Ghazali menekankan pentingnya tazkiyah, penyucian batin, agar manusia dapat merasakan kesadaran sejati. Tanpa penjernihan hati, pencarian makna akan terhenti pada permukaan, terperangkap oleh kenikmatan lahir dan keinginan duniawi (al-Ghazali, 1983). Suluk, dengan demikian, adalah cara manusia mendekat pada hakikat eksistensi, kebutuhan intrinsik yang tidak bisa diabaikan.
Sufi klasik melihat suluk sebagai proses universal, menyentuh setiap lapisan keberadaan: fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Al-Qusyairi menegaskan bahwa perjalanan seorang salik adalah transformasi diri, mengenali keterikatan yang tidak sehat pada dunia, dan menundukkan ego demi kesadaran Ilahi (al-Qusyairi, 1966).
Pengalaman lintas budaya juga menunjukkan kesamaan kebutuhan ini. Mistisisme Kristen, Hindu, maupun Buddha menekankan perjalanan batin untuk menemukan keseimbangan dan kesadaran sejati. Suluk Islam, dalam konteks ini, menjadi ekspresi universal manusia, bukan sekadar praktik ritual, melainkan respons eksistensial terhadap kebutuhan mendasar jiwa.
Puisi sufistik menegaskan hal serupa. Rumi menulis bahwa setiap jiwa membawa rindu untuk kembali ke sumbernya, meski jalannya tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari (Rumi, 1926). Rindu ini bukan sentimental, tetapi ontologis: dorongan melekat dalam keberadaan manusia, menandai bahwa perjalanan pulang adalah bagian integral hidup.
Dalam kehidupan modern, kesadaran akan kebutuhan batin ini semakin penting. Kelelahan psikis, percepatan zaman, dan tekanan sosial membuat manusia cenderung mengabaikan dimensi batin. Suluk hadir sebagai pengingat lembut bahwa dunia luar tidak cukup memuaskan. Kebutuhan manusia mencakup batin yang haus akan makna dan kesatuan dengan Yang Sakral.
Dengan demikian, suluk adalah kebutuhan universal manusia, menyentuh inti eksistensi: kesadaran bahwa hidup bukan hanya bertahan atau mencapai tujuan lahir, tetapi memahami diri, mengingat asal, dan menata hati. Tanpa perjalanan batin ini, manusia modern tetap merasa hampa meski berada di tengah kelimpahan, dan puisi, filosofi, serta tasawuf menjadi peta yang menuntun menuju pusat itu.
7. Pengalaman Kehilangan Arah dalam Hidup
Hampir setiap manusia, pada suatu titik, merasakan kehilangan arah. Fenomena ini bukan sekadar sensasi sementara, tetapi pengalaman eksistensial yang menandai ketidakharmonisan antara jiwa dan dunia luar. Di era modern, kehilangan arah muncul di tengah pilihan yang tak terhitung, target yang terus bergeser, dan tuntutan yang tak berujung. Seseorang bisa memiliki pekerjaan mapan, keluarga lengkap, atau prestasi membanggakan, namun tetap merasa hidupnya berjalan tanpa peta.
Sekali lagi, Erich Fromm menjelaskan bahwa krisis ini timbul ketika manusia menekankan “memiliki” daripada “menjadi”; identitas dan makna hidup diukur dari kepemilikan materi, status, atau prestasi lahiriah, bukan kedalaman batin (Fromm, 1976). Saat pencapaian tidak lagi memuaskan, muncul rasa hampa yang menyentuh inti eksistensi: kebingungan ontologis ketika jiwa tidak menemukan rumahnya.
Tradisi tasawuf memberi bahasa bagi pengalaman ini. Ibn ‘Arabi menyatakan bahwa manusia lahir dengan rindu primordial untuk kembali ke pusat asalnya, tetapi sering kehilangan arah akibat keterikatan duniawi: kesibukan, ambisi berlebihan, atau obsesi akan status dan citra (Ibn ‘Arabi, Fusus al-Hikam, Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1965). Setiap keterikatan yang tidak disadari menambah kabut yang menghalangi pandangan batin, sehingga jiwa tersesat meski hidup terasa aman dan terpenuhi.
Kehilangan arah biasanya disertai kegelisahan psikis dan rasa jenuh yang sulit dijelaskan. Viktor Frankl menegaskan bahwa manusia yang kehilangan makna hidup mengalami kekosongan yang lebih berat daripada penderitaan fisik (Frankl, 1959). Momen hening atau peristiwa yang menuntut refleksi sering menjadi titik sadar: pencapaian lahiriah tidak menjawab pertanyaan terdalam, “Siapakah aku, dan ke mana aku seharusnya pulang?”
Pengalaman ini juga membuka pintu bagi kesadaran spiritual. Dalam tasawuf, keterasingan jiwa bukan kegagalan, tetapi undangan untuk menempuh suluk: perjalanan batin menuju kesadaran akan Yang Sakral. Al-Ghazali menggambarkan hati manusia seperti cermin yang mudah ternoda oleh kesibukan duniawi; hanya ketika sadar akan keterasingannya, jiwa mulai membersihkan cermin itu melalui tazkiyah, menata ulang arah hidup (al-Ghazali, 1983). Kesadaran ini berkembang perlahan melalui refleksi, keheningan, dan perhatian penuh terhadap tanda batin.
Sastra sufistik memberikan bahasa bagi pengalaman ini. Rumi menulis tentang manusia tersesat seperti anak-anak yang mencari rumah asalnya: perjalanan pulang penuh rintangan, namun dorongan batin akan selalu menuntun kembali (Rumi, 1926). Kehilangan arah bukan kesalahan, tetapi bagian alami perjalanan spiritual: kesadaran atas ketidakpastian dan kerinduan untuk kembali adalah titik awal suluk.
Kehilangan arah juga menjadi kesempatan untuk pengamatan diri. Saat berhenti sejenak dan menoleh ke dalam, manusia mulai melihat keterikatan dan ilusi yang membutakan. Ibn ‘Ata’illah al-Sakandari menekankan bahwa manusia tersesat bukan karena dunia, tetapi karena hati yang melekat pada selain Allah; ketika hati diarahkan kembali kepada Yang Sakral, arah hidup menjadi jelas (Ibn ‘Athaillah, 2004). Hilangnya arah lahiriah menjadi panggilan untuk menemukan arah batin.
Dalam konteks modern, pengalaman kehilangan arah bersifat universal. Ia dialami oleh siapa saja yang hidup di tengah percepatan zaman, tekanan sosial, dan arus informasi tanpa henti. Kesadaran ini menegaskan bahwa suluk bukan kemewahan spiritual, melainkan kebutuhan eksistensial: tanpa menyadari kehilangan arah, manusia bisa terus sibuk tanpa tujuan sejati.
8. Ajakan Hening Memulai Perjalanan Pulang
Di penghujung refleksi ini, muncul ajakan sederhana namun mendalam: berhenti sejenak, diam, dan dengarkan panggilan batin. Hening bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang bagi jiwa untuk menyadari dirinya, menelisik arah yang hilang, dan membuka pintu perjalanan pulang. Dalam kesibukan modern, hening sering dianggap kemewahan; padahal ia sarana utama menemukan kembali pusat makna.
Rumi menulis bahwa manusia bagaikan seruling yang rindu kembali ke sumbernya, dan setiap nada hening adalah kesempatan bagi jiwa menyesuaikan diri dengan irama Ilahi (Rumi, 1926). Diam memungkinkan kita mendengar suara yang selama ini terpendam: kerinduan, rasa bersalah, harapan, dan yang terutama, suara Tuhan. Hening menjadi langkah awal suluk, pintu masuk perjalanan spiritual.
Al-Ghazali menegaskan bahwa kesadaran batin muncul saat manusia menenangkan pikiran dan membersihkan hati dari gangguan duniawi (al-Ghazali, 1983). Dengan hening, manusia mampu melihat keterikatan dan ilusi yang menutupi pandangan batin. Proses ini bukan sekadar introspeksi psikologis, tetapi tazkiyah: penyucian jiwa yang menyiapkan langkah menuju Allah. Tanpa hening, perjalanan spiritual sering tersandung kebisingan dunia dan kegelisahan batin.
Hening juga memungkinkan kita memahami pengalaman universal manusia: kehilangan arah, kebingungan, dan kerinduan pulang bukan untuk dihindari, tetapi diterima sebagai undangan bertransformasi. Ibn ‘Ata’illah al-Sakandari menekankan bahwa ketenangan hati muncul ketika manusia menyerahkan keterikatan yang salah kepada Yang Maha Esa, membiarkan jiwa menyesuaikan diri dengan cahaya Ilahi (Ibn ‘Athaillah, 2004). Dengan demikian, hening adalah langkah diam, tetapi penuh makna, memulai suluk yang sejati.
Seni dan sastra sufistik menghidupkan ajakan ini. Puisi-puisi sufi tidak sekadar bercerita, tetapi memandu pembaca merasakan keheningan dalam kata-kata. Rumi menulis: “Diam adalah bahasa jiwa; dengarkan, maka jalan pulang akan terbuka” (Rumi, 1926). Perjalanan pulang bukan langkah fisik, melainkan batin, dari kesibukan ke keheningan, dari gelisah ke sadar, dari tercerai-berai ke terpadu.
Dalam praktik, hening dapat dimulai dari hal kecil: duduk beberapa saat tanpa gangguan, merenungkan pernapasan, atau menatap alam dengan kesadaran penuh. Hal sederhana ini membuka ruang bagi jiwa mengenali dirinya, merasakan kerinduan tersembunyi, dan menyiapkan diri menapaki jalan spiritual. Hening bukan pelarian, tetapi kunci menata ulang arah hidup, menjembatani kesadaran modern dengan tradisi tasawuf yang kaya makna.
Dengan kesadaran ini, pembaca diundang menempatkan diri pada posisi jiwa yang mendengar, merasakan, dan siap menempuh jalan batin. Hening adalah panggilan awal suluk modern yang memadukan pengalaman kontemporer dengan kedalaman tradisi tasawuf. ***
——
Daftar Pustaka
al-Ghazali. 1983. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
al-Qusyairi, Abu al-Qasim. 1966. al-Risalah al-Qusyairiyyah. Kairo: Dar al-Ma‘arif.
Frankl, Viktor E. 1959. Man’s Search for Meaning. Boston: Beacon Press.
Fromm, Erich. 1976. To Have or To Be? New York: Harper & Row.
Hafiz. 1978. Divan-e Hafiz. Teheran: Amirkabir.
Ibn ‘Arabi. 1965. Fusus al-Hikam. Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Ibn ‘Arabi. 1982. Futuhat al-Makkiyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Ibn ‘Athaillah al-Sakandari. 2004. al-Hikam. Kairo: Dar al-Salam.
Nasr, Seyyed Hossein. 1989. Knowledge and the Sacred. New York: Crossroad.
Rumi, Jalaluddin. 1926. The Mathnawi of Jalaluddin Rumi. London: Luzac.
—-
*Penulis adalah penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.