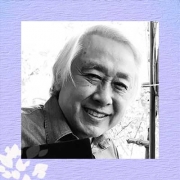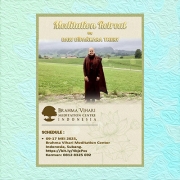Etika Bunyi, Estetika Performatif dan Problematika Subaltern
Oleh Purnawan Andra*
Malam-malam desa, jalan-jalan gang kota pinggiran, atau lapangan kecil di kampung-kampung Jawa Timur khususnya, kini sering kali bergema dengan irama dentuman bass dan sorak sorai dari pengeras suara raksasa. Fenomena ini, yang oleh masyarakat luas dikenal sebagai sound horeg, bukan sekadar perkara hiburan murah meriah. Ia adalah peristiwa budaya, semacam “konser rakyat” yang liar, kasar, sekaligus kompleks dalam jaring kekuasaan ruang, ekonomi, dan simbol-simbol identitas kelas subaltern.
Sound horeg biasanya lahir dari acara hajatan seperti pernikahan, sunatan, atau perayaan ulang tahun. Tapi ekspansinya menjadikan ia tak hanya sebagai pengiring acara, melainkan sebagai tontonan utama. Di Jawa Timur khususnya, sound horeg bahkan telah menjadi bentuk “pergelaran baru”, lengkap dengan MC, penari, lighting, dan efek asap panggung, menyerupai miniatur festival musik elektronik kelas kampung.
Pergelaran dan Ritus Sosial
Dalam kajian antropologi pertunjukan, apa yang disebut sound horeg bisa dibaca sebagai perluasan dari ritus komunal. Dahulu, masyarakat Jawa mengenal tayuban, sandiwara keliling, atau ludruk sebagai ruang selebrasi rakyat. Kini, sound horeg mengambil alih fungsi-fungsi itu dalam bentuk yang lebih digital, lebih massal, dan lebih gegap gempita. Ia menjadi salah satu contoh transformasi medium, jika bukan transformasi makna.
Kita menyaksikan bagaimana masyarakat kelas bawah membentuk cara berbahasa budaya mereka sendiri. Alih-alih mengundang grup musik ternama atau menampilkan gamelan, mereka lebih memilih “sound system segede gunung” dan DJ lokal yang memainkan remix dangdut koplo hingga EDM. Dalam banyak hal, ini menjadi artikulasi baru dari hak atas hiburan dan selebrasi, di tengah ketimpangan akses terhadap pertunjukan yang lebih elitis dan berbayar.
Di sisi lain, budaya ini menunjukkan bagaimana masyarakat tak hanya mewarisi tradisi, tetapi juga menafsir ulang dan mengadaptasinya ke dalam format masa kini, meskipun kadang menuai resistensi dari generasi sebelumnya.
Sebagaimana Emile Durkheim pernah katakan, ritus sosial selalu menjadi peristiwa kolektif yang mempersatukan masyarakat lewat simbol dan tindakan bersama. Dalam hal ini, sound horeg menjadi ajang pelepasan tekanan sosial, terutama bagi kelas pekerja yang hidup dalam keterbatasan. Dentuman musik menjadi katarsis, tubuh yang bergoyang menjadi pelampiasan, dan panggung terbuka menjadi ruang eksistensi diri.
Dalam hal ini, sound horeg membongkar batas-batas konvensional dalam pergelaran. Dengan ruang terbuka, publik, dan merembes ke jalan-jalan, suara menjadi elemen utama, yang bahkan mengalahkan visual dan bentuk narasi.
Dalam logika performatif, ini adalah bentuk ruang publik sebagai panggung yang cair di mana semua orang adalah penonton sekaligus performer. Tidak ada panggung tunggal, tapi ada atmosfer tunggal berupa gebrakan/sensasi suara. Dengan begitu, sound horeg menjadi perayaan keterbukaan ruang dan suara di mana tubuh-tubuh merespons frekuensi bunyi bukan secara koreografis formal, tetapi lewat spontanitas yang justru menciptakan bentuk tarian sosial tersendiri.
Ekonomi Hingar Bingar dan Kapitalisasi Bunyi
Namun sound horeg bukanlah praktik yang steril dari logika kapital. Ia tumbuh dalam lanskap ekonomi informal. Pemilik usaha rental sound, MC, operator lighting, hingga penjual minuman di sekitar acara, semuanya membentuk ekosistem yang bergantung pada event ini. Di beberapa tempat, terdapat kompetisi antar grup sound system untuk pamer kemampuan suara dan perangkat, seperti kontes adu kuat dan “bening” audio.
Fenomena ini memperlihatkan satu hal: bunyi telah menjadi komoditas. Dalam dunia sound horeg, kualitas suara bukan soal artistik belaka, tetapi soal prestise dan nilai jual. Seturut logika ahli ekonomi dan sosial Prancis Jacques Attali, bunyi bukan hanya perwujudan ekspresi estetis, tapi juga alat produksi, konsumsi, dan kontrol sosial. Volume menjadi kuasa. Siapa yang punya suara paling besar, dialah yang menguasai ruang dan mendapatkan respek.
Sayangnya, logika kapital dalam sound horeg juga menjebak masyarakat dalam pola konsumsi berlebihan. Tidak jarang, penyelenggara hajatan rela berutang atau menjual aset demi menyewa sound system besar dan panggung megah. Ini menunjukkan bahwa sound horeg, selain sebagai wujud kesenangan kolektif, juga bisa menjadi tekanan sosial—semacam ‘gengsi budaya’ yang melelahkan.
Ruang Publik dan Konflik Sosial
Konsekuensi lain dari sound horeg adalah konflik atas ruang dan waktu. Sound horeg mengaktifkan ruang komunal, tapi juga memproduksi ambiguitas, antara gotong royong dan dominasi suara, antara perayaan dan gangguan. Ada warga yang larut dalam kegembiraan, tapi tak sedikit pula yang terganggu karena suara hingga dini hari. Protes kerap muncul, dan tak jarang berujung cekcok bahkan kekerasan.
Di sinilah sound horeg menjadi titik tarik ulur antara kebebasan berekspresi dan hak atas ketenangan hidup bersama. Ia menjadi ajang tawar-menawar tentang batas toleransi sosial, etik budaya akustik, dan regulasi ruang publik di tingkat lokal.
Pada saat yang sama, ruang publik kita kerap kali tak punya regulasi kultural yang memadai. Negara tak hadir dalam bentuk aturan kultural yang adil dan adaptif, sementara masyarakat dibiarkan menyelesaikan konflik secara informal, sering kali dengan cara koersif. Dalam konteks ini, sound horeg menjadi simbol dari ketidakteraturan manajemen ruang bersama. Siapa yang bersuara lebih besar, dialah yang berkuasa.
Sejarawan agama dan kritikus budaya Prancis Michel de Certeau pernah membedakan antara “strategi” dan “taktik” dalam cara masyarakat menggunakan ruang. Sound horeg, dalam pandangan ini, adalah taktik masyarakat kecil untuk merebut ruang dari dominasi narasi elite. Tapi jika tak dikelola, taktik ini justru berbalik menjadi instrumen represi terhadap yang lain.
Imajinasi Sosial dan Representasi Kelas
Lebih jauh, sound horeg dapat dibaca sebagai manifestasi dari imajinasi sosial tentang bagaimana rakyat ingin mempresentasikan dirinya yaitu meriah, bergengsi, tampil. Dalam kondisi hidup yang serba kekurangan, sound horeg memberikan ilusi kemewahan. Acara digelar dengan panggung besar, tata lampu canggih, dan sensasi euforia yang luar biasa. Ini adalah bentuk pertunjukan tentang “eksistensi kita”.
Ini menjadi penanda penting dalam dinamika identitas kelas. Sound horeg bukan sekadar hiburan murahan, melainkan bentuk negosiasi visual dan audio tentang siapa kita, apa yang ingin kita tunjukkan, dan bagaimana kita ingin dikenang. Dalam hal ini, sound horeg menyuarakan suara mereka yang sering kali tak terdengar di panggung politik dan budaya arus utama.
Tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua ekspresi rakyat harus didewakan tanpa kritik. Kekerasan simbolik yang terjadi di panggung sound horeg seperti kekerasan akustik, penjajahan etika publik, okupasi ruang sosial, hingga glorifikasi konsumsi, perlu dikritisi. Tapi kritik tersebut harus disertai pemahaman atas konteks sosial yang melahirkannya, bukan semata dari moralisme kelas menengah. Apakah sound horeg adalah bentuk kebudayaan baru yang membebaskan, atau justru kebisingan kapital yang menyingkirkan bentuk-bentuk kebersamaan yang lebih intim dan berakar?
Menimbang Ulang Bunyi dan Budaya Kita
Fenomena sound horeg seharusnya menyadarkan kita bahwa ruang-ruang kebudayaan rakyat tidak boleh diremehkan. Di tengah banalitas media sosial dan keterasingan urban, peristiwa seperti ini justru menghadirkan kebersamaan, walau dalam bentuk yang sering kali dianggap “liar” atau “kampungan.” Tantangannya bukan menertibkan dengan pendekatan aparat, melainkan menghadirkan dialog kultural dan penataan ruang yang lebih sensitif terhadap realitas sosial.
Barangkali kita perlu membayangkan bagaimana jika sound horeg diberi panggung dalam festival kebudayaan lokal yang inklusif? Bagaimana jika tata kelola suara diatur berbasis musyawarah warga? Bagaimana jika negara hadir bukan sebagai pemadam kebisingan, melainkan fasilitator kreativitas rakyat?
Sound horeg, pada akhirnya, bukan hanya perkara selera. Ia adalah soal siapa yang boleh bersuara, siapa yang didengar, dan siapa yang diredam. Dan dalam kultur kita yang kian bising oleh berbagai kepentingan, barangkali kita perlu lebih jeli membedakan antara suara yang mengganggu dan suara yang selama ini dipinggirkan.
—
*Purnawan Andra, alumnus Governance & Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan