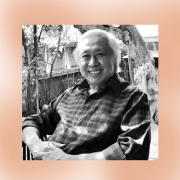Balada Sepeda Listrik, BWCF 2024
Oleh Nina Masjhur
“Nanti di sebelah sana, kalian bisa memakai sepeda listrik yang disediakan,” seseorang berkata kepada kami, dengan maksud menyemangati kami.
“Baiklah,” bisikku dalam hati sambil berjalan dengan super hati-hati di tanah berlumpur itu. Pada hari pertama Borobudur Writers & Culture Festival 2024 di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi itu, kami diturunkan di wilayah yang sedang dikerjakan untuk membangun fasilitas pendukung KCBN Muarajambi. Entah kenapa, kabarnya kami tidak diperkenankan turun di tempat yang seharusnya. Ya sudah, kami pun berjalan sambil menggerendeng dan tertawa-tawa bersama-sama. Seru juga sih…
Aku menyiapkan mentalku dalam hal mengorbankan sepatu sandal kesayanganku untuk bergelimang habis-habisan dalam lumpur. Namun, sebelum hal itu terjadi, jalanan berubah menjadi sebentuk jalan setapak dengan kerikil putih. Syukurlah! Tak lama, mungkin setelah berjalan sekitar sepuluh menitan (kalau tak salah ingat), kami tiba di sebuah pertigaan. Di lapangan berumput yang lebih terbuka di depan kami, berbaris sepeda-sepeda listrik berbagai warna.
“Silakan yang mau pakai sepeda listrik, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk melanjut ke Candi Kedaton,” beberapa petugas di situ mempersilakan kami –Candi Kedaton itu adalah tempat Borobudur Writers & Culture Festival (BWCF) ke-13 2024 diadakan.
“Terima kasih,” seruku riang gembira, “sayangnya saya tidak tahu beda antara pedal rem dan pedal gas,” jawabku menjelaskan —bahwa apakah sepeda listrik punya pedal atau tidak saja, aku pun sejatinya tak tahu sama sekali.
Beberapa orang menerima tawaran tadi dengan sukacita, dan mereka melaju menuju ke Candi Kedaton dengan sepeda listrik. Sebagian menggoncengi temannya. Pada salah satu dari mereka, yang menggoncengi rekannya, aku menitipkan tas milikku yang berisi tempat duduk lipat. Itu yang pertama. Lalu, kulihat ia kembali untuk menjemput rekan yang lain. Sekali lagi aku menitipkan tas, kali ini tas yang sungguh tak praktis untuk berjalan jauh —hari itu aku salah pakai tas, bukannya ransel, tapi tas ibu-ibu yang model cangklong di bahu dan kempit di ketiak.
Di sore pada hari yang sama, karena sesuatu dan lain hal, aku terpaksa tak ikut rombongan ekskursi yang berjalan kaki bersama dari Candi Kedaton ke Candi Koto Mahligai. Sebabnya adalah, karena tas kursi lipatku masih tertinggal di tenda ceramah umum. Aku memilih untuk tidak menyerahkan tas itu pada nasib —maksudnya, tak meninggalkan tas dan isinya itu sambil berdoa besoknya masih ada. Jadi, aku memisahkan diri dari rombongan pejalan kaki dan kembali ke Candi Kedaton.
“Nanti, kamu minta saja diantar seseorang dengan motor ke Candi Koto Mahligai,” temanku Debra si pembawa acara di BWCF menyarankan.
Semula niatku adalah, setelah mengambil tas kursi lipat aku akan berjalan kaki sendiri saja. Merasa yakin kalau jalan yang akan ditempuh adalah jalan setapak penuh kepastian. Tapi, rupanya sangat tak disarankan untuk jalan sendirian ke Candi Koto Mahligai. Baik berjalan kaki atau memakai kendaraan roda dua, tanpa didampingi orang setempat atau yang hafal jalan. Bukan karena hari sudah larut senja, tapi karena jalan setapak itu tak hanya lurus ke satu arah. Bakal banyak belokan di tengah-tengahnya.
KCBN Muarajambi ini sangat luas, hampir mencapai 4 hektar –tepatnya 3.981 hektar. Lingkungan sekelilingnya pun bukan perkampungan. Melainkan hutan, yang juga menjadi tempat hidup hewan-hewan liar. Jarak antara Candi Kedaton dan Candi Koto Mahligai hampir satu kilometer jauhnya.
Tiba kembali di tenda ceramah umum, di mana tas kursi lipat kutinggalkan, aku bertemu dengan beberapa peserta —kukenali dari warna lanyard-nya yang biru. Mereka mungkin tidak mengikuti kunjungan situs yang dipimpin oleh Dr. Agus Widiatmoko, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V Kota Jambi. Jelang malam nanti di Koto Mahligai akan ada Seni Pertunjukan: Malam Tari sebagai rangkaian acara BWCF 13. Aku tak tahu apakah mereka ini akan ke Koto Mahligai untuk menonton atau tidak. Aku juga tak tahu apakah selesai menonton seluruh peserta dan semua orang akan kembali ke Kedaton atau tidak.
Bagaimanapun, kupikir ada baiknya kalau aku menempelkan diri pada rombongan kecil ini. Kalau nanti kami tersasar, aku tak sendirian hahaha… Setelah merasa tenang —entah mengapa tadinya aku merasa agak tak tenang lho— kubertanya apakah mereka akan ke Candi Koto Mahligai atau tidak. Jawabannya, ya, mereka akan ke sana.
“Pakai sepeda listrik,” jawab seorang kakak cantik berjilbab, ketika kutanya bagaimana cara mereka pergi.
“Waduh, saya tak paham cara pakainya,” keluhan standarku keluar lagi.
“Nanti ibu ikut saya saja,” sarannya.
Jadilah saya digoncenginya. Tas kursi lipat saya dibawakan peserta lain yang mengendarai sepeda listrik lainnya. Sementara, tas ibu-ibu kempitan tetap saya pegang. Kurasa, jalan berkerikil membuat sepeda likstrik tak terlalu stabil geraknya. Susah payah saya berusaha menyeimbangkan duduk saya. Sungguh tak mudah karena tempat duduk sepeda listrik kecil saja, tidak seperti tempat duduk di motor listrik yang cukup luas dan nyaman. Belum lagi harus memegang tas ibu-ibu kesayangan.
Untunglah kakak cantik yang memboncengi saya sangat lihai dalam mengendarai sepeda listrik itu. Hanya sekali saya harus turun, ketika kami akan melaju di sebuah jembatan yang sedikit tinggi dari jalan setapak. Sudahlah tinggi, ia agak menikung, dan sedikit berlumpur. Lebih aman kalau aku turun dari goncengan dan berjalan sedikit. Tiba di tujuan, kakak cantik memarkir sepeda listrik di antara sepeda-sepeda listrik yang sudah terparkir duluan. Aman!
Selama BWCF, hanya sekali itu saja aku menunggangi sepeda listrik. Besok-besoknya sudah tidak ada kesempatan lagi karena memang tidak perlu. Kuamati saja sepeda-sepeda listrik beraneka warna itu aktif berseliweran di area acara, atau terparkir pada tempat-tempat tertentu. Entah mengapa, senang hatiku melihatnya. Satu kali, di depan tenda makan dekat Candi Koto Mahligai, aku melihat beberapa sepeda listrik dinaikkan ke atas gerobak motor roda tiga. Eh, mau dibawa ke mana tuh, pikirku.
“Habis listrik, hendak di-charge,” seseorang menjelaskan situasi pengangkutan itu.
Oh…
Untuk area luas seperti KCBN Muarajambi ini, berkeliling memakai sepeda listrik adalah ide yang tepat. Memudahkan pengunjung mengelilingi kompleks percandian, dan lebih ramah lingkungan karena tanpa bahan bakar fosil. Kita pun tak terganggu oleh bau asap atau bisingnya knalpot. Saya sangat setuju dengan moda transportasi ini, meski tak bisa mengendarainya.
“Pengunjung biasanya datang ke KCBN dengan kendaraan pribadi. Kendaraan diparkir, lalu mereka bisa menyewa sepeda listrik untuk jalan-jalan,” cerita Ahok, seorang teman asal Muarojambi yang juga kru BWCF.
Sepeda-sepeda listrik di arena BWCF itu bukanlah milik tim BWCF, bukan pula punya pihak pengelola KCBN Muarajambi. Melainkan, milik sejumlah warga setempat yang biasa menyewakannya kepada pengunjung KCBN. Tim BWCF menyewa sepeda listrik dalam jumlah yang cukup banyak, untuk selama tiga hari dari empat hari pelaksanaan. Apalagi kalau bukan untuk kepentingan festival, dan kenyamanan peserta serta pengunjung festival.


Sepeda-sepeda listrik yang disediakan oleh BWCF. (Foto: Dokumentasi BWCF)
Menariknya bagi saya, bahwa di satu sisi ini merupakan salah satu bentuk penyerapan sumber daya lokal selama pengadaan festival. Adalah hak masyarakat setempat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari sebuah kegiatan di tempatnya. Dosen saya masa kuliah dulu yang juga seorang arkeolog pelestari, Bapak Mundardjito, pun selalu menekankan pentingnya bahwa penduduk di sekitar sebuah situs arkeologi memperoleh keuntungan ekonomi dari keberadaan situs tersebut. Tentunya dengan cara yang baik. Menyewakan sepeda listrik saya yakin merupakan salah satu caranya. Hei, Anda boleh tidak setuju dengan pendapat saya lho!
Saya jadi ingat dengan kendaraan sejenis di kompleks Kampus Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Berbeda dengan sepeda-sepeda listrik yang warnanya rupa-rupa, di kampus UI hanya satu warna, ungu. Beam Rover namanya, skuter listrik ramah lingkungan sebutannya —saya sungguh tak tahu bedanya atau persamaan teknis antara skuter listrik dan sepeda listrik, ataukah itu hanya sekedar beda penyebutan saja.
Keduanya sama-sama tak memerlukan surat-surat tertentu untuk pengoperasiannya. Tak ada tuh yang namanya STNK atau SIM diperlukan. Untuk penggunaan Beam Rover di UI, seseorang harus mengunduh aplikasi tertentu. Pemakaiannya tidak gratis, tapi konon harganya sangat terjangkau —pastinya harga mahasiswa. Pembayaran tidak dilakukan dengan tunai, tapi secara daring melalui aplikasi yang sudah diunduhnya di ponsel.
Sementara, pemakaian sepeda listrik di area BWCF sangat gratis —kan sudah dibayar oleh panitia. Pengguna tak perlu mengunduh aplikasi apa-apa. Tinggal duduk, putar kunci, nyalakan mesin, srrrrrrr… berangkat! Mudah dan asik, bukan!?
Pengelolaan sepeda listrik di BWCF macam itu bukannya tanpa masalah. Pasti ada! Sejak hari pertama, di grup WhatsApp peserta mulai keluar pemberitahuan bahwa siapapun yang lupa, atau tak sengaja membawa kunci sepeda listrik, diminta agar segera mengembalikannya kepada panitia. Waduh…
Di hari kedua, semakin ramai saja permintaan pengembalian kunci sepeda listrik. Karenanya, pada hari ketiga supaya lebih aman, panitia mengikat kunci ke sepeda. Dengan menggunakan seutas tali plastik. Hahaha…
Tapi, tali plastik kan bisa dipotong ya. Maka, keluar lagi lah pengumuman permintaan untuk segera mengembalikan kunci. Bahkan, di malam hari ketiga itu panitia juga mengirimkan pesan WhatsApp yang bertanya apakah ada yang memakai sepeda listrik berwarna jambon tapi lupa mengembalikannya. Sampai larut malam, si jambon itu belum ditemukan.
Hari terakhir tak lagi kulihat sepeda-sepeda listrik yang biasanya menggerombol terparkir di beberapa titik. Kukira, panitia kapok sehingga menghentikan pengadaan alat transport praktis itu. Tapi, ternyata fasilitas itu memang hanya disediakan untuk tiga hari pertama saja. Hari keempat atau hari terakhir tidak ada.
Pada akhirnya, aku mendapat cerita bahwa sepertinya hampir semua kunci sepeda listrik ditemukan kembali —yang tidak, toh ada kunci cadangan. Tentang si jambon yang menghilang itu, akhirnya ia ditemukan tapi entah di mana saya tak tahu. Rupanya, saat dipakai tiba-tiba listriknya habis dan lalu si pengguna meninggalkannya begitu saja di mana sepeda mogok. Tepok jidad…
Repot memang urusan seperti itu. Panitia tak membatasi siapa-siapa saja yang boleh jadi pengguna. Pun semua benar-benar berdasarkan kepercayaan belaka. Siapapun yang ada di sana, bebas memakai. Peserta, panitia, atau pengunjung lain yang tak memakai ID card resmi BWCF 13. Ya sudah, bersyukur saja bahwa akhirnya semua urusan terselesaikan dengan baik.
Terima kasih ya, sepeda listrik. Teruslah melaju memajukan KCBN Muarajambi… =^.^=
—
*Nina Masjhur, penulis dan editor.