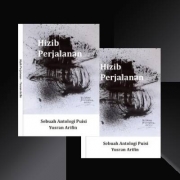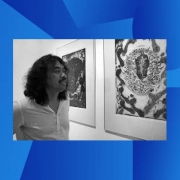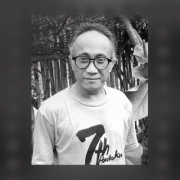Menyigi Historiografi yang Abai pada Estetika dan Seni
Oleh: Prof. Dr. Kasiyan, M.Hum.
“History is not a mere chronicle of events, but the re-enactment in the historian’s mind of past thought, an imaginative act that rescues human experience from oblivion.”
— R.G. Collingwood, The Idea of History (1946)
Kita membaca sejarah Indonesia, dan yang paling sering tampak hanyalah deru peperangan, pergantian rezim, atau narasi nasionalisme yang dipahat sebagai mantra resmi. Kroniknya riuh oleh gejolak politik, tetapi jarang menyentuh elan puitik yang ikut menandai kelahiran bangsa. Nama pahlawan dipahat di monumen, sementara jejak gamelan yang berevolusi di bawah bayang kolonialisme, atau pelukis yang menyoal getir zaman di atas kertas lusuh, hampir selalu absen. Historiografi kita ibarat peta yang hanya menandai sungai dan tapal batas, melupakan aroma hutan, denyar suluk, dan katarsis batin lahir dari seni.
Adagium lama menyebut, “sejarah ditulis oleh para pemenang”. Namun yang jarang disorot ialah bagaimana “pemenang” selalu dimaknai secara politis, tak pernah direvisi terminologinya, sehingga estetika dan seni terus dikalahkan dari panggung sejarah peradaban. Dalam wacana publik, sejarah tampil sebagai daftar kejadian yang berdentum: perang, pemberontakan, pembangunan, statistik yang kaku—tetapi bungkam tentang bagaimana bangsa ini belajar merasakan keindahan, membangun simbol, menumbuhkan cita rasa. Kita tumbuh dengan ingatan timpang: hafal siapa memimpin pertempuran, nyaris lupa siapa yang memelihara jiwa bangsa lewat musik, lukisan, dan drama.
Ironi itu kembali terasa ketika pada 2025 pemerintah meluncurkan proyek besar menulis ulang sejarah nasional dengan melibatkan ratusan sejarawan. Tujuannya: menghapus bias kolonial, menyegarkan narasi kontemporer, menegaskan perspektif “Indonesia-centric”. Namun kritik bermunculan: prosesnya dianggap kurang transparan, rawan melahirkan tafsir tunggal, bahkan menjadikan sejarah instrumen legitimasi kekuasaan.
Seperti diingatkan Michel Foucault lewat Power/Knowledge (1980), “Sejarah selalu menjadi medan pertempuran wacana, bukan sekadar arsip netral”. Dan seperti dikatakan Walter Benjamin dalam bukunya Theses on the Philosophy of History (1940), “Tak ada dokumen kebudayaan yang bukan sekaligus dokumen barbarisme” (Selama estetika dan seni tetap dianggap aksesoris, bukan denyut yang memberi makna terdalam, setiap revisi hanya akan memperluas arsip para pemenang—tanpa membebaskan ingatan bangsa dari kebisuan yang paling halus.
Mengapa Seni Disingkirkan
Historiografi kita, sejak mula, dibangun dengan heuristik yang sempit: seolah hanya kronologi diakronik yang dianggap sah, sedangkan dimensi sinkronik—cahaya yang memancar dari seni dan kebudayaan—diletakkan di sudut, menjadi tamu asing. Dalam The Order of Things (1966), Foucault menyebut “arsip” sebagai penentu apa yang layak disebut pengetahuan dan apa yang dibuang ke liminal kejumudan.
Arsip sejarah Indonesia cenderung menjunjung determinisme faktual: perang, politik, pergantian rezim—mengunci narasi dalam garis lurus dan menutup diri terhadap sintesis cakrawala, antara pengalaman lahir dan batin yang berdiam di karya seni. Jika kita mendengarkan abad ke-19 hanya lewat Perang Diponegoro, misalnya, kita kehilangan kisah suluk mistik, motif batik, atau puitika wayang yang menyimpan katarsis kolektif.
Kita mewarisi warisan panjang dari kolonialisme: paradigma positivistik yang menilai hanya yang terukur dan tercatat sebagai bernilai. Setelah merdeka, negara yang masih rapuh meniscayakan pembangunan identitas lewat simbol kekuasaan: pahlawan, garis front, tindakan heroik.
Seni, pendidikan, kebudayaan yang tak mendukung agenda politik legitimasi diletakkan sebagai catatan kaki atau bahkan dihapus. Nietzsche dalam The Birth of Tragedy (1872), memperingatkan bahwa peradaban yang hanya menyanjung rasionalitas Apollonian, sambil mengabaikan vitalitas Dionysian dalam seni, akan kehilangan daya vitalnya. Ia menulis: “We have art in order not to perish of the truth.” Seni bukan pelarian dari realita sengsara, melainkan cara untuk membentur realita, merasakan dan mengubahnya.
Di buku pelajaran kita, ketiadaan seni paling jelas: halaman-halaman panjang didedikasikan pada: perang, traktat politik, konfrontasi ideologis; tapi perjalanan wayang, ukir Toraja, atau eksperimen sastra modern sama sekali steril, tak ada. Padahal artefak-artefak itu menyimpan denyar imajinasi kolektif, katarsis serta gebu yang membantu bangsa memahami ruang, waktu, dan semesta kosmologi dan kesadaran identitasnya dengan lebih utuh. Tanpa kesadaran estetis, sejarah menjadi daftar nama dan tanggal yang membeku—prasasti dipahat tanpa roh.
Adalah ironis, bahwa kritik utama terhadap sejarah nasional selalu tertuju pada bias kolonial dan politik—benar, ini penting—tetapi hampir tak pernah ada yang mengangkat soal seni dan estetika yang “dikeluarkan” dari narasi resmi. “Pemenang” secara klasik ialah rezim politik dan kekuasaan, sedangkan seni—yang mungkin menang dalam hati massa, rakyat—terus dikalahkan, ditaklukkan dalam historiografi kebudayaan.
Jika kita tak mulai merevisi arsip, tidak sekadar menambah bab, tetapi mengganti cara kita melihat masa lalu, maka kita terus mewariskan sejarah yang hampa akan rasa, bisu akan keindahan, tanpa kemampuan memahami bahwa kejadian terbesar tak hanya apa yang terjadi, tapi bagaimana masyarakat meresapi.
Luka dan Ingatan Kolektif
Mengembalikan seni ke pangkuan sejarah, bukan sekadar memperluas daftar catatan; ia menuntut perubahan mendasar dalam paradigma tentang apa yang kita anggap penting dalam perjalanan bangsa. Selama ini, arsip yang diwariskan lebih menyerupai katalog kemenangan politik, daftar tanggal dan deklarasi, ketimbang cermin kompleksitas pengalaman kolektif.
Padahal, seperti diingatkan Edward Said dalam Culture and Imperialism (1993), “Setiap sejarah adalah sejarah seleksi: yang diangkat dan yang disenyapkan selalu ditentukan oleh relasi kuasa.” Dalam relasi itulah artefak budaya—dari manuskrip lontar Bali, Wayang Beber Pacitan, sampai poster teater eksperimental dekade 1970-an—sering diposisikan sekadar ornamen eksotis, bukan bukti kecerdasan historis yang menghidupkan denyut batin masyarakat yang kritis.
Proyek penulisan ulang sejarah nasional yang dicanangkan pada 2025, memberi peluang untuk membongkar bias lama, namun juga menyimpan bahaya baru. Janji pemerintah untuk menghapus warisan kolonial patut diapresiasi, tetapi kritik muncul karena prosesnya terkesan elitis, berjarak dari komunitas yang hendak diwakilinya.
Tanpa keberanian membuka diri pada dimensi emosional, imajinatif, dan estetis, yang lahir hanya versi lain dari “sejarah pemenang,” sekadar mempercantik monumen kekuasaan. Hannah Arendt mengingatkan dalam Between Past and Future (1961): “Tanpa kesadaran akan estetika dan seni, sejarah hanya mengulangi kronika keruh jelaga kekuasaan, bukan mengingat kemanusiaan.” Mengabaikan estetika dan seni berarti membiarkan kekuasaan bekerja diam-diam, menghapus lapisan kepekaan yang lebih dalam daripada sekadar fakta atau kenyataan.
Mengapa kita jarang membaca sejarah melalui aroma tanah basah yang mengiringi ritus panen, atau melalui garis ekspresif seniman yang merekam luka kolektif? Sebab cara pandang kita masih menempatkan estetika di pinggir, seolah tak memiliki bobot epistemik yang mampu menyingkap kedalaman pengalaman manusia dalam lintasan waktu.
Seni adalah modus pengetahuan yang menyingkap jalan lain menuju kebenaran—sebuah cakrawala yang, menurut Merleau-Ponty dalam Eye and Mind (1964), lahir dari “penglihatan yang mengandung pemahaman.” Dalam perspektif ini, seni tidak sekadar memperindah atau memberi ornamen pada masa lalu; ia menelusup ke bawah permukaan kronologi, mengurai simpul emosi, ingatan, dan makna yang kerap tersembunyi di balik fakta-fakta. Melalui sensibilitas estetis, sejarah menjadi lebih dari sekadar laporan tentang apa yang terjadi: ia menjelma sebagai ruang tafsir yang memulihkan pengalaman manusia, menghadirkan denyut batin yang tak dapat dijangkau oleh catatan yang hanya sekadar mendokumentasi.
Tugas sejarawan, karenanya, bukan hanya menata ulang fakta, melainkan memulihkan resonansi batin yang terkandung dalam karya seni dan estetika. Sejarah yang hidup adalah sejarah yang mengakui bahwa puitika, irama, dan simbol sama pentingnya dengan traktat politik. R.G. Collingwood lewat The Idea of History, (1946), pernah menegaskan bahwa “The historian’s business is to re-enact in his own mind the thought whose history he is studying”; suatu penekanan bahwa sejarah sejati melibatkan kehadiran kembali jiwa dan makna. Tanpa itu, kita hanya menyalin daftar kejadian yang dingin, meninggalkan generasi mendatang dengan arsip yang bisu terhadap getar kehidupan. Sejarah yang membebaskan adalah sejarah yang memberi ruang bagi seni dan estetika untuk menyapa—sebagaimana ia, sejak awal, berbicara kepada manusia yang mencari arti di tiap kala.
Membuka Ruang Imajinasi dalam Historiografi
Menulis sejarah dengan mengakui estetika bukanlah kompromi terhadap objektivitas, melainkan upaya heuristik yang lebih terbuka, revisionisme yang berani meneroka cakrawala pengalaman manusia. George Santayana dalam The Sense of Beauty (1896,) menulis: “Kecantikan adalah janji kebahagiaan.” Dalam lanskap historiografi, keindahan menjadi janji pemahaman yang melampaui kalkulasi data: manusia digerakkan bukan semata oleh nalar utilitarian, tetapi oleh gairah untuk mencipta makna.
Bayangkan buku sejarah yang tak hanya menyebut Chairil Anwar sebagai penyair kemerdekaan, tetapi menempatkannya sebagai simpul fusi antara modernisme global dan luka lokal; atau narasi tentang wayang kulit sebagai pertemuan metafisika, politik, dan katarsis rakyat; atau arsitektur masjid dan pura yang dipahami bukan sekadar dari segi teknik, melainkan sebagai denyar rohani yang membentuk ruang hidup. Sejarah yang mengintegrasikan dimensi sinkronik dan diakronik akan membebaskan kita dari teleologi sempit dan determinisme yang memiskinkan imajinasi.
Historiografi Indonesia lama berada dalam bayang kuasa: kolonialisme yang memuja arsip, nasionalisme yang mencari legitimasi, dan birokrasi pendidikan yang mengatur pengetahuan. Dalam matriks itu, seni ditempatkan di pinggir, jauh dari narasi yang dianggap “serius.” Michel Foucault dalam The Archaeology of Knowledge (1969), mengingatkan bahwa pengetahuan selalu lahir dalam jaringan kuasa.
Karena seni tak segera menyokong legitimasi negara, ia sering menjadi catatan kaki yang jarang dibaca. Padahal relief Borobudur bukan hanya bukti hadirnya Budha di Jawa, melainkan arsip teknik batu, visi kosmologis, dan kegembiraan membangun dunia simbol. Begitu pula perjalanan keroncong, dangdut, dan musik independen: semuanya adalah respons terhadap perubahan sosial, bukan sekadar hiburan.
Menafsir ulang sejarah berarti memandang masa lalu sebagai gelanggang tempat politik, ekonomi, agama, sains, dan estetika bersilangan. Arsip, naskah, dan artefak bukan semata kumpulan fakta, melainkan entitas makna yang menubuh di dalamnya. Sejarah wayang kulit, misalnya, adalah riak interaksi budaya, katarsis moralitas, dalam kehidupan. Pendidikan seni di Taman Siswa tak hanya kebijakan, tetapi kisah bagaimana estetika menjadi kendaraan emansipasi manusia muda dari feodalisme. Kebudayaan bukanlah hiasan bagi politik atau ekonomi; ia medan tempat manusia menemukan kemungkinan dirinya.
Pendekatan semacam itu menuntut keberanian epistemologis: kesediaan melampaui inertia metodologis yang hanya percaya pada statistik atau kronik militer. Sejarah perlu menyambut etnografi, kritik seni, hermeneutika, bahkan psikoanalisis—apa saja yang mampu mengungkap simpul-simpul halus peradaban. Namun lebih dari itu, ia memerlukan keberpihakan etis: kesediaan menghadirkan suara yang lama dibisukan.
Seniman yang dibuang ke Pulau Buru, pelukis yang karyanya disensor, penulis yang diasingkan, guru seni yang mengajar dalam bayang represi—mereka bagian dari narasi bangsa. Tanpa kisah mereka, sejarah hanyalah katalog resmi yang dingin, tanpa gebu dan katarsis batin. Historiografi yang berani menyertakan estetika akan memperlihatkan bangsa ini bukan sekadar agregat kemenangan dan kekalahan, melainkan organisme yang, dalam deru dan lirih, terus menciptakan wajahnya sendiri.
Merayakan Seni dalam Narasi Bangsa
Yang kita perlukan bukan sekadar menambah bab dalam buku pelajaran, melainkan membongkar kebekuan arsip yang membekukan pengalaman estetik. Di balik teks resmi, tersembunyi catatan harian pelukis yang menyaksikan 1965 dengan tangan gemetar; novel atau puisi yang menyelundupkan satire di masa sensor; mural jalanan yang menjadi katarsis di tengah deru pembangunan. Semua itu menunggu ditafsir dengan historisme kritis yang tak alergi pada puitik.
Benedict Anderson dalam Imagined Communities (1983) mengingatkan: komunitas politik lahir dari cerita yang dibayangkan bersama. Seni—lukisan, musik, tari, puisi—adalah medium cerita itu. Jika estetika terus menjadi paria dalam historiografi, yang tersisa hanyalah kerangka tanpa jiwa: negara tanpa daya hidup, masa lalu tanpa katarsis.
Mendesak bagi kita adalah keberanian menyeberangi batas disiplin, mengkritisi arsip yang liminal, membiarkan denyar kreativitas masuk ke naskah sejarah. Sejarah yang memuliakan estetika memperlihatkan bahwa bangsa hidup bukan hanya dengan mempertahankan tanah dan institusi, melainkan dengan menjaga imajinasi dari kedegilan klise. John Dewey dalam Art as Experience (1934) menulis: seni adalah intensifikasi pengalaman hidup.
Menyertakan seni berarti mengakui bahwa perjalanan bangsa tidak berhenti pada statistik perang atau daftar kabinet; ia juga mencakup suara-suara dari studio kecil, bengkel kerajinan, ruang kelas sunyi, atau panggung teater yang melawan represi. Di sanalah logos dan aisthesis bersua, mencipta horizon yang menyelamatkan kita dari teleologi yang memiskinkan makna.
Historiografi yang memberi ruang bagi seni memungkinkan lahirnya peta sejarah yang lebih utuh: ia menyingkap persilangan politik dan estetika, menelusuri bagaimana karya seni menjadi medan dan arena kritis halus atas kuasa sekaligus penawar luka sosial. Melalui kepekaan ini, sejarah hadir bukan hanya sebagai kronologi, melainkan lanskap makna yang memulihkan pengalaman manusia.
Dengan memasukkan dimensi sinkronik ke dalam rentang diakronik, kita menolak determinisme yang membekukan daya hidup kreatif. Sejarah seperti itu tidak hanya menginventaris fakta, tetapi membantu kita memahami bagaimana masyarakat membayangkan dirinya dan memberi arti pada hidup bersama.
Mengimajinasikan seni ke dalam historiografi, bukan sekadar strategi metodologis, melainkan keberpihakan etis. Ia menggeser fokus dari “apa yang terjadi”, ke pertanyaan “bagaimana manusia mengalami dan menafsirkan yang terjadi”. Ini mengakui bahwa bangsa hidup bukan semata dari kemenangan, tetapi juga dari kemampuan mengolah penderitaan menjadi lagu, trauma menjadi tarian, absurditas menjadi satire. Dalam setiap amalgam ekspresi itu terdapat revisionisme yang menantang kebekuan masa lalu—katarsis yang membuka cakrawala baru bagi pengetahuan historis.
Jika seni terus dibiarkan di luar halaman sejarah, kita hanya memelihara kebekuan, membiarkan masa lalu membatu tanpa gebu kehidupan. Tetapi ketika historiografi mendengar musik, membaca puisi, melihat lukisan, mencium aroma kayu yang dipahat, kita memperoleh sejarah yang lebih jernih, lebih manusiawi.
Sejarah yang tak hanya mencatat tanggal proklamasi atau daftar operasi militer, melainkan juga menyerap denyar batin yang melahirkan batik, novel, atau mural jalanan. Sejarah yang, dalam deru dan lirih, mengakui bangsa ini sebagai organisme yang mencari cahaya melalui estetika—narasi yang membebaskan kita dari involusi birokratis dan membuka peta keberadaan yang lebih luas dan indah lanskap bianglala cakrawalanya.
Penutup
Kita tak bisa lagi membiarkan historiografi Indonesia terjebak dalam involusi narasi yang tuli pada estetika dan seni. Terlalu lama sejarah kita mengulang dirinya dalam gema arsip yang beku, seolah masa lalu hanyalah deretan fakta yang patuh pada determinisme sejarah, tanpa ruang bagi elan imajinasi atau gebu katarsis yang lahir dari pengalaman estetik.
Padahal, bangsa yang sehat tidak hanya menata ingatan lewat statistik dan protokol, tetapi juga merawat yang luput dari angka: rintih dan tawa, lirih dan deru, aroma kayu yang dipahat, tiupan mendayu seruling yang membangkitkan harapan. Di sanalah sejarah dan seni bertemu, menyatu dalam perjumpaan paradigma, antara fakta dan puitik yang memperluas cakrawala keberadaan.
Sudah saatnya kita menjelajah arsip yang tersembunyi, menyoal jejak yang selama ini dianggap liminal atau sekadar hiasan di pinggir teks resmi. Seni adalah heuristik yang membuka lapisan makna, sekaligus perlawanan terhadap kejumudan historisme kritis, yang hanya menghitung kronologi tanpa memahami resonansinya.
Tanpa keberanian seperti itu, historiografi hanya akan menjadi proyek administrasi memori yang miskin spirit, membiarkan yang hidup meredup menjadi catatan kaki. Susan Sontag pernah menulis dalam Against Interpretation (1964), “Dalam kebudayaan yang sehat, seni bukan pelengkap, melainkan pusat.” Ungkapan itu lebih dari sekadar provokasi intelektual; ia adalah peringatan etis, bahwa sejarah yang abai terhadap pusat estetik, sedang melupakan denyut nadi jantungnya sendiri.
Pengetahuan historis yang benar, tidak lahir dari determinisme yang kaku, tetapi dari kesiapan untuk membuka diri pada amalgam pengalaman—sinkronik sekaligus diakronik, politis sekaligus puitik. Ia mengakui, bahwa sebuah bangsa bukan hanya produk teleologi kekuasaan, melainkan organisme yang terus mencipta dirinya melalui seni, simbol, dan imajinasi.
Ketika kita memisahkan sejarah dari seni dan estetika, kita sedang memutus aliran vital yang memberi daya kehidupan pada ingatan kolektif yang mahal; kita mengubah masa lalu menjadi arsip dingin tanpa denyut batin, menyingkirkan puisi, musik, dan simbol yang menjahit pengalaman bersama, padahal di sanalah terletak kekuatan yang menghidupkan makna perjalanan suatu bangsa.
Tugas kita kini bukan sekadar menambah bab tentang seni di buku teks sekolah atau museum, melainkan membangkitkan historiografi yang berani menempatkan estetika di jantung penuturannya. Ia mesti memanggil kembali dimensi katarsis, keberanian untuk melihat luka dan kegembiraan dalam satu tarikan napas simultan, serta kesanggupan untuk merawat elan penciptaan yang membuat sebuah bangsa tetap hidup dan bertahan.
Historiografi yang demikian tidak akan tunduk pada inertia birokratis atau revisionisme yang sekadar memoles citra kekuasaan. Ia justru akan menghadirkan peta yang lebih utuh: sejarah yang mendengar imajinasi, memelihara kebijaksanaan, dan menyinari masa depan, dengan daya hidup yang lahir dari keberanian mencipta.
Dalam optik pandang seperti itu, sejarah berhenti dari menjadi monumen beku-statis, dan kembali menjadi narasi yang dinamis, bergerak, menyala, memberi arah. Ia menolak menjadi kronik yang membatu di bawah beban teleologi, memilih menjadi ruang di mana bangsa dapat membaca dirinya sendiri dengan kesadaran kritis dan sensibilitas estetik.
Inilah tantangan paling mendesak hari ini: merumuskan historiografi yang tak sekadar memanggul beban masa lalu, tetapi juga menajamkan perspektif masa depan. Sejarah harus hidup dari imajinasi, ditopang keberanian estetis-etis, dan setia pada suara yang melawan reduksi klise. Tanpa keberanian menghidupkan imajinasi estetis, historiografi hanya akan menjadi katalog debu; padahal sejarah seharusnya merengkuh denyut pikiran dan rasa, menyelamatkan pengalaman manusia dari kuburan kelupaan.
Hanya dengan itu, historiografi dapat terlibat dan memposisikan diri terus-menerus di tengah arus zaman, membuka ruang kritis bagi bangsa untuk tiada henti: membaca, menafsir, dan merekonstruksi semesta kronika komprehensif kemanusiaan, dalam pendar nyala fusi horizon harapan yang lebih mencahayakan.
—
*Prof. Dr. Kasiyan, M.Hum. Guru Besar Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta