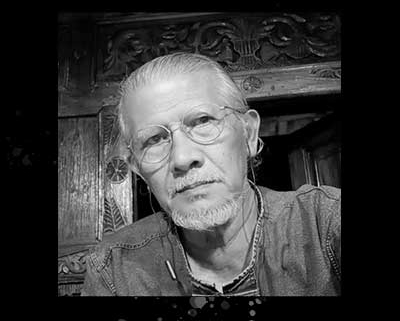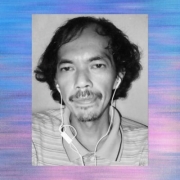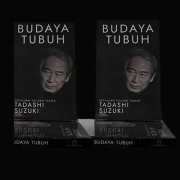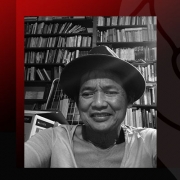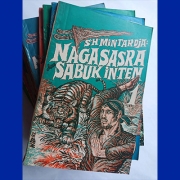Kontroversi (penulisan) Sejarah Indonesia 2
Oleh Riwanto Tirtosudarmo*
Apa yang ditunggu akhirnya datang. Meskipun masih dalam bentuk draft, buku sejarah yang menjadi kontroversi ini akhirnya bisa dibaca oleh publik. Pada tanggal 28 Juli 2025 pagi saya mendapatkan draft buku itu melalui link yang dikirim sahabat saya, seorang sejarawan yang tinggal di Malang, Sisco (Fransico Hera). Sebelumnya, pada tanggal 24 Juli sekitar jam 5 sore saya menerima undangan untuk menghadiri diskusi publik buku sejarah yang sedang ditulis oleh sebuah tim yang dipimpin Profesor Susanto Zuhdi. Saya tidak mengira akan mendapatkan undangan itu karena saya pikir acara itu tidak jadi atau jadi diadakan tapi saya tidak diundang. Kepada pengirim WA itu, Annisa dari Direktorat Sejarah Kementrian Kebudayaan saya mengatakan “trimakasih, tapi kok waktunya mepet banget”.
“Diskusi Publik” yang rupanya mengganti istilah yang sebelumnya dipakai “Uji Publik” itu akan diadakan tgl 25 Juli mulai jam 13 sampai selesai. Melihat daftar yang diundang, sebagian besar adalah lembaga-lembaga pemerintah yang tampaknya dipilih karena berhubungan dengan sejarah atau pendidikan. Selain lembaga, ada sejumlah nama individu dalam daftar undangan termasuk nama saya. Sebagian nama-nama itu adalah anggota tim penulis sendiri dan nama-nama lain yang saya tidak kenal. Pada tanggal 26 Juli pagi, saya mendapatkan WA dari beberapa rekan, termasuk kolega saya di LIPI dulu, sejarawan Asvi Warman yang menanyakan apakah saya mempunyai draft buku sejarah yang akan didiskusikan. Beberapa rekan yang menghubungi saya itu mengira saya memiliki draft karena saya termasuk yang diundang.
Saya periksa lagi undangan yang saya terima memang tidak ada lampiran apa-apa. Saya kemudian terlibat pembicaraan dengan Asvi Warman soal undangan karena saya menanyakan apakah AKSI (Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia) sebagai pihak yang menentang rencana penulisan buku sejarah itu diundang. Menurut Asvi, semula AKSI diundang, tetapi kemudian datang lagi undangan kedua, dimana tidak ada lagi nama AKSI katanya. Kedua undangan itu sama-sama bertanggal 18 Juli 2025. Saya periksa undangan yang saya terima, memang bertanggal 18 Juli, yang angka 18-nya ditulis tangan bukan diketik. Saya berasumsi kalau undangan yang saya terima adalah versi kedua, yang saya lihat memang tidak ada undangan untuk AKSI disana. Dari Asvi saya juga dapat penegasan tidak ada orang AKSI yang diundang.
Saya mulai berpikir untuk tidak hadir, selain karena waktunya mepet, sejak saya berkomunikasi dengan Profesor Susanto Zuhdi saya mengatakan kalau saya akan hadir, tentu jika diundang, apabila semua pihak baik yang pro maupun yang kontra rencana penulisan buku sejarah itu diundang. Sekali lagi saya periksa daftar undangan, dan saya menilai memang tidak ada nama mereka yang saya kenal yang menentang rencana penulisan buku sejarah itu, seperti Asvi Warman atau Ita F Nadia. Pagi itu juga saya putuskan tidak hadir, melalui WA yang saya tujukan kepada Profesor Susanto Zuhdi yang saya duga meminta kepada panitia untuk mengundang saya, meskipun undangan untuk saya itu datang hanya sehari sebelum acara. WA saya untuk Susanto Zuhdi sebagai berikut:
Bung Susanto Zuhdi, trimakasih atas undangan untuk menghadiri uji publik naskah buku sejarah nasional yang penulisannya anda pimpin. Saya memutuskan untuk tidak hadir karena dari daftar undangan saya menilai tidak terlihat perwakilan dari mereka yang menentang rencana penulisan buku sejarah ini. Bagi saya ini sebuah pertanda kuat bahwa buku sejarah ini memang direncanakan dan ditulis secara sepihak, tertutup dengan agenda dan kepentingan yang telah dikunci dan diarahkan dari atas. Sesungguhnya selama ini saya telah memberikan the benefit of the doubt kepada anda sebagai kolega yang menjunjung tinggi integritas akademik seperti telah diberi contoh oleh guru-guru kita Pak Sartono Kartodirdjo Pak AB Lapian dan Pak Abdurachman Suryomiharjo. Saya merasa ada perbedaan pandangan dan sikap yang mendasar diantara kita tentang integritas dan kebebasan akademik. Saya berharap meskipun berbeda dalam pilihan yang mau tidak mau berimplikasi pada posisi politik kita masing-masing, kita tetap menjaga persahabatan karena pada dasarnya kita sama-sama mencintai Indonesia tempat kita tegak berdiri. Salam hangat, Riwanto Tirtosudarmo.
Menjelang sore saya mendapat kiriman link acara diskusi publik dari Seno Joko Soeyono, kawan saya mantan wartawan kebudayaan Tempo. Berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar dari video acara itu saya membuat catatan seperti ini.
Sebagai moderator Kasijanto, sejarawan yang kebetulan juga saya kenal baik, dalam pengantarnya membuat observasi yang menarik. Menurut Kasijanto, jika para penulis sejarah itu adalah generasi kedua sejarawan setelah kemerdekaan. Generasi pertama sejarawan itu misalnya Sartono Kartodirdjo dan Marwati Djoened Pusponegoro, sementara generasi kedua adalah Susanto Zuhdi dll. Oleh Suzanto Zuhdi observasi Kasijanto dikoreksi karena selain generasi kedua juga ada generasi ketiga. Generasi ketiga ini antara lain adalah murid-murid Suzanto Zuhdi. Kasijanto juga memberikan komentar menarik karena semua yang terlibat mulai dari menterinya, para stafnya dan penulis buku adalah sejarawan. Fadli Zon mendapatkan gelar doktor dari jurusan sejarah UI dengan promotor Profesor Iskandar (bukan Suzanto Zuhdi seperti saya tulis sebelumnya), dan Susanto Zuhdi sebagai ko-promotornya. Susanto Zuhdi memberitahu saya kalau disertasi Fadli Zon adalah tentang pemikiran ekonomi Mohamad Hatta.
Dalam sambutannya Fadli Zon mengatakan bahwa benar sekali adagium bahwa sejarah selalu ditulis oleh pemenang, karena dalam penulisan buku sejarah ini penulisnya adalah “Indonesia” sebagai pemenang. Menurut saya klaim bahwa penulis buku sejarah yang sedang disiapkan ini adalah “Indonesia” sebagai pemenang perlu diberi catatan khusus. Klaim itu mengaburkan kenyataan dalam konteks politik hari ini yang secara faktual dimenangkan oleh Prabowo Subianto, dimana Fadli Zon menjadi salah satu anak buahnya yang penting. Oleh karena itu harus diakui secara jujur bahwa pemenang sesungguhnya adalah Fadli Zon sendiri, dan saat ini dialah yang sedang menuliskan ulang sejarah Indonesia. Bahwa dia mengatakan bahwa sejarah memang seharusnya ditulis oleh sejarawan dan bukan yang lain seperti yang dia puji dengan tim penulisan sejarah ini, hanya tampaknya saja benar, tetapi juga harus kita periksa pernyataan ini dengan teliti karena akan terlihat bagaimana sesengguhnya relasi kekuasaan yang bermain dalam proyek politik penulisan sejarah ini.
Hampir tengah malam saya mendapat balasan WA dari Susanto Zuhdi yang mengatakan bahwa dia sebetulnya sudah meminta kepada panitia untuk mengundang AKSI atau wakilnya dalam acara diskusi publik yang pertama di FIBUI tanggal 25 Juli itu. Namun, Santo mengatakan bahwa keputusan untuk menentukan siapa yang akan diudang berada diluar kekuasaannya, kekuasaan itu ada ditangan panitia yang tampaknya berada pada Dr. Restu Gunawan, seorang sejarawan lulusan UI juga yang saat ini menjadi salah satu Dirjen d Kementrian Kebudayaan. Dalam sambutannya, Fadli Zon menceritakan bahwa Direkorat Sejarah adalah lembaga yang begitu dia dilantik sebagai Menteri Kebudayaan akan dia hidupkan kembali. Rupanya lembaga ini telah dihapus pada masa kepresidenan Jokowi ketika Hilmar Farid menjadi Dirjen Kebudayaan.
Dari penampilan aktor-aktor utama yang terlihat di panggung diskusi publik sdraft buku ejarah di FIBUI tanggal 25 Juli sore itu sebagai penonton kita menyaksikan bagaimana relasi kekuasaan diantara para aktor itu berlangsung. Dalam piramida kekuasaan proyek politik penulisan buku sejarah ini duduk di puncak tentu saja Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dibawahnya Restu Gunawan (Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi) dan dibawah Dr. Restu Gunawan adalah Profesor Agus Mulyana (Direktur Sejarah dan Permuseuman). Tim penulis yang otoritas tertingginya dipegang oleh Susanto Zuhdi dengan 2 editor umum lainnya, membawahi 10 editor jilid yang masing-masing membawahi sejumlah penulis yang disebutkan telah mewakili Indoesia secara geografis dan secara jender – sebuah klaim yang penting untuk mengatakan bahwa tim penulis benar-benar telah merepresentasikan Indonesia.
Dari penjelasan Santo dalam WA ke saya bahwa kewenangan untuk mengundang peserta diskusi diluar kekuasaannya memperlihatkan bahwa Santo tidak memiliki kebebasan akademik untuk menjalankan peranya sebagai sejarawan dalam mengarahkan bagaimana semestinya proses penulisan buku ini dijalankan, misalnya dalam menjamin asas keterbukaan dan akuntabilitas untuk menjamin bahwa semua pihak haruslah didengar suaranya.
Dalam esai ini saya ingin memberi catatan dan komentar pada draft bab pendahuluan yang disiapkan oleh ketiga editor umum. Di halaman 5 saya menemukan kalimat sebagai berikut:
Oleh karena itu, penulisan sejarah kebangsaan bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan merupakan investasi strategis dan kultural dalam membangun kesadaran kolektif serta memperkuat keberlangsungan Indonesia sebagai suatu entitas bangsa dan negara.
Dari kutipan diatas, apa yang saya persoalkan dalam esai saya “Kontoversi (penulisan) Sejarah Indonesia” – https://borobudurwriters.id/kolom/kontroversi-penulisan-sejarah-indonesia/ – memperoleh penegasan. Berikut saya kutipkan apa yang saya sampaikan dalam esai saya itu:
Sampai disini memang kemudian menjadi problematik bagi Profesor Susanto Zuhdi ketika dia mengatakan bahwa penulisan itu akan tetap berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah. Problemnya, mana yang akan menjadi prinsip utama yang akan diikuti, kaidah-kaidah ilmiah atau kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai yang tidak mungkin tidak bersifat politis-ideologis.
Bagi saya, seperti apa yang tertulis di halaman 5 dalam bab pendahuluan draft buku sejarah tampak jelas bahwa kaidah ilmiah atau akademik akan tunduk pada tujuan politis-ideologis yang sejak awal memang menjadi niat dari penulisan buku sejarah versi Kementrian Kebudayaan ini. Berulang kali kita temukan pernyataan, baik dalam pidato maupun dalam draft buku ini bahwa sejarah yang sedang ditulis adalah sejarah kebangsaan, atau sejarah yang ditulis dengan perspektif kebangsaan. Menjadi keyakinan penulisan buku sejarah ini bahwa kebangsaan Indonesia perlu dirumuskan kembali relevansinya dalam konteks perubahan politik nasional dan global yang berlangsung cepat.
Buku sejarah yang “Indonesia sentris” dengan perspektif kebangsaan perlu ditulis terutama mengingat generasi muda yang dalam bahasa editor umum buku ini digambarkan pada halaman 4 sebagai berikut:
Hal ini terutama sangat menonjol pada generasi muda, di mana tingkat partisipasi mereka dalam berbagai isu sosial-politik sangat tinggi, tetapi tidak sebanding dengan pemahaman mereka terhadap sejarah kebangsaan. Ketimpangan ini berkontribusi pada terbentuknya opini dan sikap yang sering kali ahistoris, serta menjauhkan mereka dari akar nilai-nilai kebangsaan. Akibatnya, tingkat kepercayaan mereka terhadap institusi negara cenderung menurun, karena mereka tidak memiliki kerangka historis yang memadai untuk memahami legitimasi, peran, dan dinamika kelembagaan dalam konteks perjalanan bangsa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kohesi nasional dan memperbesar jarak antara negara dan warga negaranya.
Pada diskusi publik tanggal 25 Juli 2025 dalam sesi tanya jawab yang terburu-buru karena terbatasnya waktu, ketika seorang peserta dari Bima mengusulkan bahwa “Peristiwa Ngali” yang terjadi di Bima bisa dimasukkan dalam buku sejarah yang sedang dipersiapkan, editor jilid yang bertanggungjawab pada masa itu mengatakan bahwa dalam menulis sejarah fakta sejarah tidak mungkin semuanya dimasukkan karena harus di seleleksi mana yang relevan dan tidak. Saya kira apa yang dikatakan oleh editor jilid ini menggambarkan dengan baik bagaimana nanti buku sejarah yang sedang ditulis ini adalah hasil seleksi dari fakta-fakta sejarah, ada yang dimasukkan ada yang dibuang atau disisihkan. Kembali disini apa yang dikatakan oleh rekan saya Hermawan Sulistyo benar, tidak ada sejarah yang lurus, karena sejarah selalu bengkok, tergantung fakta sejarah mana yang dipakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk “memahami legitimasi, peran dan dinamika kelembagaan dalam konteks perjalanan bangsa” – halaman 5.
Saya tertarik dengan penjelasan tiga periode sejarah yang mungkin paling penting setelah kemerdekaan. Pertama, dalam halaman 15 bab pendahuluan ditulis sebagai berikut:
Tragedi nasional Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) merupakan titik balik fundamental dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya menandai kehancuran kekuatan kiri, khususnya PKI, tetapi juga membuka jalan bagi militer, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, untuk mengambil alih kendali politik nasional. Dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di tengah ketegangan Perang Dingin, Soeharto membangun rezim Orde Baru yang didasarkan pada agenda utama: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan komunisme.
Kedua, pada halaman 16 tentang kebangsaan pada masa Orde Baru dituliskan sebagai berikut:
Kebangsaan versi Orde Baru bersifat teknokratis, elitis, dan eksklusif, dipengaruhi oleh paradigma liberal dan teori modernisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini mengabaikan pemerataan, partisipasi politik, dan hak sipil. Identitas kebangsaan dibentuk dari atas tanpa melibatkan masyarakat, sehingga identik dengan disiplin politik, efisiensi administratif, dan depolitisasi rakyat, bukan sebagai ruang inklusif bagi partisipasi warga negara. Kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi yang eksklusif dan praktik kekuasaan yang represif menjadi sebab struktural dari runtuhnya rezim Orde Baru dan menjadi babak baru dalam sejarah kebangsaan Indonesia.
Ketiga, tentang periode pasca Orde-Baru, pada halaman yang sama, ditulis sebagai berikut:
Namun, demokrasi Indonesia secara luas menghadapi tantangan substantif. Di balik prosedur elektoral yang demokratis, kebangsaan justru menghadapi fragmentasi baru yang ditandai oleh domestifikasi oligarki dalam struktur politik. Demokrasi elektoral berkembang secara transaksional, ditandai oleh dominasi uang, patronase, dan pembajakan partai oleh elite ekonomi, sementara lemahnya pendidikan politik turut memperburuk kualitas demokrasi. Koalisi elite politik dan pengusaha besar merusak integritas perwakilan dan menciptakan ekonomi monopolistik yang melanggar prinsip keadilan sosial Pasal 33 UUD 1945. Agenda reformasi untuk membangun kebangsaan inklusif justru tersandera oleh ketimpangan dan eksklusi sosial dalam wajah baru yang lebih “demokratis”. Kebebasan politik pasca-Orde Baru memunculkan dinamika identitas etnis, agama, dan lokal yang kompleks. Meski merupakan ekspresi demokratis, politik identitas ini berisiko merongrong narasi kebangsaan inklusif jika tidak ditopang toleransi, solidaritas antarkelompok, dan konsensus Pancasila sebagai etika publik.
Ketiga bagian yang saya kutip dari bab pendahuluan adalah narasi tentang sebuah periode yang penuh dengan fakta-fakta sejarah. Dalam ketiga periode itu kita bisa membayangkan sangat kompleknya hubungan antara aktor-aktor sejarah pada setiap periode: Pra dan Pasca 1965, Orde Baru dan Pasca Orde Baru atau yang disebut periode reformasi. Membaca ketiga kutipan diatas, muncul sebuah pertanyaan di kepala saya, dimanakah akan dituliskan secara kritis, terbuka, adil dan seimbang dalam draft sejarah yang sedang ditulis itu penjelasan tentang sebab-musabab dari ketiga periode sejarah politik Indonesia yang memperlihatkan betapa sesungguhnya negara telah gagal dalam mengelola dinamika politik, mengutip kalimat terakhir bab pendahuluan – halaman 25, untuk “…mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera, bersatu dalam kemajemukan, dan berkemajuan serta berkeadaban” ?.
Malang, 28 Juli 2025.
—-
*Riwanto Tirtosudarmo adalah peneliti.