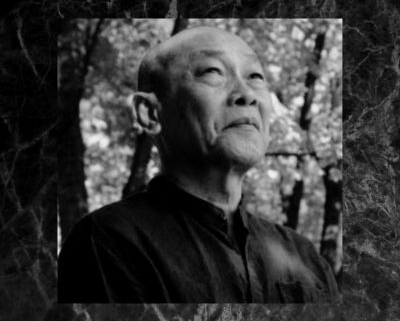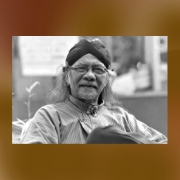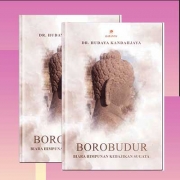Dicari: Politik Tata Ruang Kebudayaan untuk Jakarta
Oleh: Halim HD*
Ungkapan tentang kota menjadi hutan rimba dalam pergaulan sosial nampaknya bukan suatu dramatisasi bagi kehidupan masa kini. Tingkat kekerasan dalam berbagai wujudnya hampir setiap hari kita dengar dan baca di media, dari kalangan elite sampai dengan lingkungan kampung dan di jalanan. Sangat mungkin dampak dari fluktuasi ekonomi dalam kehidupan sosial dalam masyarakat khususnya di lingkungan kelas menengah dan bawah punya peranan penting yang ikut mempengaruhi tingkah laku sosial dan membentuk agresifitas yang bisa menciptakan konflik antar komunitas, kampung, geng. Apalagi kondisi itu ditambah oleh situasi dan kondisi sosial- politik yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional ikut menggiring dan membelah lapisan masyarakat ke dalam arus yang menjurus kearah konflik sosial diberbagai lapisan. Nampaknya tak ada lagi ruang dialog yang bisa menciptakan suasana dialogis kearah terwujudnya tatanan nilai silaturahim. Musyawarah hanya terjadi di lingkungan elite dalam konteks bargaining dan loba lobi politik untuk kepentingan pragmatisme partai atau golongan dan kelompok pengelola kapital.
Diantara itu, melalui berbagai sorongan iklan di media sosial maupun media elektronika kita menyaksikan suatu gambaran kenikmatan kelas menengah atas dalam cengkerama yang seolah akrab, penuh kegembiraan sambil berucap “jangan lupa bahagia” di suatu café, restoran atau tempat rekreasi. Untuk meraih suasana akrab masyarakat dan warga kota membutuhkan biaya ekonomi yang lumayan tinggi. Secangkir kopi dan sepotong pisang goreng saja bisa senilai dua tiga kilogram beras. Menjadi pertanyaan kita, sejauh manakah modernisasi tata ruang kota bisa menempatkan posisi manusia, warga kota, ke dalaam lingkungan dan suasana nyaman, yang tak harus dibebani oleh nilai ekonomi yang membekuk? Bagaimanakah tata ruang kota dirancang menjadi ruang kebudayaan. Melalui asumsi dan konsep tentang ruang kebudayaan sebagai ruang bagi perwujudan nilai-nilai humanisme, kita bisa melanjutkan pertanyaan, sejauh manakah praktek politik tata ruang pengelola di dalam mewujudkan ruang kebudayaan.
Jakarta yang sejak tahun 1970-an dicanangkan menjadi kota metropolitan yang sekaligus juga dirangkapkan ke dalam konsep kota kebudayaan sejak periode Ali Sadikin sebagai gubernur. Taman Ismail Marzuki (TIM) menjadi sejenis proyek percontohan bagi kota-kota lain, yang pada ujungnya tak mampu mengikuti praktek politik kebudayaan yang diterapkan oleh Ali Sadikin. Konsekuensi logis dari kondisi itu, TIM bukan hanya menjadi “pusat kesenian” dengan beban sentralisasi dalam tatanan nilai pada skala nasional, tapi juga menjadi impian bagi siapapun yang tinggal di Jakarta. Kaum seniman-urbanis, kaum yang datang dari berbagai daerah yang bermukim di Jakarta yang cikal bakalnya adalah kaum perdesaan (rural), berlomba-lomba membuktikan diri sebagai peserta lomba kearah jenjang legitimasi kebudayaan. Penabalan sebagai peserta acara di TIM merupakan jenjang yang selalu diimpikan, suatu impian menjadi kaum modernis.
Yang menarik, politik tata ruang Ali Sadikin tak hanya menciptakan TIM sebagai pusat kesenian. Dibangunnya Gelanggang Remaja (GR) di lima wilayah di Jakarta merupakan suatu wujud politik tata ruang yang cerdas: GR menjadi ruang dialog bagi kaum muda seniman-urbanis yang ingin berlagak memasuki pusat tatanan nilai TIM. Periode Ali sadikin berlanjut dengan periode Tjoropranolo yng nampaknya masih memiliki komitmen kepada politik tata ruang Jakarta dengan pembentukan Balai Rakyat (BR) di setiap Kecamatan.
Catatan ringkas tentang TIM, GR, BR perlu dipikirkan Kembali sehubungan dengan sejauh manakah Jakarta yang kian membengkak oleh urbanisasi, sementara itu pada sisi lainnya kota membutuhkan ruang-ruang berekspresi. Kita bisa bertanya-tanya, masih adakah tata ruang publik di perkampungan di Jakarta bagi dan untuk kegiatan kesenian? Jika Soedjatmoko, salah satu anggota dan pendiri Akademi Jakarta pada tahun 1970 menyampaikan pidato kebudayaan di TIM dengan tajuk “Menjelang Politik Kebudayaan” dan dia menguraikan betapa pentingnya suatu kerangka kebudayaan berkaitan antara nasionalisme, keIndonesiaan dengan rasionalitas serta posisi kota, merupakan lontaran pemikiran yang perlu kita ingat dan kaji kembali, bahwa rasionalitas perkotaan kini sedang mengalami krisis berat. Sebagaimana Soedjatmoko, beriringan dengan pemikiran Ir. Sutami yang menyatakan bahwa suatu ekosistem yang berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan syarat mutlak, conditio sine quanon, bagi perkembangan kota kearah metropolitan dalam politik, ekonomi dan kebudayaan. Ekosistem itu berupa suatu penataan ruang yang berkaitan dengan dinamika dan aktifitas warga dalam suatu lingkungan yang bersifat ekologis.
Jakarta bukan lagi metropolitan, bahkan menuju megapolitan yang merangkum beberapa wilayah di sekitarnya sejak dua dekade terakhir. Pembengkakan wilayah Jakarta nampaknya tak cukup didukung oleh politik tata ruang kebudayaan. Aspek ekonomi menjadi yang utama, yang juga mengubah ruang-ruang publik menjadi ruang ekonomi seiring dengan ruang menjadi komoditas. Salah satu dampak komodofikasi ruang publik inilah yang menciptakan himpitan sosial-psikologis khususnya bagi masyarakat kelas menengah-bawah, yang megap-megap oleh tekanan sosial-ekonomi, yang berlanjut kepada tekanan politik.
Kembali kita bertanya-tanya, bagaimana posisi politik kebudayaan dalam hubungannya dengan tata ruang di Jakarta untuk bisa mengeliminir dampak sosial berupa konflik? Idealisasi posisi-fungsi kebudayaan bahwa tatanan nilai kebudayaan memiliki kandungan untuk menciptakan kondisi kearah penjadian warga sebagai individu yang memiliki kapasitas humanis melalui kesenian? Dan pertanyaan ini berlanjut kepada posisi-fungsi kaum seniman dan lembaga keseniannya, adakah kaum seniman memiliki komitmen dan memiliki kesadaran berorganisasi, suatu gerakan sosial untuk menciptakan perubahan cara berpikir pengelola kota? Dari kasus “Save TIM” saya mendapatkan kesan bahwa terasa kaum seniman-urbanis Jakarta masih dan hanya bersikukuh tentang TIM, dan melupakan infra struktur GR, BR dan ruang-ruang publik perkampungan di Jakarta. Cara berpikir sentralisasi seniman-urbanis yang juga dipenuhi oleh nostalgia TIM lama demikian akut, terasa ahistoris.
Catatan akhir yang ingin saya sampaikan disini, ketika dalam suatu diskusi via zoom yang diselenggarakan oleh Dirjenbud, pengelola M-Bloc menyatakan bahwa Jakarta menjadi inklusif melalui proyek M-Bloc, muncul pertanyaan dalam diri saya: berapa ratus miliar untuk menciptakan inklusifitas suatu ruangan jika M-Bloc menjadi ukuran? Inklusifitas bagi siapakah, lapisan sosial kelas menengah-atas? Seperti kaum seniman-urbanis yang ahistoris, nampak pengelola M-Bloc melupakan Jakarta dalam konteks sejarah sosialnya, bahwa kota merupakan konfederasi perkampungan dan komunitas yang menciptakan kota menjadi tumbuh berkembang kearah pembentukan kebudayaan melalui cikal bakal tradisi yang datang dari berbagai penjuru nusantara dan membentuk menjadi khasanah hibrida yang berkembang dan menjadi ciri khas perkotaan dan pembentukan ke-Indonesia-an.
Pada tanggal 23 September 2024 Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menyelenggarakan Dialog Publik Seni di TIM dengan mengundang tiga pasangan calon gubernur (cagub) Jakarta. Kita berharap semoga dialog itu bukan hanya basa-basi dari cagub, dan bukan pula luapan curhat kaum seniman. Semoga kaum seniman dan pemeikir kebudayaan yang diundang menyadari dan memahami, bahwa Jakarta sebagai proyek ke-Indonesia-an sebagaimana kota-kota lainnya membutuhkan bukan hanya kesadaran kepada politik tata ruang kebudayaan. Lebih dari itu, secara khusus dibutuhkan gerakan sosial kaum seniman secara berkesinambungan untuk menjaga ekosistem kebudayaan yang dinamik dengan visi rasionalitas.
Studio Plesungan, Karanganyar, 23 September 2024
*Halim HD, Networker & Organizer Kebudayaan