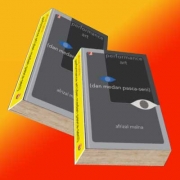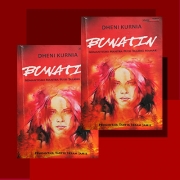Sepi yang Menggerogoti “Eksil”
Oleh Razan Wirjosandjojo (Studio Plesungan, Karanganyar)
Dinginnya Minggu (4/2) menggelitik ketika saya turun dari kereta komuter. Solo digempur hujan, saya kira Jogja hanya tinggal menunggu giliran. Saya memasuki gedung bioskop Empire XXI, mencetak tiket yang sudah saya pesan sebelumnya. Saya menunggu kurang lebih separuh jam dengan tiket yang menunjukkan nomor “4”. Tak lama saya memasuki ruang teater, kursi mulai diisi oleh penonton lainnya. Segelintir kelompok anak muda masuk menyaksikan, namun kebanyakan berambut putih.

Tiket bioskop untuk menyaksikan “Eksil” (Dok. Pribadi)
Film dimulai dengan lantunan dendang bernuansa Minang yang menerbangkan saya menuju kota-kota lain, lebih jauh – negara-negara lain. Bermula dari kubus-kubus gedung perkantoran ibukota dengan pernak-pernik kekacauannya, perlahan bersandar pada punggung dan telapak tangan orang tua yang berwajah pribumi. Mereka menapakkan kaki di antara lekuk-lekuk bangunan yang asing.

Tangkapan layar trailer film Eksil (Sumber : Kanal YouTube Lola Amaria Production)
Kumpulan pengalaman dari Hartoni Ubes, I Gede Arka, Tom Iljas, Waruno Mahdi, Herudjagio Mintardjo, Nurkasih Mintardjo, Asahan Aidit (alm), Chalik Hamid (alm), Djumaini Kartaprawira (alm), Kuslan Budiman (alm), Sardjio Mintardjo (alm), dan Sarmadji (alm) menjadi titik-titik yang disambung oleh Lola Amaria sebagai sutradara. Mereka merupakan eks-mahasiswa yang melanjutkan studi di luar negeri pada masa pasca-proklamasi. Pada masa Soekarno memimpin, intelektual yang berpotensi didukung untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Beberapa dikirim ke Jerman, Rusia, China, dan negara-negara lainnya. Mereka diharapkan menjadi muda bangsa yang dapat menyumbangkan pengetahuannya untuk pembangunan Indonesia yang saat itu masih belia. Pecah geger kudeta pada tahun 1965, harapan itu harus sirna.
Benang merah terjahit di antara pengalaman para mahasiswa yang ditendang, atau menendang diri dari tanah air. Kudeta yang terjadi pada 30 September 1965 terasa pahit bagi para mahasiswa tersebut, karena negara memaksa mereka untuk “menelan” rezim yang baru. Para narasumber adalah segelintir dari para mahasiswa yang menolak atau terpaksa bersembunyi, atas dasar pemusnahan paham komunisme yang membabi buta. Mereka yang tidak setuju terhadap pemakzulan Soekarno, harus merelakan kewarganegaraannya.
Satu per satu rekam cerita para narasumber terpapar, latar belakang kisah mereka sebagai eksil dibuka. Sejak mereka hengkang, paspor mereka mati. Tidak ada cara untuk memperpanjang dan mengambil hak kewarganegaraan itu kembali. Beberapa menyelamatkan diri ke negara yang lebih aman, beberapa terjebak, terpinggirkan, tergelandang. Cerita lalu-lalang mereka terbayang layaknya setan gentayangan mencari jalan pulang. Kata “jauh” pun masih terlalu dekat bagi mereka yang telah kehilangan daya untuk menjangkau jarak rumahnya.
Genosida yang terjadi di Indonesia pasca G30S juga menimbulkan perpecahan di lingkaran mahasiswa di luar negeri. Moskow merupakan salah satu kota yang menjadi saksi konflik tersebut. Mahasiswa yang memiliki latar belakang anggota, simpatisan, atau “berbau” kiri dipojokkan oleh pemerintah dan mahasiswa yang pro-orba. Uni Soviet mengirim mereka yang “ditinggalkan” ke pelosok negeri, diawasi siang-malam. Kabar pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia dan pengawasan ketat yang menyelimuti keseharian, mengendapkan kerak kecurigaan dalam hati para narasumber. Mereka terpaksa memelihara prasangka buruk, dihunuskan ke setiap kepala yang terlihat sebagai upaya melindungi diri.

Tangkapan layar trailer film Eksil (Sumber : Kanal YouTube Lola Amaria Production)
Cerita dari ingatan masa lalu para narasumber terdengar seperti sedang mengurai kerikil-kerikil tajam yang terkumpul menjadi satu bongkah batu. Lama didiamkan, pecah pun menyakitkan. Sedikit demi sedikit, kerikil tersebut menancap di ulu hati, perihnya masuk ke mata dan kuping. Kendati begitu, mata para narasumber ikut menceritakan percik semangat bertahan hidup. Ada api jiwa yang menjaga kapal tubuh mereka yang terombang-ambing agar tetap mengapung hingga akhir.
Harmoni kepedihan yang merantai dari cerita-cerita para narasumber terpecah menjadi lajur-lajur sikap yang mereka pikul. Alasan-alasan mereka untuk bertahan mulai tampak. Beberapa eksil memiliki latar belakang sebagai simpatisan atau pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka menyatakan pendapatnya masing-masing terhadap rezim orde baru. Tegangan muncul di benak saya ketika Asahan Aidit menyiratkan agresi yang tersisa ketika mereka aktif mendukung Partai Komunis Indonesia.
Saya tidak bisa mengelak bahwa G30S adalah klimaks dari perseteruan ideologi politik yang masif. Tidak hanya di Indonesia, namun kondisi saling slengkat antar praktik politik liberal – komunis merupakan fenomena global. Klimaks yang menyayat harus kita terima sebagai hasil dari politik jotos-jotosan tersebut. Begitu adanya, saya tertarik pada pernyataan salah satu eksil yang mengatakan bahwa PKI mungkin melakukan kesalahan, Soekarno sempat mengatakan bahwa pada saat itu PKI keblinger dengan kejayaan dan popularitasnya. Namun kesalahan-kesalahan tersebut tetap tidak sebanding dengan gedung kebohongan yang dibangun sebagai monumen untuk mempersekusi jutaan manusia. Peristiwa 30 September 1965 menjadi kebengisan struktural yang berhasil mencabik kemanusiaan, akal sehat, dan kompas moral begitu banyak orang di Indonesia.

Tangkapan layar trailer film Eksil (Sumber : Kanal YouTube Lola Amaria Production)
***
Embun-embun sepi menempel pada rantai peristiwa yang dialami narasumber di berbagai lempeng dunia. Tiap-tiap bait cerita yang dilantunkan oleh narasumber bernada hening. Kesendirian diam dan bergerak di sela-sela tanaman, atau dibalik bangku yang berserakan. Soeharto tidak hanya menyobek paspor mereka, namun juga mengoyak-oyak mereka dengan sepi. Sepi mewujud “hantu” yang mencekam hidup para eksil.
Sapardi Djoko Damono dalam puisinya “Pada Suatu Malam “ mengatakan “Sunyi adalah minuman keras”. Saya pikir tepat adanya. Menepi dan nyepi menjadi cara jitu untuk menjaga akal sehat, khususnya di tengah riuh kondisi politik yang ledakannya memekakkan telinga. Sejak awal film diputar, para eksil memilih sepi sebagai sikap mereka terhadap teriakan rezim. Mereka membangkang dari upaya orkestrasi mahasiswa untuk mengikuti paduan suara kebencian dan pengkhianatan. Diam dan hening menjadi suara perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Maka, sepi menjelma whiskey yang menendang. Hangatnya memberi kekuatan menghadapi malam-malam musim dingin. Mabuknya melarutkan duka. Namun siapa yang mampu menjaga kesadaran dan bertahan menegak sepi selama 32 tahun?

Tangkapan layar trailer film Eksil (Sumber : Kanal YouTube Lola Amaria Production)
Mereka pikir sepi ini hanya cerpen yang segera tuntas, namun ternyata ia bak novel tebal berjilid-jilid. Sepi menggigit, semakin jadi – ia menggerogoti. Mereka tak berdaya menghadapi sepi yang tak berkesudahan. Surat-surat mereka tak mampu menjangkau keluarga, bahasanya tak mampu dipahami tetangga. Sepi menjadi parang yang digunakan untuk menggorok leher mereka sendiri, mengalami mati berkali-kali. Mereka terpaksa membunuh cinta, benci, marah, dan segala perasaan terhadap diri mereka dan orang-orang yang (pernah) mereka kenal. Sesekali jejak kematian itu mencuat dari cerita para eksil yang rela ditinggalkan istrinya. Pasangan mereka dikabarkan telah menikah kembali, bahkan menjalin kasih dengan sahabat sendiri. Mereka terima selapang gurun Sahara. Saya membayangkan satu “kuburan massal” yang mereka gali untuk orang-orang terkasih di dalam pikiran dan kesadaran. Senyum-senyum kecil mereka menyiratkan liang lahat yang begitu dalam.

Tangkapan layar trailer film Eksil (Sumber : Kanal YouTube Lola Amaria Production)
epi melanda, saya melihat buku kerap hadir sebagai teman yang setia. Rumah-rumah para eksil yang tersorot di dalam film menunjukkan koleksi buku yang membanjir di dalamnya. Di antara buku-buku “terlarang”, ada pula arsip-arsip teman lama, novel, jurnal, dan berbagai kertas-kertas yang menggunung. Meminjam ungkapan Halim HD ketika saya menghadiri kelasnya, buku dapat menjadi teman yang baik. Dalam film ini, buku dapat melampaui fungsinya sebagai sumber pengetahuan. Ia menjadi dongeng yang mencerahkan malam-malam yang kelam, menjadi lagu cinta yang melipur jiwa yang senyap, menjadi tarian yang melenggang di kasur yang senggang, menjadi bising yang mengisi kursi-kursi kosong. Buku menjadi kerabat yang tidak akan pergi dan mengkhianati.

Tangkapan layar trailer film Eksil (Sumber : Kanal YouTube Lola Amaria Production)
Hilangnya sosok tanah air di ujung pandang terus berlangsung sampai Soeharto secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden. Berita tersebut dipercaya sebagai tanda tuntasnya cengkeraman Orde Baru, mengembalikan jarak yang lama hilang. Harapan yang lama terkubur mereka gali dan lap kembali. Mereka menunggu kilau harapan itu dapat ditukar emas garuda yang tergambar di cover paspor. Sayangnya, harum harapan yang menyeruak pada era pemerintahan Gus Dur kembali kecut. Para narasumber memilih jalan putar balik, mendaftarkan diri sebagai warga negara tempat mereka tinggal. Paspor barunya memberikan jembatan lain bagi mereka untuk menyeberang.
Eksil yang kembali ke Indonesia bukannya tanpa kesukaran. Melihat perubahan drastis dari kondisi sebelum mereka pergi, mengunjungi keluarga yang masih bermimpi buruk, negara yang masih menyimpan dendam. Mereka tetap menjadi hantu di negaranya sendiri. Asing tidak hanya dari paspor, tapi juga dari bagaimana keluarga dan negara menatap mereka. Meskipun demikian, mereka tak patah arang. Kekecewaan menjadi cinderamata, nasionalisme yang mereka jaga tetap hidup walau tercabut dari tanah asalnya. Kondisi tak berkewarganegaraan melatih mereka untuk memaknai tubuh sebagai rumah dan negara yang paling kokoh dan setia.
Pada akhir film, saya merasa para eksil sejatinya tidak sendiri. Mereka berdua dengan sepi. Tubuh mereka menata ulang seluruh senyawa di dalamnya, membuat kesendirian dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk tetap bertahan. Ketika film selesai, pikiran saya bergumam ”kodrat kesendirian manusia menghadiahkan kebersamaan sebagai ujian seumur hidup”. Saya ke luar dari teater menyembunyikan sepi yang menetes dari wajah saya bersama deras hujan di kota Jogja.
***
Film “Eksil” Lola Amaria menjadi kolase cerita-cerita para eksil politik yang sebelumnya kedap di mulut. Ia rapat terikat di lidah, terbungkam dalam rahang yang bergetar. Bebunyiannya tak berhenti menggiring penonton untuk masuk ke bilik-bilik tertentu, menjadikan film ini gaduh. Bagaimanapun, kegaduhan tersebut cukup berarti untuk menggaungkan sisi kenyataan yang lain, yang kicaunya dikerangkeng sangkar cendana dan dikelukupi bendera Golkar.

Tangkapan layar trailer film Eksil (Sumber : Kanal YouTube Lola Amaria Production)
Sesekali cerita para narasumber diilustrasikan dengan animasi dua dimensi hitam-putih, ditawarkan sebagai “alat bantu” untuk penonton dalam membayangkan peristiwa tersembunyi dalam bayang-bayang gelap sejarah. Sekilas gaya animasi tersebut mengingatkan saya pada karya “Acung Memilih Bersuara” oleh Amelia Hapsari, yang juga mengangkat isu genosida pasca G30S. Bagi saya, teknik animasi yang digunakan terlalu didaktis dan meng-kubu-kan. Animasi itu menghadirkan kubu yang berkuasa rampak tersenyum bengis dan marah, dan yang tersingkir selalu muram dan sedih. Peristiwa yang surealistik dan kontradiktif, disederhanakan menjadi kejadian yang “hitam-putih”. Menjadi soal siapa baik-siapa buruk. Lain hal, ketika rekam suara narasumber dipertemukan dengan gambar atau pemandangan yang (hampir) tidak berkaitan secara naratif. Pikiran saya justru mulai “menggerakkan” cerita tersebut menjadi warna-warna yang personal. Saya pikir Lola perlu lebih mempercayakan kapasitas penonton dalam berimajinasi sebagai perangkat untuk menciptakan dunia kritik yang lebih intim.
Daya transendental yang muncul dari cerita-cerita para eksil justru runtuh karena monolog-sajak yang diucapkan oleh Lola. Teks sajak yang terlampau dramatis, semakin terbanting karena suara sang sutradara. Tidak bertubuh, namun suaranya juga tak mampu menjadi setan yang merasuk ke dalam sanubari penonton. Suaranya justru mencabut saya dari belantara kisah para narasumber. Wes kecer tur mblasuk ke dalam semak cerita narasumber, harus terpontal jengkel mendengar sajak Lola yang terdengar seperti pembawa acara infotainment di TV.

Tangkapan layar trailer film Eksil (Sumber : Kanal YouTube Lola Amaria Production)
Pewarnaan gambar di film ini tidak muluk, namun cukup untuk ikut menyelimuti suasana dengan biru sendu rindu. Jahitan antar cerita juga menjadi garis yang terasa berkelok-kelok, namun dapat dibaca mengarah pada tujuan yang spesifik, seperti naik mobil ke Padang lewat kelok 9.Dominasi laki-laki dalam film ini juga masuk akal, mengingat berbagai faktor politis dan psikologis. Ketiadaan narasumber perempuan dapat dilakukan untuk alasan pelindungan sekaligus kritik atas sejarah perempuan yang rawan penindasan, termasuk penindasan politik. Terlepas dari itu, pertanyaan atas ketiadaan itu tetap saya ajukan dan tetap pantas untuk ditanyakan.
Melihat film “Eksil” dilayar bioskop seperti membaca majalah dinding yang sempat dilarang terbit. Ia menyajikan artikel-artikel yang tidak saling bersambung, namun berkaitan dengan tema majalah tersebut. Pada akhir film, Lola juga menampilkan artikel-artikel yang gagal terbit karena penulisnya sudah keburu “pensiun”. Lola hadir sebagai penyunting yang ikut menyampaikan gagasan dan harapannya lewat mosaik artikel-artikel para penulis. Film “Eksil” dapat hadir sebagai majalah dinding yang bermakna bagi masyarakat Indonesia yang malas membaca dan enggan berpolitik. Ia dapat mengetuk pintu moral bagi generasi baru yang nihil ingatan masa lalu, sekaligus peringatan bagi kita semua untuk menghadapi kebuasan sepi sebagai buta kala yang lahir dari rezim mendatang.
Razan Wirjosandjojo adalah seorang seniman yang saat ini tinggal di Solo, Indonesia. Ia menyelesaikan studinya di Jurusan Tari Institut Seni Indonesia Surakarta. Razan mulai aktif menari pada tahun 2010 dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu dari berbagai ruang dan komunitas di Jakarta hingga tahun 2017. Setelah pindah ke Solo, ia belajar bersama Melati Suryodarmo sejak tahun 2018 hingga sekarang. Sejak 2020, Razan mulai
menciptakan karyanya sendiri dan memperluas sudut pandangnya dalam melihat tubuh sebagai wahana dan mengembangkannya dalam wujud seni pertunjukan, seni performans, film, dan fotografi. Saat ini Razan merupakan murid dan staf paruh waktu di Studio Plesungan.