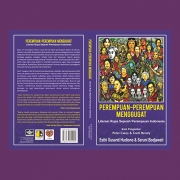Seni Rupa Indonesia Mau Dibawa ke Mana?
(Tanggapan untuk empat tulisan di Kompas Minggu)
Oleh Arahmaiani
Tulisan kritis Aminudin TH Siregar (Ucok) yang dimuat di Kompas Minggu (30/5/2021) dengan judul “Takjub Ajoeb: Kepada Bung Hendro Wiyanto” telah memantik perenungan tentang sejarah Indonesia dalam hubungannya dengan aspek kebudayaan dan seni. Di dalam kenyataannya jikalau kita mulai memikirkan permasalahan sejarah dan budaya memang masih ada bagian-bagian yang “remang-remang” dan belum cukup terjelaskan. Baik di masa modern ataupun sebelumnya, ketika dinamika budaya Nusantara sudah melewati jangka waktu ribuan tahun perjalanan sejarah. Tulisan yang ditujukan kepada Hendro Wiyanto dan kemudian ditanggapi yang bersangkutan serta penulis-penulis lainnya, telah memicu imajinasi saya akan masalah budaya ruwet negeri yang pernah dijajah pihak asing selama ratusan tahun ini. Walaupun kemudian akhirnya merdeka pada 1945 (sekalipun pihak penjajah Belanda baru mengakuinya pada 1949). Kemudian wilayah ribuan pulau dengan penghuni beragam kelompok suku atau masyarakat adat ini lalu menjadi sebuah negara berdaulat: Indonesia.
Ketika mencoba menelusuri dan memahami alur sejarah politik modern dalam hubungannya dengan aspek seni dan budaya, terasa seperti ada ketidakjelasan hubungan. Terutama sesudah terjadinya tragedi 1965 yang boleh dianggap sebagai bagian sejarah kelam dan “misterius” bangsa yang masih bergulat dengan identitasnya ini. Dan bangsa ini sepertinya masih mendapat tantangan untuk memaknai istilah “kemerdekaan” yang tampaknya belum tuntas hingga saat sekarang pun. Memunculkan banyak pertanyaan seperti: apakah bangsa dan negara yang diistilahkan sebagai bagian dari “the 3rd world”atau “negara berkembang” ini sesungguhnya sudah betul-betul terbebas dari penjajahan? Lalu apa yang terjadi di dalam praktek sistem ekonomi global dan juga pengaruhnya di ranah budaya dan seni? Yang nampak bukan tanpa masalah dengan berbagai dampak negatif ataupun positifnya. Apalagi sesudah wabah covid-19 merajalela dan hidup dilanda malapetaka ketidakpastian dan kematian yang bisa terjadi dalam waktu singkat.
Ucok memulai tulisannya dari kutipan Joebaar Ajoeb tentang seni rupa pasca-1965. Ia mempertanyakan peran seni rupa di dalam dinamika kehidupan berbangsa di era “pembangunan”. Pernyataan keraguan Ajoeb tentang peran seni rupa di masa itu dinyatakan dalam kalimat: hanya dianggap berpapasan saja dengan gempita pembangunan. Seni rupa seperti tak diajak berpartisipasi atau bisa disimpulkan menderita inferioritas! Dengan memberikan contoh lukisan yang dibuat S. Sudjojono Maka Lahirlah Angkatan’66 (1966) dan AD Pirous Mentari Setelah September 1965 (1968), Ucok lanjut membahas polemik politik-sosial-budaya yang ia lihat sebagai permasalahan yang harus didalami lebih jauh. Dan tentunya pemikiran atas pembacaan karya-karya ini juga muncul dari pemahaman akan fakta. Hasil penelitian tentang tragedi 1965 sampai sejauh ini memang menunjukkan adanya “permainan”.

S. Sudjojono, Maka Lahirlah Angkatan ’66 (1966)

A.D. Pirous Mentari Setelah September 1965 (1968)
Respon dan bantahan Hendro Wiyanto juga menarik, dimuat di Kompas Minggu (13/6/2021). Ia berusaha memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan Ucok yang dikemas dalam tuturan kutipan-kutipan pendapat para pemikir seni rupa lewat contoh karya-karya di atas. Lalu ia memberikan contoh karya Semsar Siahaan yang gahar kritis atas kondisi kehidupan yang dikendalikan “ideologi pembangunan” di bawah rezim militer otoriter pimpinan Soeharto. Untuk menegaskan contoh karya seniman yang tidak hanya sekedar “berpapasan” dengan kegempitaan proyek pembangunan, tetapi tegas mengambil peran “menggedor” pintu ruang politik yang ditutup rapat-rapat. Juga dalam menanggapi tragedi 1965 Hendro Wiyanto mengajukan pendapat dengan memberikan contoh khazanah sastra yang menanggapi kerumitan “konflik psikologis dan manipulasi ideologis”. Menegaskan kesimpulan penting bahwa permasalahan sebetulnya terletak pada para pelaku aksi kekerasan, bukan korban.

Semsar Siahaan, Para Pekerja Perempuan Diantara Pabrik & Penjara (1982)
Selanjutnya ditarik kesimpulan lain: masalah seni rupa bangsa ini mestinya tidak cukup dipaparkan saja, tapi mesti “ditemukan” di dalam karya. Yang tentu benar adanya—dan mengingatkan Ucok untuk tidak hanya sibuk mengurusi pewacanaan saja. Sebagai seorang seniman tentu saja saya tidak akan membantah pernyataan itu. Sisi lain yang muncul dan menarik untuk direnungkan adalah bagaimana “provokasi” Ucok berhasil menggugah argumentasi bernada cukup emosional yang positif. Merangsang imajinasi untuk menjadi lebih aktif dan bahkan agak “liar”. Karena saya merasakan adu argumen yang bersifat oposisional bisa melahirkan dinamika pada satu sisi. Namun jika terus diulang-ulang dalam pola yang sama, terasa seperti menjadi “mentok”. Hanya seperti berputar-putar di ruangan yang sama. Dan ketika situasi seperti ini muncul, maka timbul semacam reaksi psikologis untuk tidak terperangkap di dalam jebakan. Lalu mencari “jalan keluar” dan tidak bergabung dengan kelompok “cebong” atau “kampret”. Supaya kreatifitas bisa terus dijelajahi. Dan itulah fungsi media seni. Sehingga kita tidak perlu terjebak dalam pola pikir “hitam-putih”.
Perasaan ini juga muncul ketika Asmujo J Irianto berbicara tentang “dominasi” dan pengaruh Barat di dalam pewacanaan dan pemaknaan sejarah seni rupa modern-kontemporer yang dimuat di Kompas Minggu (11/7/2021). Wacana Barat menjadi rujukan untuk memahami praktek seni rupa di Indonesia, dalam posisinya yang marjinal di dalam konteks dunia seni rupa internasional. Globalisasi dan kemudahan arus informasi mempercepat tersebarnya pengaruh wacana seni rupa di Barat menjadi wacana global. Ah, ini lagi-lagi terasa seperti dorongan ke depan pintu gerbang perangkap pola pikir “oposisi- biner”. Walaupun tentu saja saya juga setuju untuk melakukan perlawanan jika ada pihak yang mau mendikte dan menguasai pewacanaan sesuai dengan agenda penjajahan gaya baru. Tetapi jika istilah pluralisme dan prinsip multikultural sudah dimunculkan dan diterapkan harusnya agenda “penjajahan” sudah tidak diberlakukan lagi. Hanya saja topik budaya untuk bangsa Indonesia sendiri entah disampaikan lewat karya ataupun pewacanaan masih harus menghadapi beberapa tantangan permasalahan serius. Khususnya dalam konteks hari ini.
Ya, saya merasa harus waspada akan perangkap pola “hitam-putih” ini sebab dalam konteks sejarah politik hal seperti ini bisa membawa konsekwensi berbahaya dan mengerikan. Saya kira itulah sebabnya kenapa Bung Karno tidak setuju ketika Affandi akan mendesain mural di museumnya dengan tema “kanan lawan kiri” atau para kere berhadapan dengan para borju. Sebagai seorang politisi pastilah beliau paham kalau pola pikir macam itu akan gampang dimanipulasi menjadi strategi “adu domba” oleh pihak-pihak yang akan memanfaatkan keadaan demi kepentingan agenda kekuasaan ataupun keuntungan finansial. Dan memang kemudian terbukti menjadi kenyataan yang memilukan. Berupa aksi pembantaian dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh mereka yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Sejarah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat yang memakan korban kematian hampir 1 juta orang ini hingga sekarang belum terselesaikan baik di ranah hukum ataupun ranah sosial-budaya. Tampaknya budaya kekerasan hanya dianggap sebagai bagian yang wajar dari kehidupan.
Kita sudah menyaksikan sendiri gejala kembali aktifnya budaya kekerasan ini. Malah seperti semakin menggila karena sipelaku sendiri bisa tega untuk “menghabisi” dirinya (bahkan anggota keluarganya sekalian) ketika melakukan penyerangan. Mereka yang dituduh bersalah karena tidak sama keyakinannya menjadi sah untuk dibantai. Atau jika diberi label “komunis” maka boleh dianiaya atau bahkan dihilangkan nyawanya! Begitulah kondisi nyata perkembangan situasi politik lokal nasional yang terkait sistem global. Telah melahirkan kelompok “teroris” yang bisa dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian publik dari hal yang lebih penting. Seperti eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang cenderung “dilindungi” peraturan yang berpihak pada pemilik modal. Ya, dalam kenyataannya agama bisa diinstrumentalisasi untuk melancarkan agenda penguasaan dan pengalihan perhatian. Maka bumi yang menjadi sumber kehidupan seperti menjadi kurang penting dibanding agama yang menjanjikan surga di ahirat kelak. Sekalipun bumi dijadikan neraka. Ibu Pertiwi dianiaya dan kaum perempuan diposisikan tidak setara dengan pria.
Lalu apa hubunganya dengan seni rupa ya? Apa urusan seniman dengan politik dan lingkungan hidup? Ah, sudahlah gak usah cerewet, buat saja karya indah biar laku di pasar. Untuk bisa bertahan hidup dan membiayai kebutuhan keluarga. Begitu pula para kurator dan kritikus ngapain ngurusin masalah beginian sih. Dunia seni rupa kan cuma butuh pasar pada dasarnya. Kalau bisa bermanfaat untuk yang disebut pemilik galeri dan kolektor, selain si seniman – ya sudah cukup toh Cok?! Itu suara yang muncul di wilayah “otak kiri” saya yang membuat saya mengangguk-anggukan kepala. Tapi kemudian dari “otak kanan” terdengar bisikan: gak kreatif kamu kalau cuma mikirin estetika saja—apalagi cuma buat cari duit melulu. Hidup ini perlu dipahami lewat pendekatan menyeluruh, diwarnai emosi positif indah dan bermanfaat untuk semua. Dan saya pun mengangguk-angguk lagi. Lalu berdiri tegak memandang sekeliling, merasa tersadarkan akan potensi manusia yang perlu dipahami dan tidak perlu ada bagian dinafikan. Bahwa “kiri dan kanan” sebaiknya dinegosiasikan sehingga kita bisa menemukan “jalan tengah” untuk mencapai keseimbangan dan perdamaian.
Itulah kesadaran yang sebetulnya muncul sesudah saya mempelajari sejarah politik dan budaya dari masa kuno yang terlupakan. Yaitu periode jauh hari sebelum penjajah datang. Kemudian saya tafsir ulang dalam konteks hari ini menjadi sebuah karya lukisan dengan judul Lingga-Yoni (1993). Visualisasi “lingga-yoni” adalah simbol dari hubungan seimbang dua kekuatan berlawanan di alam semesta. Atau terkadang diistilahkan sebagai “keseimbangan enerji feminin dan maskulin”. Pada awalnya karya ini dianggap bermasalah oleh kelompok “garis keras Islam” di tahun 1994 hingga boleh menjatuhkan vonis: bahwa darah saya “halal untuk diminum”! Dan hal itu terjadi karena mereka tidak memahami sejarah dan akar budaya warisan leluhur. Yang bersifat terbuka untuk akulturasi dan sinkretisasi berbagai macam kebudayaan dan keyakinan. Karena semua yang berbeda itu diposisikan di dalam kesetaraan. Itulah indikator nyata bagaimana kebudayaan lokal sudah tidak dipahami lagi dan membawa permasalahan “krisis identitas”. Yah, kalau pengetahuan budaya sendiri saja bermasalah, lalu seni (dan seni rupa khususnya) apakah bisa dikembangkan dengan karakter khas? Memiliki pijakan dan kepribadian dasar yang kuat dan tidak akan didikte oleh pihak liyan.
Beruntung saya bisa selamat dan juga karyanya. Pada tahun 2018 karya itu ditampilkan dalam pameran tunggal saya di Museum MACAN dan tidak mendatangkan permasalahan. Tampaknya sudah ada kemajuan pengetahuan dan perkembangan pemahaman budaya di masyarakat kita. Dan sepertinya akan bisa terus lanjut berkembang seiring dengan sikap terbuka pihak pemerintah, khususnya Kementrian Agama yang akan membuka candi Borobudur sebagai tempat kegiatan spiritual umat Budha. Peninggalan berharga dari masa lalu yang bermakna mendalam ini akan mendorong manusia menyadari potensi positifnya: melahirkan rasa welas asih dan laku bajik. Memahami nilai-nilai universal dan spiritual yang menghubungkan budaya maupun keyakinan berbeda. Dan perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman tetapi merupakan sumbangan kekayaan budaya . Sehingga prinsip Bhinneka Tunggal Ika bisa ditegakan dan dipraktekkan di dalam kehidupan. Itulah sebabnya berbagai macam budaya dan keyakinan atau agama bisa hidup berdampingan di dalam perdamaian dan persaudaraan. Tidak memicu kebencian dan mendukung budaya kekerasan.

Lukisan Tankha, “Lingga-Yoni” versi Tibet
Sekali lagi di dalam hal ini saya sangat beruntung karena menemukan kembali tradisi budaya leluhur yang “hilang” atau terlupakan di plateau Tibet. Mungkin terdengar agak absurd ya, apa sih hubunganya Tibet dengan leluhur Nusantara. Karena tak pernah ada penjelasan mengenai hal ini di dalam buku-buku sejarah resmi yang diterbitkan di sini. Saya sendiri ketika “kesasar” ke Tibet pada 2010 dan mendapat informasi fakta ini, hanya bisa terbengong dan melongo. Nah, ini satu contoh lagi bagaimana bagian sejarah budaya yang penting bisa “hilang”—dan kalau tidak dipahami lagi tentunya akan membawa dampak buruk. Poin penting lainya adalah hubunganya dengan seni rupa tentunya. Bagaimana di masa silam leluhur Nusantara sudah mengolah media seni rupa secara kreatif, mengangkat nilai-nilai luhur. Tidak hanya asik dan repot dengan aspek fisik dan visualnya saja. Tetapi sanggup menggabungkan sisi visual-material dengan nilai-nilai spiritual ataupun bidang ilmupengetahuan lainya. Yang menjelaskan pemahaman hubungan manusia dan alam di dalam keselarasan atau keharmonisan. Untuk supaya saling memberi manfaat dan dukungan.
Sangat berbeda dengan cara pikir dan gaya hidup modern yang dianggap “maju”. Yang cenderung mengumbar ego dan ketamakan lalu menciptakan sistem ekonomi dan politik eksploitatif dan bersifat menjajah. Tidak adil dan hanya menguntungkan segelintir orang, selain merusak lingkungan hidup yang menjadi “rumah” bagi semua mahluk. Begitulah ketika manusia melihat dirinya sebagai “penguasa” alam dan bukan bagian yang harus menjaga keselarasan, maka ia akan dikendalikan oleh egoisme dan kerakusan. Kenyataan ini akan tampak jelas ketika kita memahami sejarah politik, ekonomi dan budaya serta berbagai ilmu pengetahuan pendukungnya. Begitulah cara pandang yang terpapar di dalam ajaran- ajaran peninggalan leluhur yang kaya ilmu pengetahuan dan dikombinasikan dengan kearifan. Memahami manusia dengan segala potensi positif maupun negatif untuk diolah dan diwaspadai demi kemaslahatan bersama di dalam kehidupan yang damai, tentram dan aman. Melahirkan manusia berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan etika.
Yang tidak akan mendukung dan membenarkan laku korupsi ataupun pelemahan KPK. Membuat peraturan-peraturan yang memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan industri ekstraksi dan perkebunan kelapa sawit untuk menghancurkan lingkungan hidup. Memberi kesempatan untuk mengeksploitasi buruh dengan membuat peraturan yang tidak melindungi mereka. Begitu pula perlakuan atas masyarakat adat yang disingkirkan dari pemukiman dan sumber kehidupannya, ketika hutan ulayat disita dan dijadikan wilayah industri. Sumber air dikuasai atau bahkan dalam beberapa kasus dihancurkan. Karena ditemukan unsur alam lain yang dianggap lebih berharga yang bisa dimanfaatkan. Padahal dengan hilangnya sumber air—bukan hanya manusia yang menderita tetapi akan membuat semua mahluk kesusahan dan juga unsur alam lainya bisa dilanda kepunahan. Membentuk sistem hierarki represif di mana kelas bawah yang dimarjinalkan (seperti kelompok orang miskin dan papa atau kaum perempuan) akan ditindas dan dieksploitasi.
Tradisi budaya Nusantara yang dilestarikan dan masih dipraktekkan di Tibet diperkenalkan dan diajarkan oleh seorang biksu berasal dari India bernama Atisha Dipankara Srijnana. Yang pernah belajar kepada Mahaguru lokal bernama Dharmakirti selama sekitar 12 tahun di biara Muara Jambi (juga belajar dan mengajar semedhi di Tempuran Elo-Progo di dekat candi Borobudur) sekitar 1000 tahun yang lalu. Di masa itu kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Medang Kamulan di Jawa bersatu-padu dan menjadi keluarga. Selain menganut keyakinan sama yang kemudian melahirkan budaya dan tradisi ajaran Bodhisatwa yang unik dan sangat beradab. Terukir secara lengkap di panel-panel relief candi Borobudur. Dengan landasan prinsip ajaran dasar tugas manusia untuk “membebaskan semua makhluk dari penderitaan”. Yang didasari rasa welas asih dan sikap hidup tanpa kekerasan. Tradisi ini juga dilengkapi dengan kemampuan mengolah logika dan rasionalisme yang dihubungkan dengan filsafat, ilmu pengtahuan dan seni. Dan menyangkut aspek seni rupa, bisa dilihat pada banyaknya karya-karya seni lukis maupun patung yang memenuhi kuil-kuil suci atau tempat-tempat “peribadatan” (tempat praktek ritual-ritual keagamaan dimana mereka berlatih melantunkan mantra ataupun semedhi. Selain belajar dan mendengarkan ceramah para Lama & Geshe).

Lukisan (thanka) Mandala Tibet

Candi Borobudur, Magelang (Jawa Tengah)
Penemuan ini memotivasi saya untuk terus lanjut menggali warisan budaya masa lalu. Dan menjadi lebih memahami masalah “keterputusan” alur sejarah dan akar budaya. Yang bisa terjadi akibat perubahan zaman baik yang bersifat “alami” ataupun yang “dikonstruksikan”. Yang biasanya dilakukan oleh kelompok elit penguasa baik yang lokal-nasional (seperti sudah disinggung diatas ketika diktator Orde Baru berkuasa) maupun penjajah asing. Terjadi dari waktu ke waktu dalam periode berbeda-beda. Mulai dari masa kuno (Animisme, Hindu, Buddha), masa Islam, dan juga masa penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris dan Jepang. Bahkan terjadi penjarahan artefak dan manuskrip oleh pihak penjajah. Dan Belanda menjarah secara masif! Sekalipun sudah mulai dilakukan pengembalian (repatriasi) sejak tahun 70-an namun hingga saat ini masih ada lebih dari 10.000 artefak dan ratusan ribu manuskrip yang masih tersimpan di museum-museum Belanda. Pemerintah Belanda sudah berjanji akan mengembalikan semuanya (tahun lalu keris Diponegoro sudah dikembalikan), tetapi apakah pihak pemerintah Indonesia sudah siap untuk merawat dan menyimpanya dengan aman?! Nah, ini juga berhubungan dengan pertanyaan kawan-kawan.
Pengembalian keris Diponegoro tentunya berhubungan dengan lukisan Raden Saleh yang dibuat pada tahun 1857. Melukiskan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh pihak Belanda yang dilakukan dengan cara yang curang atau ditipu dan dijebak. Raden Saleh pun kemudian memberikan lukisan itu kepada Raja Belanda Willem III. Ya, lukisan itu diberikan—bukan dijual. Tentunya sebagai ungkapan sikap “protes” lewat karya seni yang ditujukan pada pihak penjajah. Yang membutuhkan keberanian dan ketegasan sikap dengan segala resikonya. Jadi peran seorang seniman (dalam hal ini perupa) sebagai agen kreatif bisa bersifat “multi-tasking” atau menjalankan berbagai peran dengan mengerjakan beragam pekerjaan/tugas. Diekpressikan lewat karya dan tindakan kongkrit di dalam kehidupannya. Setelah program reptriasi dijalankan karya lukis penting ini pada tahun 1975 ahirnya diserahkan ke pemerintah Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Lalu disimpan di Istana Merdeka dan pada tahun 2014 dipindahkan ke Museum Kepresidenan Yogyakarta. Kasus yang menarik, bukan?

Raden Saleh, Penangkapan Pangeran Diponegoro (1857)
Kembali ke topik masalah dunia seni rupa hari ini yang pada dasarnya tidak cukup mendapat dukungan dari pemerintah. Tapi mendapat dukungan dari para filantropi lewat mekanisme pasar. Walaupun tidak selalu stabil dan hanya mengakomodasi perupa-perupa tertentu yang karyanya diminati. Biasanya karya-karya yang diminati tidak perlu mengangkat wacana atau permasalahan seputar topik sejarah, politik, sosial, budaya ataupun lingkungan hidup. Diistilahkan sebagai seni rupa otonom atau gerakan seni untuk seni di dalam tulisan Asmudjo J Irianto yang kritis terhadap hal ini. Karena dianggap menyebabkan posisi seniman menjadi sangat berjarak dengan masyarakatnya. Dan kemudian ia juga menyampaikan informasi tentang gerakan perlawanan oleh “kolektif seni”. Yang mendapat tanggapan serius dari Documenta. Sebuah organisasi non-profit di Jerman yang mengadakan pameran seni rupa berskala internasional setiap 5 tahun sekali di kota Kassel. Dan untuk pameran yang akan datang pada tahun 2022, kolektif Ruang Rupa ditunjuk sebagai Direktur Artistiknya.
Kondisi “gerhana” dunia seni rupa Indonesia seperti yang disimpulkan Aminudin TH Siregar, Hendro Wiyanto maupun Asmudjo J Irianto dengan segala argumenya tampaknya memang benar adanya. (Seperti sudah saya paparkan di atas—saya juga melihat cukup banyak permasalahan mendasar). Sekalipun disanggah oleh Yuswantoro Adi dalam tulisanya yang dimuat di Kompas Minggu (27/6/2021) dan menyampaikan berita baik yang datang dari Yogyakarta. Mungkin atmosfir dunia seni rupa di Yogyakarta berbeda dengan di Bandung, Jakarta, Bali ataupun kota dan wilayah Indonesia lainya. Yang konon dalam situasi pandemi sekalipun masih ada pelukis/perupa yang bisa menjual karya, walaupun harganya harus diturunkan. Saya merasa tak perlu menanggapi pendapat dan pemaparan dari kawan seniman yang merasa tak punya masalah. Sekalipun di dalam hati saya muncul pertanyaan: betulkah situasi umumnya kehidupan para seniman di Yogyakarta baik-baik saja—apa lagi sesudah dilanda pandemi virus covid-19. Karena dari berita yang saya dengar baik dari teman-teman ataupun media, situasinya jelas tidak bisa dikatakan “baik-baik” saja.

Arahmaiani, Proyek Bendera (2007)
Sebelum mengahiri tulisan ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada para penulis. Saya ingin mengetahui pendapat Anda sekalian tentang karya seni rupa yang tidak konvensional (bukan lukisan atau patung dengan media biasa). Karena di dalam tulisan-tulisan ini tidak mendapat perhatian apalagi bahasan atas karya seni rupa seperti itu. Padahal sudah banyak karya seni rupa dibuat dengan menggunakan media yang bukan berupa lukisan atau patung biasa seperti: seni performans, seni video, seni multi media, lukisan digital, dan yang diistilahkan sebagai karya “seni berbasis komunitas”. Atau juga yang disebut oleh Asmudjo sebagai “seni kolektif”. Hanya saja penjelasanya sangat singkat yaitu: praktek seni rupa yang dikembalikan kepada masyarakat. Sebagai seorang seniman saya sendiri meyakini bahwa semua orang pada dasarnya memiliki kemampuan kreatif yang bisa diekspresikan lewat beragam media. Dan masih bisa terus dikembangkan sejalan dengan semangat eksplorasi kreatifitas untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ataupun tantangan kehidupan lewat perspektif estetika yang akan melahirkan karya yang indah dan bermakna.
***
*Arahmaiani adalah Perupa