Buruh dan Sintjhia: Cerpen Kho Ping Hoo Tentang Imlek
Oleh Jafar Suryomenggolo
Sekedar pengantar: Terbit pertama kali di mingguan Star Weekly no. 684 (7 Februari 1959), hlm. 11-13, cerpen “Buruh dan Sintjhia” adalah salah satu cerpen awal karya Kho Ping Hoo許平和 atau Asmaraman Sukowati (1926-1994), yang kini lebih kita kenal sebagai penulis cerita silat. Cerpen pertamanya terbit pada 1958, saat ia berusia 32 tahun – sebuah usia yang relatif sudah cukup matang. Seperti yang dicatat Myra Sidharta (1994)), ia mulai menulis cerita silat, yang pertama terbit pada 1960, semata-mata menggantikan penulis awal yang sibuk.
Di dalam cerpen ini, Kho mengangkat kisah penghidupan keluarga orang biasa, yang bekerja sebagai ‘buruh ketjil’ menjelang Sintjhia 新正, Tahun Baru Imlek. Berbeda dari kesan mewah ala crazy rich yang kerap mencari sensasi medsos kita, kehidupan orang biasa ini digambarkan secara riil dan sederhana dalam menghadapi inflasi keuangan masa 1950-an, situasi yang mirip dengan apa yang kita hadapi sekarang ini dalam deraan pandemi global. Bagi banyak orang, terutama mereka yang kondisi ekonominya sudah terhimpit, Tahun Baru sulit disambut dengan perayaan. Kesulitan ekonomi memaksa orang untuk memberi arti baru atas perayaan Tahun Baru.
Di dalam cerpen ini, satu-dua kosakata Hokkien meluncur bebas begitu saja sebab diandaikan para pembaca sudah paham. Ini pertanda bahwa kosakata tersebut sudah lazim dipergunakan sebagai peninggalan sastra Melayu Tionghoa di awal abad ke-20. Jadi, bisa dipastikan bahwa pembaca cerpen ini adalah orang Tionghoa peranakan yang hidup di kota. Boleh jadi juga, mereka merasakan apa yang dialami tokoh utama cerpen ini. Meski kisah cerpen ini terkesan getir, Kho menulis dengan sangat mengesankan. Kiranya pembaca masa kini, sekitar 60 tahun setelah cerpen ini terbit, bisa menikmatinya dengan seksama sambil memahami bagaimana Tahun Baru Imlek disambut, dirayakan dan ditafsir-ulang oleh masyarakat Tionghoa peranakan sepanjang zaman.
Cerpen ini diterbitkan ulang semata-mata sebagai apresiasi sastra yang selama ini terkubur. Hak cipta pengarang tetap ada pada Kho Ping Hoo. Ejaan Suwandi tetap dipertahankan apa adanya.
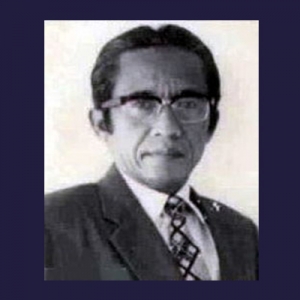
Foto Kho Ping Hoo
—–
SETELAH mandi, aku duduk melamun di ruang depan memandang air hudjan jang bertjutjuran dari genting rumahku. Air kamar mandi jang dingin telah menjegarkan tubuhku dan mengusir pergi kelelahan duduk sehari penuh di kantor.
Tapi pikiranku tak sesegar tubuku. Hatiku mangkal. Seingatku, tiap habis tahun dan Tahun Baru Imlek mendjelang tiba, di dalam beberapa tahun ini, pasti datang padaku perasaan jang serba tak menentu ini. Bingung, mangkal, dan chawatir.
Dulu aku tidak begini. Ketika aku masih ketjil, aku selalu menjambut kedatangan Tahun Baru dengan tak sabar dan penuh kegembiraan, seperti halnja dengan anak-anakku sekarang. Sedjak beberapa hari jang lalu, belum pernah sehari terlewat tanpa kumendengar mereka menjebut-njebut Tahun Baru, seakan-akan mereka hendak memperingatkan aku bahwa Tahun Baru akan datang dan pasti datang dan agar aku djangan sampai melupakan hal ini.
Dan sebutan Tahun Baru itu selalu mendatangkan bajang-bajang seram di bulu mataku. Pakaian baru, kue kerandjang, kue-kue lain, kirim uang orangtua, angpau¹, hadiah anak-anak. Dan semua bajang-bajang ketjil ini berlindung di bawah bajangan jang lebih seram lagi: bon utang baru kepada thauwke!² Satu-satunja djalan keluar. Tapi djalan keluar ini mendatangkan akibat jang tiada akan habisnja selama aku hidup agaknja, atau setidaknja selama aku masih mendjadi seperti sekarang: buruh ketjil. Akibatnja ialah bahwa hadiah tahunan jang akan kuterima di achir tahun nanti hanja akan ditukar dengan bon utang djalan keluar itu. Dan terpaksa membuat bon baru, tutup lobang gali lobang!
Hudjan makin menderas dan lamunanku makin melantur djauh. Maka berhentilah djalan pikiranku kepada sebuah peristiwa empat tahun jang lalu dan aku memusatkan seluruh pikiran untuk mengenangkannja kembali.
KETIKA itu anakku baru tiga orang. Gadjiku hanja besar angkanja saja, tapi nilainja tak mentjukupi kebutuhan sehari-hari. Buktinja, biarpun isteriku telah berhemat sedapat-dapatnja, tetap sadja tiap bulan di latji kasir bon utangku makin bertambah. Sebulan sehelai, setahun duabelas helai, dan selalu djumlahnja tjotjok dengan uang hadiah jang kudapat. Djadi, tjotjok, utang lunas, bon dirobek habis seperti kalender tahun lama. Dan seperti kalendar pula, datang bon-bon baru sesuai dengan datangnja tahun baru.
Ketika itu aku telah menerima hadiah tahun baru dari thauwkeku jang berupa robekan bon-bon utangku tahun jang lalu. Aku kumpulkan robekan bon-bon itu dan kubawa pulang. Isteriku tidak heran atau terharu melihat robekan kertas itu, lagu lama baginya. Hanja, seperti tahun-tahun jang lalu, wadjahnja jang manis mendjadi keruh, awan keketjewaan mengantjam kerukunan kami. Biasanja kalau sudah begitu, aku lalu mengeluarkan uang utangku jang baru, kuberikan kepadanja untuk membeli pakaian anak-anak dan pakaiannja sendiri, dan ia tak pernah lupa membelikan pakaian untukku, karena kesukaannja jang terbesar katanja memilihkan pakaian untukku. Memang ia seorang isteri jang baik dan mentjinta suami. Dan semua akan mendjadi beres dan lantjar.
Tapi pada waktu itu aku tidak mengeluarkan apa-apa, ketjuali kata-kata jang agak sukar keluar dari mulutku dan kuatur sebaik-baiknja:
“Mah, kurasa engkau akan senang djuga kalau kita dapat berbelandja untuk sintjhia memakai uang kita sendiri, bukan uang utang.”
Wadjahnja membajangkan keheranan, kemudian harapan baik. “Tentu sadja, pah.” Matanja memandangku dengan tadjam dan penuh pertanjaan hingga aku terpaksa melihat ke arah djempol kakiku.
“Maksudku begini, mah.” Aku berhenti untuk berdeham, menghilangkan sesuatu jang agaknja menggandjal di kerongkonganku. “Kita dapat mengatur agar pada tahun-tahun jang akan datang kita dapat menerima uang hadiahku dengan bersih, tidak perlu membajar utangku.”
“Bagaimana maksudmu? Aku tak mengerti,” djawabnja dan aku makin bingung, tak tahu bagaimana harus mengatur kata-kataku, tapi kemudian aku mengumpulkan semua ketabahanku dan berkata terus-terang.
“Salahnja keadaan kita ini ialah karena setiap datang sintjhia aku selalu utang kepada thauwke, sehingga uang hadir terpaksa tak dapat kuterima, untuk melunasi utang itu. Kalau sekarang aku tidak membuat utang baru, tentu lain tahun aku akan menerima hadiah bersih. Dan kita akan dapat bersintjhia dengan uang hadiah itu. Bukan senang, mah?”
Ia mengangguk mengerti, tapi kernjit di keningnja mendatangkan alamat buruk:
“Habis, untuk sintjia sekarang ini kita harus bagaimana? Pakaian anak-anak, kue kerandjang, antaran kue-kue untuk tetangga, kiriman uang untuk orangtuamu dan orangtuaku?”
Sungguhpun aku telah menjangka akan datangnja serangan ini, namun setelah serangan datang, aku mendjadi gugup djuga. Tapi karena sudah kuatur tadinja, aku dapat mendjawabnja:
“Kita ‘kan masih mempunjai pakaian tahun lalu jang agak baik? Biarlah kita pakai pakaian lama, pengurbanan ketjil ini kita lakukan untuk kesenangan tahun depan. Papah-mamah tentu akan dapat memaklumi pula asal kita dapat memberi alasan.”
“Kau maksudkan anak-anak dan aku harus pergi paytjia³ dengan pakaian usang? Dan tetangga-tetangga tak dikirimi kue? Ah, aku malu! Lebih baik aku tinggal di rumah. Tak mau menemui tamu jang datang, tak sudi pula pergi paytjia ke mana djuga.”
Untuk inipun aku sudah sedia djawaban: “Tidak paytjia pun tidak apa, mah. Jang terpenting kita harus pergi ke orangtua memberi hormat, tapi tamu-tamu bagaimana djuga harus disambut, biarpun hanja dengan hidangan teh dan pisang goreng.”
“Tidak sudi! Engkau akan membikin malu aku? Engkau tidak mau mentjari uang aku tak peduli. Memang engkau jang berkuasa. Engkau utang atau tidak masa bodoh. Tapi menjuruh aku paytjia dan menjambut tamu dengan pakaian usang, terima kasih! Biar ke rumah orangtua-pun aku tidak mau!”
Karena kehabisan akal, aku menggunakan siasatku terachir. Kuhibur-hibur hatinja dengan kata-kata manis dan kukatakan padanja bahwa aku mempunjai akal untuk membuat ia tak sampai malu kepada orang lain.
“Mah, kemarin aku berdjumpa dengan uwak Loan,” kataku lemah lembut. “Ia berkata bahwa ia mempunjai dagangan gelang dan leontine berlian dan ia minta supaja aku bantu
mendjualkan. Besok pagi ia akan datang pula mengantarkan barang-barang itu padaku. Kautahu, aku sering mendjualkan dagangannja, dan ia tinggal di kota jang 60 kilometer djauhnja dari sini.”
“He, pah, apa maksudmu?” mata isteriku memandangku dengan takut dan kaget, agaknja timbul persangkaan jang bukan-bukan di dalam benaknja.
“Bukan maksud buruk, mah. Sabarlah. Kurasa perhiasan itu kaupindjam sebenar, untuk sehari duahari. Mana lebih baik: memakai pakaian baru tanpa perhiasan, atau memakai pakaian jang agak lama tapi mengenakan perhiasan indah? Dengan begitu, engkau takkan kehilangan muka. Dan uwak Loan tinggal djauh dari sini. Jang punja barang tentu orang di kotanja. Tak seorang akan tahu.”
Lebih sepuluh menit isteriku tak berkata-kata. Achirnja ia mendukung anak kami jang terketjil memasuki kamar dan mengomel: “Engkau ini ada-ada sadja.”
Aku hampir berlompat-lompat kegirangan. Usahaku berhasil. Tahu benar aku, bahwa djika isteriku berkata “ada-ada sadja” maka itu berarti bahwa ia setudju, tidak berkeberatan. Ah, tahun ini aku akan terlepas dari gangguan setan utang!
KETIKA hari Sintjhia tiba, isteriku dengan tiga anak kami pergi paytjia. Pakaian jang dipakai mereka pakaian tahun lalu. Tapi siapakah jang dapat membedakan pakaian baru dan setengah baru? Karena bagiku, tiap kali berdjumpa dengan orang, belum pernah aku ingat untuk memperhatikan pakaiannja. Setelah orang jang kudjumpai pergi, maka lupalah aku sama sekali akan warna pakaiannja. Tapi mungkin tidak demikian dengan perempuan. Entahlah.
Aku tinggal di rumah menjambut kedatangan tamu-tamu muda jang datang berpaytjia. Karena isteriku sedang keluar, maka aku tidak sukar mentjari alasan akan kekurangan djamuan jang kukeluarkan.
Hatiku puas dan girang. Semua berdjalan lantjar dan beres menurut rentjana. Setelah tamu-tamu habis, aku duduk mengisap rokok dan berbaring di kursi malas dengan enak sambil membajangkan kesenangan tahun depan. Hadiah penuh, berbelandja dengan uang sendiri. Aduh, senangnja!
Sebuah betja jang berhenti di depan rumah mengusir lamunanku. Dua orang anak turun dari betja, disusul oleh isteriku jang mendukung anakku jang paling ketjil. Hatiku senang melihat
anak-anak berseri-seri sambil mengeluarkan bungkusan merah dari saku, membukanja dan menghitung-hitung uang kertas jang terbungkus di dalamnja. Mereka lupa akan pakaian mereka jang tidak baru agaknja, pikirku.
Tapi kesenanganku lenjap. Ketika melihat wadjah isteriku, pikiranku jang tadinja terang benderang tiba-tiba mendjadi gelap gulita, bagaikan aliran listrik terputus di waktu malam. Aku heran. Mata isteriku basah, wadjahnja kemerah-merahan, dan ketika ia memandangku, seakan-akan aku dipandang oleh seekor singa betina kelaparan jang hendak menerkamku.
“Ada apa, mah?” tanjaku kuatir.
Tiba-tiba, bagaikan mendung jang terlampau tebal dan tjair mendjadi air hudjan, kedua matanja bertjutjuran air mata, membandjir memenuhi kedua pipinja jang kemerah-merahan. Dan bagaikan kawah gunung Merapi jang telah terlampau lama dan panah mendidih, tiba-tiba marahnja jang agaknja telah ditahan-tahan dari tadi meledak keluar dari bibirnja.
“Engkau lelaki tak tahu malu. Membikin tjelaka aku. Sudah tidak bisa menjenangkan hati anak-isteri pada waktu Tahun Baru, bahkan membikin malu semau-maunja. Perhiasan orang disuruh pakai. Suami tak kenal kewadjiban! Orang tak tahu diri!”
Dengan djari tangan gemetar ditanggalkannja leontine jang masih bergantung dilehernja dan melepas gelang dari tangannja, lalu dilemparkan barang-barang itu ke hidungku. “Nih, barang-barangmu. Barang pindjaman membikin tjelaka!” Kemudian larilah ia memasuki kamar sambil menangis terisak-isak.
Aku berdiri dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Tak mengerti apakah jang harus kulakukan. Setelah agak reda terkedjutku, aku membungkuk memungut gelang dan leontine jang terdjatuh di depan kakiku, memasukkannja ke dalam saku tjelana dan menjusul isteriku dalam kamar dengan hati berdebar takut.
Ia sedang rebah miring memeluk bantal. Tubuhnja jang berguntjang-guntjang menjatakan padaku betapa keras dorongan tangis jang ditahan-tahannja.
“Mah,” aku memberanikan diri, “mengapa engkau menangis?”
“Pergilah engkau dengan barang-barang pindjamanmu!” dengusnja.
“Djangan begitu, mah. Kalau memang aku bersalah, djelaskanlah apa kesalahanku itu,” aku membudjuk.
Ia menangis terus. Kemudian dengan suara terputus-putus, keluar djuga keterangan dari bibirnja, di sela tjatjian dan teguran kepadaku jang dianggapnja “laki-laki tak punja malu,” “suami lupa kewadjiban,” dan lain-lain makian sopan lagi. Memang isteriku paling anti memaki kotor, karena kalau orangtua suka memaki, anak-anakpun akan beladjar memaki, katanja.
TERNJATA bahwa ketika ia sedang pergi paytjia berputar di rumah-rumah keluarga dan kenalan – tentu merasa bangga dengan perhiasan itu, pikirku – ia berdjumpa dengan seorang perempuan di rumah kawannja. Ia tak kenal perempuan itu, tapi ketika melihat perhiasan jang dipakainja, perempuan itu bertanja: “Wah, djadi adikkah jang membeli perhiasanku? Mengapa ntjim Loan belum menjetorkan uang? Berapa adik membelinja?” Tentu sadja isteriku kaget setengah mati dan tak dapat mendjawab.
Ketika didesak, ia menjatakan bahwa suaminjalah jang membeli dan ia tidak tahu berapa harganja. Peristiwa itu disaksikan oleh banjak njonja lain, sehingga ia “hampir mati karena malu,” katanja.
“Tjoba kau pikir!” Ia mengachiri keterangannja jang tertjampur aduk dengan penjesalan dan kemarahan itu, “alangkah maluku. Dan tak lama lagi mereka pasti akan tahu semua bahwa barang itu hanja pindjaman! Dan akulah orang jang akan menderita malu, bukan engkau! Padahal semua ini adalah gara-gara akal-bulusmu jang kotor!” Kembali ia menangis.
“Ah, mengapa engkau pergi mengundjungi teman-teman, mah?” Suara setan agaknja itu, karena aku hampir tak kenal suaraku sendiri, kemudian dengan tak kusadari bibirku bergerak mengotjeh pula, “Engkau tahu bahwa perhiasan itu barang pindjaman, mengapa engkau bawa-bawa memamerkan kepada teman-temanmu?” Ah, mau aku memukul mulutku.
Dengan serentak isteriku bangun dari pembaringan, memandangku dengan mata seorang haki memandang pesakitan jang akan didjatuhi hukuman. “Memamerkan? Engkau masih dapat menjalahkan aku? Dasar orang rendah!” Baru sekali ini sedjak kami kawin, aku dihadiahi sebutan “rendah” oleh isteriku.
Kemudian ia berkemas, dan sambil membawa ketiga anak kami, ia pergi ke stasiun otobis, pulang ke rumah orangtuanja. Budjukan-budjukanku kasar-halus tak memasuki telinganja. Sepatahpun kata tak keluar dari mulutnja sedjak ia menjebutku “rendah” sampai ketika otobis membawanja pergi. Aku jang terpaksa mengikutinja ke stasiun otobis hanja dapat berdiri di situ memandang asap jang keluar dari knalpot otobis dan debu jang mengebul di belakangnja.
“Tjelaka tigabelas!” gerutuku sambil berdjalan pulang, lemas luar-dalam.
Tetapi ternjata bahwa sebenarnja isteriku telah merasa menjesal meninggalkan rumah dan sorenja telah pulang kembali. Baiknja pada waktu hari Sintjhia, kalau tidak, tentu akan menimbulkan dugaan jang bukan-bukan dari pihak mertuaku.
Meskipun demikian, namun soal gelang dan leontine itu masih tetap merupakan gandjalan. Maka setelah beberapa hari aku memutar otak, achirnja kuputuskan untuk membeli sadja perhiasan itu. Tapi dari mana aku dapat mengumpulkan uang untuk membelinja? Terpaksa aku mendjual mesin tik dan sepedaku. Biarlah, untuk kesenanganku mengarang dapat kugunakan pulpen dan untuk pergi ke kantor dapat kugunakan kedua kakiku. Tapi pendapatan uang pendjualan kedua barang itu, jang kulakukan dengan diam-diam, masih belum tjukup untuk membeli perhiasan itu. Terpaksa akan membuat bon utang.
Tentu sadja isteriku merasa girang bahwa perhiasan itu telah kubeli, sehingga dapat dipakainja dengan leluasa, tanpa chawatir diketahui orang bahwa perhiasan itu barang pindjaman belaka. Tapi ketika mengetahui bahwa mesin tik dan sepedaku tidak ada, ia merasa terharu. Agaknja ia tak mau kalah menundjukkan kebaikan hatinja daripadaku. Segera ia minta padaku supaja perhiasan itu didjual lagi. Dan tentu sadja didjual dengan rugi. Dan ketika uang itu kupakai membeli mesin tik dan sepeda, ternjata masih kurang sedikit. Terpaksa pindjam lagi dari thauwkeku. Dalam hal memberi pindjaman uang kepadaku, thauwkeku memang istimewa. Selalu diberi. Tapi kalau meminta naik gadji, djangan harap!
NAH, demikianlah peristiwa empat tahun jang lalu jang memenuhi lamunanku pada sore hari hudjan deras itu.
Aku menghela napas. Tahun Baru kurang sebulan lagi. Utangku tahun ini agaknja lebih besar daripada hadiah jang akan kuterima. Dan besok terpaksa aku membajar utang itu dengan seluruh hadiah jang kudapat untuk diganti dengan utang baru. Tidak ada lain djalan. Tiap tahun, semendjak peristiwa itu terdjadi, selalu begini. Tutup lobang gali lobang. Aku tidak berani mentjoba lain akal lagi semendjak akal jang dulu itu hampir-hampir mentjelakakan rumah-tanggaku.
Biarlah, besok akan kubuat bon baru. Tidak apa, memang aku seorang buruh.
Tapi akan beginikah selamanja? Mudah-mudahan tidak. Kalau terus menerus begini, sedangkan anak-anakku jang makin banjak ini makin lama makin besar dan membutuhkan pengeluaran uang lebih banjak, maka akan tjelaka tigabelas benar-benar aku….
_________________
¹Hokkien (紅包) : amplop merah.
²Hokkien (頭家): bos/ majikan.
³Hokkien (拜正): salam hormat silahturami saat Tahun Baru.
*Penulis adalah anggota Centre Asie du Sud-Est (CASE), Paris dan Peneliti Tamu Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS), Jeonbuk National University, Korea Selatan.












