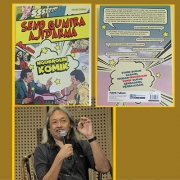Syair Braen: Dari Doa Ritual menuju Etika Sosial dan Tasawuf Komunal
Oleh Abdul Wachid B.S.*
Syair Braen: Doa, Perempuan, dan Ingatan Kolektif Jawa-Islam
Syair Braen tidak dapat dipahami hanya sebagai teks atau pertunjukan. Ia adalah ingatan yang dilagukan. Ia hidup dalam tubuh orang-orang desa, dalam suara perempuan, dan dalam situasi-situasi genting ketika hidup berhadapan langsung dengan batasnya: kematian, sakit, kehilangan, dan harapan yang digantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di wilayah Cahyana, yang kini kita kenal sebagai Rajawana, Purbalingga, Jawa Tengah, Braen hadir bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai cara hidup religius yang diwariskan secara turun-temurun.
Dalam penelusuran sejarah lisan dan praktik ritualnya, Braen diyakini berakar pada tradisi doa yang dipimpin oleh perempuan keturunan Syekh Makhdum Husen. Sosok Rubiyah (gelar bagi pemimpin ritual Braen) menempati posisi yang tidak lazim dalam tradisi keagamaan arus utama: perempuan menjadi pusat doa, pengatur ritme spiritual, sekaligus penjaga keberlanjutan nilai. Fakta ini pernah saya catat sebagai fenomena kultural yang khas Islam Nusantara, di mana otoritas spiritual tidak selalu dibangun melalui struktur formal, melainkan melalui kepercayaan komunitas dan ketekunan laku ritual (Abdul Wachid B.S., et.al., 2024. “Peran Perempuan melalui Kesenian Braen.” Jurnal Mabasan: Masyarakat Bahasa & Sastra Nusantara, Vol. 18, No. 1, hlm. 87–126).
Penting ditegaskan sejak awal bahwa kutipan-kutipan Syair Braen yang menjadi objek kajian esai ini tidak semata bersumber dari ingatan lisan, melainkan dari sebuah naskah yang disusun oleh Tim Keluarga Rubiyah di Rajawana, Purbalingga, Jawa Tengah, tertanggal 26 Mei 1979. Naskah ini menunjukkan bahwa tradisi doa tersebut tidak hanya diwariskan melalui hafalan dan praktik, tetapi juga pernah dibukukan sebagai upaya sadar untuk menjaga kesinambungan spiritual komunitas. Di tangan perempuan-perempuan Rubiyah, syair tidak sekadar dilantunkan, melainkan dirawat sebagai pusaka ruhani: sebuah arsip hidup yang terus berfungsi dalam ritus dan laku sosial sehari-hari.
Braen dengan demikian bukan sekadar “seni doa”, melainkan ruang bersama tempat komunitas belajar merasakan Tuhan secara kolektif. Doa dilantunkan, bukan dibaca. Kata-kata tidak diarahkan ke atas semata, tetapi berputar di antara sesama: yang hadir, yang pergi, yang sakit, yang tertinggal. Dalam setiap lantunan, selalu ada kesadaran bahwa keselamatan seseorang tidak dapat dilepaskan dari keselamatan orang lain. Inilah sebabnya mengapa Braen lazim hadir dalam ritual kematian, ruwatan, dan permohonan hidup; ia bekerja di wilayah paling rapuh dari eksistensi manusia.
Dari sudut pandang kultural, Braen memperlihatkan bagaimana Islam diterjemahkan ke dalam bahasa rasa Jawa. Unsur doa, sholawat, dan pengakuan tauhid berpadu dengan imaji tubuh, laut, perahu, lapar, telanjang, dan cahaya. Islam di sini tidak hadir sebagai doktrin yang kaku, melainkan sebagai laku batin yang membumi. Sebagaimana saya kemukakan dalam artikel tersebut, Braen menjadi medium akulturasi yang tidak menghapus budaya lokal, tetapi mengolahnya menjadi jalan spiritual yang dapat dipahami dan dijalani bersama.
Karena itu, membaca Syair Braen semata-mata sebagai teks ritual akan mereduksi kedalaman maknanya. Di dalamnya tersimpan tasawuf komunal; tasawuf yang tidak menyendiri, tidak elitis, dan tidak terpisah dari etika sosial. Doa selalu berujung pada kepedulian: memberi makan yang lapar, memberi air yang haus, memberi perlindungan bagi yang rapuh. Spiritualitas tidak berhenti pada wirid, tetapi menjelma menjadi tanggung jawab sosial.
Prolog ini hendak menegaskan satu hal penting: Syair Braen adalah cara masyarakat Jawa-Islam merawat hubungan dengan Tuhan sekaligus dengan sesama. Ia adalah doa yang bergerak, tasawuf yang berwajah sosial, dan ingatan kolektif yang terus dijaga melalui suara perempuan. Dari titik inilah esai ini melangkah; membaca Syair Braen sebagai perjalanan dari doa ritual menuju etika sosial dan tasawuf komunal.
1. Syair sebagai Kesadaran Jiwa yang Bergerak Menuju Tuhan
Leng-leng wangun jiwa-jiwane nut maring maring ati
Allah lir ing birahi ing pangeran ya ilalah hu ilallah.
(Syair Braen, Baris 23 / Hal. 2)
Syair Braen tidak pernah memulai dari suara yang riuh. Ia justru berangkat dari keadaan “leng-leng”, hening, jernih, dan terjaga. Kata ini bukan sekadar penanda suasana, melainkan kondisi batin yang disengaja. Jiwa dibangunkan dari kelengahan, lalu diarahkan “nut maring maring ati”, bergerak perlahan menuju pusat rasa. Dalam tradisi Jawa, ati bukan hanya organ perasaan, melainkan ruang terdalam tempat kesadaran dan kehendak bertemu.
Pada titik inilah Braen menempatkan doa bukan sebagai rangkaian permintaan verbal, tetapi sebagai peristiwa batin. Jiwa tidak serta-merta meminta, melainkan terlebih dahulu disiapkan. Hening menjadi pintu masuk. Kesadaran didudukkan. Baru setelah itu nama Tuhan dilafalkan, bukan sebagai sebutan formal, melainkan sebagai daya tarik paling dalam dari keberadaan manusia.
Ungkapan “Allah lir ing birahi” sering disalahpahami jika dibaca secara literal atau moralistik. Dalam konteks Syair Braen, birahi tidak menunjuk pada hasrat jasmani, melainkan kerinduan ontologis: dorongan terdalam manusia untuk kembali kepada asalnya. Tuhan hadir sebagai yang dirindukan, bukan yang ditakuti. Ia menjadi pusat magnet batin, tempat jiwa bergerak tanpa paksaan.
Di sinilah terasa jelas bahwa tasawuf dalam Braen tidak disampaikan melalui istilah teknis atau konsep abstrak. Ia hadir melalui bahasa rasa yang akrab dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Kerinduan kepada Tuhan diterjemahkan dengan kosa kata yang hidup di tubuh dan perasaan. Justru karena itulah syair ini mampu bekerja secara kolektif: setiap orang dapat merasakannya, meski tanpa pendidikan tasawuf formal.
Pembacaan semacam ini memperlihatkan bahwa doa dalam Braen bukan tindakan satu arah. Ia adalah dialog batin, bahkan lebih tepat disebut sebagai penyerahan diri yang sadar. Jiwa bergerak, bukan didorong. Tuhan dihadirkan, bukan dipanggil dari kejauhan. Dalam konteks ini, Braen menegaskan bahwa spiritualitas tidak selalu dimulai dari permintaan, melainkan dari kesiapan jiwa untuk mendekat.
Tesis awal esai ini bertumpu pada pemahaman tersebut: Syair Braen menempatkan doa sebagai peristiwa kesadaran jiwa. Ia adalah latihan batin kolektif yang menata hubungan manusia dengan Tuhan sejak dari dalam, sebelum meluas ke relasi sosial dan etika hidup. Dari satu baris inilah, perjalanan makna Braen bermula: hening yang melahirkan gerak, dan gerak yang mengarah pada tanggung jawab spiritual yang lebih luas.
2. Syair Braen sebagai Tasawuf Simbolik Jawa–Islam
Syair Braen tidak memperkenalkan Tuhan melalui definisi teologis yang kaku, melainkan melalui bahasa kosmos yang hidup dalam imajinasi budaya Jawa. Pada titik ini, Braen bekerja sebagai tasawuf simbolik, sebuah laku pengenalan Tuhan yang ditempuh lewat citraan inderawi dan metafora alam, bukan melalui argumentasi rasional atau spekulasi filsafat.
Hal ini tampak jelas dalam syair berikut:
Wujudulah ilalahu ilalah iwujudulah tuwan ilalahu ilalah.
Wujude pangeran benang, amedun saking lautan tuwan ilalahu ilalah,
rupa ombo ilalahu ilalah, rupa rembu rupane Pangeran benang amedun saking lautan ilalah
(Syair Braen, Baris 92 / Hal. 4)
Tuhan (Pangeran) dihadirkan sebagai benang yang amedun saking lautan—turun dari samudra. Benang, dalam kosmologi simbolik Jawa, bukan sekadar benda, melainkan lambang penghubung, penyambung, dan penata keteraturan. Ia mengikat yang tercerai, menuntun yang tercerabut, sekaligus menjadi garis halus antara yang lahir dan yang batin. Ketika Tuhan dimetaforakan sebagai benang, Braen sesungguhnya sedang menegaskan kehadiran Ilahi yang menyusup, halus, namun menentukan seluruh tatanan hidup.
Lautan (segara, ombo) dalam syair ini bukan sekadar ruang fisik, melainkan citra ketakterhinggaan, asal mula, dan rahim kosmik. Dari lautan itulah benang Ilahi “turun”, menandai relasi antara Yang Maha Luas dan dunia yang terikat oleh ruang dan waktu. Sementara kata ombo dan rembu (luas, merata, menyebar) memperkuat gambaran Tuhan sebagai kehadiran yang meliputi, bukan yang berjarak.
Tasawuf dalam Syair Braen dengan demikian bukan tasawuf konseptual sebagaimana berkembang dalam wacana filsafat Islam klasik, melainkan tasawuf visual dan imajinal; tasawuf yang bekerja melalui penglihatan batin, perasaan, dan pengalaman simbolik. Tuhan tidak dijelaskan, tetapi dihadirkan. Tauhid tidak diajarkan, melainkan dihidupkan dalam citra.
Dalam kajian yang saya tulis bersama Aufannuha Ihsani dan Teguh Trianton, ditegaskan bahwa kesenian Braen merupakan perwujudan seni ritual yang tidak hanya berfungsi sebagai permohonan kepada Tuhan, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai-nilai keislaman melalui bahasa budaya lokal (Abdul Wachid B.S., Aufannuha Ihsani, Teguh Trianton, Perempuan Kesenian Braen di Purbalingga, Purwokerto: Penerbit Lembaga Kajian Nusantara Raya, 2023). Bahasa simbolik dalam syair-syair Braen menjadi jembatan antara ajaran tauhid dan kosmologi Jawa yang telah lama hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat.
Dengan cara ini, Braen memperlihatkan bahwa tauhid Nusantara tidak tumbuh dari abstraksi filsafat, melainkan dari penginderaan simbolik yang berakar pada pengalaman kultural. Tuhan dikenal melalui metafora yang bisa dibayangkan, dirasakan, dan dihayati bersama. Inilah tasawuf komunal: tasawuf yang tidak eksklusif bagi kaum sufi, tetapi hadir dalam laku budaya masyarakat.
Syair Braen, pada titik ini, bukan sekadar teks ritual, melainkan ruang perjumpaan antara Islam dan Jawa; tempat tauhid menemukan tubuh kulturalnya, dan budaya menemukan ruh transendennya.
3. Kepasrahan Total dan Penyerahan Diri
Syair Braen tidak berhenti pada pengenalan Tuhan melalui simbol kosmik, tetapi bergerak lebih jauh menuju laku batin penyerahan diri. Pada tahap ini, tasawuf tidak lagi berada di ranah pengenalan (ma‘rifah), melainkan memasuki wilayah kepasrahan eksistensial: penyerahan badan dan nyawa sebagai kesadaran terdalam manusia.
Syair berikut menjadi penanda kuat laku tersebut:
Kesah-kesah tuwan sae-sae angaturi badan nyawa ing pangeran,
lan badan kurungan ing pangeran
(Syair Braen, Baris 15 / Hal. 2)
Ungkapan angaturi badan nyawa (mempersembahkan badan dan nyawa) menunjukkan bahwa relasi manusia dengan Tuhan dalam Braen bukan relasi kontraktual (memohon lalu menunggu balasan), melainkan relasi totalitas diri. Yang dipersembahkan bukan sekadar doa, tetapi keberadaan itu sendiri. Tubuh dan nyawa tidak diposisikan sebagai milik mutlak manusia, melainkan sebagai titipan yang sewaktu-waktu harus dikembalikan kepada Sang Pemilik.
Frasa badan kurungan mengandung makna simbolik yang sangat dalam. Tubuh dipahami sebagai kurungan sementara, tempat ruh menjalani laku hidup sebelum kembali kepada asalnya. Pandangan ini berakar kuat dalam kosmologi Jawa sekaligus sejalan dengan tasawuf Islam, yang melihat dunia sebagai ‘alam al-majāz: ruang singgah, bukan tujuan akhir. Dengan demikian, Braen menanamkan kesadaran bahwa hidup di dunia bukan untuk dimiliki, melainkan dijalani dengan kesadaran akan kefanaan.
Namun, kepasrahan dalam Syair Braen tidak menjelma menjadi asketisme ekstrem atau penolakan terhadap dunia. Justru sebaliknya, ia mengajarkan apa yang dapat disebut sebagai zuhud aktif: hidup sepenuhnya di dunia, menjalankan peran sosial, tetapi tidak terikat secara batiniah pada kepemilikan dan ambisi. Tubuh tetap bekerja, tetapi ruh tetap bebas.
Pandangan ini selaras dengan temuan saya dalam kajian tentang Braen sebagai seni ritual dan media dakwah kultural. Dalam artikel tersebut ditegaskan bahwa Braen menginternalisasikan nilai keislaman tidak melalui doktrin normatif, melainkan melalui pengalaman spiritual yang hidup dan membumi di tengah masyarakat (Jurnal Mabasan, 2024). Kepasrahan dalam Braen bukan sikap individual yang sunyi, tetapi kesadaran kolektif yang dilantunkan bersama, dihayati bersama, dan diwariskan secara komunal.
Dengan demikian, Syair Braen mengajarkan bahwa penyerahan diri kepada Tuhan tidak harus diwujudkan dengan menjauh dari kehidupan sosial. Sebaliknya, kepasrahan sejati justru diuji dalam keterlibatan manusia di tengah dunia, saat badan tetap berada dalam “kurungan” sosial dan kultural, sementara ruh tetap terjaga orientasinya menuju Pangeran.
Di sinilah Braen memperlihatkan wajah tasawuf Nusantara yang khas: tasawuf yang tidak melarikan diri dari dunia, tetapi memurnikan cara berada di dalamnya.
4. Nabi sebagai Poros Cinta dan Permohonan Ampunan
Jika pada bagian sebelumnya Tuhan dihadirkan sebagai pusat penyerahan diri, maka pada bagian ini Syair Braen menempatkan Nabi Muhammad sebagai poros cinta, penghubung batin antara manusia dan Tuhan. Relasi ketuhanan dalam Braen tidak pernah bersifat langsung dan dingin; ia selalu melewati jalan mahabbah, cinta yang mengalir melalui figur Rasul.
Hal itu tampak jelas dalam lantunan syair berikut:
Yuna-ayuna yun Mohammad, Mohammad kekasihing Allah
tan la ila hailalah muhamad Rasulullah x2
neda sama pangapura x2 pangapura laila hailallah Muhammad rasulalah x2
neda jiad kaberkatan laila hailalah Muhammad Rasulallah
neda seger kewarasan, la ila hailalah Muhammad Rosulullah
(Syair Braen, Baris 57 / Hal. 3)
Penyebutan Nabi Muhammad sebagai kekasihing Allah menempatkan Rasul bukan semata figur historis atau pembawa syariat, melainkan subjek cinta kosmik. Dalam tradisi tasawuf, Nabi dipahami sebagai al-ḥabīb, yang dicintai Tuhan, sekaligus pintu kasih bagi umat. Braen dengan sangat halus menyerap pandangan ini ke dalam bahasa Jawa yang lembut, repetitif, dan merangkul rasa.
Doa-doa yang menyertai pujian kepada Nabi pun mencerminkan horison spiritual yang luas. Permohonan tidak dibatasi pada keselamatan akhirat, tetapi mencakup seluruh dimensi hidup: pangapura (ampunan), kaberkatan (keberkahan), hingga seger kewarasan (kesehatan dan kewarasan jasmani-rohani). Dengan demikian, Braen menampilkan Islam sebagai agama yang memeluk kehidupan secara utuh: ruh dan raga, dunia dan akhirat.
Pola ini menegaskan bahwa dakwah dalam Braen tidak dibangun melalui retorika ketakutan, ancaman dosa, atau hukuman ilahi. Sebaliknya, ia bergerak melalui cinta, pengharapan, dan kelembutan rasa. Nabi hadir sebagai figur yang mendekatkan, bukan menghakimi; mengayomi, bukan menakut-nakuti. Inilah dakwah berbasis mahabbah yang menjadi ciri kuat Islam Nusantara.
Dalam kajian saya tentang kesenian Braen, ditegaskan bahwa syair-syair yang dilantunkan oleh Rubiyah mengandung pesan-pesan Islam yang disampaikan secara persuasif dan afektif, sehingga mudah diterima oleh masyarakat lintas usia dan latar sosial (Jurnal Mabasan, 2024). Cinta kepada Nabi dalam Braen bukan sekadar ekspresi teologis, tetapi juga strategi kultural dakwah yang efektif: menggerakkan rasa sebelum pikiran.
Lebih jauh, pengulangan nama Nabi dalam ritme yang nyaris melagukan zikir menunjukkan bahwa Braen bekerja sebagai ruang latihan spiritual kolektif. Cinta kepada Rasul tidak diajarkan sebagai konsep, tetapi dilatih melalui suara, irama, dan kebersamaan. Dengan cara ini, umat tidak hanya mengetahui siapa Nabi Muhammad, tetapi merasakan kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari.
Di titik ini, Braen memperlihatkan wajah Islam yang ramah dan menghidupkan: Islam yang menjadikan Nabi sebagai pusat cinta, dan dari cinta itulah mengalir ampunan, berkah, dan kesehatan hidup. Sebuah dakwah yang tidak menekan dari atas, melainkan mengalir dari hati ke hati.
5. Hidup, Mati, dan Ketundukan pada Takdir Ilahi
Pada bagian ini, Syair Braen berbicara tentang wilayah yang paling sunyi sekaligus paling mendasar dalam kehidupan manusia: hidup dan mati. Namun, keduanya tidak dipertentangkan secara keras, apalagi ditampilkan sebagai kutub yang saling meniadakan. Dalam Braen, hidup dan mati justru diikat dalam satu tarikan kesadaran ilahi yang sama: tenang, pasrah, dan tidak hiruk-pikuk.
Hal itu terungkap dalam bait berikut:
Mala-mala ikat nusa pati lawan urip denemuta urip iki Allah x2
Mala-mala ekat sawit urip saya tulah den emuta urip iki Allah x2
(Syair Braen, Baris 63–64 / Hal. 3)
Ungkapan ikat nusa pati lawan urip menunjukkan bahwa hidup (urip) dan mati (pati) bukan dua peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan terikat dalam satu jaringan takdir. Keduanya berada dalam genggaman Tuhan—denemuta urip iki Allah. Bahasa yang digunakan sederhana, hampir lugu, tetapi justru di situlah kekuatan spiritualnya: kesadaran bahwa hidup bukan milik manusia sepenuhnya, dan kematian bukan peristiwa yang harus ditakuti secara berlebihan.
Yang menarik, Braen tidak pernah mendorong sikap pasrah yang lumpuh atau menyerah tanpa usaha. Kepasrahan yang diajarkan adalah kepasrahan yang menenangkan, bukan fatalisme yang mematikan daya hidup. Manusia tetap hidup, bekerja, dan berelasi, tetapi dengan kesadaran bahwa semua itu berada dalam lingkar kehendak Ilahi. Inilah teologi yang membebaskan batin dari kecemasan berlebih, tanpa mencabut tanggung jawab etis manusia.
Dalam konteks ritual kematian (fungsi awal kesenian Braen) syair ini bekerja sebagai penghibur kolektif. Ia menenangkan keluarga yang ditinggalkan, mengajarkan bahwa kematian bukan keterputusan total, melainkan peralihan yang telah disiapkan dalam takdir Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam buku saya (Perempuan Kesenian Braen di Purbalingga), Braen sejak awal berfungsi sebagai doa keselamatan dan sarana mendekatkan diri kepada Tuhan dalam peristiwa-peristiwa batas seperti kematian
Lebih jauh, kesadaran hidup–mati dalam Braen juga memiliki implikasi etis. Jika hidup dan mati berada dalam satu ikatan ilahi, maka hidup tidak boleh dijalani secara serampangan. Setiap tindakan manusia memiliki resonansi spiritual. Kesadaran ini membentuk etika sosial yang halus: hidup dengan hati-hati, menjaga relasi, dan tidak semena-mena terhadap sesama.
Dengan demikian, Braen menghadirkan pandangan hidup yang seimbang. Ia tidak menafikan penderitaan dan kehilangan, tetapi juga tidak larut dalam keputusasaan. Hidup dijalani dengan kesungguhan, mati diterima dengan ketundukan. Dalam ruang antara keduanya, manusia diajak untuk tenang karena: urip iki Allah. Sebuah ajaran sederhana, tetapi dalam, yang lahir dari kearifan spiritual Jawa-Islam dan tetap relevan di tengah kegelisahan manusia modern.
6. Doa Keselamatan Kolektif dan Etika Sosial
Jika pada bagian-bagian sebelumnya Braen menata relasi vertikal manusia dengan Tuhan, maka pada bagian ini Syair Braen bergerak lebih jauh: menurunkan doa ke dalam ruang sosial. Doa tidak berhenti sebagai komunikasi personal antara hamba dan Khaliknya, melainkan menjelma menjadi energi kolektif yang mengikat satu komunitas dalam kesadaran bersama.
Hal itu tampak jelas dalam bait berikut:
Masigit tuwan tinunda pitu kinalara serawa sare,
tiwatuntunaji kekirim donga slamet,
sing lunga pada slamet, sing keri wara-warasan,
adohna bilahine, perekna tuwan rejekine,
slameta salungguhe slameta salakune,
slameta tuwan ing pondokan,
slameta ing pagulingan,
anyadung mas mirah ngaspen sri sedana,
jinunjunga derajate maring kang darbe kawula.
(Syair Braen, Baris 85 / Hal. 4)
Syair ini memperlihatkan bagaimana keselamatan dipahami secara inklusif dan menyeluruh. Doa tidak hanya ditujukan kepada individu yang sedang memiliki hajat, tetapi mencakup “yang pergi” dan “yang tinggal”, keselamatan fisik dan batin, rezeki, tempat tinggal, bahkan martabat sosial: jinunjunga derajate maring kang darbe kawula. Dengan demikian, Braen tidak mengajarkan spiritualitas yang sempit dan egoistik, melainkan spiritualitas yang berwatak sosial.
Menariknya, keselamatan dalam Braen tidak dipahami sebagai kondisi pasif tanpa gangguan, melainkan sebagai keadaan hidup yang tertata: aman dalam perjalanan, tenteram dalam tinggal, cukup dalam rezeki, dan terjaga dalam kehormatan. Doa menjadi mekanisme kultural untuk merawat tatanan sosial agar tetap seimbang. Dalam hal ini, Braen bekerja sebagai etika sosial yang dinyanyikan, bukan diajarkan secara dogmatis.
Sebagaimana dicatat dalam penelitian saya, kesenian Braen berfungsi sebagai ritual kolektif yang mempertemukan seniman, penanggap, dan masyarakat dalam semangat kebersamaan dan tolong-menolong (Jurnal Mabasan, 2024). Syair tidak hanya dilantunkan, tetapi dihayati bersama, sehingga doa berubah menjadi pengalaman sosial yang hidup.
Dalam konteks ini, perempuan (melalui peran Rubiyah) menjadi penjaga dan penggerak etika sosial tersebut. Ia bukan sekadar pemimpin doa, melainkan figur yang memusatkan harapan kolektif komunitas. Doa yang ia lantunkan menata kembali relasi sosial yang mungkin retak oleh konflik, ketimpangan, atau kecemasan hidup sehari-hari.
Dengan demikian, Braen dapat dipahami sebagai ruang produksi solidaritas. Solidaritas tidak dibangun melalui wacana ideologis atau seruan moral, melainkan melalui pengalaman ritual yang berulang, akrab, dan menyentuh lapisan emosional masyarakat. Doa kolektif ini menegaskan bahwa keselamatan bukan milik satu orang, melainkan milik bersama. Dalam dunia yang semakin individualistik, etika sosial Braen justru menawarkan pelajaran penting: bahwa keberkahan hidup hanya mungkin tumbuh ketika didoakan dan diupayakan secara komunal.
7. Perjalanan Spiritual dan Etika Kemanusiaan
Pada bagian ini, Syair Braen mencapai puncak etikanya: perjalanan spiritual tidak berhenti pada ritual, melainkan berbuah pada tindakan kemanusiaan. Simbol Mekah, yang dalam tradisi Islam lazim dipahami sebagai pusat ibadah, ditafsirkan ulang secara kultural dan sufistik. Mekah tidak lagi semata-mata ruang geografis, melainkan ruang kesadaran moral.
Hal itu tergambar dalam bait berikut:
Nyong nenungsung-nungsung,
tuwan nyong nemungsung pituwan teka sing Mekah,
ora olih paran-paran, olih nyaur sejatine,
yasukur rulah rahmatulah olih ujar sejatine
(Syair Braen, Baris 118 / Hal. 5)
Ungkapan ora olih paran-paran, olih nyaur sejatine menunjukkan bahwa perjalanan ke Mekah tidak dimaknai sebagai pencapaian status atau kebanggaan simbolik. Yang diperoleh bukan “paran-paran” (kedudukan atau prestise), melainkan ujaran sejati: kesadaran etis tentang makna menjadi manusia. Di sini, Braen menempatkan haji bukan sebagai puncak ritual formal, tetapi sebagai proses penyucian makna hidup.
Kesadaran itu kemudian diuji dan diwujudkan dalam tindakan sosial yang sangat konkret, sebagaimana dituturkan dalam lanjutan syair:
aweh pangan wong keluwen,
aweh banyu wong kasatan,
aweh sandang wong kewudan,
aweh aling-aling wong kepanasan,
aweh tudung wong kodane,
aweh teken wong kelunyon,
aweh obor wong kepetengen
(Syair Braen, Baris 118 lanjutan / Hal. 5)
Daftar tindakan ini membentuk semacam etika kemanusiaan elementer: memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi perlindungan, memberi penerang. Tidak ada istilah teologis yang rumit; yang ada adalah bahasa kebutuhan dasar manusia. Inilah titik temu antara tasawuf dan kemanusiaan: spiritualitas diuji bukan pada seberapa tinggi seseorang berbicara tentang Tuhan, tetapi pada seberapa nyata ia hadir bagi sesama.
Dalam kerangka ini, Braen memperlihatkan apa yang dapat disebut sebagai haji sosial. Kesalehan tidak diukur dari jarak tempuh menuju tanah suci, melainkan dari jarak kepedulian terhadap penderitaan manusia. Tafsir semacam ini sejalan dengan pandangan tasawuf Nusantara yang menekankan keseimbangan antara hablun minallah dan hablun minannas, suatu ciri yang berulang kali muncul dalam tradisi Islam Jawa (Abdul Wachid B.S., Sastra Pencerahan, 2020).
Lebih jauh, tafsir kultural ini menunjukkan bahwa Braen tidak memisahkan ibadah dari realitas sosial. Justru, realitas sosial menjadi medan aktualisasi ibadah itu sendiri. Dengan demikian, Syair Braen tidak hanya memproduksi kesadaran religius, tetapi juga mendidik kepekaan etis masyarakat. Kesalehan yang diajarkan bukan kesalehan simbolik, melainkan kesalehan yang bekerja, yang memberi, melindungi, dan menerangi.
Pada titik ini, Syair Braen memperlihatkan relevansinya yang sangat kuat dengan dunia kontemporer. Di tengah kecenderungan spiritualitas yang sering terjebak pada ritualisme dan simbol identitas, Braen menawarkan pengingat yang jernih: bahwa perjalanan menuju Tuhan selalu melewati sesama manusia.
8. Syair sebagai Jalan Hidup
Pada akhirnya, Syair Braen tidak dapat diperlakukan semata sebagai artefak budaya yang dibekukan dalam katalog warisan. Ia adalah praktik hidup: doa yang dilantunkan, kesadaran yang diwariskan, dan etika yang terus diperbarui melalui perjumpaan sosial. Braen hidup justru karena ia terus dipraktikkan, didaraskan, dan dialami sebagai bagian dari ritme kehidupan masyarakat Rajawana dan wilayah sekitarnya.
Sebagai doa, Braen tidak berhenti pada permohonan verbal. Sejak bait-bait awalnya, ia telah menempatkan doa sebagai peristiwa kesadaran jiwa: gerak batin yang “leng-leng” menuju pusat Ilahi. Sebagai tasawuf, Braen tidak mengajarkan pengasingan diri dari dunia, melainkan penjernihan makna hidup di tengah dunia. Tauhid tidak hadir sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai pengalaman simbolik yang dekat dengan kosmologi lokal: benang, lautan, perjalanan, dan tubuh manusia itu sendiri. Inilah yang menandai watak tasawuf Nusantara: bersifat imajinal, membumi, dan komunikatif.
Lebih dari itu, Braen menjelma sebagai tasawuf komunal. Doa tidak diucapkan sendirian; keselamatan tidak dimohonkan untuk diri sendiri. Yang pergi dan yang tinggal, yang hidup dan yang wafat, semua dirangkul dalam satu tarikan doa. Dalam praktik semacam ini, spiritualitas tidak melahirkan jarak, tetapi justru memperkuat ikatan sosial. Braen menjadi ruang produksi kebersamaan, solidaritas, dan empati; nilai-nilai yang kian langka dalam kehidupan modern yang cenderung individualistik.
Puncak dari semua itu adalah etika sosial yang lahir dari pengalaman spiritual. Perjalanan ke Mekah ditafsirkan sebagai perjalanan kesadaran; ibadah diwujudkan dalam tindakan memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi penerang bagi yang gelap. Di sini, Syair Braen menegaskan bahwa kesalehan sejati selalu bersifat relasional: ia hadir dalam cara manusia memperlakukan sesamanya. Tafsir semacam ini menunjukkan bahwa tradisi lokal tidak berada di pinggiran Islam, melainkan justru menyumbang pembacaan etis yang sangat esensial.
Karena itu, selama Syair Braen terus dilantunkan, dalam ritual kematian, doa keselamatan, atau syukuran hidup, ia akan tetap menjadi jalan pulang: jalan pulang manusia kepada Tuhan, sekaligus jalan pulang manusia kepada kemanusiaannya sendiri. Dalam pengertian inilah Braen tidak pernah usang. Ia bergerak bersama zaman, tanpa kehilangan ruhnya; bertahan bukan karena dilestarikan secara formal, melainkan karena dibutuhkan secara batin. ***
—–
Daftar Pustaka
Suharto, Abdul Wachid Bambang, Aufannuha Ihsani, dan Teguh Trianton. 2024. “Peran Perempuan melalui Kesenian Braen.” Jurnal Mabasan: Masyarakat Bahasa & Sastra Nusantara, Vol. 18, No. 1, hlm. 87–126. p-ISSN: 2085-9554; e-ISSN: 2621-2005.
Wachid B.S., Abdul, Aufannuha Ihsani, Teguh Trianton. 2023. Perempuan Kesenian Braen di Purbalingga, Purwokerto: Penerbit Lembaga Kajian Nusantara Raya, ISBN 978-623-09-6631-6.
Wachid B.S., Abdul. 2020. Sastra Pencerahan. Yogyakarta: Penerbit Basabasi.
—–
*Penulis adalah penyair dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.