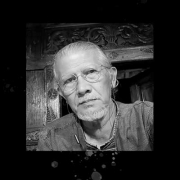Sistem Desentralisasi sebagai Product-Market Fit yang Belum Sesuai untuk Indonesia

Oleh Kelvin William
Judul: MENCARI INDONESIA Jilid 5: Ketimpangan, Ketidakadilan, & Masyarakat Pinggiran
Penulis: Riwanto Tirtosudarmo
Penerbit: Media Nusa Creative Publishing, Malang
Cetakan: I, 2025
Tebal: x–xxiv + 390 halaman
Dalam dunia entrepeneuership, istilah product-market fit merujuk pada kondisi ketika sebuah produk benar-benar menemukan pasarnya, yakni dibutuhkan, digunakan, dan diapresiasi oleh penggunanya. Konsep ini sesungguhnya tidak hanya relevan bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi negara. Sistem politik, hukum, dan birokrasi dapat dipandang sebagai “produk” yang ditawarkan negara kepada rakyatnya. Sementara itu, rakyat berperan sebagai pasar yang setiap hari merasakan dan menilai apakah sistem tersebut layak digunakan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Indonesia sebagai sebuah negara sudah mencapai product-market fit dengan rakyatnya? Apakah sistem yang berjalan hari ini benar-benar mampu menjawab aspirasi, kebutuhan, dan ekspektasi masyarakat?
Jika kita menoleh ke belakang, jawaban atas pertanyaan itu tidaklah sederhana. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia membangun sistem pemerintahan dengan fondasi sentralistis. Federalisme yang sempat ditawarkan justru ditolak mentah-mentah karena dianggap sebagai “akal-akalan Belanda” untuk memecah belah Indonesia. Maka yang dipilih adalah sentralisme, dengan Jakarta sebagai pusat segala keputusan, sementara daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan. Sistem ini memang menjaga kesatuan secara formal, tetapi sejak awal juga menyisakan jurang antara aspirasi lokal dan kepentingan pusat.
Desentralisasi, Produk Lama dalam Kemasan Baru
Reformasi 1999 menjadi momentum besar yang mengguncang sistem tersebut. Presiden B.J. Habibie (1936-2019, menjabat 1998-1999) memperkenalkan kebijakan desentralisasi dengan tujuan mendistribusikan kekuasaan agar lebih dekat kepada masyarakat. Harapannya, daerah tidak lagi menjadi sekadar pelaksana keputusan pusat, melainkan memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.
Namun pelaksanaan desentralisasi ternyata tidak sepenuhnya melepaskan diri dari pola lama. Kebijakan otonomi daerah pasca-reformasi lebih menekankan wewenang pada kabupaten dan kota, sementara provinsi justru ditempatkan hanya sebagai koordinator. Keputusan ini lahir dari kompromi politik yang cukup kompleks. Di satu sisi, pemerintah berusaha merespons tuntutan reformasi untuk mengakhiri dominasi sentralistik orde baru. Di sisi lain, kekhawatiran terhadap stigma federalisme, potensi ancaman disintegrasi, serta posisi militer yang masih kuat membuat otoritas pusat tetap mempertahankan kendali utama.
Sebagai konsekuensi, jumlah kabupaten dan kota yang begitu banyak membuat koordinasi antar wilayah menjadi rumi hingga melahirkan fragmentasi kebijakan yang sulit disatukan. Alih-alih menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, desentralisasi justru membuka ruang baru bagi penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi yang dahulu terpusat di lingkaran elit nasional kini merambat hingga ke daerah, memberi kesempatan bagi para bupati dan wali kota untuk memanipulasi otonomi demi kepentingan pribadi. Sentralisme pun tidak benar-benar hilang, hanya berganti rupa melalui figur-figur baru di kursi pemerintahan. Pada akhirnya, sistem ini lebih menyerupai produk lama dengan kemasan baru, desentralisasi tidak melahirkan sistem yang lebih dekat dengan rakyat, melainkan justru mempertahankan pola lama dalam bentuk yang berbeda.
Minahasa dan Tradisi Egaliter yang Terpinggirkan
Kegagalan menemukan product-market fit ini tampak jelas ketika negara berhadapan dengan daerah-daerah yang memiliki karakter sosial-budaya khas, berbeda dengan arus utama politik Indonesia. Minahasa di Sulawesi Utara bisa menjadi contoh pertama. Sejak lama, masyarakat Minahasa hidup dengan tradisi egaliter dan demokratis. Hubungan sosial yang terjalin cenderung setara, keputusan penting diambil melalui musyawarah, dan keterbukaan dianggap sebagai nilai penting dalam kehidupan bersama. Pengaruh pendidikan Barat dan agama Kristen yang masuk sejak abad ke-19 semakin memperkuat pola pikir yang modern serta partisipatif.
Melalui konteks semacam itu, birokrasi Indonesia–terutama di masa orde baru–yang mekanistis, hierarkis, dan paternalistik, jelas terasa janggal. Struktur atasan-bawahan yang kaku, dimana keputusan hanya mengalir dari otoritas pusat ke lapisan bawah tanpa ruang untuk berdialog, bertolak belakang dengan budaya lokal yang hidup dari musyawarah dan rasa kesetaraan antar pemimpin maupun masyarakat. Pola ini jelas tidak sesuai dengan kultur egaliter Minahasa.
Akibatnya yang lahir bukanlah integrasi, melainkan keterasingan antara birokrasi dan masyarakat. Aspirasi rakyat Minahasa seringkali tidak tersampaikan karena gaya pemerintahan pusat berjalan di atas logika yang sama sekali berbeda dengan nilai-nilai lokal. Negara, dengan demikian, gagal menyesuaikan “produk”-nya dengan karakter “pasar” Minahasa. Maka, tidak mengherankan jika kemudian muncul perlawanan terbuka yang berakar pada ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan pusat.
Kondisi keterasingan inilah yang kemudian menemukan momentumnya dalam peristiwa Permesta (Perdjuangan Rakjat Semesta, 1957-1958). Gerakan ini lahir dari ketidakpuasan yang semakin menumpuk terhadap pemerintahan pusat, terutama terkait monopoli ekspor kopra yang kala itu menjadi komoditas utama rakyat Sulawesi Utara. Permesta sering dilabeli sekadar “pemberontakan daerah”. Namun, bagi masyarakat Minahasa, ia merupakan simbol perjuangan melawan ketidakadilan yang dipaksakan dari pemerintahan pusat. Permesta adalah penegasan bahwa ketika aspirasi lokal diabaikan, daerah akan mencari jalannya sendiri.
Warisan historis ini memperlihatkan bahwa kegagalan negara menyesuaikan diri dengan karakter egaliter Minahasa melahirkan konsekuensi serius. Tradisi musyawarah, rasa kesetaraan, dan keterbukaan yang menjadi fondasi sosial masyarakat tidak pernah benar-benar masuk ke dalam logika pemerintahan pusat yang sentralistis. Akibatnya, jarak antara negara dan masyarakat justru melebar, dan Minahasa merespons dengan mengartikulasikan bentuk perlawanan yang sesuai dengan nilai-nilainya sendiri.
Namun, di balik itu semua terdapat risiko sosial-politik yang patut dicermati. Jika nilai-nilai tradisi egaliter Minahasa mampu digali dan diakomodasi dalam kebijakan nasional, ia bisa menjadi kekuatan progresif untuk meningkatkan partisipasi publik serta kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, keterbukaan, dan kesetaraan antar pemimpin dapat dijadikan fondasi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Akan tetapi, bila nilai-nilai ini terus diabaikan atau bahkan ditekan, kondisi yang semula konstruktif dapat berubah menjadi kedaerahan sempit yang justru berbenturan dengan semangat kesatuan nasional. Dengan kata lain, Minahasa adalah daerah dengan potensi besar untuk memberi kontribusi positif bagi pembangunan demokrasi Indonesia, tetapi juga berisiko tinggi bila terus merasa terpinggirkan.
Sistem sentralistis orde baru terbukti gagal membaca karakter egaliter masyarakat Minahasa. Aspirasi rakyat yang menekankan partisipasi, kesetaraan, dan dialog tidak sesuai dengan gaya pemerintahan pusat yang kaku dan hierarkis, sehingga menciptakan keterasingan dan mendorong lahirnya perlawanan terbuka seperti Permesta. Kondisi ini menunjukkan bagaimana ketidaksesuaian antara “produk” negara dan “pasar” lokal dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi integrasi sosial-politik. Namun, mismatch (ketidak-cocokan) antara “produk” negara dan “pasar” lokal tidak hanya terjadi di Minahasa. Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat menawarkan gambaran yang sama pentingnya, meski dengan konteks berbeda.
Lombok Barat dan Ilusi Keseragaman Pembangunan
Berbeda dengan Minahasa yang egaliter dan demokratis, masyarakat Lombok Barat hidup dalam basis agraris yang ditandai dengan struktur sosial lebih hierarkis dan religius. Tingkat kemiskinan di Lombok Barat relatif lebih tinggi dibanding wilayah Indonesia bagian barat, sementara infrastruktur dan sumber daya ekonomi juga terbatas. Dalam kondisi demikian, pembangunan seharusnya mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan lokal. Sayangnya, pemerintah pusat kerap menyusun kebijakan pembangunan secara seragam, seolah semua daerah memiliki latar sosial, ekonomi, dan budaya yang sama.
Analogi yang kerap muncul seperti hubungan guru dan murid. Semua dipaksa mengikuti kurikulum yang sama, meskipun kemampuan dan latar belakang setiap murid berbeda. Demikian pula Lombok Barat, dipaksa mengikuti resep pembangunan yang disusun dengan standar Jawa atau Sumatera, padahal kapasitasnya jauh berbeda. Akibatnya, banyak program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan justru tidak efektif karena tidak menyentuh realitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Aspirasi lokal sering terabaikan dan pembangunan yang seragam malah menimbulkan rasa ketidakadilan.
Konsekuensinya, penerapan pembangunan yang seragam bukan hanya gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi bumerang. Ketika kebutuhan, kondisi, dan aspirasi lokal diabaikan, masyarakat merasa kebijakan yang diterapkan tidak relevan atau bahkan merugikan mereka. Kekecewaan ini memicu frustasi, rasa ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi, kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas sehari-hari menciptakan jurang sosial yang rawan merusak integrasi. Alih-alih memperkuat persatuan, sentralisme justru menghasilkan ketidakpuasan yang berulang, memperbesar potensi konflik lokal, dan membahayakan stabilitas sosial-politik jangka panjang.
Hal ini kemudian memunculkan kritik tajam atas pola pembangunan yang berlangsung di Lombok Barat, yakni sentralisme yang memaksakan keseragaman kebijakan seolah semua daerah setara dalam kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Padahal, apa yang tampak seragam di permukaan tidak serta-merta mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan prioritas yang berbeda; keseragaman yang dipaksakan justru menimbulkan ketidakadilan baru, karena kebijakan tidak menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Dengan kata lain, negara gagal mencapai product–market fit karena menutup mata terhadap keragaman “pasar” yang dimilikinya sendiri.
Papua, Identitas yang Terpinggirkan di Negeri Sendiri
Jika di Lombok Barat kesenjangan muncul karena resep pembangunan yang dipaksakan dari luar, maka gambaran yang lebih kompleks dapat ditemukan di Papua. Di Papua, tantangan tidak hanya soal keseragaman pembangunan, tetapi juga terkait sejarah panjang pengaturan identitas, marginalisasi, dan dominasi pusat yang membuat setiap intervensi menjadi problematik.
Integrasi Papua ke dalam Indonesia sejak awal tidak pernah dianggap alami oleh banyak orang Papua. Hal ini tampak jelas dari sejarah perubahan nama wilayah tersebut. Dari West New Guinea menjadi Irian Barat, lalu Irian Jaya, hingga akhirnya Papua. Pergantian nama yang terus berlangsung bukan sekadar urusan terminologi administratif, melainkan penanda bahwa identitas Papua kerap ditentukan dari luar. Identitas kolektif masyarakat seakan menjadi ruang kosong yang bisa diisi sesuai kepentingan negara, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi orang Papua sendiri untuk menegaskan siapa mereka dan bagaimana mereka ingin dipandang.
Sejak masa orde baru, Papua menjadi salah satu wilayah yang paling gencar menerima program transmigrasi. Ribuan keluarga dari Jawa, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara dipindahkan ke tanah Papua dengan janji kesejahteraan dan lahan yang luas. Namun, kehadiran pendatang dalam jumlah besar lambat laun menggeser posisi Orang Asli Papua (OAP) di tanahnya sendiri. Di kota-kota besar seperti Jayapura, Timika, dan Sorong, OAP bahkan seringkali menjadi minoritas. Pergeseran ini tidak hanya bersifat demografis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kultural.
Migrasi besar-besaran tersebut memicu fragmentasi sosial yang dalam. Hubungan antara OAP dengan para pendatang kerap diwarnai ketegangan, baik dalam persaingan ekonomi maupun dalam interaksi sehari-hari. OAP sering merasa tidak memperoleh posisi setara dalam struktur sosial baru yang terbentuk. Di sisi lain, budaya Papua perlahan terdesak oleh budaya dominan dari luar, hingga bahasa-bahasa lokal banyak yang berada di ambang kepunahan. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa identitas OAP terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri.
Selain transmigrasi, eksploitasi sumber daya alam menambah lapisan ketidakadilan. Kekayaan emas, tembaga, hutan, dan hasil bumi Papua dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar terhubung langsung dengan pusat, salah satunya Freeport. Kendali ekonomi berada di tangan korporasi tersebut, sementara pemerintah daerah hanya menerima bagian kecil dari nilai yang dihasilkan. Pendapatan asli daerah Papua jauh lebih kecil dibandingkan besarnya keuntungan yang mengalir keluar, menciptakan jurang lebar antara potensi yang dimiliki dengan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ironisnya, manfaat yang diterima masyarakat lokal nyaris tidak sebanding dengan beban yang mereka tanggung. Lahan adat menyusut, hutan yang selama ini menjadi sumber pangan dan identitas kultural semakin digunduli, dan ruang hidup tradisional tergerus oleh operasi berskala besar. Dari sudut pandang banyak orang Papua, kondisi ini menyerupai bentuk kolonisasi internal, ketika penguasaan tanah dan kekayaan mereka berlangsung dengan dukungan negara, tetapi tanpa kendali yang berarti dari masyarakat asli.
Di ranah politik, apa yang disebut sebagai otonomi khusus di Papua sering dipandang hanya sebagai langkah “setengah hati”. Secara formal, kebijakan ini memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Namun, dalam praktiknya, banyak keputusan strategis tetap ditentukan di Jakarta, mulai dari alokasi anggaran, pengelolaan sumber daya, hingga arah pembangunan. Kondisi ini membuat otonomi khusus lebih menyerupai label administratif ketimbang instrumen nyata untuk menguatkan kedaulatan politik lokal. Bagi orang asli Papua, kondisi tersebut menegaskan bahwa kendali sesungguhnya tidak pernah benar-benar berpindah ke tangan mereka, melainkan tetap berada di pemerintahan pusat.
Kekecewaan terhadap otonomi khusus yang setengah hati semakin diperparah oleh kehadiran militer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Di banyak wilayah, aparat ditempatkan dalam jumlah besar dengan alasan menjaga stabilitas dan keamanan. Namun, keberadaan aparat bersenjata dalam intensitas tinggi justru menimbulkan ketegangan sosial yang terus berulang. Kontak senjata di daerah pedalaman, razia, dan operasi keamanan membuat rasa takut menjadi bagian dari rutinitas, terutama bagi orang Papua yang tinggal di wilayah rawan konflik. Alih-alih menghadirkan rasa aman, militerisasi justru meneguhkan pengalaman historis masyarakat Papua bahwa negara hadir lebih sebagai kekuatan pengawas dan penekan daripada pelindung.
Kondisi di Papua sekali lagi menegaskan bahwa negara gagal menyesuaikan “produknya” dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal. Berbagai kebijakan yang seharusnya membawa pembangunan atau stabilitas justru tidak menciptakan rasa aman maupun keadilan bagi orang asli Papua. Alih-alih menjadi fasilitator kesejahteraan dan perlindungan, negara hadir sebagai pengatur dari luar, memaksakan identitas, mengontrol sumber daya, dan menempatkan aparat militer secara masif. Akibatnya, orang Papua merasa terpinggirkan, suara mereka kurang didengar, dan hak-hak mereka atas tanah, budaya, dan kesejahteraan ekonomi kerap diabaikan.
Belajar dari Kegagalan Product–Market Fit
Seperti halnya di Minahasa dan Lombok Barat, Papua menunjukkan bahwa produk negara yang sama, dalam bentuk kebijakan, pembangunan, dan kontrol politik, tidak dapat diterapkan secara seragam. Kesalahan ini memperlihatkan bahwa sistem negara seringkali gagal melakukan “user research”, yaitu mendengar dan memahami aspirasi rakyatnya sendiri. Tanpa pemahaman mendalam terhadap kebutuhan lokal, kebijakan yang dibuat cenderung tidak sesuai dengan realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.
Desentralisasi yang diterapkan pasca-reformasi pun tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Tanpa perubahan paradigma dalam pengelolaan kekuasaan dan pengambilan keputusan, desentralisasi hanya memindahkan masalah dari pusat ke daerah, bukan menyelesaikannya. Sentralisme yang terselubung tetap hadir dalam bentuk birokrasi yang kaku, fragmentasi kebijakan, dan kontrol politik yang tidak merata, sehingga potensi perbaikan bagi rakyat tidak benar-benar terealisasi.
Kondisi di Minahasa, Lombok Barat, maupun Papua menegaskan bahwa kebutuhan setiap daerah sangat berbeda. Kebijakan seragam yang diterapkan untuk semua wilayah sering gagal merespons konteks lokal, baik dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi. Untuk mencapai product-market fit yang sejati, negara memerlukan kebijakan yang fleksibel dan adaptif, yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik unik setiap daerah, bukan sekadar menetapkan satu pendekatan yang sama di seluruh wilayah.
Kegagalan menyesuaikan sistem dengan konteks lokal juga membuat alienasi terus berkembang. Masyarakat merasa aspirasi, hak, dan kebutuhan mereka diabaikan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan, frustrasi, dan bahkan resistensi terhadap negara. Studi kasus di Minahasa, Lombok Barat, dan Papua menunjukkan bahwa tanpa product-market fit yang tepat, integrasi sosial-politik dan pembangunan yang adil akan sulit tercapai, sementara ketimpangan antara pusat dan daerah tetap terjadi.
Gagasan dalam buku “Mencari Indonesia” oleh Mohamad Sobary menegaskan refleksi penting mengenai kondisi ini. Menurut Sobary, “Mencari Indonesia” bukanlah soal mencari barang hilang, melainkan posisi, sikap, dan provokasi untuk berpikir kritis tentang negara dan rakyatnya. Istilah ini sendiri muncul dari pengalaman pengungsi konflik Timor Timur, Luluk Lukiyati, yang mengatakan mereka “sedang mencari Indonesia sebagai tempat aman dan nyaman.” Pesan inti buku tersebut menegaskan kenyataan yakni bagi sebagian warga, Indonesia masih timpang dan jauh dari rasa aman.
Kondisi masyarakat Papua menjadi contoh nyata dari ketimpangan ini. Identitas, hak atas tanah, dan kesejahteraan ekonomi mereka sering terabaikan, sementara kontrol politik dan ekonomi tetap berada di tangan pusat atau korporasi besar. Pengalaman ini bukan sekadar kegagalan administratif; ia menegaskan bahwa tanpa kesesuaian nyata antara kebijakan negara dan kebutuhan lokal, integrasi sosial-politik menjadi rapuh, dan rasa aman serta keadilan yang seharusnya diberikan negara tidak tercapai.
Mencari Indonesia, Mencari Rasa Aman
Dengan demikian, gagasan pada buku “Mencari Indonesia” bukan hanya refleksi belaka, tetapi juga panggilan bagi negara untuk mengevaluasi “produk” yang ditawarkannya kepada rakyat. Konsep ini terasa sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi Minahasa, Lombok Barat, maupun Papua, daerah-daerah yang telah menunjukkan bagaimana kegagalan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal menimbulkan alienasi, ketidakadilan, dan frustrasi publik. Desentralisasi, pembangunan, dan pengaturan politik tidak boleh sekadar menjadi retorika formal; mereka harus mampu membaca, memahami, dan menyesuaikan diri dengan ciri khas setiap wilayah. Hanya dengan begitu, integrasi yang adil, rasa aman, dan kepercayaan publik bisa diwujudkan.
Seperti yang dikatakan Riwanto Tirtosudarmo tentang Sorong, “Ada kehendak yang seolah ingin ditegakkan, ada yang ingin disemai dan dibesarkan, tapi ada kecemasan dan ketidakpedulian. Orang-orang lalu lalang bersimpangan, ada keteraturan yang seolah berjalan sendiri, mereka bergerak dan bersuara meski tak selalu setujuan.” Indonesia memang berjalan, tetapi ia masih jauh untuk dapat disebut sebagai rumah yang benar-benar nyaman dan adil bagi seluruh warganya. Pertanyaannya pun bukan lagi sekadar desentralisasi atau federalisme. Melainkan, apakah Minahasa, Lombok, Papua, dan seluruh warga Indonesia bisa sama-sama merasa bahwa rumah ini adil dan nyaman? Selama hal itu belum tercapai, jangankan Indonesia Emas, Indonesia Perak pun belum dapat tercapai.
—–
* Kelvin William, Mahasiswa International Business Management Universitas Ciputra Angkatan 2024