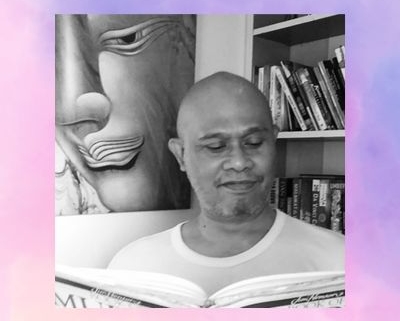Zaman Batu yang Tidak Pernah Serentak: Catatan Historiografis tentang Borobudur, Manjusrigrha, dan Wihara Abhayagiri
Oleh: Budi Murdono*
Munculnya beberapa prasasti dalam waktu berdekatan menggoda kita untuk menyatukannya ke dalam satu peristiwa besar. Apa lagi jika prasasti-prasasti itu ditemukan dalam lokasi yang juga berdekatan, ada kecenderungan yang hampir tak terhindarkan untuk menulis sejarah berdasarkan prasasti-prasasti itu, seolah-olah masa lalu bekerja dengan serentak dan rapi.
Di Jawa Tengah, pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9, berdiri
beberapa prasasti yang menandai pendirian bangunan-bangunan suci Buddha. Prasasti-prasasti Kalasan (778), Kelurak (782), Manjusrigrha (792), Abhayagiri (792), lalu Karangtengah dan Tri Tepusan (824) berdiri seperti gugusan batu penanda. Dari sana muncul kesimpulan yang tampak masuk akal: bahwa candi Borobudur, Candi Sewu, dan Wihara Abhayagiri dibangun pada waktu yang sama, sebagai satu ledakan pemuatan bangunan suci agama Buddha oleh Wangsa Syailendra.
Tapi sejarah jarang bekerja seperti itu. Yang lebih sering terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih manusiawi: gagasan yang bertumbuh perlahan, kebijakan yang berubah arah, dan bangunan yang lahir tidak sekaligus, tetapi berlapis-lapis, mengikuti denyut kekuasaan dan semangat keagamaan.
Prasasti sebagai Jejak, Bukan Jam
Kesalahan paling umum dalam membaca prasasti adalah memperlakukannya sebagai titik awal. Padahal, dalam tradisi Jawa Kuna, prasasti lebih sering menjadi titik penegasan—saat suatu bangunan, lembaga, atau keputusan dianggap cukup penting untuk diabadikan dalam batu atau tembaga.
Prasasti Manjusrigrha (792 M), misalnya, tidak mengatakan: “Hari ini kami mulai membangun.” Tulisan dalam prasasti ini lebih menyerupai kalimat: “Apa yang telah berdiri dan berfungsi ini kini kami tetapkan, kami lindungi, kami legitimasi.”
Dengan cara baca seperti itu, Candi Sewu tidak muncul sebagai bangunan yang baru dimulai dibuat pada 792 M, melainkan sebagai institusi Buddhis yang sudah mapan, yang sedang diteguhkan kembali statusnya di tengah dinamika politik yang berubah.
Hal yang sama juga berlaku pada Prasasti Abhayagiri Wihara di Ratu Boko.
Tahun 706 Saka (792 M) yang terpahat pada prasasti itu bukanlah tahun kelahiran mendadak sebuah kompleks suci, melainkan momen ketika sebuah bukit sunyi diangkat ke dalam ingatan resmi kerajaan—sebuah tindakan yang justru terasa reflektif, hampir asketis, bukan monumental.
Borobudur dan Waktu yang Panjang
Borobudur menolak keserempakan dengan caranya sendiri. Ia terlalu besar untuk lahir dari satu keputusan, terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu generasi. Setiap tingkatnya menyimpan waktu: waktu para perancang, para pemahat, para bhiksu yang menafsirkan ajaran, dan para penguasa yang silih berganti memberi restu.
Dalam konteks ini, Borobudur bukan “sezaman” dengan Manjusrigrha atau Abhayagiri dalam arti kronologis sempit. Ia beririsan dengan keduanya—ya—tetapi bergerak dalam tempo yang berbeda, seperti gunung yang tumbuh sementara desa-desa di sekitarnya datang dan pergi.
Borobudur adalah proyek kosmologis yang membutuhkan stabilitas jangka panjang.
Semenatara Sewu adalah proyek institusional yang menuntut pengorganisasian. Sedangkan Abhayagiri adalah proyek batin, pertapaan, pelepasan. Ketiganya lahir dari satu iklim ideologis, tetapi menempuh jalan waktu yang berlainan.
Gelombang, Bukan Ledakan
Jika kita melepaskan diri dari kebutuhan akan keserempakan, maka lanskap akhir abad ke-8 menjadi jauh lebih hidup.
Kita melihat gelombang awal, ketika negara menata fondasi Buddhisme melalui vihara-vihara institusional seperti Kalasan dan Sewu. Kita melihat gelombang tengah, ketika Borobudur mulai dinaikkan perlahan sebagai gunung pemaknaan, proyek yang melampaui satu masa pemerintahan. Dan kita melihat gelombang lanjut, ketika Abhayagiri berdiri di atas bukit sebagai ruang sunyi—sebuah penanda bahwa kekuasaan, pada titik tertentu, ingin berhenti berbicara keras dan mulai mendengarkan.
Gelombang-gelombang ini bertumpang tindih, saling menyentuh, tetapi tidak pernah benar-benar menyatu dalam satu detik sejarah yang sama.
Mengapa Keserempakan Terlihat Menggoda
Keserempakan memberi rasa tuntas. Ia memudahkan narasi: satu wangsa, satu kebijakan, satu masa emas. Namun justru di sanalah sejarah kehilangan ketegangannya. Dengan menerima bahwa Borobudur, Manjusrigrha, dan Abhayagiri tidak dibangun serentak, kita membuka ruang bagi konflik kecil, penyesuaian kebijakan, perubahan orientasi spiritual—semua hal yang membuat masa lalu terasa manusiawi, bukan mitologis.
Seperti kita memandang kekuasaan, yang tidak hanya terpaku pada tanggal, kita melihat proses pembuatan ketiga bangunan suci Buddhis itu tidak sebagai garis lurus, melainkan sebagai arus yang berbelok, melambat, dan kadang berhenti, diam.
Penutup: Batu-Batu yang Bergerak dalam Waktu
Bangunan-bangunan itu memang terbuat dari batu. Tetapi sejarahnya tidak pernah beku. Borobudur, Candi Sewu, dan Wihara Abhayagiri adalah saksi dari satu masa ketika Jawa Tengah menjadi ruang pertemuan antara semangat keagamaan, kekuasaan, dan kesunyian. Mereka tidak lahir bersama, tetapi berbicara satu sama lain melintasi waktu.
Dan mungkin, justru di sanalah warisan mereka yang sesungguhnya:
bukan pada keserempakan, melainkan pada kemampuan untuk bertahan dalam perbedaan tempo sejarah.***
Daftar Pustaka
de Casparis, J.G. Indonesian Palaeography: A history of Writing in Indonesia from the Beginnings to C.A.D.1500, E.J. Brill, 1975
Dumarcay, J. Borobudur, Oxford University Press, Inc, US, 1978
Kandahjaya, Hudaya, Borobudur: Biara Himpunan Kebajikan Sugata, Karaniya, 2021
Soekmono, R. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II, Yayasan Kanisius, 1973
———-
*Budi Murdono, pengajar yoga-meditasi freelance.