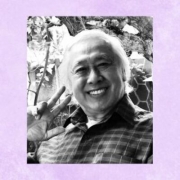Menjaga Bahasa Puisi: Antara Kebebasan Imajinasi dan Tanggung Jawab Makna
Oleh: Abdul Wachid B.S.*
1. Pendahuluan
Dalam beberapa dekade terakhir, dunia perpuisian Indonesia memperlihatkan gejala yang menarik sekaligus mengkhawatirkan: semakin banyak puisi ditulis dengan gaya yang cenderung mengabaikan kejelasan makna. Kata-kata berjejal dalam deretan larik yang puitik secara bunyi, namun tak jarang kehilangan daya ungkap secara substansial. Bahasa seakan hanya menjadi parade metafora dan irama, bukan lagi kendaraan utama untuk menyampaikan gagasan, pengalaman batin, atau kebenaran yang ingin dipancarkan.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan penyair pemula, tetapi juga merambah karya-karya yang sempat mendapat panggung di media sastra dan forum publik. Imajinasi seolah-olah menjadi pembenar bagi segala bentuk kebebasan bahasa, bahkan ketika kebebasan itu justru menjerumuskan puisi ke dalam kekacauan lambang dan absurditas makna.
Sebagian penyair mungkin beranggapan bahwa puisi tidak harus logis. Bahwa keindahan justru terletak pada kebebasannya dari nalar dan keteraturan makna. Namun, benarkah demikian? Apakah puisi memang harus dilepaskan dari daya koherensinya sebagai wacana yang bermakna dan bertanggung jawab? Sampai di manakah batas kebebasan imajinasi itu dibenarkan?
Penyair besar Amerika, T.S. Eliot dalam Selected Essays 1917–1932, pernah mengingatkan, “Genuine poetry can communicate before it is understood”; “Puisi sejati dapat menyentuh sebelum benar-benar dipahami” (New York: Harcourt, Brace & World Inc., 1950). Namun, ia tidak berkata bahwa puisi tidak perlu bisa dipahami. Sebaliknya, sentuhan awal itu mesti membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam, bukan menutup rapat makna di balik tirai bunyi dan absurditas lambang.
Dalam konteks ini, menjadi penting untuk merenungkan ulang posisi bahasa dalam puisi. Sebab ketika bahasa tidak lagi menjembatani antara pengalaman batin penyair dan pembaca, maka puisi kehilangan substansinya. Ia menjadi sekadar permainan estetika, tanpa ruh dan arah.
2. Bahasa Puisi dan Tanggung Jawab Simbolik
Bahasa dalam puisi bukan sekadar medium estetika, melainkan sarana untuk menyingkapkan makna yang tersembunyi di balik pengalaman batin, spiritualitas, atau realitas yang tak terjangkau oleh nalar sehari-hari. Puisi mengandalkan bahasa bukan untuk mengaburkan kenyataan, tetapi untuk mengolah kenyataan menjadi lebih jernih secara batiniah. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam puisi menuntut tanggung jawab simbolik: bagaimana tiap kata, metafora, dan lambang diarahkan bukan untuk menyamarkan kehampaan, melainkan untuk menggali dan menghidupkan kedalaman makna.
Simbol dan metafora, sebagai unsur utama dalam bahasa puitik, bukanlah hiasan kosong yang bisa dipilih secara acak. Ia harus bersumber dari pengalaman spiritual, historis, atau budaya yang mengandung resonansi makna. Jika tidak, maka metafora hanya akan menjadi “hiasan retoris” yang lepas dari daya gugah maupun daya pikir. Hal inilah yang dikritik oleh penyair dan filsuf Paul Valéry, yang mengingatkan agar puisi tidak terjebak pada kepuitisan tanpa kedalaman: “Poetry is the union of sense and sound. But sound must never overpower the sense, lest the poem become merely noise.”; “Puisi adalah persatuan antara makna dan bunyi. Namun bunyi tidak boleh mengalahkan makna, sebab jika demikian puisi hanya menjadi kebisingan semata.” (The Art of Poetry: The Collected Works of Paul Valéry, Volume 7. Trans. Denise Folliot. Princeton University Press, 1958).
Dalam konteks ini, kekhawatiran atas maraknya penggunaan metafora absurd yang tak mengakar pada pengalaman eksistensial penyair menjadi wajar. Ada kegelisahan yang muncul ketika bahasa puisi diperlakukan seperti permainan puzzle yang rumit tanpa pesan yang menyentuh. Bahkan Gaston Bachelard, dalam karyanya yang mendalam tentang imajinasi, menekankan bahwa metafora harus memiliki akar dalam “pengalaman konkret yang dihayati secara puitik”, bukan berasal dari kemauan arbitrer semata: “The poetic image is not an echo of the past. It is the soul directly experiencing the expansion of the being.”; “Citra puitik bukanlah gema dari masa lalu. Ia adalah jiwa yang secara langsung mengalami perluasan keberadaan.” (The Poetics of Space. Trans. Maria Jolas. Boston: Beacon Press, 1994).
Karena itu, tanggung jawab simbolik penyair adalah memastikan bahwa lambang-lambang dalam puisinya hadir bukan sebagai kedok kehampaan, tetapi sebagai jalan menuju pengalaman yang lebih hakiki, yang mungkin tak bisa diucapkan dengan bahasa biasa, namun tetap bisa didekati dengan bahasa puisi yang jernih dan bersumber dari kedalaman jiwa.
3. Imajinasi Kreatif vs Kekacauan Lambang
Imajinasi adalah jantung dalam proses penciptaan puisi. Namun tidak semua yang imajinatif otomatis bermakna. Ada perbedaan mendasar antara imajinasi kreatif (yang lahir dari perenungan dan pengalaman batin yang dalam), dengan kekacauan lambang, yakni puisi yang sekadar bermain-main dengan kata-kata tanpa dasar makna atau arah yang jelas. Imajinasi sejati bukan pelarian dari realitas, tetapi cara baru untuk memandang realitas dengan kedalaman spiritual dan kearifan simbolik.
Bahaya muncul ketika puisi hanya menjadi ajang permainan semiotik. Dalam konteks ini, puisi bisa berubah menjadi kudeta semiotik; sebuah pemberontakan terhadap makna, di mana simbol-simbol digunakan tanpa akar kesejarahan, kehilangan resonansi maknanya, dan menjelma jadi sekadar bunyi atau bentuk. Hal ini yang dikritik oleh penyair dan pemikir Octavio Paz:
“When a poet breaks with tradition, he must create a new tradition; if not, he is nothing but a juggler of words.”; “Ketika seorang penyair memutuskan hubungan dengan tradisi, ia harus menciptakan tradisi baru; jika tidak, ia hanyalah pesulap kata belaka.” (The Bow and the Lyre: The Poem, the Poetic Revelation, Poetry and History. Trans. Ruth L. C. Simms. University of Texas Press, 1973).
Imajinasi dalam puisi memang bebas, namun kebebasan itu tidaklah tanpa batas. Sebagaimana etika sosial dan etika spiritual, ada yang disebut etika simbolik dalam kepenyairan: simbol harus dipilih dan diolah dengan kesadaran sejarah, spiritualitas, dan tanggung jawab atas efeknya terhadap pembaca.
Kritik tajam juga disampaikan oleh T.S. Eliot, ketika ia menekankan pentingnya hubungan antara tradisi, pengalaman personal, dan tanggung jawab dalam penciptaan puisi, “Genuine poetry can communicate before it is understood.”
Pernyataan Eliot tersebut menunjukkan bahwa puisi yang baik memang tak harus segera dimengerti secara rasional, namun tetap mengandung kekuatan makna yang bisa dirasakan. Artinya, makna dalam puisi tidak boleh ditiadakan, apalagi diganti dengan kekacauan metaforis yang tidak berakar pada pengalaman hidup, sejarah, atau spiritualitas.
Dengan demikian, imajinasi dalam puisi seharusnya diarahkan untuk menciptakan pengalaman baru yang menyentuh dan mencerahkan, bukan sekadar merangkai simbol yang gelap dan membingungkan tanpa arah. Penyair tidak hanya bertanggung jawab terhadap kata, tetapi juga terhadap makna yang ia bangun melalui lambang-lambang yang ia pilih.
4. Menempatkan Puisi sebagai Jalan Hikmah
Dalam tradisi sufistik, puisi tidak berhenti sebagai ekspresi estetika atau permainan imajinasi. Ia adalah jalan hikmah: ikhtiar untuk menyentuh hakikat, menyingkap makna-makna terdalam kehidupan, bahkan sebagai medium mendekatkan diri kepada Yang Maha Gaib. Bahasa dalam puisi sufistik adalah bahasa penyingkapan, bukan penyamaran; ia tidak bersembunyi dalam absurditas, tetapi membuka lapisan-lapisan realitas spiritual yang tak tampak oleh mata lahir.
Sebagaimana dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, seorang sufi dan penyair besar Persia: “The wound is the place where the Light enters you.”; “Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu.” (The Essential Rumi. Translated by Coleman Barks. San Francisco: HarperOne, 1995).
Kata-kata Rumi di atas mencerminkan bahwa puisi adalah proses transendensi: dari pengalaman batin yang perih, sang penyair menyuling cahaya, menyampaikan hikmah melalui metafora yang menyala. Dalam konteks ini, setiap lambang dalam puisi menyimpan sejarah makna; bukan sekadar citraan estetis, melainkan pantulan nilai-nilai spiritual dan kultural yang telah teruji dalam perjalanan peradaban.
Penyair bukan hanya penggubah kata, tetapi penjaga bahasa dan penuntun makna. Ia menunaikan tugas profetik: memelihara kesadaran manusia melalui bahasa yang bernas, penuh tanggung jawab, dan tak melulu tergoda oleh absurditas bentuk. Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Iqbal, penyair dan filsuf dari Pakistan: “The poet is essentially a seer; he sees what ordinary eyes do not see.”; “Penyair sejatinya adalah seorang peramal; ia melihat apa yang tidak terlihat oleh mata biasa.” (The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1930).
Dalam ranah ini, puisi menjadi wasilah (perantara) antara dunia dan hakikat. Penyair tidak boleh tergelincir menjadi pembuat ilusi, yang mengalihkan manusia dari makna sejati kepada kesenangan estetika yang dangkal. Ia justru harus menjadi juru bicara makna, mengajak pembaca menyelami kedalaman lambang, bukan tenggelam dalam gemerlap permukaannya.
Sebagaimana pesan sufistik dari Syekh Ibnu ‘Arabi: “Al-kalām la budda lahu min rūḥin yashī fīhi.”; “Setiap kata harus memiliki ruh yang mengalir di dalamnya.” (Fusûsh al-Hikam, edisi Nasruddin al-Albani, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002). Artinya, kata dalam puisi bukan benda mati. Ia hidup, mengandung roh, dan mampu menggugah jiwa pembacanya apabila ditata dalam kesadaran spiritual yang jernih.
5. Penutup
Dalam dunia kepenyairan yang terus bergerak dan bereksperimen, penting untuk membangun kesadaran bersama akan tanggung jawab dalam menulis puisi. Kebebasan dalam berkarya adalah anugerah, tetapi kebebasan yang tanpa arah dan makna justru bisa menyesatkan, menjadikan puisi kehilangan daya ruhani dan fungsinya sebagai jalan pencerahan.
Gagasan dalam puisi tidak harus selalu linier atau logis secara akademik, tetapi harus tetap memiliki jiwa; sebuah intensi batin untuk menyampaikan kebenaran, kebijaksanaan, atau pengalaman manusia secara mendalam. Dengan kata lain, puisi harus tetap bertanggung jawab secara simbolik dan spiritual, tidak menjadi sekadar parade kata-kata yang indah tetapi hampa, atau permainan lambang yang kehilangan akar kesejarahannya.
Sebagaimana ungkap penyair besar Indonesia, Goenawan Mohamad dalam “Tuhan & Hal‑Hal yang Tak Selesai “: “Yang indah memang bisa menghibur selama‑lamanya, membubuhkan luka selama‑lamanya, meskipun puisi dan benda seni bisa lenyap. Ia seakan‑akan roh yang hadir dan pergi ketika kata dilupakan dan benda jadi aus.” Ungkapan ini menegaskan bahwa kekuatan puisi tidak diukur dari keberlangsungan keberadaannya secara fisik, melainkan dari keteguhan rohaninya, yang terus menghidupkan kembali makna meski kata dan materi melesap.
Ketakselesaiannya dalam tafsir bukan berarti kehilangan arah, melainkan membuka lapisan-lapisan makna yang bisa terus digali, asalkan landasan simboliknya kuat dan tak kehilangan ruh. Harapan bersama, agar dunia puisi di Indonesia tidak larut dalam euforia kebebasan yang nihil, tetapi terus tumbuh dalam kebebasan yang bernurani, yang menyinari, bukan merancukan; yang membimbing, bukan mengaburkan.***
——-
*Abdul Wachid B.S., penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto.