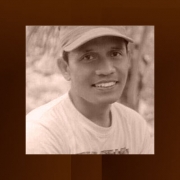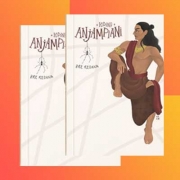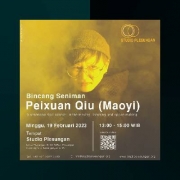Nisan, Artefak Kecil yang Menjaga Kebudayaan
Oleh: Purnawan Andra*
Cirebon selalu digambarkan sebagai kota pelabuhan yang terbuka. Dari masa awal pembentukannya, wilayah ini sudah menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, seperti Jawa, Sunda, Arab, Gujarat, Tionghoa, dan tradisi pesisir Nusantara.
Namun sering kali kita memaknai Cirebon hanya lewat cerita besar tentang kesultanan, perdagangan, dan tokoh-tokoh politik agama. Padahal, jejak kebudayaan yang paling jujur justru sering tersimpan pada benda-benda kecil yang dianggap tidak penting. Nisan makam adalah salah satunya.
Tahun ini, Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF) diselenggarakan di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada 20-22 November 2025. Festival budaya yang diselenggarakan sejak tahun 2012 itu mengangkat tema ”Estetika Nisan-nisan Islam Nusantara dan Dunia Ketuhanan Tarekat Syattariyah di Cirebon”.
Cirebon dipilih sebagai tempat penyelenggaraan BWCF Ke-14 Tahun 2025 ini karena memiliki peran vital dalam politik dan kekuasaan bergaya Islam pada abad ke-15 dan ke-16 dengan tinggalan arkeologis masa Islam yang cukup signifikan. Sebagai kota pusaka yang bersejarah, Cirebon memiliki warisan cagar budaya yang cukup berlimpah, mulai dari kompleks keraton, masjid kuno, kompleks taman, hingga makam-makam Islam kuno (Harian Kompas, 12/11/2025).
Teks Budaya
Nisan, menurut pandangan antropolog Clifford Geertz dalam Tafsir Kebudayaan (1992), bisa dibaca sebagai “teks budaya”—sebuah artefak yang menyimpan nilai, simbol, dan tata pikir masyarakat yang membuatnya. Di Cirebon (baca: Nusantara) nisan bukan sekadar penanda kematian. Ia adalah arsip pertemuan budaya, cara masyarakat membaca dunia, dan cara mereka memaknai hidup dan mati. Ketika nisan dibaca sebagai teks, kita akan menemukan lapisan-lapisan sejarah yang tidak pernah ditulis oleh istana atau penguasa.
Banyak nisan tua di Nusantara menunjukkan gabungan estetika yang menarik. Ada bentuk kepala nisan yang mengikuti gaya Islam awal dari Gujarat, ada ukiran floral khas pesisir yang tidak menghindari bentuk naturalis, dan ada juga motif-motif yang sering ditemukan dalam seni Tionghoa.
Campuran ini menegaskan bahwa Islam tidak datang sebagai paket lengkap yang seragam, tetapi melalui proses negosiasi dengan budaya lokal. Seperti dicatat Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya, budaya pesisir tumbuh bukan melalui penyeragaman bentuk, tetapi melalui kemampuan menyerap, meramu, dan menata ulang pengaruh luar secara kreatif. Hibriditas inilah yang membuat seni pesisir—termasuk di Cirebon—memiliki karakter yang lentur dan hidup.
Di banyak nisan, kita melihat ornamen bunga, daun, sulur, bahkan bentuk-bentuk hibrid yang dalam perspektif Islam ortodoks mungkin dianggap tidak lazim. Tetapi di pesisir, simbol-simbol itu menjadi jembatan antara tradisi lama dan ajaran baru.
Inilah bukti konkret bagaimana Islam Nusantara dihidupi, bukan hanya diperdebatkan. Nisan-nisan tersebut menjadi saksi nyata bahwa tradisi keagamaan di Nusantara sejak awal bersifat terbuka, lentur, dan tidak tunggal. Ia bergerak mengikuti masyarakat, bukan memaksakan pola yang datang dari luar.
Catatan Sosial
Nisan juga bisa dibaca sebagai catatan sosial. Jenis batu yang digunakan, gaya ukiran, serta kerumitan motif sering menunjukkan posisi sosial orang yang dimakamkan. Batu paras biasa dipakai untuk masyarakat kebanyakan; batu andesit atau batu karang keras lebih sering ditemukan pada makam keluarga bangsawan atau pedagang kaya.
Ini memperlihatkan struktur sosial masyarakat pesisir yang berbeda dengan masyarakat agraris. Mobilitas sosial di pelabuhan lebih cair. Seorang pendatang bisa naik status dengan cepat melalui perdagangan, dan tanda-tanda itu muncul pada nisannya.
Dengan kata lain, nisan menjadi catatan hubungan sosial, ekonomi, dan religius yang jarang dibicarakan dalam sejarah resmi. Seperti yang dikatakan Michel Foucault, kekuasaan bukan hanya bergerak di lembaga besar, tetapi juga di benda-benda kecil yang “mengatur ingatan”. Nisan adalah alat ingatan. Ketika ia hilang, ingatan sosial ikut hilang.
Namun hari ini, banyak nisan tua di Cirebon rusak atau hilang tanpa dokumentasi. Ada yang terhapus oleh pembangunan, ada yang dilapisi ulang dengan keramik modern, ada yang dipindahkan tanpa catatan, dan ada yang dibiarkan hancur karena dianggap tidak penting.
Reformasi makam sering dilakukan tanpa pandangan arkeologis. Makam-makam yang awalnya penuh jejak estetika kini banyak yang diseragamkan menjadi marmer putih. Dalam cara pandang modern yang serba praktis, nisan dianggap tidak lebih dari penanda administratif.
Padahal ini bukan hanya soal benda yang hilang, tetapi hilangnya kemampuan membaca masa lalu. Sejarawan Taufik Abdullah pernah mengatakan bahwa masyarakat yang kehilangan ingatan akan mengulang kesalahan yang sama karena ia tidak tahu dari mana ia datang. Jika nisan hilang, kita kehilangan arsip tentang bagaimana masyarakat pesisir membentuk identitasnya, bagaimana Islam diterjemahkan ke dalam estetika lokal, bagaimana hubungan sosial dibangun, dan bagaimana kematian dipahami.
Membicarakan nisan juga berarti membicarakan relasi kita dengan kematian. Tapi masyarakat modern kini cenderung menyederhanakan kematian menjadi urusan administratif. Ini tampak jelas di banyak kuburan kota yang seragam, datar, cepat, dan kadang tanpa simbol.
Bandingkan dengan makam-makam lama di Cirebon dan Nusantara lainnya yang penuh ukiran dan motif. Dulu, kematian tidak hanya menandai berakhirnya hidup, tetapi menjadi bagian dari kehidupan budaya. Ia adalah ruang untuk menunjukkan rasa hormat, kreativitas, dan pandangan dunia.
Imajinasi Budaya
Perubahan ini menunjukkan penyempitan imajinasi budaya. Ketika simbol-simbol lama hilang, bukan hanya bentuk seni yang hilang, tetapi cara kita memandang manusia dan kehidupan juga menyempit. Kita tidak lagi menganggap penting jejak-jejak kecil yang membangun kebudayaan.
Cirebon adalah contoh bagaimana kota pelabuhan menyimpan ingatan yang lebih rapuh dibanding kota agraris. Kita tahu, pelabuhan selalu penuh perubahan. Dengannya, benda-benda kecil menjadi satu-satunya penanda kesinambungan.
Maka ketika nisan hilang, hilang pula jejak identitas pesisir yang selama ini jarang mendapatkan ruang dalam sejarah resmi. Seperti dikatakan James C. Scott, masyarakat yang kecil suaranya sering menitipkan sejarahnya pada benda-benda kecil, bukan pada catatan negara. Nisan adalah salah satu “arsip senyap” itu.
Karena itu, membaca nisan bukan soal romantisasi tradisi. Ini soal kemampuan kita mengenali dasar-dasar kebudayaan. Orang yang terbiasa memperhatikan hal kecil akan lebih peka terhadap perubahan sosial. Masyarakat yang merawat situs-situs kecil seperti makam akan lebih punya ruang untuk melihat diri mereka dalam lintasan sejarah yang panjang. Sebaliknya, masyarakat yang membiarkan benda-benda kecil hilang biasanya juga kehilangan kemampuan membaca masa depan.
Pada akhirnya, pembicaraan tentang nisan makam adalah pembicaraan tentang bagaimana kita memaknai kebudayaan. Kebudayaan bukan melulu tarian, upacara, atau festival. Ia juga hidup dalam batu kecil yang diletakkan di atas makam seseorang ratusan tahun lalu. Batu itu mungkin sederhana, tetapi ia memuat jejak pertemuan dunia, perubahan keyakinan, perpindahan manusia, dan cara hidup suatu masyarakat.
Merawatnya berarti merawat kemampuan kita untuk membaca diri sendiri. Tanpa itu, kita akan menjadi masyarakat yang bergerak cepat tetapi tidak tahu ke mana arah yang dituju.
Kebudayaan selalu membutuhkan ingatan. Dan kadang, ingatan itu justru terletak pada nisan makam-makam yang diam itu.
—-
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, penerima fellowship Governance & Management of Culture di Daegu Catholic University, Korea Selatan.