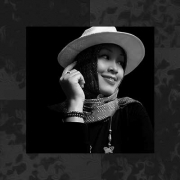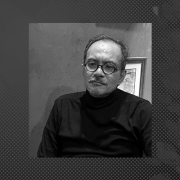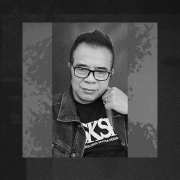Etnografi Ziarah Kubur: Tradisi, Kesakralan, dan Kontestasi Spiritual Kaum Nahdhiyin
Oleh: Gus Nas Jogja*
Fenomena ziarah kubur pada kaum Nahdhiyin adalah salah satu ekspresi keagamaan yang paling mencolok dan mendalam. Ia merupakan manifestasi lahiriah dari keyakinan batin yang teguh pada tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah atau Aswaja, yang pada praktiknya diperkaya secara fundamental oleh dimensi Tasawuf Ijmali (Tasawuf yang dianut mayoritas) [1]. Ziarah Kubur ini melampaui sekadar kunjungan doa; ia adalah ritual kontinuitas spiritual, menghubungkan peziarah dengan kontinuum karamah para wali dan ulama yang telah meninggal. Ruang makam adalah gerbang, bukan akhir, tempat di mana hukum fisika –kematian– disublimasi oleh hukum spiritual –keabadian ruh–.
Di Tanah Jawa, ritual ini mencapai intensitas kulturalnya, di mana kunjungan ke makam Walisongo, Raja-raja Mataram, hingga makam ulama kontemporer seperti Gus Dur, adalah pencarian barakah (keberkahan), laku tawassul (perantara), dan peneguhan sanad (rantai transmisi spiritual). Secara filosofis, peziarah mencari jejak fana’ (peleburan diri dalam Tuhan) yang pernah dicapai oleh wali, berharap esensi fana’ tersebut menular melalui ruang sakral.
Tulisan ini akan mempertajam analisis etnografi, sosiologi, dan antropologi agama yang sudah ada, dengan membedah dimensi spiritual filosofis yang melandasi setiap praktik ziarah, menegaskan bahwa makam keramat adalah panggung bagi pietas kolektif Nahdhiyin di tengah modernitas dan kontestasi teologis.
Kerangka Sosiologi dan Antropologi Agama: Kontinuitas Sakral dan Filosofi Barakah
Untuk menelaah ziarah, kita menggunakan konsep sakral dan profan (Durkheim [2]) dan liminalitas (Brian Turner [6]). Makam wali, sebagai sacred space, adalah titik di mana kekuatan spiritual terpusat, memisahkan peziarah dari keterbatasan dunia profan. Tujuan filosofisnya adalah mencapai transformasi internal melalui perendaman dalam energi sakral tersebut.
Barakah dalam konteks ini adalah energi residu kesalehan; sebuah kekuatan Ilahi yang dianugerahkan kepada wali –sebagai individu yang sudah mencapai maqam makrifat atau dekat dengan Tuhan– dan kini tersemat pada makamnya. Secara filosofis, ziarah adalah upaya untuk mendapatkan transmisi sirr (rahasia spiritual) atau faydh (limpahan) dari wali. Peziarah tidak meminta kepada wali, melainkan menggunakan wali sebagai antena spiritual dalam jaringan kosmis, untuk mengakses faydh yang berasal dari Tuhan.
Secara esoteris, tawassul adalah pengakuan filosofis terhadap hierarki eksistensial (maqam) di alam semesta. Wali diyakini telah mencapai maqam tinggi—seperti maqam ridha atau maqam mahabbah—yang memberikan mereka kedekatan khusus dengan Hadirat Ilahi. Ketika seorang Nahdhiyin bertawassul, ia mengakui bahwa ruh wali adalah entitas yang hidup dan berkesadaran (hayat ruhaniyah), yang doanya lebih mungkin diterima, bukan karena kekuatan wali itu sendiri, melainkan karena tingkat wushul (sampainya) mereka kepada Tuhan.
Bagi kaum sālik atau pengamal spiritual dan pengikut Tarekat Mu’tabarah, ziarah kubur adalah praktik sulūk –perjalanan spiritual– yang berkesinambungan, yakni: Sanad Barakah sebagai makna Kontinuitas Nur Ilahi. [8]
Inti mistis ziarah adalah penguatan sanad (rantai transmisi) spiritual, yang melacak jalur otentikasi spiritual hingga Nabi SAW. Makam seorang mursyid tarekat berfungsi sebagai titik tajalli (penampakan) dari nur (cahaya) spiritual yang diwarisi melalui sanad tersebut. Peziarah datang untuk mengisi ulang baterai spiritual mereka, memastikan bahwa sirr (rahasia batin) mereka tetap terhubung dengan sumber otentik Tasawuf. Ini adalah sebuah upaya filosofis untuk memastikan bahwa praktik agama mereka tidak terputus dari kearifan profetik.
Syaikh Abdul Qodir Al-Jilani: Manifestasi Sulthān al-Auliyā’ [9]
Syaikh Abdul Qodir Al-Jilani (w. 1166 M), Sulthān al-Auliyā’, adalah arketipe wali dalam imajinasi Nahdhiyin. Anekdot tentang karamah beliau, yang selalu dibacakan dalam Manaqib dan Tahlil, berfungsi sebagai pedagogi mistis. Kisah-kisah tersebut mengajarkan filosofi qudrat (kemampuan mutlak) yang terdelegasikan. Bahwa wali, melalui kedekatannya dengan Tuhan –konsep wilāyah–, dapat melakukan tindakan di luar kebiasaan (khariqul ‘adah). Ini bukan pemujaan, melainkan pengakuan bahwa fana’ kepada Tuhan menghasilkan baqa’ (keabadian dalam Tuhan) dan kekuatan untuk mempengaruhi alam.
Amalan Ziarah untuk Pencapaian Maqamat
Pertama, I’tikaf dan Uzlah: Praktik pengasingan diri di makam adalah upaya untuk mencapai kondisi hāl –keadaan spiritual– yang bersih, memudahkan futūh –pembukaan ilham.
Kedua, Tawajjuh Mursyid: Mursyid Tarekat memimpin tawajjuh—sebuah praktik konsentrasi intens yang diarahkan ke makam—untuk membantu murid menembus batas ego (nafs) dan mencapai fana’ ruhani, peleburan kesadaran batin dengan sirr wali. Ini adalah latihan filosofis untuk memahami bahwa semua eksistensi pada akhirnya kembali kepada Sang Pencipta.
Ziarah ke makam Gus Dur di Tebuireng adalah afirmasi filosofis terhadap Islam Inklusif dan Humanisme Religius. Gus Dur, sebagai wali politik, mencontohkan maqam tawadu’ (kerendahan hati) dan keberpihakan pada kaum mustadh’afin (yang dilemahkan). Kekeramatan yang dicari peziarah adalah barakah moralitas dan spirit keberanian untuk membela keadilan. Secara filosofis, Tebuireng adalah pusat ziarah yang menegaskan bahwa wilāyah (kewalian) di era modern harus terwujud dalam etika sosial dan politik.
Makam Raja-raja Mataram dan makna Manunggaling Kawula Gusti. [3] Makam di Imogiri dan Kotagede adalah panggung di mana filosofi Jawa-Islam tentang kedaulatan dipentaskan. Kepatuhan pada busana adat (laku fisik) adalah upaya untuk menyelaraskan diri dengan kosmologi Manunggaling Kawula Gusti (penyatuan Hamba dengan Tuan, yakni Tuhan). Raja Mataram diyakini sebagai khalifatullah yang mencapai Manunggal (kesatuan), dan makamnya adalah titik fokus kekuatan duniawi (kedhaton) dan spiritual (karamah). Peziarah mencari barakah harmoni kosmik dan kesuksesan dunya-akhirat, yang diperoleh melalui kepatuhan pada tatanan yang disakralkan.
Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon dan Mitos Sulūk Sembilan Pintu. [4]
Secara spiritual filosofis, arsitektur Makam Sunan Gunung Jati dengan Sembilan Pintu –Pintu Gapura, Pasujudan, hingga Teratai Emas– adalah simbolisasi arketipal dari perjalanan sulūk. Setiap pintu melambangkan maqam atau tantangan spiritual yang harus dilewati sālik untuk mencapai sirr pada inti makam.
Pintu Pasujudan, misalnya, melambangkan maqam taubat dan syariah yang harus disempurnakan. Sedangkan Pintu Teratai Emas pada Puncak melambangkan maqam makrifat atau haqiqah, di mana hanya ruh yang benar-benar suci yang dapat mendekat.
Pembatasan akses makam secara sosiologis memvalidasi ajaran Tasawuf: bahwa makrifat adalah hak istimewa yang diperoleh melalui perjuangan spiritual (riyadhah) yang ketat, dan bukan milik semua orang. Peziarah awam yang hanya bisa berdoa di pintu luar melakukan laku istiqamah dan tawadu’ dalam penantian barakah.
Makam Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dalam Tafsir Filosofi Jihad dan Istiqamah. [5] Mitologi Pancer (pusat) dan Jangkar Kedaulatan Banten berakar pada filosofi Jihad atau perjuangan fisik. Sultan Hasanuddin, sebagai pendiri dan wali, diyakini mencapai maqam tinggi melalui jihad melawan tantangan spiritual dan politik (VOC). Makamnya adalah pusat energi istiqamah dan keteguhan.
Peziarah datang ke Banten untuk mendapatkan barakah kekuatan batin yang diperlukan untuk bertahan dalam kesulitan hidup. Konsep pancer secara filosofis berarti bahwa Kesultanan, bagi komunitas Nahdhiyin, memiliki pusat kesadaran yang tak tergoyahkan yang bersumber dari spiritualitas wali/sultan. Ziarah ini adalah ritual untuk menanamkan energi ketegasan ini dalam diri, meniru keteguhan Sultan dalam mempertahankan kedaulatan spiritual dan fisik.
Fenomena ziarah kubur adalah panggung di mana dimensi ritual, sosial, dan mistis filosofis saling berkelindan. Komersialisasi atau ekonomi ritual di sekitar makam pada dasarnya adalah kompromi antara kebutuhan spiritual dan realitas ekonomi; peziarah membayar untuk mengakses dan mempertahankan ruang sakral.
Ziarah kubur bagi kalangan kaum Nahdhiyin tetap tangguh di tengah modernitas dan kontestasi ekonomi karena ia menyediakan jawaban filosofis dan mistis yang memuaskan atas kebutuhan manusia akan koneksi spiritual yang nyata dan terverifikasi melalui sanad dan anekdot kekeramatan para wali. Makam keramat berfungsi sebagai institusi sosial-mistis yang kuat, menyediakan peta jalan sulūk bagi para sālik dan meneguhkan filosofi bahwa kehidupan sejati (hayat haqiqi) hanya dicapai melalui fana’ dan baqa’ bersama Tuhan.
Wallahu A’lam.
***
Catatan Kaki
1). Aswaja dan Tasawuf: Dalam tradisi NU, Tasawuf adalah salah satu pilar utama yang dianut, mendampingi Akidah Asy’ariyah/Maturidiyah dan Fiqih Syafi’iyah. Ziarah kubur adalah praktik yang dianjurkan oleh Tasawuf.
2). Durkheim dan Ruang Sakral: Konsep makam sebagai sacred space memisahkan ruang tersebut dari aktivitas profan sehari-hari, memberikan kekuatan transformatif bagi peziarah.
3). Kekuasaan Jawa-Islam: Praktik ziarah di Imogiri mencerminkan sinkretisme politik-spiritual. Raja diyakini memiliki wahyu (legitimasi ilahi) yang setara dengan karamah wali, mencerminkan filosofi Manunggaling Kawula Gusti.
4). Struktur Makam Cirebon: Pembatasan akses di makam Syarif Hidayatullah melambangkan tingkatan spiritual (maqamat) yang harus dilalui peziarah (sulūk).
5). Banten Lama: Kompleks ini adalah bukti sejarah dari perpaduan antara pusat ibadah, pusat kedaulatan politik, dan pusat makam, yang saling menguatkan dengan narasi mistis kelautan.
6). Turner, Liminalitas: Perjalanan ziarah menciptakan fase komunitas di mana ikatan sosial horizontal menguat.
7). Geertz, Agama Jawa: Karya klasik tentang sinkretisme Islam di Jawa, termasuk praktik ritual makam.
8). Sanad dan Tarekat: Sanad adalah jaminan keabsahan spiritual dalam Tarekat. Ziarah ke makam pendiri tarekat atau mursyid adalah penguatan sanad ini.
9). Syaikh Abdul Qodir Al-Jilani: Pendiri Tarekat Qadiriyyah, dihormati secara universal oleh kaum Sufi dan menjadi tokoh sentral dalam pembacaan manaqib dan tahlil di Indonesia, menjadi arketipe karamah.
Daftar Pustaka
Geertz, Clifford. The Religion of Java. Chicago: University of Chicago Press, 1960. (Klasik Antropologi tentang Islam Jawa, termasuk ritual dan praktik keagamaan).
Durkheim, Émile. The Elementary Forms of Religious Life. Translated by Karen E. Fields. New York: Free Press, 1995. (Fondasi Sosiologi Agama, konsep Sakral dan Profan).
Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Stanford: Stanford University Press, 2008. (Referensi sejarah tentang Kesultanan Mataram dan konteks politik-keagamaan Jawa).
De Graaf, H. J. and Th. G. Th. Pigeaud. Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th Centuries. Monash University Press, 1984. (Membahas sejarah Walisongo, relevan untuk Cirebon).
Guillot, Claude. The Sultanate of Banten. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. (Karya utama tentang sejarah Banten, relevan untuk konteks politik dan maritim).
Turner, Victor. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Ithaca: Cornell University Press, 1969. (Konsep Liminalitas dan Komunitas dalam ritual).
Mujiburrahman. Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order. Amsterdam University Press, 2006. (Membahas identitas NU dan kontestasi keagamaan kontemporer).
Bruinessen, Martin van. Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia. Bandung: Mizan, 1995. (Analisis mendalam tentang peran Tarekat dan Mursyid dalam masyarakat Muslim Indonesia).
Al-Jilani, Syaikh Abdul Qodir. Sirrul Asrar (Rahasia di Balik Rahasia). (Salah satu karya Tasawuf fundamental Syaikh Al-Jilani yang menjadi rujukan spiritual banyak tarekat).
—-
*Gus Nas Jogja, budayawan.