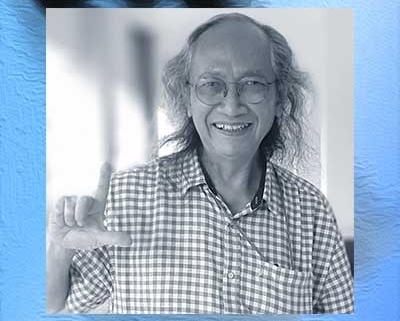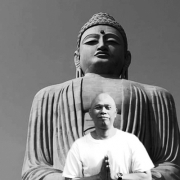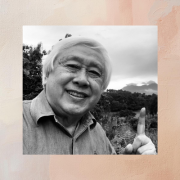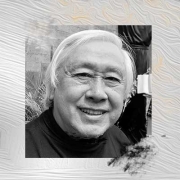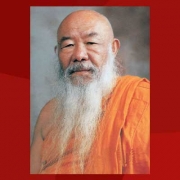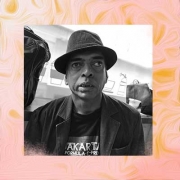Membaca Adalah Tugas Menafsir
Oleh Mudji Sutrisno SJ.
Membaca akhirnya merupakan kerja menafsir, kata Gadamer (Truth and Methods, 1980). Sang penafsir harus mampu menangkap makna awal atau asli dari teks tertulis pengarang. Dan untuk itu, penafsir harus mencermati tiga tempat beradanya makna, yaitu makna yang dihurufkan oleh pengarang dari peristiwa kehidupan atau pengalaman hidupnya yang diwujudi dalam aksara. Yang kedua, ia harus membandingkan dengan teks-teks di sekitar tema serupa yang biasanya disebut penafsir antar teks. Sedang yang ketiga, kesediaan penafsir dengan kesadaran sikapnya untuk mau rendah hati terbuka dan membuka cakrawala mata bacanya pada cakrawala makna teks sehingga saling dibuahi menemukan makna baru dalam peleburan cakrawala (fusion of horizon). Bahkan guru Gadamer yaitu Martin Heidegger (lihat: Being and Time, 1984) menegaskan bahwa menafsir adalah kesediaan untuk masuk kedalam keberadaan (das sein) teks di mana penafsir bertemu dialogis teks dalam dialog antar being yaitu dalam kehidupan itu sendiri. Secara sederhana dan saling berdialog kehidupan di antara keduanya. Dari pokok inilah dikenal dua macam cara membaca, yaitu membaca dari “dalam” proses teks itu terjadi atau ditulis yang disebut pendekatan intrinsik. Contohnya, bila mau mencari makna teks sastra, dekati dan bacalah ia melalui kode sastra tema, Yang kedua, membaca dari luar (ekstrinsik) yang menafsir sastra melalui ilmu-ilmu di luar teks sastra misalnya sosiologi sastra, mendekati sastra maknanya dari ilmu sosiologi, religiositasnya yang menyumbang toleransi keragaman dan perekat saling menghormati ketika bertemu dengan penyusun penokohan, alur kisah dalam novel sastra.
Konsekuensi logis dari penalaran di atas adalah dalam kerja membaca teks, kita dihadapkan pada pilihan, yaitu mau menafsirkannya menurut meaning (makna) penulis teks yang sebenar aslinya (original meaning) sebagai kualitas nilanya (baca: value as quality of text’s meaning) atau kita membacanya untuk mendapatkan kepentingan (interest) kita dan membongkar sisi-sisi kepentingan penulisan teks dari disiplin ilmu dari luar teks misalnya sisi kepentingan ideologis teks sejarah dengan membongkar relasi saling menguasai dan hegemoni makna yang secara ideologis penguasa menulis teks sejarahnya untuk pembenaran keberadaan rezim penguasa itu. Lalu soalnya, bagaimana membaca secara benar? Kita masuk ke dalam pendapat berikut dari Gadamer setelah paham bahwa membaca ujung-ujungnya adalah menafsir. Mengapa? karena proses baca-membaca yang merupakan kerja tafsir-menafsir hanya mungkin dilakukan lewat bahasa. Bahasa ini dibagi menjadi bahasa tulis, yaitu teks tertulis yang secara linguistik menghurufkan dan mengaksarakan komunikasi lisan, atau wacana dalam logika bahasa tulis dan mewujudkannya dalam teks dengan kerangka bahasa logis. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kalimat bermakna tertulis yang komunikatif bisa dipahami kalau dibaca berstruktur SPOK yaitu adannya subjek lalu predikat kemudian objek dan keterangan. Singkat ringkas, bahasa tulis adalah rumusan tertulis logis rasional untuk komunikasi hal-hal yang disadari untuk dibahasakan dalam tulisan. Ketika bahasa tulis atau teks melulu menuliskan yang sistematis rasional, maka ia menjadi kering karena yang dirangkum adalah dialog ilmiah rasional. Muncullah tulisan yang diberi makna imajinatif dan kalimat-kalimat berbobot inspiratif dan simbolik dalam susastra dan sastra, yaitu bahasa tulis sastrawi yang sadar dimuati makna-makna inspiratif kaya dan disusun indah menjadi misalnya prosa susastra. Ketika prosa, meskipun tertulis dan tersusun indah bertema kurang mampu menuliskan pengalaman merenungi hidup atau pengalaman sang penyair dalam menyusun naskah pujangganya, maka ditulislah puisi, baik puisi liris, puisi kekawin maupun puisi sunyi manakala nyanyi sunyi kehidupan mau dituliskan dalam aksara dan bukan dalam lagu not-not angka atau not-not balok musik yang menghurufkan nada bunyi. Bahasa tulis baru muncul dalam peradaban sesudah bahasa lisan setelah dipercepatnya huruf-huruf akasara dicetak oleh penemuan teknologi cetak. Karena itu pertanyaan mendasar yang mengikuti adalah bagaimana membaca bahasa sebagai teks tertulis dan bagaimana membaca bahasa sebagai wacana? Membaca bahasa tertulis sebagai teks adalah menafsirkannya menurut pokok makna teks ketika ditulis. Membaca bahasa lisan sebagai wacana membawa kita pada Ferdinand de Saussure yang merumuskan cara membaca bahasa sebagai penanda dan yang ditandai baik bahasa tulis dan lisan wacana. Yang terpenting adalah dibangkitkannya kesadaran pembaca untuk memahami bahasa sebagai kode tanda dan sistem tanda yang disepakati oleh komunitas bahasa mengenai maknanya dan pilihan semiotika sistem tandanya. Maka, kesadaran baru dalam membaca bahasa sebagai sistem tanda bermakna ini memudahkan pemahaman kita mengenai mengapa sebagai huruf bahasa Inggris menulis mawar dengan rose, sedangkan bahasa Indonesia dengan kata mawar. Mengapa pula puisi simbolis dan kata simbolik mawar ibu pertiwi, maknanya yang memuat arti posisi wangi perempuan buat tanah air, bisa dimengerti ketika membaca bahasa sebagai sistem tanda yang simbolik bermakna. Ketika peradaban pemberian itu sewenang-wenang oleh komunitas bahasa atau dikonsensuskan, maka di situ kita disadarkan bahwa di satu pihak ada keterbatasan bahasa sebagai sistem tanda merumuskan peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman dari kekayaan kehidupan ini sendiri yang terbatas dirumuskan oleh bahasa baik lisan apalagi bahasa tulisan. Karena itu, saat ini dalam kajian budaya (cultural studies) makna teks (tertulis) diperluas untuk mengartikan perilaku, tindakan sosial dan karya warga atau masyarakat yang menghayati kehidupannya baik secara sosial, politis maupun estetis religius. Dengan kata lain, yang dimaksud teks (kadang diberi huruf besar) adalah kehidupan itu sendiri. Alasannya, bahasa teks hanya mampu merumuskan secara sadar, rasional, logis (nalar) olahan pengalaman dari kehidupan yang mahakaya sisi, dimensinya.
Dilain pihak, disadarilah sebagian besar kehidupan ini yang tidak mampu dinalarkan dan disistematisasikan logis, rasional yang sudah hidup turun-temurun dalam tradisi kebijaksaan kehidupan (living wisdom dan living tradition) dimana kita lahir didalamnya tanpa bisa memilih. Inilah yang disebut rahim kebijaksanaan hidup dalam tradisi kejawaan, kebatakan, keminangan yang diantara kita dalam dinamika proses menjadi Indonesia sebagai bangsa dari tradisi-tradisi identitas budaya lokal, etnik atau suku. Kita lahir dalam kehidupan budaya lisan dan tulisan yang disatu segi menggugat kita untuk membari tafsiran baru dengan membacanya menurut makna tradisi. Dilain segi, kita sudah lahir dibentuk, dibebani dalam tradisi-tradisi budaya lisan atau tulisan yang kerap kita debatkan, namun sudah terus kita sikapi tetap tradisional atau osmosis saling membuahi menemukan makna baru dengan dialog yang lama? Ujung-ujung membaca (secara bahasa budaya) akhirnya adalah tugas kebudayaan untuk menafsir kehidupan sebagai teks huruf besar itu sendiri. Untuk ke arah mana? Ke arah membuat budaya hidup bersama lebih berkeadaban atau peradaban. Disinilah sebuah kesadaran credo untuk membaca dan belajar menafsir antar kita bisa dirangkum padat, bagi yang biasa berbahasa prosa atau berbahasa logis, belajarlah dari sesama yang biasa berbahasa puisi atau bahasa warna dan garis sehingga tugas memuliakan kehidupan bisa lebih cepat dibuahi dan diwujudkan dalam bahasa hukum keadilan, bahasa ekonomi kesejahteraan dan pemerataan dan religius saling memuliakan kehidupan antar sesama dalam keagungan Pencipta hidup yang mengundang kita lebih memperindah semesta dari pada menghancurkannya. Sebab kita adalah para penafsir kehidupan ini.
—–
*Mudji Sutrisno SJ, Budayawan