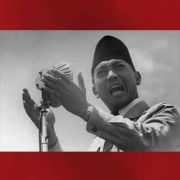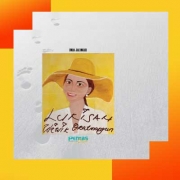Bangsa yang Gemar Tepuk Tangan
Oleh Purnawan Andra*
Kementerian Agama baru-baru ini memperkenalkan Tepuk Sakinah sebagai bagian dari program bimbingan pranikah. “Berpasangan! Janji kokoh! Saling cinta, saling hormat, saling ridho!”—begitulah yel-yel yang dimaksudkan agar nilai rumah tangga sakinah lebih mudah diingat.
Sekilas tampak kreatif, bahkan ringan dan menyenangkan. Namun di tengah angka perceraian yang terus meningkat, kasus kekerasan domestik yang masih dianggap urusan pribadi, serta tekanan ekonomi yang nyata, program ini terasa seperti ironi. Alih-alih menyentuh akar persoalan, negara justru memilih memberi yel-yel. Tepuk tangan dijadikan jawaban simbolik atas problem yang bersifat struktural.
Tepuk Sakinah hanyalah contoh terbaru dari kebiasaan lama kita bertepuk tangan, baik secara harfiah maupun simbolik. Dari ruang kelas hingga ruang sidang, dari panggung politik hingga altar pernikahan, tepuk tangan seolah menjadi tanda keberhasilan. Bahkan ketika yang diselesaikan hanyalah penampilannya, bukan substansinya. Gestur ini telah menjadi bagian dari struktur rasa bangsa. Bahwa selama sesuatu bisa dirayakan, maka ia dianggap benar.
“Teater Makna”
Antropolog Clifford Geertz, dalam The Interpretation of Cultures (1973), menyebut upacara dan simbol sebagai “teater makna” tempat masyarakat meneguhkan nilai-nilainya. Dalam konteks Indonesia, teater itu ada di mana-mana. Peresmian jembatan diiringi seremoni, program sosial dikemas dengan musik dan tepuk tangan, kebijakan politik disahkan dengan aklamasi yang berujung riuh.
Kita hidup dalam kebudayaan yang menilai keberhasilan dari kemeriahannya, bukan dari daya tahannya. Dalam bahasa Jacques Rancière, masyarakat kita mengatur distribution of the sensible—mendistribusikan rasa bahwa “ramai berarti berhasil.”
Namun di balik segala keramaian itu, tersembunyi kemiskinan refleksi. Neil Postman dalam Amusing Ourselves to Death (1985) mengingatkan bagaimana masyarakat modern berubah menjadi penonton yang lebih mementingkan hiburan ketimbang pemikiran. Televisi, katanya, telah mengubah demokrasi menjadi panggung hiburan di mana politik tampil bukan sebagai ruang perdebatan rasional, melainkan pertunjukan yang haus rating.
Kritik Postman itu menemukan bentuk paling konkret di sini. Di layar kaca, acara-acara penuh tawa dan slapstick dihidupkan oleh penonton bayaran yang riuh bertepuk tangan. Kita tidak hanya menonton hiburan, tapi kita hidup di dalamnya. Politik, pendidikan, bahkan agama kini dikemas dengan logika yang sama yaitu yang penting menghibur, menarik, dan bisa ditepuktangani.
Di ruang kelas, murid diharapkan menghafal data, bukan menggugat makna. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1984) sudah lama mengkritik sistem pendidikan gaya “bank” yang memperlakukan murid sebagai wadah kosong. Di Indonesia, tepuk tangan menjadi metafora pedagogis ketika siswa dipuji karena mengulang jawaban sesuai buku, bukan karena berani berpikir berbeda. Dengannya, pendidikan menghasilkan generasi penonton yang pandai meniru, tapi gagap merespon kenyataan dan dinamika jaman.
Simbol paling menyedihkan dari kegagalan itu bisa kita lihat di jalanan. Banyak lulusan sekolah, yang seharusnya siap kerja, berakhir menjadi pengamen di lampu merah. Mereka bernyanyi, menepuk tangan, mengetuk kaleng, berharap uang receh dari pengendara.
Gestur itu, disadari atau tidak, adalah cermin pendidikan dan ekonomi kita, yaitu hidup yang digantungkan pada apresiasi spontan, bukan keterampilan dan daya cipta. Mereka adalah potret dari logika nasional yang lebih percaya pada penampilan ketimbang proses, pada reaksi cepat ketimbang pemahaman mendalam.
Kemiskinan Makna
Fenomena ini bukan sekadar soal kemiskinan ekonomi, melainkan kemiskinan makna. Slavoj Žižek dalam The Plague of Fantasies (1997) menyebut keadaan ini interpassivity—situasi ketika kita merasa telah berpartisipasi hanya dengan menyaksikan atau menirukan gestur partisipasi. Menyaksikan orang lain bertepuk tangan, kita merasa ikut terlibat. Padahal kenyataan tetap tak berubah: penonton tetap penonton, pengamen tetap di pinggir jalan.
Hannah Arendt dalam The Human Condition (1958) menulis bahwa politik sejati adalah menghadirkan ruang publik untuk berpikir bersama tentang keadilan. Tapi di negeri ini, ruang publik lebih sering berubah menjadi panggung seremoni.
Pemerintah mengumumkan kebijakan dengan narasi gemerlap, media menyiarkannya dengan euforia, dan masyarakat menutupnya dengan tepuk tangan. Semua merasa lega karena peristiwa itu telah selesai dengan baik—padahal tak ada yang sungguh diselesaikan. Publik disulap menjadi audiens, bukan partisipan yang ikut berpikir.
Logika tepuk tangan juga merasuki cara kita beragama. Kesalehan direduksi menjadi slogan dan simbol. Keberagamaan diukur dari seberapa fasih seseorang mengulang jargon, bukan seberapa jauh ia berpihak pada yang lemah.
Tepuk Sakinah menjadi contoh kecil bagaimana nilai-nilai agama, yang mestinya mengajarkan refleksi dan tanggung jawab, direduksi menjadi hafalan ritmis yang mudah diingat tapi cepat dilupakan. Kita lebih nyaman mengucapkan janji daripada menanggung maknanya.
Franz Magnis-Suseno dalam Etika Politik (2016) mengingatkan, bangsa ini terlalu gemar mengambil jalan pintas pragmatis. Yang penting cepat, meriah, dan tampak selesai. Kecenderungan itu telah menjelma menjadi mentalitas nasional yaitu menunda kedalaman demi kecepatan, memilih efek daripada esensi. Tepuk tangan menjadi tanda bahwa kita telah “bergerak,” padahal mungkin hanya berpindah dari satu seremoni ke seremoni lain. Semakin sering menepuk tangan, semakin jauh kita dari refleksi.
Kerja Kultural
Dalam suasana seperti ini, gagasan Antonio Gramsci terasa penting untuk diingat. Dalam Selections from the Prison Notebooks (1971), ia berbicara tentang war of position—perjuangan panjang membangun kesadaran baru di tengah hegemoni lama. Perubahan sejati, kata Gramsci, tidak lahir dari seremoni, melainkan dari kerja kultural yang tekun dan sabar. Selama kita masih mengandalkan slogan, upacara, dan yel-yel, hegemoni ilusi akan terus berulang: kita merasa maju, padahal diam di tempat.
Yang dibutuhkan bangsa ini bukanlah lebih banyak tepuk tangan, melainkan keberanian untuk menahan diri agar tidak segera merayakan sesuatu yang belum selesai. Bukan euforia tapi pemahaman masalah, penemuan solusi serta kontekstualisasi dan pelaksanaannya.
Pendidikan perlu melatih kesabaran berpikir, bukan sekadar kecepatan menghafal. Politik harus membuka ruang perdebatan yang jujur, bukan menutupnya dengan aklamasi. Ekonomi seharusnya dibangun di atas visi jangka panjang, bukan proyek instan yang mudah diresmikan. Dan religiositas mesti kembali pada praksis kasih dan keadilan, bukan sekadar jargon yang dilagukan bersama.
Kita tidak kekurangan seremoni. Yang langka adalah keberanian untuk berpikir serius. Kita tidak kekurangan tepuk tangan. Yang kurang adalah budaya refleksi. Mungkin bangsa ini perlu belajar menahan telapak tangan. Bukan untuk menolak sukacita, tetapi untuk memberi ruang bagi pertanyaan, keraguan, dan keberanian berpikir ulang. Sebab membangun peradaban tak akan selesai oleh gemuruh tepuk tangan, melainkan oleh kesediaan menempuh kerja panjang, dengan kesadaran kritis dan kesabaran yang tidak mudah digoda oleh keriuhan.
Jika Tepuk Sakinah hari ini mengajarkan sesuatu, mungkin bukan tentang cara menanamkan nilai rumah tangga, melainkan tentang bagaimana kita telah terbiasa mengelola krisis dengan seremoni. Dan justru di sanalah tugas kebudayaan dibutuhkan yaitu mengingatkan bahwa bertepuk tangan bukanlah tanda akhir, melainkan panggilan untuk mulai berpikir.
—-
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, penerima fellowship Governance & Management of Culture di Daegu Catholic University Korea Selatan.